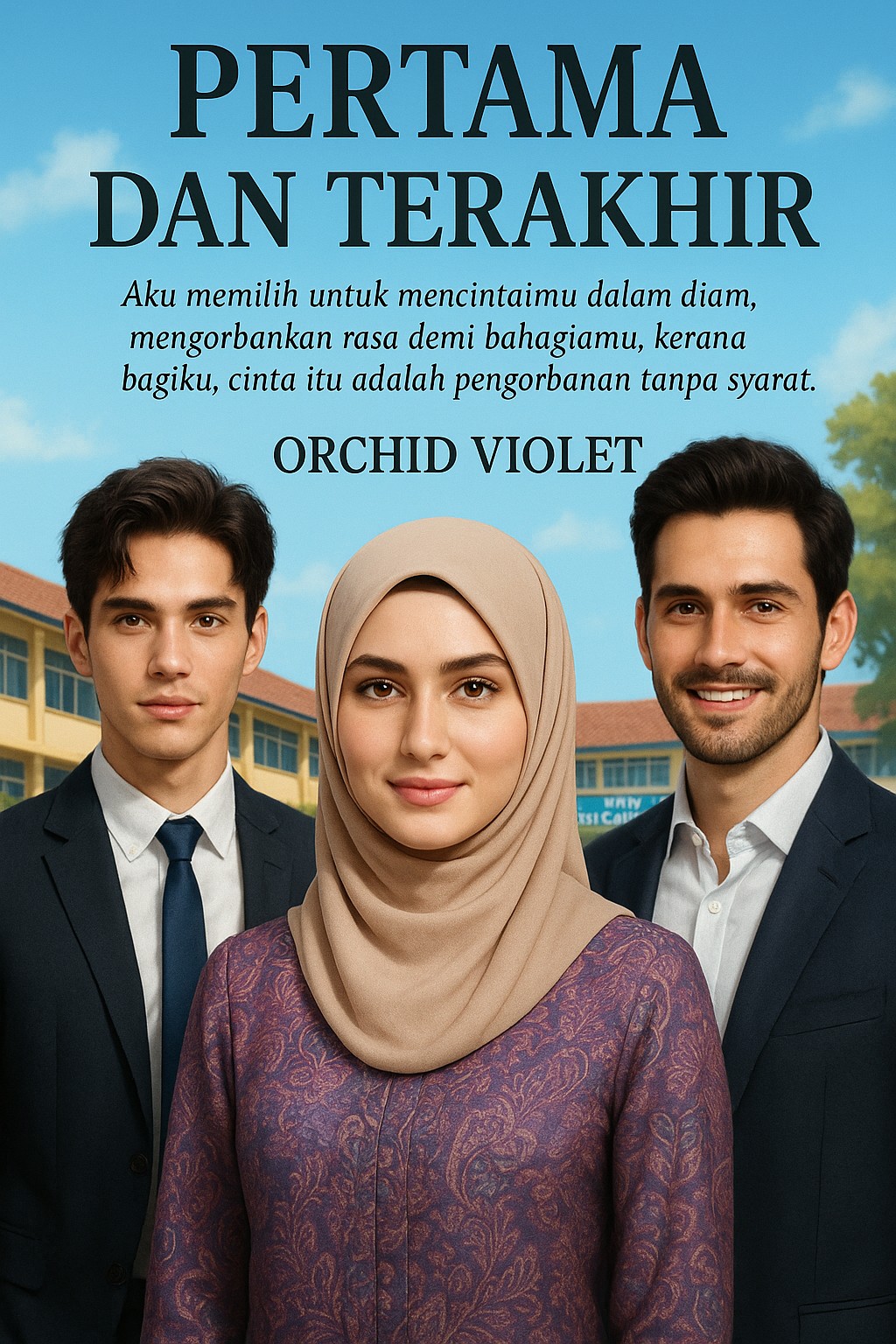
BAB 53 : INGIN MEMELUK DIRIMU
 Series
Series
 59683
59683
Sisa-sisa cahaya terik mentari yang sudah condong ke barat membias ke tingkap dewan, menyimbah warna keemasan ke atas pentas yang kini hampir sunyi. Majlis penghargaan telah ditutup dengan tepukan bergema. Penghormatan kepada para pegawai AADK yang hadir bukan sekadar sebagai tetamu, tetapi sebagai cahaya yang memandu jalan murid-murid kembali ke pangkal.
Sorakan dan tepukan gemuruh sebentar tadi masih terngiang-ngiang di dinding dewan. Pengumuman daripada pihak AADK telah meletuskan kegembiraan seluruh warga sekolah.
“Ujian saringan dadah mencatat keputusan seratus peratus negatif. Tahniah kepada SMK Seri Cahaya!”
Jeritan pelajar-pelajar bergema bagaikan di stadium. Ada yang melompat, bersiul, bersorak. Guru-guru menepuk tangan sambil tersenyum lega.
Ameena mengangkat tangan ke dada. Syukur tidak henti. Air matanya sedikit bergenang. Mengenangkan perit jerih para guru memulihkan pelajar-pelajar yang terlibat. Pelbagai kem kesedaran dijalankan. Semuanya berbaloi.
Alhamdulillah.
Wajah-wajah keletihan mula reda dengan senyuman. Satu persatu pelajar mula keluar dari dewan, berbaris kemas mengikut arahan disiplin. Hanya tinggal beberapa guru yang masih sibuk mengemaskan pentas dan menyimpan kembali peralatan PA system.
Ameena turut membantu. Tudung bawalnya sedikit senget, tersisip tidak kemas akibat pergerakan sejak tadi, namun wajahnya tetap tenang.. matanya redup. Tangannya cekap menggulung kabel panjang, lalu meletakkannya ke dalam kotak hitam bercengkerang logam.
Dewan mula sunyi. Yang tinggal hanyalah suara-suara rendah guru berbual dan sisa tawa perlahan dari sudut belakang.
“Cikgu Ameena... maaf.”
Ameena mendongak. Dahinya sedikit berkerut, perutnya terasa senak kerana terlalu lama duduk bertongkat lutut. Namun, dia tetap cuba mengukir senyuman mesra di bibir... senyuman yang selalu kelihatan walau dalam letihnya.
Lelaki itu berdiri segak di hadapannya.. berkulit sawo matang, berkaca mata, berwajah ramah namun bersih seperti seorang yang terlalu teliti. Namanya tertera jelas pada tag di dadanya. Luth Luqmani.
“Ini kad saya. Kalau Cikgu perlukan apa-apa bantuan berkenaan pencegahan dadah di sekolah, Cikgu boleh terus hubungi saya.”
Ameena menyambut kad itu dengan anggukan. Jari-jemarinya menyentuh kad nama berlamina itu, membaca perlahan di dalam hati.
“Insya-Allah... Encik Luth,” balasnya tenang.
Senyumannya tidak berubah. Tetap manis, tetap sopan. Sehinggalah lelaki itu mengangguk kecil dan melangkah pergi.
Dari kejauhan, sepasang mata tajam sedang memerhati. Eman. Rahangnya mengeras, bibir diketap rapat. Wajahnya yang biasanya lembut dan redup kini berubah tegang. Pandangannya tidak lepas daripada Ameena dan lelaki tadi.
Di sisinya, Airis masih berdiri. Wajahnya bermekap tebal, mata galak dan bibir merah menyala. Senyuman sinisnya tidak pernah lekang, seakan menikmati kerenggangan yang sedang terjadi.
Eman mula rasa rimas. Kehadiran Airis dirasakan seperti parasit yang enggan lepas, menyesak ruang dan perasaannya. Hatinya bergolak antara marah, cemburu, dan rasa tidak berdaya.
Tiba-tiba, muzik perlahan mula berkumandang.
Bunyi intro dari pembesar suara menyinggah ke seluruh ruang dewan—lagu lama, melankolik, dari zaman 90-an.
Beberapa pasang mata berpaling ke arah pentas.
Kelihatan Isa dan Fahmi berdiri santai dengan mikrofon di tangan, senyum-senyum nakal menghiasi wajah. Isa mengangkat tangan, seolah menyapa semua yang masih tinggal di dalam dewan.
“Ala, jangan matikan lagi PA system tu… kita nak test mic sikit,” usik Isa dari atas pentas, suaranya bergema bersama tawa kecil.
Beberapa orang guru hanya tergelak kecil. Ada yang masih menyusun kerusi di barisan belakang, ada juga yang bersandar penat di tiang dewan sambil menikmati saat santai terakhir hari itu.
“Bro... Eman! Jom lah... bila lagi?”
Isa menjerit lagi, mengangkat mikrofon ke arah rakan lamanya.
Eman yang sejak tadi berdiri kaku di tepi dinding, akhirnya menarik nafas panjang. Lega. Satu peluang untuk lari dari hiruk-pikuk rasa yang menyempitkan dada. Tanpa berkata apa-apa, dia terus bergerak ke pentas, mendaki empat anak tangga dengan langkah panjang.
“Bro... tahu ke kau lagu ni? Sejak bila pandai nyanyi lagu Melayu?” Isa mengangkat kening, gaya seperti penyanyi profesional yang bersedia masuk studio.
Eman hanya menggeleng perlahan, senyum nipis terbit di hujung bibir. Sebelah tangan menyeluk poket, sebelah lagi memegang mikrofon.
Intro lagu perlahan-lahan memudar masuk ke bait pertama.. lagu lama dari seberang, dendangan Dorman Manik, sebuah melodi tentang rasa yang tidak terungkap.
Isa memulakan nyanyian.
Suaranya separuh serius, separuh bergurau, namun tetap merdu di telinga yang mendengar. Suara lelaki yang sedang berjenaka, tetapi jauh di dasar nadanya... ada sesuatu yang cuba disembunyikan.
“Baru pertama aku merasakan...
Serba salah bila di depan dirimu...
Entah mengapa aku begini...
Wajahmu s’lalu terbayang-bayang...”
Cikgu-cikgu lain bersorak perlahan, sesetengahnya bertepuk tangan ikut rentak.
Namun di satu sudut dewan, Ameena hanya memandang—senyum yang tadi mekar sudah hilang. Wajahnya kaku, mata terarah ke pentas. Lagu itu... bukan sekadar gurauan.
Dan Eman, tanpa sedar, pandangannya singgah pada wajah itu.
Wajah yang dia sangat rindui.
Cikgu Fahmi mengambil alih rangkap kedua. Suaranya lebih tenang, namun nadanya bersulam usikan yang mengundang senyum di kalangan pendengar.
“Sehari saja kita tak bertemu...
Gelisah hatiku, ingin jumpa kamu...
Kerinduanku semakin mendalam...
Cintaku padamu s’makin membara...”
Sorakan perlahan dan tepukan ringan bergema dari guru-guru yang masih berada di dewan. Suasana jadi hangat dan santai, seperti pesta kecil yang tidak dirancang.
Kemudian, mikrofon bertukar tangan. Kini berada dalam genggaman Eman.
Dia diam seketika, menggenggam mikrofon erat. Nafasnya turun naik perlahan. Matanya tidak lagi melihat sekeliling. Hanya pandangan kosong ke hadapan. Dan kemudian dia mula menyanyi.. suara baritonnya meresap ke seluruh ruang.
“Bila malam, kupeluk bayang dirimu...
Dalam tidur pun kau s’lalu kuimpikan...
Aku takut berteriak memanggilmu...
Di tengah malam sunyi, ku sendiri...
Ingin memeluk dirimu...”
Nada nyanyiannya mendatar... namun penuh rasa. Bukan gurauan. Bukan main-main. Seperti jiwa yang sedang mencari.
Ameena, yang baru sahaja meletakkan gulungan kabel terakhir ke dalam kotak hitam, terdongak perlahan. Gerak tubuhnya kaku. Wajahnya kosong. Namun matanya... berkaca.
Lagu itu.
Itulah lagu yang selalu Eman nyanyikan untuknya. Lagu yang sering dipasang ketika mereka duduk berdua di dalam kereta, atau tatkala Eman mengejutkannya dari tidur dengan alunan lembut melalui telefon.
Itu lagu mereka.
Dan kini Eman menyanyikannya semula, di depan semua orang. ‘Ingatannya… dah kembali ke?’
Soalan itu menggema dalam benaknya, menggetarkan hatinya yang telah terlalu lama bersandar pada harapan.
Eman berdiri santai di tengah pentas, disinari cahaya samar lampu dewan yang mula malap.
Matanya terpaku pada Ameena.. tajam, namun penuh redup. Pandangan yang menggetarkan. Pandangan yang pernah membuat hati seorang gadis rebah tanpa sedar.
Suara Eman perlahan.. bergetar, berbalut serak-serak basah yang pernah mencairkan hati Ameena sewaktu persembahan taranum di sekolah suatu ketika dahulu.
Kini, dia menyambung nyanyian, bait demi bait seolah-olah diluah terus dari dasar jiwanya:
“Sehari saja kita tak bertemu...
Gelisah hatiku, ingin jumpa kamu...
Kerinduanku semakin mendalam...
Cintaku padamu s’makin membara...
Bila malam, kupeluk bayang dirimu...
Dalam tidur pun kau s’lalu kuimpikan...
....Aku takut berteriak memanggilmu...
Di tengah malam sunyi, ku sendiri...
Ingin memeluk dirimu...”
Suaranya tidak lantang. Tidak perlu. Kerana setiap nada yang terbit dari bibirnya cukup untuk merentap dada sesiapa yang mendengar.
Wajahnya tenang, namun jelas… ada harapan yang berselindung di balik lirikan mata itu.
Dan matanya masih… pada isterinya.
Sorakan dan tepukan dari guru-guru di bawah pentas bergema sekejap, sebelum perlahan-lahan tenggelam. Kerana bagi Eman, hanya satu wajah yang wujud dalam ruang itu. Ameena.
Ameena terpaku.
Dunia seakan terhenti.
Matanya tidak berkelip. Dadanya sesak. Lagu itu… bukan sekadar lagu.
Itu lagu mereka.
Liriknya menusuk masuk seperti belati yang tajam, membelah segala kenangan lama yang cuba disimpan kemas dalam kotak hati.
Namun saat dia berpaling sedikit, matanya terpaut pada satu wajah yang tidak seharusnya tersenyum
Airis.
Dan senyuman itu... seperti belati kedua. Hatinya retak. Dan kali ini, tidak mungkin mampu dicantumkan semula.
Dengan tiba-tiba, Ameena berpaling dan melangkah laju ke arah belakang dewan. Langkahnya longlai, lututnya menggigil. Nafasnya pendek-pendek, seolah mencari udara dalam lautan sesak emosi yang menenggelamkan.
Akhirnya, dia tiba di belakang pentas.
Sebuah ruang kecil yang sunyi. Bilik persalinan yang kosong, gelap dan dingin. Tempat yang tadi dipenuhi pelajar ceria kini menjadi tempat dia bersembunyi dari dunia.
Dia terduduk perlahan.
Bahunya merosot, tubuhnya bersandar pada daun pintu kayu yang sejuk. Tangannya menekup wajah. Dan saat itu, tangisannya pecah.. bisu, tapi dalam.
Hanya bahunya yang terhinjut-hinjut, menahan sedu yang tidak mahu kedengaran. Tapak tangannya kemas menutup ulas bibirnya.
Di luar, suara Eman masih berkumandang. Indah. Merdu. Tapi kini, bagi Ameena… suara itu cuma gema kosong dalam lorong hati yang telah patah.
Air matanya mengalir tanpa henti.
Sorakan kecil dan tepukan perlahan masih kedengaran dari dalam dewan. Beberapa guru tersenyum dan mengangguk sambil berdiri di tepi pentas, menyambut kemunculan semula Fahmi yang mengambil alih mikrofon. Suara nyanyiannya menyambung hiburan santai yang tampak ringan di mata semua… kecuali seorang.
Eman turun dari pentas dengan senyuman kecil yang dibuat-buat. Langkahnya nampak tenang, namun dalam hatinya gelora bergulung. Dia tersenyum… hanya untuk beberapa detik.
Kemudian, wajahnya berubah. Langkahnya bertukar cepat. Matanya liar, mencari. Mencari satu wajah. Ameena.
Dia tahu. Dia dapat merasakan ke mana arah wanita itu pergi.
Kerana malam tadi, satu demi satu kenangan telah kembali.. walaupun tidak semua. Tapi cukup untuk tahu. Cukup untuk faham bahawa yang lari itu bukan orang asing… tetapi isterinya. Cintanya.
Eman menyelinap ke balik pentas, menolak tirai hitam yang tergantung lesu. Kaki panjangnya melangkah laju di celah longgokan kerusi plastik yang bersandar senget. Lorong sempit menuju ke bilik persalinan pelajar kini sunyi dan lengang. Bau bedak dan pewangi masih bersisa di udara.
Langkahnya terhenti.
Di hujung ruang kecil yang muram, kelihatan satu tubuh kecil, lemah, terlerai.
Ameena.
Dia berteleku di penjuru dinding. Lututnya dilipat, tubuhnya membongkok. Bahunya terhinjut-hinjut perlahan bagaikan daun yang terbuai dalam angin lemah.Tangannya menekup mulutnya. Tangisan yang cuba disorok, sudah tidak tertahan.
Eman terpaku. Darahnya terasa beku. Jantungnya seolah terhenti. Matanya bergetar menahan sebak yang naik mendadak.
Kerana yang sedang menangis itu... bukan Ameena yang dia kenal. Ameena bukan mudah menangis. Dia adalah lambang kekuatan. Dia mampu menelan luka dalam diam, senyum walau hati koyak. Tetapi hari ini, dia runtuh.
Dan itu… adalah kerana dia.
Dengan perlahan, Eman melangkah. Sepasang matanya tak pernah beralih dari tubuh wanita yang menjadi pusat segala rindu dan munajat malamnya. Langkahnya senyap, seolah takut mengganggu luka yang sedang berdarah di hadapannya.
Dia jatuh melutut di belakang Ameena.
Lengan sasanya menggigil ketika memeluk tubuh yang makin susut itu dari belakang—erat, cermat, penuh rasa bersalah.
“Sayang…”
Suaranya serak. Nyaris tidak kedengaran.
Ameena tidak menjawab. Tidak menoleh. Tidak bergerak. Tangisnya perlahan, tetapi cukup untuk mencengkam dada.
Eman menekup wajahnya di bahu isterinya. Nafasnya naik turun, cuba menahan tangisan sendiri.
“Syhh… jangan menangis lagi, sayang…”
“Abang ada…”
“Abang takkan dengan orang lain… selain Amee…”
Nada suaranya bergetar. Tubuhnya turut menggigil dalam pelukan yang tidak ingin dilepaskan.
Pelukannya kejap. Erat. Seolah mahu menebus segala luka yang pernah dia biarkan tumbuh tanpa penjaga.
Dan di ruang kecil yang sunyi itu, dua hati yang pernah patah… kini mula retak dalam satu pelukan yang paling jujur pernah mereka kongsi.
Namun Ameena meronta.
Tubuh kecilnya menggeliat dalam pelukan Eman. Tangannya menolak lengan sasa itu, menepis lengan yang membelenggu tubuhnya.
“Lepaskan saya!”
Suara itu pecah bukan hanya oleh tangisan, tetapi oleh kemarahan dan hancurnya kepercayaan.
Wajahnya merah, basah dengan air mata yang terus mengalir deras. Matanya menyala, bukan kerana marah semata tetapi kerana terluka. Terlalu dalam. Terlalu sakit.
“Jangan sentuh saya, Cikgu Eman!”
Nada itu keras. Tajam. Menusuk.
Eman terkaku. Tapi tangannya tidak longgar. Pelukannya masih erat. Dia tahu, Ameena sedang marah. Dan di sebalik marah itu, tersembunyi cinta yang kecewa.
“Sayang… please… jangan cakap macam tu…”
Suaranya perlahan, bergetar, hampir terputus nafas.
“Awak nak saya percaya… lepas apa yang saya tengok?”
Ameena teresak. Suaranya pecah-pecah, menahan sedu.
“Pandangan mata dia… pandangan awak!”
Ameena menekup wajah, lalu menunduk ke lantai ke lantai. Hatinya patah.
“Kalau awak nak sangat Airis tu... lepaskan saya!”
Eman masih diam. Tapi pelukannya jadi lebih kejap. Bukan kerana ego. Tapi kerana kasih. Kerana dia tahu… Ameena tak benar-benar maksudkan kata-kata itu. Dia cuma terlalu hancur.
Dia tahu semuanya. Dia tahu bagaimana pandangan Airis kepada dirinya penuh harap dan angan.
Dan dia sengaja membiarkan demi memerangkap Airis.
Tapi dia lupa…
Ameena sedang memerhati. Dan wanita itu… bukan orang lain. Itu isterinya. Cinta hidupnya.
“Sayang…”
Suara itu kembali lembut. Suara seorang lelaki yang sedang menyesal.
Pelukannya diperkukuh. Kepalanya ditekup pada bahu Ameena. Ubun-ubun isterinya dikucup perlahan. Panas dan tenang. Dia menongkat dagunya di bahu itu, matanya memejam, menahan gejolak rasa.
Share this novel



