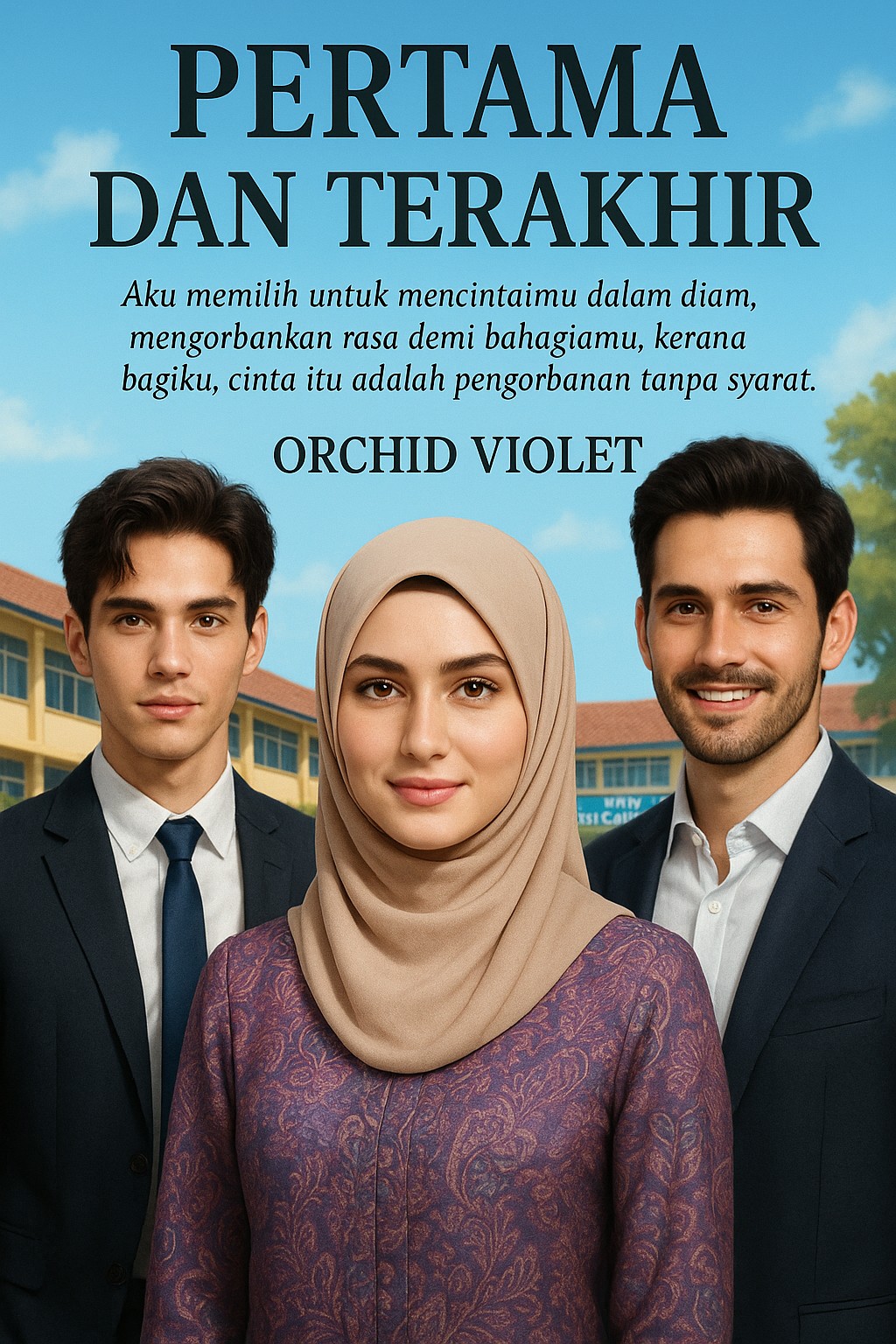
BAB 49 : BERUBAH
 Series
Series
 59683
59683
AZAN Maghrib sudah lama berlalu. Malam yang dingin itu sunyi, seperti mendengar sendiri rintihan hati yang tak bersuara.
Eman masih berteleku di atas tikar sejadah, tubuhnya membongkok, bahu terhinjut-hinjut menahan tangis. Kain pelikatnya basah di bahagian lutut, bukan kerana wuduk yang menitis… tetapi air mata yang tidak mahu berhenti mengalir.
Dia teresak. Dada terasa sempit. Nafasnya pendek-pendek. Di atas sejadah itu, dia bukan seorang guru, bukan seorang suami… hanya hamba yang sedang patah dan menyesal.
Tangan diangkat perlahan, namun berat.. seberat dosa yang tidak diketahui hujung pangkalnya.
“Ya Allah… ya Allah… ya Rahman… ya Rahim…”
Suara itu pecah dalam sebak yang tak dapat ditahan lagi. Dia tunduk, dahinya hampir mencecah lutut.
“Kalau benar aku pernah buat salah sebesar itu… kalau benar aku pernah zalimi seseorang tanpa aku tahu… aku mohon ya Allah, ampunkan aku… bersihkan aku… angkat segala hitam dalam diri ini…”
Air mata jatuh satu demi satu, membasahi dagu yang sudah mula ditumbuhi jambang nipis.
“Aku tak ingat, ya Allah… aku tak tahu… tapi hati aku sakit. Rasa bersalah ini menghancurkan seluruh tenang yang pernah aku ada…”
“Aku malu… aku takut… aku jijik dengan diri sendiri… jangan Kau buang aku jauh dari rahmat-Mu, ya Rabb…”
Dia menekup wajah.
Air mata lelaki yang jarang gugur, malam ini bagaikan hujan tak sudah.
“Dan Ameena… ya Allah…”
Nama itu terlepas perlahan. Seakan nama itu sendiri cukup untuk merobek dadanya. Eman menarik nafas payah dalam tangisnya yang menjadi teresak-esak tatkala nama itu meniti di bibirnya.
“Dia wanita baik… dia wanita yang Kau pelihara… dia kekasih hati yang aku tak pernah miliki”
Dia mendongak ke langit.. mata kabur dengan tangisan.
“Kalau aku bukan orang yang Kau takdirkan untuk bahagiakan dia… maka bahagiakanlah dia dengan orang yang lebih layak… dengan Isa… dengan sesiapa pun yang Kau redhai…”
“Lembutkan hati Isa… kembalikan cinta mereka kalau itu jalan terbaik untuk Ameena…”
“Aku terima takdir ini Ya Allah.. andai dia bukan tercipta untukku. Kalau aku tak layak, ya Allah… ambil rasa cinta ini dari hati aku…Biar aku sakit sekarang… jangan sampai aku seksa dia sepanjang hidup dia…”
Tangisannya makin kuat. Esakannya meruntun langit malam.
“Tapi kalau masih ada ruang untuk aku bimbing dia ke syurga… kalau aku masih Kau pandang sebagai lelaki yang boleh menuntunnya… Kau pulihkanlah hati aku, fikiran aku, ingatan aku… ya Allah… dengan cara yang Engkau redhai…”
“Tapi jika tidak…”
Dia tunduk kembali, tubuhnya menggigil.
“…maka aku reda. Aku lepaskan dia dalam doa. Aku relakan dia bahagia bukan dengan aku…”
Dia jatuh sujud. Teresak dalam sujud yang panjang. Menyerah seluruh cintanya kepada Tuhan. Dan malam itu menjadi saksi.. seorang lelaki yang benar-benar mencintai, sanggup melepaskan, demi kebahagiaan insan yang dia kasihi..
BILIK hospital itu sudah tidak sesuram semalam. Langit di luar jernih, awan berarak perlahan, dan burung-burung sesekali kedengaran berkicau dari celahan tingkap terbuka separuh. Namun, dalam terang yang datang bersama pagi, hati Ameena masih suram.
Kotak makanan di atas meja kecil di sisinya sudah lama tak berusik. Air suam yang dibawa jururawat pun hanya luak suku. Kartini, ibunya, sibuk melipat pakaian kecil yang mereka kemas masuk dalam beg semalam. Tapi matanya tetap menjeling ke arah anak gadisnya dari semasa ke semasa.
Ameena duduk bersandar, wajah pucat namun manis, hanya senyuman yang tidak hadir seperti biasa. Matanya menatap makanan di hadapannya dan sesekali meleret ke arah pintu. Menunggu. Mengharap.
Tangannya menggenggam sudu. Nasi di pinggan sudah mula sejuk, dia menyuap sedikit demi sedikit. Setiap suapan, berat. Pahit.
Tiba-tiba, ingatannya terbang jauh..kembali ke petang itu.
Petang yang dia hampir kehilangan permata kecil yang baru mula berdenyut dalam rahimnya.
Dia ingat betul. Saat tubuhnya lemah dan kesakitan, Eman yang mendukungnya masuk ke dalam wad kecemasan. Langkahnya pantas, namun cemas. Dadanya turun naik. Peluh menitik di dahi. Wajahnya pucat tak berdarah. Tapi mata itu… mata itu penuh ketakutan.
"Tolong! Dia mengandung… dia ada pendarahan!" suara Eman tinggi.. panik.
Beberapa jururawat terus datang bergegas, menarik stretcher ke arahnya. Eman tidak mahu melepaskan, tapi mereka perlu mengambil alih.
“Encik… sila buat pendaftaran ya. Buku merah dia mana?”
Eman terdiam seketika. Matanya keliru. Tangannya menggigil.
“Saya… saya tak tahu… Dia ada simpan sendiri…”
“Encik suami dia ya?”
Wajah Eman saat itu terhenti. Tiada kata yang terluah. Hanya senyum nipis.. terlalu nipis hingga menyakitkan.
Ameena ingat semuanya. Setiap detik. Setiap nada. Setiap getar dalam dakapan Eman yang cuba berpura-pura kuat.
Dia terasa selamat dalam pelukan itu. Dia rasa disayangi. Untuk seketika, segala ketakutan tentang kehilangan lenyap.
Namun sekarang…
Semua itu hanya tinggal kenangan.
Ameena tunduk di sisi katil. Makanan di mulut terasa tawar. Suapan seterusnya diiringi titis air mata. Bahunya terhinjut-hinjut menahan tangis. Lidahnya berat, tapi hatinya menjerit.
“Abang…” bisiknya perlahan.
‘Amee dah tak sanggup… Kejam ke kalau Amee berterus terang? Kejam ke Amee, Abang…’
Air matanya jatuh lagi. Dia cuba senyum.. senyum yang kalah oleh perit rasa di hati.
‘Amee ingat semua kenangan kita… Amee boleh ceritakan. Setiap hari, Amee sanggup cerita semua… dari mula sampai habis. Amee takkan jemu. Supaya Abang boleh ingat balik.’
Tangisnya makin deras. Dia memeluk perutnya perlahan, seperti memeluk harapan yang sedang membesar di dalam.
‘Amee tak berselera… Tapi Amee kena kuat. Sebab dalam ni ada sebahagian dari Abang. Satu-satunya yang masih ada waktu Abang makin jauh…’
“Sayang…” panggil Kartini perlahan sambil meletakkan beg pakaian ke atas kerusi.
Ameena tidak menyahut. Pandangannya kekal terarah pada daun pintu putih itu. Tangannya terus menyuap walaupun banyak yang tumpah kerana bertarung dengan esakkan diamnya.
Lambat-lambat Ameena berpaling. Matanya berkaca.
“Ibu… semalam Abang janji nak datang lepas Asar. Sampai hari ni… tak muncul pun.”
Kartini mengeluh kecil. Dia duduk di sisi katil, menggenggam tangan anaknya.
“Mungkin dia tak sempat… mungkin dia...”
“Atau mungkin dia dah tak nak datang, Ibu.” Suara Ameena hampir berbisik, namun cukup tajam menyayat.
Wajah Kartini berubah sedikit. Tapi dia tidak menyanggah.Ameena tunduk. Bahunya jatuh sedikit, menahan sesuatu dalam dada.
‘Dulu… Eman selalu datang waktu aku tak minta. Sekarang… waktu aku harap dia datang… dia hilang.’
“Kakak…” Kartini memegang pipi anaknya.
“Jangan terlalu ikut rasa. Eman tu… dia masih sedang pulih. Hatinya mungkin bercelaru. Tak semestinya dia buang Kakak.”
“Tapi kenapa rasa ni lain, Ibu?” Matanya berkaca lagi. Suaranya serak.
“Kenapa dada Kakak rasa berdebar-debar… macam ada sesuatu yang tak kena… macam ada sesuatu yang Abang Eman sorok?”
Kartini diam. Dia sendiri tidak punya jawapan. Dia hanya dapat mengusap rambut anaknya perlahan, cuba menenangkan walau dirinya juga tidak tenang.
“Jangan fikir bukan-bukan. Eman sayang Kakak. Ibu nampak dari mata dia hari tu. Tapi sekarang dia keliru. Dia takut. Dia tak ingat. Dan Kakak pun kena kuat untuk dua orang. Bukan lemah sebab satu orang.”
Kartini memegang perut anak perempuannya. Mengingatkannya tentang satu lagi insan yang perlukan Ameena.
SUDAH seminggu berlalu sejak Ameena discaj dari hospital. Dan hari ini, dia kembali ke sekolah, tempat yang selalu membuatkan jiwanya tenang. Tempat yang menyimpan ribuan kenangan manis. Terutama, kenangan bersama Eman.
Langkahnya ringan, bibirnya tidak putus menguntum senyum. Biarpun tubuh masih lemah, hatinya tekad. Dia mahu kembali mengajar. Dan… kembali menatap insan yang paling dia rindukan.. EMAN.
Ameena menuruni perlahan anak tangga ke tingkat bawah. Dia baru habis mengajar kelas Empat Sains Tulen. Eman muncul dengan buku teks sejarah di tangan. Mungkin ke kelas Lima Sains Kejuruteraan.
Langkah Ameena terhenti. Terpaku disitu. Namun Eman tidak lansung memandangnya. Tiada sapa mesra. Tiada senyum menenangkan. Hanya lirikan mata yang tawar, dan senyuman pahit yang terasa seperti pisau menikam kalbu.
Ameena menahan pedih. ‘Apa yang berlaku? Kenapa... Abang.?’
Eman sudah berubah. Eman seperti bukan Eman yang dikenalinya.
Eman bersandar lemah pada dinding koridor. Hatinya turut sakit. Sebolehnya dia mengelak untuk bertembung dengan Ameena. Namun sampai bila. Dia tahu dia akan sesakit itu.
Eman mendongak kepala memandang langit biru. Tangannya naik ke dada. Meredakan jantung yang sedang berdegup laju. Dia perasan perubahan wajah Ameena tadi. Wajah yang ceria tiba-tiba berubah mendung. Dan dia tahu dia puncanya.
‘Maafkan saya.. antara awak dan saya belum terikat apa-apa. Tapi kau dah lamar dia Eman! Kau lamar dia dekat rumah kau sendiri!
‘Tapi Airis? Maruah Airis macam mana. Dosa yang aku buat, aku tak boleh biar dia tanggung sendiri.’
Eman terbayang wajah Emak dan Abahnya. Pasti mereka malu besar kalau hal ini sampai ke pengetahuan mereka. Dada Eman sesak dengan pelbagai andaian yang masuk kedalam otaknya bertimpa-timpa.
Dari celahan kaca tingkap kecil, Eman memerhati dari balik dinding. Ameena sedang mengutip buku yang jatuh bertaburan.
Tangan Eman yang mahu membantu tadi menggigil.. namun akhirnya ditarik semula. Dia hanya mampu memandang dari jauh. Pandangan yang dipenuhi luka dan rindu yang tak mampu dia ubatkan sendiri.
“Maafkan saya, Ameena… Saya tak boleh bagi harapan palsu.”
Eman terus berlalu pergi sebelum Ameena menyedari kehadirannya.
Tapi hati wanita itu… dapat merasa sesuatu.
Hari itu juga, di kantin, Ameena cuba mendekati. Hatinya rindu untuk mendengar suara Eman. Walau satu ayat pun sudah cukup untuk melegakan rindu yang menggunung.
"Cikgu Eman… dah makan ke?"
Soalannya lembut. Wajahnya berharap.
Eman berhenti seketika. Matanya hanya menatap meja. Tiada senyum. Tiada sinar. Hanya jawapan pendek yang menikam.
“Hmm… dah.”
Tanpa sepatah tambahan, Eman berpaling dan berjalan pergi. Tanpa menoleh. Tanpa peduli air mata yang bergenang di tubir mata wanita yang sedang mengandung anaknya.
Ameena terduduk. Dada terasa sesak. Pedih.
Sekolah sudah sedikit sunyi dengan suara pelajar. Waktu pulang sudah berlalu sejam tadi. Ameena melangkah ke parkir untuk pulang, namun dia terlihat sesuatu yang mencarik perasaannya.
Eman.. bersama Airis.
Berjalan beriringan ke arah kereta. Eman membukakan pintu. Airis masuk. Dan kereta itu bergerak pergi. Bersama dua jasad. Tapi satu jiwa di belakang tertinggal, hancur berkeping-keping.
“Abang… kenapa? Apa yang dah berlaku? Kenapa hati abang seakan tertutup untuk Amee sekarang?”
Ameena memeluk beg tangannya erat-erat. Titis air mata jatuh juga di pipi yang semakin cengkung. Dia berpaling, melangkah pergi. Tapi setiap langkah bagai memijak duri.
Dalam rahimnya, ada kehidupan yang sedang membesar. Namun di luar tubuhnya, lelaki yang sepatutnya menjadi pelindung, semakin menjauh.
DI HADAPAN rumah sewa Airis. Dia menyandar di keretanya dengan hati yang semakin celaru. Airis berdiri di hadapannya dengan wajah suram dan resah yang dibuat-buat. Sesekali menjeling ke arah pintu rumah sebelah seolah-olah bimbang perbualan mereka terdengar orang.
Airis menarik nafas panjang, tangannya mengepal di sisi.
“Abang… kita kena percepatkan majlis. Kalau mak tahu... saya mati. Mak boleh bunuh saya, bang.” Nada suaranya bergetar, matanya bergenang.
Eman tidak terus menjawab. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk lutut. Dadanya sesak.
“Airis… kenapa semua ni berlaku? Kenapa saya boleh… sampai macam tu?” suara Eman rendah, seperti bergema di dalam dirinya sendiri.
Airis memandang tepat ke wajah lelaki itu.
“Abang tak ingat, tapi saya ingat. Abang paksa saya malam tu. Saya tak nak. Tapi abang… abang cakap abang sayang saya. Abang cakap nak jaga saya.”
Suaranya tenggelam dihimpit emosi. Kepuraannya tersembunyi rapi.
“Sekarang… abang nak tinggalkan saya? Lepas semua yang berlaku?”
Eman memejam mata. Nafasnya berat. Di fikirannya, wajah Ameena hadir lagi. Senyum manis, renungan lembut, suara tenang memanggilnya “Cikgu Eman” dalam kenangan samar-samar. Tapi kini wajah itu ditutupi bayang dosanya.
“Saya… saya cuma nak buat perkara yang betul.” katanya akhirnya.
“Tapi Airis… saya tak cintakan awak. Saya tak pernah pun... Ada perasaan tu. Benda tu berlaku... sebab.. mungkin saya tak waras. Saya..”
“Abang nak cakap abang menyesal?” suara Airis meninggi.
“Kalau menyesal, kenapa tak dari dulu? Sekarang dah terlanjur, baru abang nak kata semua ni silap?”
Eman menggenggam rambutnya, kepalanya tunduk.
“Saya marah dengan diri sendiri, Airis. Saya jijik dengan apa yang saya dah buat. Saya rasa... saya tak layak untuk sesiapa pun.”
Airis menggeleng perlahan. Akalnya makin menggila.
“Tapi saya tak ada orang lain, bang. Saya cuma ada abang. Kalau abang tinggalkan saya… mak saya bunuh saya.Tapi tolong… jangan tinggalkan saya.”
Eman memandang Airis. Mata gadis itu berkaca, wajahnya penuh ketakutan dan harapan yang bersilang. Tapi di hati Eman, rasa bersalah dan jijik terhadap dirinya sendiri lebih kuat dari segalanya.
Dia berdiri perlahan, langkahnya berat.
“Saya perlukan masa. Saya tak janji apa-apa, Airis. Tapi saya akan cari jalan…” Dia berhenti sejenak.
“Kalau saya buat keputusan, saya akan beritahu.”
Airis tidak menjawab. Dia hanya memandang Eman dengan tatapan kecewa yang menjerut.
Share this novel



