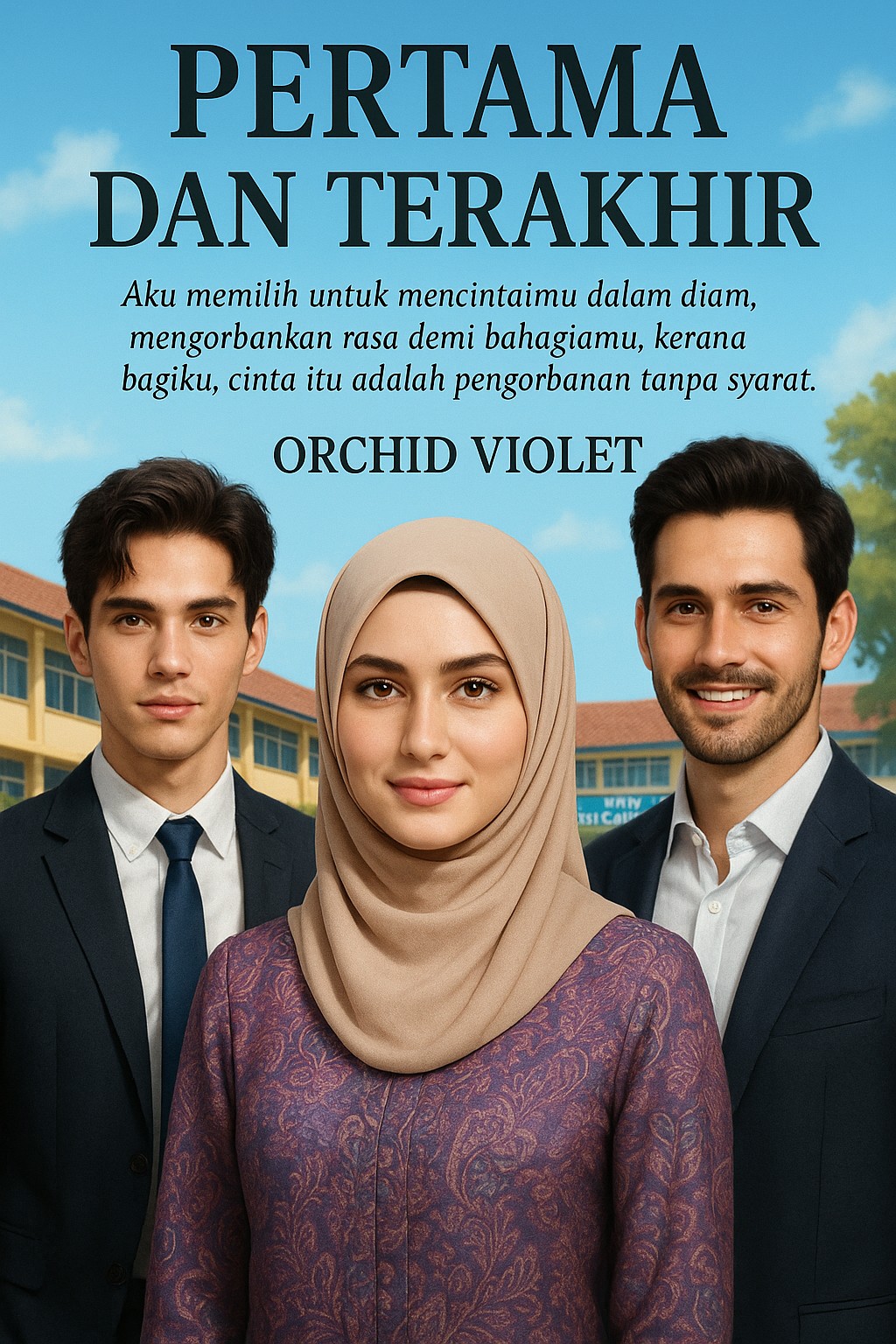
BAB 42 : KHABAR SUKA YANG DUKA
 Series
Series
 53124
53124
Petang itu, Eman akhirnya dipindahkan dari ICU ke wad biasa.
Langit kelihatan kelabu dari jendela, bayu petang menolak tirai putih yang separuh terkuak.
Suasana wad itu sedikit lebih cerah berbanding ICU.
Dindingnya berwarna biru lembut, lantai berkilat bersih, dan aromatherapy daripada difuser hospital masih kuat menyelubungi udara.
Sebuah kerusi malas diletakkan di sisi katil, bersama meja kecil beroda.
Di sisi Eman, setia berdiri Airis, dengan senyumannya yang penuh rasa bangga.
Seolah-olah seluruh dunia kini berada dalam genggamannya.
Beberapa guru dari sekolah tiba tidak lama kemudian. Cikgu Reena, Cikgu Yasmin, Cikgu Julia, dan Cikgu Lily. Mereka datang beriringan, wajah masing-masing bercampur lega dan terkejut.
Leganya kerana Eman sudah kembali sedar.
Terkejutnya apabila melihat figura yang dikenali bukan sesiapa pun dengan Eman tetapi seolah-olah begitu mesra di sisi Eman.
"Assalamualaikum, Eman..."
Cikgu Reena membuka salam, matanya sekilas merenung Airis.
"Waalaikumsalam, Kak Reen..."
balas Eman ceria, senyumannya lebar, tanpa menyedari kekok yang menyelimuti suasana.
Cikgu Yasmin membetulkan cermin matanya, cuba menyembunyikan keterkejutannya.
Cikgu Julia dan Lily saling berpandangan, tidak perlu berbicara untuk memahami perasaan masing-masing.
Kenapa Airis... kerani sekolah mereka ada disitu?
Dan di mana Ameena?
Hampir serentak, Isa dan Fahmi muncul di muka pintu.
Isa segak dalam kemeja polos, tapi wajahnya kelihatan tegang melihatkan figura di sisi Eman.
Fahmi, dengan jaket sukan tergantung di lengan, juga tampak serba salah.
Tidak lama selepas itu, dalam kelam keliru itu, Ameena melangkah masuk. Tubuhnya kurus, langkahnya perlahan, seperti memaksa setiap inci dirinya untuk bertahan.
"Abang tak salah... Aku kena kuat untuk dia..."
bisik hatinya.
Sejurus matanya bertembung dengan wajah Eman, dunia seakan berhenti berputar.
Eman tersenyum.. senyum ceria, polos, tanpa beban.
Dan kata-kata pertama yang meluncur dari bibirnya menghancurkan kesunyian bilik itu
"Eh, Bro! Datang juga kau..."
"Ingatkan masih honeymoon dengan Cikgu Ameena!"
Ketawa kecil Eman bergema di bilik itu. Namun tiada siapa ketawa bersamanya.
Isa membeku dengan senyuman hambar. Ameena sudah menceritakan kepada Cikgu Fahmi dan Isa keadaan Eman.
Ameena mengigit bibir bawahnya, menahan sesuatu yang terasa mencucuk dada.
Cikgu Reena, Yasmin, Julia, dan Lily hanya mampu berpandangan sesama sendiri..... terkejut dan keliru.
Airis, yang berdiri di sisi katil, hanya tersenyum nipis, seolah-olah puas menyaksikan drama yang perlahan-lahan mengorbankan semua yang pernah bertakhta di hati pesakit itu.
Seisi bilik dibungkam oleh suasana yang aneh...suatu ruang kosong yang dipenuhi luka yang tidak kelihatan. Eman pula terasa kata-katanya menikam hatinya sendiri. Dalam sudut yang paling dalam di hatinya, ada suara yang bagaikan tersekat. Di dasar memorinya terasa ada ingatan yang diikat dan digari kuat.
Ameena tidak menunggu lebih lama.
Dengan seluruh kudrat yang berbaki, dia memusingkan badan, melangkah keluar dari bilik itu.
Langkahnya longlai, wajahnya pucat lesu.
Dadanya berombak menahan sebak yang mula memberat di kerongkong.
Cikgu Lily, yang sejak tadi menyedari perubahan pada riak wajah Ameena, segera mengekorinya.
Isa juga menapak perlahan di belakang, serba salah.
Belum sempat Ameena melepasi koridor kecil itu.. tubuhnya terhuyung-hayang, lalu terjelepuk jatuh ke lantai berjubin sejuk. Satu keluhan kecil terlepas dari bibirnya.
"Ameena!" jerit kecil Cikgu Lily, cepat memaut tubuh kurus itu. Wajah Ameena yang pucat membuatkan Cikgu Lily cemas.
Isa berdiri kaku. Tangannya terangkat separuh, kemudian jatuh semula ke sisi.
Dia sedar dia tiada hak lagi.
Jururawat yang bertugas di kaunter melihat insiden itu, tergamam seketika sebelum bergegas datang.
Mereka segera membawa kerusi roda, membantu Ameena yang hampir tidak sedarkan diri.
Sepanjang didorong dengan kerusi berroda dua itu, Ameena membiarkan dirinya dipandu diam, tidak melawan, tidak bertanya.
Senyuman pahit yang cuba dipaksakan hanya sempat terukir seketika, sebelum lenyap dibawa angin yang berhembus dari pendingin udara hospital.
Hatinya yang remuk seakan-akan turut dirasakan oleh para jururawat.
Mereka menatap Ameena dengan pandangan simpati yang berat.
Hancurnya hati isteri pesakit mereka jelas terpampang walaupun tiada sepatah kata terluah.
Di bilik pemerhatian kecil, seorang doktor perempuan muda menghampiri.
Senyuman lembut terukir di wajahnya.
"Puan Ameena, saya ada berita gembira..."
suara doktor itu perlahan, seolah-olah tidak mahu mengejutkan pesakit yang rapuh di hadapannya.
Ameena memandang, matanya kosong.
"Tahniah... Puan sedang hamil. Usianya baru sekitar lima minggu, masih awal, tapi sangat stabil. Ini satu keajaiban..."
ucap doktor itu perlahan, matanya bersinar penuh harapan.
Ameena terdiam.
Wajahnya pucat tidak berubah, tetapi kelopak matanya tiba-tiba bergenang.
Dalam diam, setitik dua airmata menitis perlahan ke pipi.
Tangisannya bukan jeritan. Bukan esakan. Tetapi tangisan yang keluar dari luka paling dalam.
Sedih.. kerana tidak dapat berkongsi berita bahagia ini dengan Eman, orang yang paling dinantikan untuk sama-sama menyambut anugerah ini.
Gembira.. kerana doa mereka berdua, di dalam setiap sujud dan tangisan sebelum ini, akhirnya dimakbulkan Allah.
Satu senyuman kecil terbentuk di bibir pucat itu, sambil air matanya mengalir tanpa suara.
"Alhamdulillah..."
bisiknya perlahan, seolah-olah berbicara hanya kepada dirinya sendiri.
Atau mungkin kepada hati Eman, yang pernah berjanji mahu menjadi ayah kepada anak mereka.
“Ibu janji, Ayah akan sambut kehadiran Sayang nanti. Membesarlah dengan sihat .. Sayang ibu..” dan airmatanya berguguran tanpa dibendung lagi. Lebat seperti badai di musim tengkujuh.
Dan di luar bilik itu,
petang semakin menguning,
seakan-akan turut berkabung atas sebuah cinta yang sedang diuji sehabis-habisnya.
Lorong sepi di luar bilik Ameena terus mendakap senyapnya. Tiada langkah, tiada bicara, tiada gelak mesra. Yang ada cuma resah yang duduk diam di setiap kerusi menunggu. Lampu kuning di siling hospital menyimbah wajah-wajah yang tenggelam dalam buntu dan rasa bersalah yang tak terucap.
Fahmi bersandar pada dinding yang dingin, jari-jemarinya mengepal erat. Matanya memaku lantai seperti mencari jawapan di celahan ubin yang membisu. Isa duduk mencangkung, wajahnya tenggelam dalam dua tapak tangan. Nafasnya berat, dadanya sesak menahan sesuatu yang tak mampu diluah.
Cikgu Lily berdiri tidak jauh dari situ, tubuhnya sedikit membongkok ke hadapan, seolah memikul beban yang jauh lebih berat dari tubuh kecilnya. Bahunya jatuh, dan setiap helaan nafasnya seperti berusaha menghalau perasaan bersalah yang makin menggila dalam dada.
Berita kehamilan Ameena tadi—yang sepatutnya menjadi khabar gembira—telah membungkam mereka. Bukan tidak bahagia mendengarnya. Tapi mereka tahu… jiwa yang sedang luka bukan tempat terbaik untuk membawa khabar suka. Takut andai khabar itu mencarik lebih dalam luka yang belum pun sempat tertampal.
Kalau Ameena terus berjumpa dengan Eman dalam keadaan itu…
Sedangkan Eman langsung tak mengingati siapa dia…
Apa akan jadi pada hatinya?
Pada kandungannya?
“Cuti sakit... dua minggu?” soal Fahmi akhirnya, suaranya parau seperti baru bangkit dari tenggelam.
Isa mengangguk perlahan. “Paling minimum. Tapi doktor kata kemungkinan besar sebulan. Eman tak boleh stres. Silap langkah, dia boleh hilang lebih dari sekadar ingatan.”
Senyap lagi. Diam yang menyakitkan.
Lily melepaskan keluhan yang dalam, seperti cuba melepaskan beban yang bersarang di jiwanya sejak sekian lama. “Dan sekolah… siapa nak uruskan peperiksaan akhir? Semua tu Eman yang rancang dari awal tahun. Tak ada siapa yang tahu struktur sistem dia sepenuhnya kecuali dia.”
“Kita buat sama-sama,” pintas Fahmi. “Kita uruskan. Kita tanggung. Tapi masalah sekarang... bukan sekolah.”
Isa mendongak perlahan, wajahnya muram. “Ameena...”
Nama itu membuatkan ketiga-tiganya terdiam serentak. Dada mereka seolah ditusuk serentak. Berat. Sakit.
Dari celahan pintu yang sedikit terbuka, kedengaran sayup suara jururawat yang cuba memujuk Ameena untuk berehat. Tiada balasan. Tiada suara. Hanya sepi yang menjawab. Dan diam Ameena lebih menakutkan dari tangisannya.
“Dengan keadaan dia yang mengandung... dengan emosi dia yang sekarang ni…” Isa menyambung, nadanya hampir berbisik, “...aku bimbang dia simpan semuanya sendiri. Dan bila dah penuh… dia akan pecah.”
Lily memeluk tubuhnya sendiri. Nafasnya bergetar. “Airis… perempuan tu takkan lepaskan Eman. Cara dia pandang kita tadi pun macam... dia dah menang. Dia nak Eman jadi milik dia. Sampai bila?”
Fahmi mengetap bibir. Rasa geram dan kasihan bersatu di hujung mata. Tapi dia tahu, ini bukan masa untuk marah.
Lily kembali bersuara, namun nadanya berubah. Lembut. Menggigil.
“Kalaulah dulu aku tak kejar benda yang bukan hak aku… Kalaulah aku tak ikut cemburu buta aku dulu. Kalaulah aku sedar lebih awal betapa dalamnya rasa Ameena pada Eman…” dia tunduk, mata berkaca, “...mungkin semua ni takkan jadi.”
“Cikgu Lily…” Fahmi memandang, cuba menenangkan.
Lily senyum tawar. Satu senyuman yang menakutkan—kerana ia sarat dengan luka yang tak terubat.
“Tapi kalau semua boleh diperbaiki dengan ‘kalau’… semua benda akan jadi indah. Luka boleh sembuh. Penyesalan boleh hilang. Tapi hidup ni bukan macam tu…”
Isa mengangguk perlahan. Wajahnya penuh penyesalan yang lebih lama tersimpan.
“Kita semua ada silap. Tapi sekarang... bukan masa untuk tenggelam dalam rasa bersalah. Kita kena fikir macam mana nak lindungi Ameena dan Eman. Mereka berdua… saling menyelamatkan satu sama lain dulu. Sekarang giliran kita.”
Dan untuk satu saat yang sunyi, hanya degupan jantung masing-masing yang terdengar. Degupan yang penuh harapan. Degupan yang penuh penyesalan. Degupan yang mahu berjuang… walau luka masih merah berdarah.
Kerana cinta… bukan sekadar tentang memiliki.
Cinta juga adalah tentang siapa yang sanggup tinggal, diam-diam menunggu, meskipun dalam derita.
Share this novel



