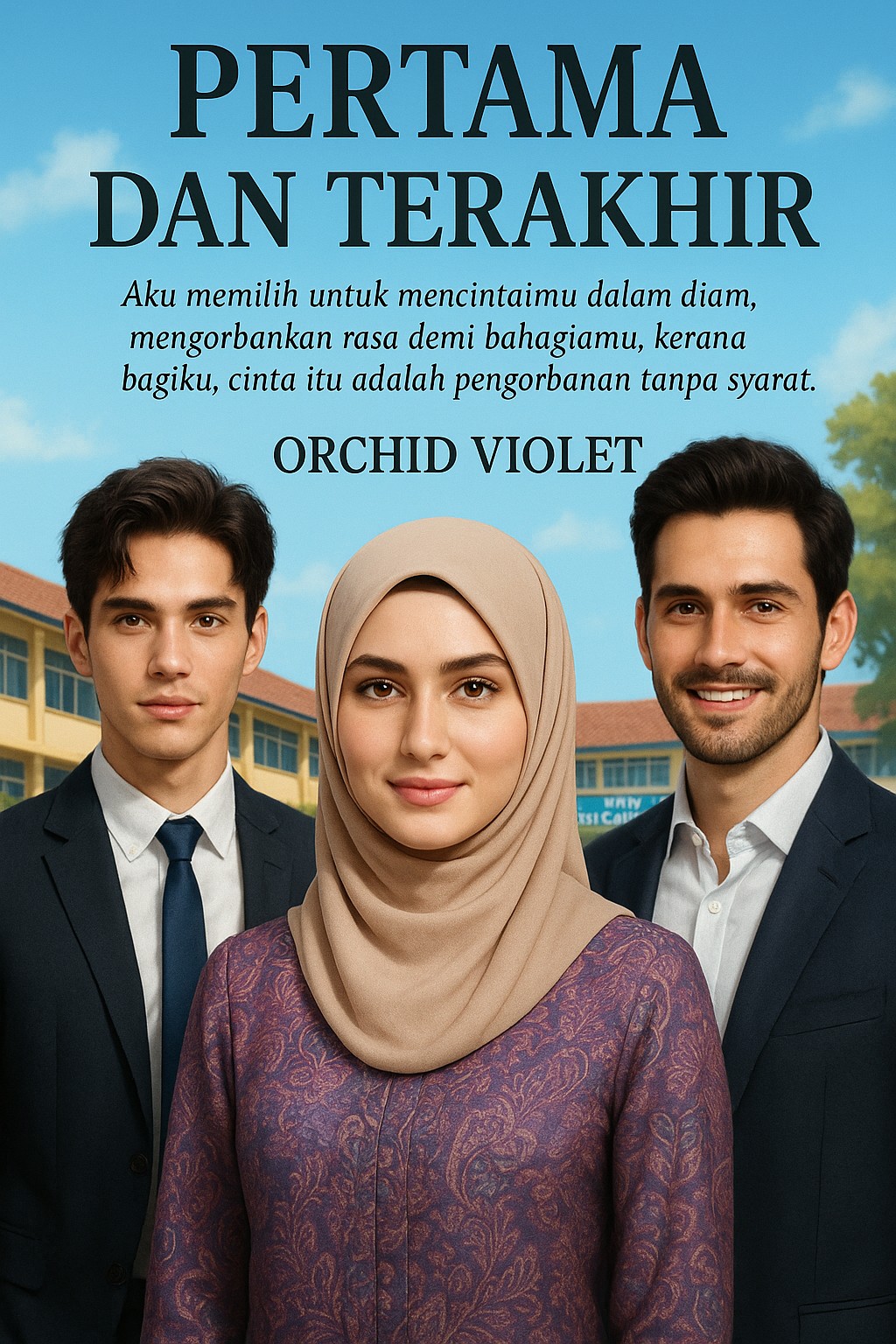
BAB 41 : HILANG INGATAN
 Series
Series
 53124
53124
DI SEBALIK kaca berlapis dua yang memisahkan bilik ICU daripada kaunter jururawat, suasana tampak tenang dari luar. Namun di dalam hati beberapa jururawat bertugas, taufan keraguan sedang menggila.
"Kau rasa pelik tak?" bisik Irdina, salah seorang jururawat senior, sambil menjeling ke arah Eman yang kini terbaring lemah, wajahnya separuh tersenyum kepada seorang perempuan muda yang baru muncul.
"Aku pun hairan. Sepanjang dua minggu jaga dia... tak pernah nampak pun perempuan tu," balas Hazirah, membetulkan fail di tangannya. "Bukan ke sebelum ni ada perempuan lain? Yang selalu duduk baca Yassin, yang bisik-bisik kata semangat kat dia?"
Irdina mengangguk, wajahnya serius. "Ya... Yang tu... setiap hari datang. Kadang-kadang aku tengok dia usap tangan Encik Eman... baca surah dengan suara yang buat kita pun rasa sejuk hati. Mana dia sekarang?"
"Kau rasa Encik Eman confuse ke?" tanya Hazirah separuh berbisik.
Irdina mengerut dahi. "Tak mungkin. GCS dia full score tadi masa Doktor Asrar buat assessment. Pukul empat pagi tadi pun aku check, 15 penuh. Mata buka spontan, boleh ikut arahan, bercakap coherent."
Hazirah menggigit bibir, ragu-ragu. "Tapi... macam ada yang tak kena."
Irdina memandang sahabatnya dengan pandangan bermakna. "Kita assess lain sikit nak? Luar daripada protokol."
Hazirah ternganga kecil, namun kemudian mengangguk laju. "Apa soalan?"
Irdina mengira dengan jari, matanya bersinar nakal. "Kita tanya: kenapa dia masuk ICU. Kita tanya umur dia. Kita tanya... dia kahwin ke belum."
Hazirah membulatkan mata. "Eh, gila ke? Boleh ke macam tu?"
Irdina ketawa kecil, tapi matanya tetap serius. "Kita bukan nak rosakkan patient. Kita nak screen kalau-kalau ada partial retrograde amnesia, kesan daripada sedatif yang lama."
Hazirah menghela nafas. "Baik. Kalau nampak simptom pelik, kita rujuk Doktor Asrar."
Mereka berpandangan, semangat mula membara. Ini bukan sekadar tugas, ini tentang memastikan seorang pesakit tidak terus terperangkap dalam kekeliruan.
Maka, bermulalah misi kecil mereka. Misi menyiasat dengan penuh cermat, tanpa mengganggu emosi pesakit yang baru sahaja kembali ke dunia nyata dari tidur panjangnya.
Bilik ICU itu kekal dengan suasana dingin, sunyi kecuali deruan ventilator dan hembusan lembut alat pernafasan. Bau antiseptik menyengat halus ke rongga hidung. Lampu putih yang suram membias pada lantai berkilat, memantulkan bayang Eman yang menyandar lemah di atas katil khas ICU.
Airis duduk di sebelah katil Eman, membetulkan tudungnya dengan gerakan perlahan. Senyuman terukir di bibirnya.. bukan senyuman kasih, tetapi senyuman kemenangan. Pandangannya tajam, penuh bangga memerhati Eman yang kini ‘miliknya’.
Airis berbicara tentang itu dan ini, tentang masa depan mereka yang kononnya akan bahagia. Senyum Eman hanya hadir sekilas, hambar. Ada rasa yang tidak mampu dibendung, rasa yang berlapis antara tanggungjawab dan keengganan. Dia tersenyum tapi dalam terpaksa dan untuk Airis, senyuman itu membuatkan dia terbuai dengan impian dan angannya.
Di dasar hati Eman, dia tahu. Hubungan ini bukan berakar dari hatinya sendiri. Ia tumbuh dari hasrat keluarga, dari suara lembut emaknya yang memintanya untuk ‘mencuba’ membina hidup baru bersama Airis.
"Ikhlaskan hati kamu, Along. Kamu akan belajar sayangkan dia nanti," terngiang pesan Hajah Sufiah.
Belajar... ya. Tapi kenapa hatinya terasa kosong?
Eman menghela nafas panjang, cuba mengumpul kekuatan untuk membina satu babak hidup yang dia sendiri tidak pasti mampu dihayati sepenuhnya
Dua jururawat, berpakaian seragam hijau lembut dengan tag nama yang tergantung kemas di dada — Irdina dan Hazirah menghampirinya dengan clipboard dan ‘tablet’ di tangan. Irdina, seorang jururawat berwajah lembut dalam usia lewat dua puluhan, mengekori Hazirah yang sedikit lebih senior, berusia awal tiga puluh, berwajah tegas namun tetap menjaga budi bicara.
Airis sempat menjeling ke arah mereka. Sinis. Pandangannya menjelajah dari wajah ke hujung kaki jururawat itu dengan keangkuhan yang sukar disembunyikan.
Baginya, mereka hanya jururawat biasa, bukan setaraf dengan dirinya yang bakal jadi menantu keluarga berharta dan bersuamikan seorang guru. Bibirnya sedikit mencebik, hampir tidak peduli pada kehadiran mereka.
"Assalamualaikum, Encik Eman," sapa Hazirah ramah, namun nada profesional tetap terjaga.
Eman mengangguk perlahan, senyuman tawarnya masih terpaksa. Airis menggenggam tangan Eman seolah menunjukkan kepada jururawat itu siapa yang kini 'berkuasa' di sisi lelaki itu.
Namun lelaki yang tahu batas itu, cepat-cepat menarik lembut tangannya sekaligus... air muka Airis berubah. Malu!
"Kami nak buat sedikit penilaian lanjut ya, Encik Eman. Ini prosedur biasa selepas pesakit sedar dari sedasi," ujar Irdina lembut tanpa menghiraukan perubahan wajah Airis.
Hazirah membuka lembaran soalan. Suaranya jelas, tenang.
"Encik Eman, boleh beritahu umur encik sekarang?"
Eman mengerutkan dahi, memandang jauh ke hadapan, seakan mengorek ingatan dari lubuk yang samar.
"Dua puluh... lapan..." jawabnya akhirnya, dengan suara parau yang masih serak. Anak tekaknya masih terasa sakit.
Irdina dan Hazirah bertukar pandang sekilas. Rekod dalam sistem jelas mencatat umur Eman adalah 31 tahun.
Airis di sisi Eman hanya menguntumkan senyum tipis, seolah-olah menahan tawa. Dalam hatinya, dia puas. Eman kini seolah-olah bergantung penuh pada dirinya dan lebih penting, tidak mengingati sesiapa selain dirinya.
Hazirah menulis cepat dan menyambung soalan.
"Encik Eman, ingat tak kenapa encik dimasukkan ke hospital?" Sekali lagi dahi Eman berkerut. Ada kegusaran yang bertapak di wajahnya.
"Kemalangan motor..." jawabnya perlahan.
Jururawat muda itu hampir melepaskan keluhan kecil. Ini tak kena berdasarkan rekod, Eman mengalami serangan renal colic akibat batu karang yang tersekat di ureter, dan dirancang untuk prosedur ureteroscopy.
Hazirah menahan keresahan dalam dirinya. Prosedur menilai fungsi kognitif pesakit selepas sedasi memang kadangkala mengelirukan, tetapi respons yang salah terhadap soalan-soalan tersebut mengundang lebih banyak kebimbangan.
Irdina, dengan sopan, mengajukan soalan terakhir.
"Encik Eman... encik dah kahwin ke belum?"
Suasana tiba-tiba menjadi tegang.
Eman diam. Nafasnya seolah tertahan. Matanya memandang ke arah Airis... wajah yang tenang tetapi penuh desakan halus.
Airis membalas pandangan itu dengan anggukan perlahan yang sukar ditafsirkan. Seolah memberi isyarat kepada Eman bahawa jawab sahajalah mengikut kehendaknya.
Yakin sekali dia yang Eman lansung tidak mengingati apa-apa.
Namun lidah Eman seakan-akan menjadi berat. Hatinya bergetar, ada sesuatu yang menjerit dari dalam dirinya... sesuatu yang belum dapat dia capai dengan sedarnya.
Suasana beku.
Jururawat-jururawat itu menunggu dengan penuh debaran, dan di ruang itu, di bawah cahaya putih ICU yang suram, sesuatu yang tidak kelihatan mula berputik...iaitu satu rahsia yang belum terungkai.
DI DALAM bilik wad Kenanga yang sederhana besar itu, suasana sunyi membungkus erat setiap inci ruang. Hanya bunyi halus pendingin hawa dan hembusan nafas perlahan Ameena yang mendayu dalam lena separa sedarnya.
Kartini memeluk erat tubuh kurus puteri tunggalnya itu, seolah mahu menyalurkan seluruh kekuatan yang tinggal ke dalam jasad yang terasa begitu rapuh. Hatinya menangis diam-diam, memandang wajah Ameena yang kosong... kosong sekosong langit kelabu di luar tingkap sana.
Tangisan Ameena sudah lama terhenti. Kini hanya ada diam.
Sunyi yang memekakkan jiwa. Wajahnya seputih awan yang hilang warna.
Pintu bilik terbuka perlahan. Ameer dan isterinya, Qadeeja, melangkah masuk, dan serentak itu dada Ameer terasa dihimpit rasa yang sukar dijelaskan. Seolah-olah seluruh udara di dalam bilik itu berubah berat.
Pandangan Ameer jatuh pada wajah kakaknya. Wajah kosong itu pernah dia lihat dulu,
dalam fragmen kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi.
Memori itu menyerbu tanpa amaran.
Hari itu, langit juga mendung seperti hari ini.
Ameena berdiri di ruang tamu villa besar mereka, tubuh kecil itu menggigil, berhadapan dengan Tuan Zulkifli yang sedang memarahinya dengan suara keras. Hanya kerana dia gagal kertas ujian percubaan Fizik.
"Kalau rasa malas nak belajar, boleh keluar dari rumah ini! Jangan susahkan kami! Cari duit sendiri!"
Teriakan itu bagaikan belati menembusi jiwa Ameer yang bersembunyi di balik dinding, menyaksikan segalanya. Dia ingat jelas.. mata Ameena berkaca.
Tapi bukan air mata yang jatuh, hanya kaca bening yang membeku di tubir, menahan luka.
Dan lebih menyakitkan... bibir Ameena tetap terkunci.
Wajahnya kosong. Tiada rengekan, tiada rayuan. Seolah haknya telah direnggut kejam.
Hanya diam... diam yang lebih pedih dari seribu jeritan.
Ameer tahu, saat itu, sesuatu dalam diri kakaknya telah patah.
Dia sendiri keliru ketika itu haruskah dia menyalahkan Ameena kerana gagal memenuhi harapan ayah,
atau haruskah dia marah pada ayah mereka yang tidak memahami?
Kini, di hadapannya, wajah yang sama kembali. Wajah Ameena yang kosong.
Seolah-olah dunia telah memadamkan semua rasa dari jiwa kakaknya.
Ameer melangkah perlahan ke sisi katil. Qadeeja di belakangnya, menggenggam erat tangan suaminya.
Air matanya bergenang, tetapi dia tahan. Tidak terduga olehnya, kedatangannya ke bumi Malaysia kali ini disambut tangisan duka. Dalam hati kecilnya, Ameer berbisik,
"KakChik... jangan pergi jauh lagi. Aku ada di sini."
Ameer perlahan-lahan duduk di sisi katil, jari-jarinya yang hangat mengusap perlahan bahu kakaknya.
Dia tunduk, membisikkan kata-kata lembut di telinga Ameena..
"KakChik... Aku ada di sini..."
"Kau tahu kan? Kau boleh kongsikan apa saja dengan aku..."
Bisikan itu seolah-olah hanyut ke udara.
Ameena tetap diam. Tetap kaku.
Seperti patung porselin yang retak, tapi masih menegakkan diri.
Wajahnya tiada riak.
Matanya kosong.. seolah-olah seluruh dunia telah tercabut dari hatinya.
Apa yang dilihatnya tadi... bukan sekadar menghancurkan hatinya tapi
ia menghempas seluruh jiwanya ke dasar yang paling gelap.
Ameer menahan rasa kecewa yang mengetuk dadanya. Adakah dia sudah tidak lagi dianggap pelindung kepada KakChik yang pernah berlari mencarinya bila disakiti? Adakah tembok kesakitan itu kini terlalu tinggi untuk dia daki?
Dia menggenggam jemari kurus itu, menahan sebak.
Pintu bilik terbuka perlahan. Hajah Sufiah dan Cikgu Hasyim muncul.Wajah mereka sarat kerisauan.
Cikgu Hasyim terus mendapatkan Tuan Zulkifli yang bersandar di dinding, yang sedang berteka teki dengan hatinya. Huluran tangan Cikgu Hasyim bersambut dengan anggukan dan senyum separuh.
Hatinya masih bertanya...
Bukankah Eman sudah sedar?
Kenapa Ameena tetap di sini, tidak mahu melawat suaminya?
Hajah Sufiah sudah menerpa ke arah katil, memeluk Ameena erat-erat
seperti seorang ibu yang mahu menyatukan kembali serpihan hati anaknya yang pecah berderai.
"KakLong... tetap menantu Mak..."
bisik Hajah Sufiah, penuh ketulusan seorang ibu.
"Jangan susah hati, sayang. Along akan ingat KakLong. Sekejap saja ya... kita doa sama-sama. Mak tahu... dia sayang sangat dekat awak..."
"Airis tu lansung tak ada dalam hati dia. Maafkan Eman, ya sayang..."
Air mata Hajah Sufiah mengalir, membasahi pipi Ameena yang tetap diam, tetap membatu.
Kartini yang mendengar itu terkejut.
Pandangannya beralih kepada Tuan Zulkifli dan kemudian kepada Cikgu Hasyim, mencari jawapan.
Cikgu Hasyim menghela nafas berat. Dengan wajah yang keruh, dia mengusap wajahnya yang berkerut sebelum mengangkat wajah, menatap mereka satu persatu.
"Saya kena jelaskan sesuatu..." suaranya serak menahan beban kata-kata.
"Eman... sekarang ni... mengalami sejenis kehilangan ingatan sementara, kesan daripada ubatan sedatif yang digunakan semasa rawatan ICU. Katanya kerana terlalu lama atau sistem badan Eman tidak dapat terima."
Semua yang ada terdiam.
Ameer mengetap rahang, sukar mempercayai apa yang didengarnya.
"Eman ada alergik terhadap ubat sedatif waktu di bilik bedah. Jadi, ubat yang digunakan untuk tidurkan dia hari tu... sedatif jenis lain dan mungkin lebih kuat untuk pastikan dia stabil masa prosedur kritikal itu. Tapi kesan sampingannya — dia mengalami hilang ingatan sementara tapi tak semua... hanya separuh."
Cikgu Hasyim menghela nafas perlahan, berat.
"Kita tak tahu berapa lama dia akan begini. Bergantung pada diri dia sendiri. Ada pesakit yang pulih dalam beberapa hari... ada yang mengambil minggu... bahkan ada yang berbulan. Tapi... yang penting, sekarang, kita tak boleh paksa dia ingat. Kita tak boleh membantah atau melawan apa yang dia fikir dia tahu. Kalau kita paksa, kita mungkin mencetuskan keadaan di mana pesakit akan jadi lebih keliru dan mungkin bertindak agresif atau menarik diri lebih jauh."
"Doktor Asrar dah rujuk kes ni kepada Jabatan Psikiatri dan Neurologi untuk penilaian dan rawatan susulan. Mereka akan pantau rapat dari aspek kognitif dan emosi dia."
Kata-kata itu bagaikan kabus tebal menyelubungi bilik itu. Ameer memandang wajah kakaknya yang masih diam. Mungkin sedang menghadam kata-kata ayah mertuanya.
Hatimu terlalu lelah, KakChik...
Dan kini, orang yang kau pertaruhkan seluruh cinta dan doamu..
tidak lagi mengingati kau...
Ameer memejam mata, menahan air mata yang hampir gugur.
"Aku janji, KakChik... aku tetap ada... dan aku percaya Dalam hati Abang Eman hanya ada kau."
Share this novel



