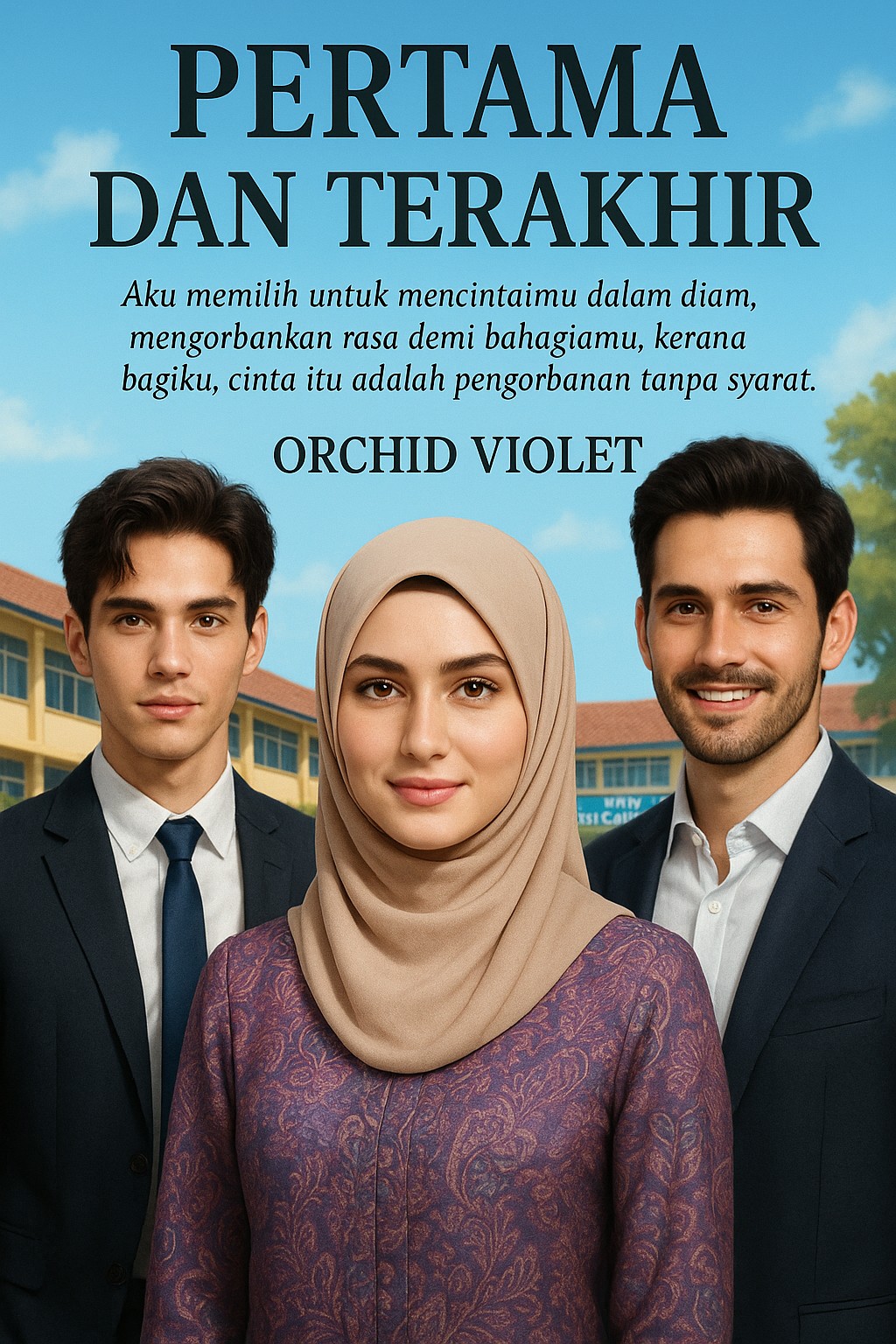
BAB 40 : KEMBALI BUKAN UNTUKKU
 Series
Series
 52946
52946
EMAN berdiri sendirian di tengah dewan yang berbalut cahaya suram. Wangian bunga segar membelai deria, namun tiada kehangatan di dalam hatinya.
Di hadapannya, Ameena kekasih hatinya yang tidak pernah dia miliki.. berdiri ayu berselubung gaun putih, disunting tangan lelaki lain. Ya...Isa.
Mereka tersenyum di atas pelamin indah. Bunga-bunga sakura berguguran perlahan, seperti air mata langit merestui sebuah takdir.
Eman mengorak langkah perlahan, seakan setiap tapak mengukir luka dalam jiwanya.
Di hadapan Ameena, dia mengukir senyum hambar — senyuman orang yang telah lama kalah dalam perang hatinya.
Dengan suara yang hampir pecah, dia membisik,
"Tahniah, Ameena... Semoga awak bahagia... selamanya."
Ameena hanya membalas dengan senyum, seolah-olah dunia ini tidak pernah menyaksikan kisah cinta sunyi yang terpendam dihatinya. Biarlah jadi rahsia pecinta sepi sepertinya.
Dalam hati, Eman mengaku,
"Aku lelaki pengecut.
Aku yang melepaskan tanpa berjuang.
Aku yang berdiri di belakang, membiarkan kau bahagia dalam pelukan orang lain.
Selayaknya kau bersama Isa, bukan aku...
Semoga kau bahagia, walau tanpa aku di sisi."
Perlahan-lahan, bayangan itu memudar, diseret kabus yang dingin.
Dan Eman... membuka matanya.
Bip... Bip... Bip...
Bunyi mesin ventilator menderu di sisi. Namun rentaknya tidak lagi seiring dengan nafasnya — seperti jiwanya yang berkelana mencari sesuatu yang hilang.
Eman merasa sesak, dadanya berombak mahu melawan tiub pernafasan yang masih menahan suara dan nafasnya.Kelopak matanya memberat, tubuhnya memberontak. Pintu ICU terkuak. Langkah tergesa beberapa orang doktor masuk.
Dr. Asrar meneliti skrin ventilator dan cardiac monitor. Matanya berkaca sedikit, faham keresahan yang terpancar di wajah pesakitnya yang separa sedar.
"Dr. Amira, tengok ni. Respiratory rate dia dengan PEEP tak synchronize.
Pressure terlalu tinggi. Dia cuba nafas sendiri, tapi mesin masih over-assist," kata Dr. Asrar perlahan, hampir berbisik kepada doktor muda itu dan jururawat yang mengiringi.
Dr. Amira mengangguk cemas, tangan bersedia di peralatan kecemasan.
"Kita kena turunkan setting ventilator tapi with close monitoring. Biarkan dia take over sendiri. Kita monitor oxigenation dan tidal volume dia. Kalau stabil... petang ni kita boleh extubate," sambung Dr. Asrar.
Sementara itu, Eman cuba memberi isyarat dengan tangan yang lemah. Matanya basah. Nafasnya parah dihalang tiub. Dr. Amira cepat-cepat menghampiri, cuba menenangkan.
"Encik Eman... relax, ya? Tahan sikit lagi. Petang nanti insyaAllah kami akan buka tiub tu," suara lembut itu seperti bayu, membelai hati yang sedang tercarik.
Eman menutup matanya. Air mata halus meluncur jatuh di sisi pipinya. Dalam hatinya, dia berbisik kepada Tuhan...
"Ya Allah... izinkan aku hidup.
Aku mahu melihat senyuman Ameena sekali lagi... dengan mataku sendiri."
Dan ventilator itu, masih berbunyi.. seolah-olah turut berdoa bersama Eman.
DI ANTARA kelam dan terang, Ameena melihat seseorang datang menghampiri.
Langkahnya berat, perlahan, seolah-olah dipikul ribuan beban dunia.
Eman.
Tapi Eman yang ini... bukan seperti yang Ameena kenal. Tiada senyum yang selalu menyalakan pagi-pagi mereka. Tiada sinar di mata yang biasa membuatkan dunia terasa baik-baik saja.
Hanya wajah hampa. Wajah seorang lelaki yang sudah kehilangan segala.
Eman berdiri beberapa langkah di hadapannya. Mereka saling memandang tanpa sepatah kata.
Tiada ucapan, tiada salam, tiada genggaman tangan yang dirindui.
Dan perlahan-lahan, tubuh Eman memudar. Langkahnya mengundur, semakin jauh... semakin jauh... Hingga akhirnya, yang tinggal hanyalah bayang yang tak dapat digapai.
"Abang!" jerit Ameena dalam mimpinya, suaranya serak dibawa angin.
Tiba-tiba, di hadapan Ameena, muncul sebatang batu nisan.
Putih bersih. Diukir kemas di atasnya satu nama...
Eman Al Hadi Bin Hashim.
Dada Ameena bagai dihentak sesuatu yang tidak terlihat.Luluh, remuk, ranap. Dia terduduk di tanah mimpi itu, meraung sekuat hati, menangis sehingga dunia bergetar dalam air matanya.
"Jangan pergi, Eman... jangan tinggal saya..."
"Saya perlukan awak..."
Tangis itu begitu dalam, mengoyakkan lapisan demi lapisan hatinya, hingga akhirnya.. Ameena terjaga.
Tangis dari mimpi bertukar menjadi jeritan.
Tangisan yang liar, tidak terkawal, penuh hiba dan ketakutan.
"ABANG!!!" jerit Ameena, suaranya nyaring menembusi segenap ruang wad. Tubuhnya menggigil, matanya liar mencari sesuatu yang tiada.
Kartini, yang tidur di kerusi, tersentak panik. Dia segera menekan loceng kecemasan.
"Ameena! Sabar, Kakchik! Kakak!" Kartini cuba mendakap, namun Ameena meronta hebat, seolah-olah mahu lari dari dunia nyata.
Jururawat datang berlari, cuba menenangkan. Tetapi tangisan Ameena makin menjadi-jadi.
Suara seraknya bergema, menyayatkan hati sesiapa sahaja yang mendengarnya.
"Tak mahu! Tak mahu! Eman! Jangan tinggalkan saya!"
"EMAN!!!"
Seorang jururawat cuba memegang bahunya, namun Ameena menolak keras, hampir jatuh dari katil. Tubuhnya basah dengan peluh dingin. Matanya berkaca, kosong, penuh luka.
Seorang doktor muda, Dr. Farhana, segera tiba bersama sekotak ubat penenang.
"Dia diserang acute grief reaction," bisik doktor itu pada jururawat. "Ada trauma mimpi mungkin."
Dengan penuh cermat, doktor menyuntik ubat penenang kepada Ameena.
"Kakchik... tenang ya, sayang... tenang," suara Kartini merintih, tangannya menggenggam tangan Ameena yang menggigil.
Beberapa minit berlalu, tangisan dan jeritannya mereda perlahan-lahan.
Tangisnya bertukar menjadi sedu perlahan. Tubuhnya akhirnya tenang, tenggelam dalam tidur yang dipaksa ubat.
Tapi air mata itu... masih mengalir, membasahi pipinya seperti hujan yang tidak mampu dihentikan sesiapa.
Di sudut bilik, Kartini menutup wajahnya, menangis dalam diam.
RUMAH itu terasa semakin sunyi, sepi... seolah-olah menolak kehadirannya.
Airis berdiri lama di tepi pintu, memandang ke seluruh ruang yang pernah dia anggap sebagai permulaan kebahagiaannya. Namun realitinya? Hanya kehinaan yang dia telan diam-diam.
Eman... lelaki itu tidak pernah mencintainya.
Sejak mula lagi, tatkala dia cuba menghampiri, tatkala dia mengukir senyum seramah mungkin,
Eman hanya membalas dengan tatapan kosong, dingin, jauh, dan penuh kekosongan.
Tidak pernah sekali pun dia melihat Eman melemparkan senyum yang tulus kepadanya. Tidak ada lembut di mata itu. Tidak ada kasih di senyum itu.
Dan kini, apabila Eman terbaring antara hidup dan mati... Airis sedar, tiada apa pun yang dia miliki sebenarnya.
Hatinya berdetik marah.Tajam. Menyakitkan.
‘Biar dia mati.
Biar Ameena jadi gila kerana kehilangan dia.
Kalau aku tak dapat Eman, tak ada sesiapa pun berhak memilikinya.’
Dia mengetap bibir, menahan rasa kecewa yang membuak.
Tidak ada lagi makna untuk dia bertahan di sini. Tidak guna lagi duduk di rumah ini, menghirup udara yang penuh dengan bayang-bayang Ameena.
Segala 'rancangan' yang dibina dengan penuh harapan, kini hanya tinggal debu. Dia mahu pergi.
Pindah ke rumah sewa kecil berhampiran sekolah. Menjauhkan diri.
Dan kemudian, akan mohon pertukaran ke sekolah lain. SMK Seri Cahaya bukan lagi tempat untuknya. Segala-galanya sudah rosak.
Airis menekan kelopak matanya yang panas. Bukan kerana sedih, tetapi kerana marah. Marah kepada takdir yang seakan-akan mempermainkannya.
Dalam kepala, terngiang kembali suara ibunya, Saleha.
"Sabar, Airis. Orang berusaha, akhirnya menang. Eman tu harta besar. Dia anak orang baik-baik, terpelajar, ada masa depan cerah. Kau kena sabar."
Saleha..wanita yang tamak pada harta dan kemewahan. selalu menasihati anaknya supaya menang dalam apa jua cara. Sabar bukan untuk cinta. Sabar untuk kuasa dan kedudukan.
Tetapi sekarang?Apa lagi yang mahu direbut?
Semua sudah berakhir, Mak.
Semua sudah hancur.
Airis mengangkat begnya. Langkahnya perlahan, tetapi hatinya penuh dendam yang dalam.
Sebelum keluar, dia sempat menjeling ke arah rak kecil yang mempamerkan gambar-gambar lama Eman dan Ameena. Gambar-gambar yang dipenuhi tawa, bahagia, dan kasih sejati.
Airis mengukir senyuman sinis. "Tak ada siapa boleh menang bila aku kalah."
Dengan satu hela nafas, dia melangkah keluar, membiarkan pintu terkuak perlahan..
seolah-olah rumah itu sendiri melepaskan segala bayang gelap yang selama ini bertapak di dalamnya.
SENJA memeluk bumi Kuala Terengganu, langit berbalam jingga kemerahan, seperti lukisan yang Tuhan lukis dengan penuh rahsia.
Feraz, Yaser, dan Zeyad akhirnya sampai. Wajah masing-masing lesu dek perjalanan panjang dari Pahang. Namun semangat mereka menyala, menahan bimbang yang membuak sejak menerima panggilan dari Abah mereka, Cikgu Hasyim.
Di koridor yang suram, mereka bertembung dengan Aryan, Arief, dan Ameer — adik-beradik Ameena. Pelukan menjadi bahasa rindu yang tidak perlu diterjemahkan.
"Feraz... Yaser... Zeyad... Alhamdulillah, selamat sampai," sambut Ameer, mengeratkan dakapan adik-adik ipar kakaknya. Masing-masing saling bersalaman dan berpelukan. Hampir setahun mereka tidak bersua muka.
Belum sempat berbicara panjang, muncul kelibat yang mereka rindukan.
Cikgu Hasyim.
Langkahnya berat, tapi matanya bercahaya. Ada sesuatu dalam pandangannya yang membuatkan tiga beradik itu menahan nafas.
“Abah...” suara Feraz bergetar.
Cikgu Hasyim menarik nafas panjang, lalu senyum — walau senyum itu dibalut linangan air mata.
“Along... Along dah sedar. Alhamdulillah... Allah bagi kita peluang lagi...”
Suaranya serak menahan haru.
Tiga beradik itu seolah-olah tidak percaya apa yang mereka dengar. Serentak, tanpa arahan, mereka sujud syukur di atas lantai koridor hospital, tangisan mereka meledak bersama ucapan penuh syukur kepada Ilahi.
Beberapa orang yang lalu berhenti seketika, mengelap air mata melihat keikhlasan kasih adik-adik yang berpelukan tanpa tahu apa lakaran ceritanya.
"Abah... Kaklong tahu tak Along dah sedar?" tanya Yaser, matanya masih merah.
Aryan menggeleng perlahan. "Belum... KakChik masih terlalu lemah. Tiga malam dia berjaga... Sekarang KakChik rehat di Wad Kenanga."
“Boleh melawat sekarang?” tanya Zeyad, suaranya sarat dengan kerisauan. Di sisinya, Yaser dan Feraz turut berkongsi resah yang sama. Wajah-wajah mereka membenarkan kegusaran yang tak mampu disembunyikan.
Aryan tersenyum nipis.. masih sarat dengan gusar. Kemudian dia mengangguk perlahan.
Tanpa berlengah, mereka bergerak menuju ke Wad Kenanga. Langkah mereka penuh debar, penuh rindu, penuh doa.
Dalam bilik itu, Ameena tidur lena. Wajahnya pucat, namun tetap tenang. Nafasnya perlahan, seperti anak kecil yang akhirnya terlelap setelah keletihan bertarung dengan badai.
Zeyad, si bongsu yang paling manja dengan Ameena, mendekat perlahan. Dia duduk di tepi katil, menggenggam jari jemari Ameena yang dingin.
"Kaklong..." bisiknya, suara menggeletar.
"Along dah bangun, Kaklong... Tolong kuat, ya? Bangun... Senyum untuk Along."
Butir air mata gugur satu-satu di pipinya.
Feraz dan Yaser berdiri memandang, menahan rasa.
Bibir mereka terkunci, hanya doa yang tidak henti-henti bergema dalam hati, mendoakan agar Kaklong kesayangan mereka segera bangun membawa senyuman kembali ke dunia yang kian suram ini.
Di luar tingkap, senja beransur kelam.
Dan di dalam bilik, harapan terus bergantung di langit-langit doa.
Suasana di hadapan bilik ICU malam itu masih tegang, namun sedikit lega bila kelibat Doktor Asrar muncul, membawa sinar harapan.
Dengan langkah tenang, beliau mendekati Cikgu Hasyim dan ahli keluarga yang berkumpul.
Senyumannya tidak pernah berubah.. tenang, memujuk hati-hati yang gelisah.
"Assalamualaikum," sapa Doktor Asrar.
"Waalaikumussalam," balas Cikgu Hasyim, suaranya sedikit bergetar.
Doktor Asrar menggenggam tangan tua itu, seolah mahu memindahkan kekuatan.
"Alhamdulillah, Encik Eman menunjukkan tanda-tanda positif sejak sedar tengah hari tadi," ujarnya perlahan, namun penuh keyakinan. "Paras oksigen kini stabil tanpa perlu bantuan tinggi dari ventilator, tekanan darah konsisten, dan refleks pernafasan juga kembali aktif."
Mereka yang mendengar, menarik nafas lega.
"Lalu, apa langkah seterusnya, Doktor?" tanya Aryan, cuba menyusun debar di dadanya.
Doktor Asrar tersenyum kecil, menenangkan.
"Sekarang kami akan mulakan proses extubation, iaitu mengeluarkan tiub endotrakeal dari saluran pernafasan Encik Eman."
Beliau menyambung, menerangkan lebih jelas.
"Prosedur extubation ni, kami lakukan apabila pesakit menunjukkan keupayaan bernafas sendiri tanpa sokongan mesin. Kami pastikan bacaan arterial blood gases stabil, paras oksigen memadai, tahap karbon dioksida normal, dan pesakit menunjukkan usaha pernafasan sendiri."
Semua mendengar penuh tekun. Feraz bertanya perlahan, "Kalau sudah extubate, selamat ke?"
Doktor Asrar mengangguk yakin.
"Insya-Allah. Tapi selepas extubation, pemantauan rapi diperlukan. Kami akan pastikan Encik Eman boleh mengekalkan kadar pernafasan yang stabil, tidak sesak nafas, tidak memerlukan oksigen tambahan secara agresif, dan suara juga diperhatikan jika ada perubahan. Kadangkala, risiko seperti bengkak tekak, atau kegagalan bernafas boleh berlaku. Tapi peluang beliau sangat cerah."
Yaser pula menyoal, "Boleh kami masuk tengok?"
Doktor Asrar menggeleng perlahan.
"Maafkan kami. Prosedur ini memerlukan fokus penuh dan kawasan steril. Tiada lawatan dibenarkan malam ini. Insya-Allah esok pagi, waktu melawat ICU, Encik Eman akan lebih stabil."
Mereka semua patuh, walau jauh di sudut hati terasa hampa. Namun mereka tahu keselamatan Along mereka lebih utama daripada keinginan sendiri.
"Teruskan doa ya," kata Doktor Asrar sambil tersenyum sekali lagi sebelum melangkah masuk ke bilik ICU.
Setelah Doktor Asrar menghilang ke dalam ruang ICU, keluarga Cikgu Hasyim masih tegak berdiri di luar, wajah masing-masing terpamer letih yang tak mampu disembunyikan.
Melihat keadaan itu, Aryan menghampiri ayahnya, Tuan Zulkifli, lalu berbicara perlahan,
"Ayah... saya rasa lebih baik kita ajak keluarga Abang Eman semua bermalam di rumah. Tak elok kalau semua terus bertahan macam ni."
Tuan Zulkifli mengangguk perlahan. Sebagai ayah, dia juga tahu betapa beratnya hati Cikgu Hasyim dan Hajah Sufiah waktu ini.
Tuan Zulkifli melangkah ke depan, menghampiri sahabat lamanya, Cikgu Hasyim dan isterinya, Hajah Sufiah.
"Cikgu Hasyim.. Hajah Sufiah..," panggil Tuan Zulkifli lembut.
"Baliklah dulu ke rumah kami. Berehat sekejap. Rumah kami rumah kalian juga. Malam ni memang tak dibenarkan melawat. Esok pagi, kita datang semula sama-sama."
Pak Long dan Pak Ngah yang mendengar turut mengangguk, setuju.
Kartini yang dari tadi berdiri diam, menghampiri Hajah Sufiah. Tangannya menggenggam tangan sahabatnya itu.
"Sofi," bisik Kartini dengan suara sarat perasaan, "Tini kena temankan Ameena di sini. Sofi baliklah dulu. Rehat sikit. Saya bimbang awak jatuh sakit pula nanti."
Hajah Sufiah memandang wajah Kartini yang sarat keikhlasan. Mata tuanya berkaca.
"Terima kasih, Tini...," ucap Hajah Sufiah, hampir berbisik, suara bergetar menahan sebak.
"Sofi, kita satu keluarga," ujar Kartini, menenangkan. "Eman tu dah macam anak Tini juga."
Cikgu Hasyim hanya mampu menundukkan kepala, mengusap wajah yang berlapis duka itu.
Satu persatu mereka bersalam, memeluk erat Kartini dan Tuan Zulkifli sebelum berangkat pergi meninggalkan duka yang sudah hampir pergi.
Villa besar yang penuh kenangan, warisan Tuan Zulkifli.. kini menjadi tempat berteduh untuk kasih keluarga yang sedang diuji.
Tuan Zulkifli memandang Kartini penuh kasih. Dan Kartini, dengan langkah tegar, kembali ke sisi puteri sulung yang sedang berjuang, dalam dunia lena. ‘semoga esok ada senyuman di wajah kamu.’
Malam itu, Villa Tuan Zulkifli berdiri sunyi dalam perumahan elit yang damai, berteman cahaya lampu jalan yang suram dan angin malam yang dingin.
Dari luar, bangunan villa itu kelihatan megah dengan rekaan moden bertingkat, berdinding kaca dan batu granit berkilau.Namun, melangkah masuk ke dalam, suasana berubah.. lantai kayu walnut yang hangat, lampu gantung klasik menghiasi siling, dan perabot berwarna tanah memberi rasa tenang dan mendamaikan.
Sentuhan moden dan klasik bersatu dalam harmoni yang sederhana, sesuai dengan jiwa pemiliknya yang mementingkan nilai keluarga.
Ruang tamu yang luas hanya diterangi lampu lantai malap, cukup untuk mencipta suasana rehat.
Di satu sudut, beberapa orang berbual perlahan sambil menikmati air teh suam.
Ada yang memilih untuk berbaring seketika di sofa empuk, melepaskan lelah perjalanan jauh dan tekanan perasaan seharian.
Aryan dan Arief duduk bersebelahan di tepi tingkap yang menghadap ke halaman kecil villa.
Cahaya bulan membentuk bayang halus di lantai marmar.
Dalam suasana itu, Aryan membongkok sedikit, mendekat ke telinga Arief sambil menahan senyumnya.Dengan nada perlahan yang hanya mereka berdua sahaja dengar, dia berbisik,
"Aku tengok kau dari tadi tak berani nak angkat muka... si Raihana tu duduk sebelah sikit pun kau gelabah. Kenapa? Takut kantoi ke?"
Arief tersentak kecil, menjeling Aryan dengan muka merah padam.
"Diamlah abang... orang lain dengar kang."
Dia membalas dalam bisik cemas, sambil pura-pura membetulkan bantal di belakang punggungnya.
Aryan terus menahan tawa, melihat telatah adiknya yang jelas resah.
"Relax la, bukannya aku nak jerit satu rumah. Tapi aku tahu... lama dah kau simpan rasa tu kan? Dari zaman Rai baru masuk Uni lagi."
Arief meraup rambutnya dengan tapak tangan, geram dan malu bercampur.
Dia hanya mampu menggeleng perlahan, sambil menjeling ke arah Raihana yang dari jauh sedang berbual dengan Feraz dan Yaser, tidak menyedari langsung gelagat mereka.
Aryan menepuk perlahan belakang Arief,
"Sabar... nanti bila semua dah tenang, abang support kau. Janji jangan takut bayang sendiri sudah." Bisik Aryan, masih dalam nada bergurau kecil tetapi bersahabat.
Mereka sama-sama ketawa kecil, cukup perlahan supaya tidak mengganggu yang lain.
Gelak yang bukan gelak gembira tapi satu kelegaan kecil di tengah lautan resah yang belum surut.
Sedang Aryan masih menahan ketawa di sudut bibir, langkah ringan Raihana mendekat.
Gadis itu, dengan jeans longgar dan blaus putih santun, membawa bersama satu aura tenang yang tersendiri.
Wajahnya polos, senyumannya tidak dibuat-buat.
"Abang Arief..." Sapa Raihana lembut, matanya bersinar mesra.
Arief yang baru sahaja ingin menghela nafas, kaku seketika. Wajahnya merah sepenuhnya, dan jantungnya berdegup bagai baru lepas berlari satu padang.
Aryan di sisi hampir tidak mampu menahan diri lagi.Tangannya menekup mulut sendiri, menahan tawa yang hampir meletus melihat perubahan drastik adiknya itu.
"Eh, kenapa muka abang Arief macam nampak hantu?" Raihana mengusik, suaranya santai dan bersahaja.Satu keningnya terangkat nakal, tapi senyumnya tetap manis.
Arief tergagap kecil,"Tak... tak ada apa-apa."
Dia membetulkan duduknya, berusaha keras untuk kelihatan tenang walaupun jelas gugup.
Aryan akhirnya hanya mampu menggeleng kecil, menyerah kalah pada kecomelan momen itu.
Dia bersandar ke sofa, membiarkan Arief bergelut dengan debaran hatinya sendiri.
Dalam sunyi yang sederhana itu, dalam ruang tamu villa megah yang berbau kayu dan vanila lembut, mereka bertiga berkongsi satu detik kecil. Detik di mana luka dihiasi tawa kecil, dan esok yang penuh harapan perlahan-lahan menampakkan sinarnya
Di luar jendela besar villa, angin malam mengalun dedaunan.
Dan dalam hati masing-masing, mereka tahu... esok, perjuangan sebenar menanti.
Namun buat seketika ini, mereka menghargai detik kecil yang menghangatkan jiwa.
AMEENA melangkah laju, nafasnya hampir tersekat menahan gembira.
Suasana pagi di hospital terasa bagai terang, walau hakikatnya lampu neon masih suram.
Dalam dadanya, debaran dan syukur bertaut erat, mengalunkan doa dalam diam.
"Sikit lagi, Ya Allah... sikit lagi Kau pulangkan dia kepadaku..."
Hatinya bagai bunga yang mekar seribu kelopak.
Air mata yang ditahan-tahan sejak malam tadi, kini bergetar di tubir, menahan luapan syukur yang tak terkata.
"Ya Allah... suamiku..."
Bisik hatinya, langkahnya makin laju, kain kurungnya berkibar lembut menyapu lantai putih.
Sesampai di hadapan pintu ICU, jantung Ameena berdetak bagai dipalu. Dia berhenti sebentar, menarik nafas panjang. Tangannya yang menggigil, perlahan menolak daun pintu kaca yang berat itu.
Dan di situlah...
Dunia Ameena seakan-akan berhenti berputar. Pandangannya jatuh pada satu figura yang amat dikenalinya.
Di sisi katil Eman, seorang wanita muda berdiri, tubuh ramping itu membongkok sedikit, menyuakan straw ke bibir lelaki itu.
Ada senyuman di wajahnya.. bukan sekadar mesra, tapi penuh dengan rasa kemenangan, sinis, dan menguasai.
Ameena berdiri membatu. Bagaikan bumi tempat dia berpijak terbelah dua.
Eman yang baru saja sedar sepenuhnya, menoleh perlahan.
Saat matanya bertemu mata Ameena, Eman ukirkan senyum lemah, penuh kerinduan yang tersembunyi.
Namun dalam hati Eman, ada sesuatu yang mengusik.
Ada duka yang terpancar di wajah Ameena.. duka yang tidak dia mengerti.
Kenapa? Kenapa Ameena kelihatan begitu hiba? Mana Isa? Mana suaminya?
Eman mengerut kening perlahan. Suatu rasa lain meledak dalam dadanya.
Suatu jeritan senyap..
"Bukan itu yang aku mahu lihat..." tapi dia sendiri tidak mengerti dari mana datangnya rasa itu.
Dengan suara serak, Eman cuba mengukir kekuatan.
"Cikgu Ameena..."Dia memanggil perlahan, hampir berbisik. Terlalu lama dia mendambakan wajah itu. Tetapi kenapa kini, pertemuan ini terasa... retak?
Dia berpaling pada gadis di sisinya. Dengan nafas perlahan, dia berkata,
"Kenalkan... ini tunang saya, Airis."
Airis tersenyum.. sebuah senyuman tipis yang tajam, menusuk ke jantung sesiapa yang melihat. Matanya tidak lagi seramah tadi... ada nada menang yang jelas terpancar. Ingatannya kembali kepada waktu dia sampai tadi.
Airis datang seawal pagi tadi, setelah menerima panggilan daripada Saleha, ibunya.
Saleha yang licik, mengatur langkah, menggunakan pengaruhnya untuk mendekati keluarga Eman ketika mereka dalam keadaan paling rapuh.
Sebaik sahaja doktor mengesahkan Eman stabil dan sedar, Airis, dengan penuh yakin menuju ke arah Eman. Melihatkan senyuman pada wajah Eman yang menjurus ke arahnya.. membuatkan dia merasa ada harapan.
Dalam keadaan Eman yang keliru dan masih di bawah pengaruh sedatif ringan, Airis mengambil tempat di sisi lelaki itu, memainkan peranan yang tidak pernah dia miliki. Dan bertambah terkejut apabila Eman memperkenalkan Airis sebagai tunangnya kepada jururawat di situ.
Dan di situlah dia berada sekarang.. berdiri di tempat yang tidak layak untuknya, menghulurkan straw, mengukir senyuman seolah dunia sudah berpihak kepadanya.
Ameena mengerdipkan mata, menahan air mata daripada tumpah.
Senyumannya mati perlahan-lahan. Hatinya luluh dan keliru. Namun dia hanya diam, berdiri di situ.. menjadi saksi kepada kebisuan takdir yang membelit mereka berdua.
Langkah Ameena terhuyung-hayang saat dia meninggalkan ruang ICU.
Segala kekuatan yang tadi membara kini seakan dicabut perlahan-lahan, meninggalkan tubuhnya kosong, ringan dan hampir rebah.
Tangannya sempat berpaut pada dinding koridor. Kaki terasa bagai tidak berpijak di bumi nyata.
“Kenapa, Ya Allah... kenapa begini jalan cerita kami?”
Matanya kabur oleh genangan air mata yang enggan berhenti. Setiap hela nafas bagai menikam dada sendiri.
Dari jauh, Hajah Sufiah yang sedang duduk menunggu, terpandang wajah menantunya yang pucat lesi. Tanpa berlengah, dia bergegas menghampiri.
"Ameena!" Suara Hajah Sufiah sarat panik.
Kartini yang baru keluar dari lif juga bergegas, hatinya terkejut melihat wajah Anaknya yang seakan roh sudah tercabut separuh dari tubuh.
Mereka berdua memegang lengan Ameena, memapahnya perlahan ke kerusi panjang di hujung koridor.
Ameena terjelepuk duduk, tangan menutup muka. Tubuhnya teresak kecil, mematahkan hati semua yang melihat.
"Kenapa, sayang? Apa jadi? Cerita pada Mak..." pujuk Hajah Sufiah, membelai kepala menantu perempuannya penuh kasih.
Ameena hanya menggeleng, tidak mampu bersuara. Tangisnya pecah, dalam diam, menyesakkan ruang yang sudah berat dengan pilu.
Kartini menekup mulut, menahan sebak. Dia tahu pasti ada sesuatu yang lebih parah daripada apa yang mereka semua sangka.
Sementara itu, di dalam dadanya, Ameena berperang dengan rasa.. rasa hancur, rasa kehilangan, rasa dikhianati oleh harapan yang dia pupuk selama ini.
Semua rasa itu menghempasnya serentak, tanpa belas.
'Aku salah... aku terlalu percaya pada takdir bahagia. Sedangkan dia kembali bukan untukku..'
Jauh dalam sudut hatinya, satu suara bergema:
"Sabar, Ameena... ini belum penamat cerita kamu..."
Share this novel



