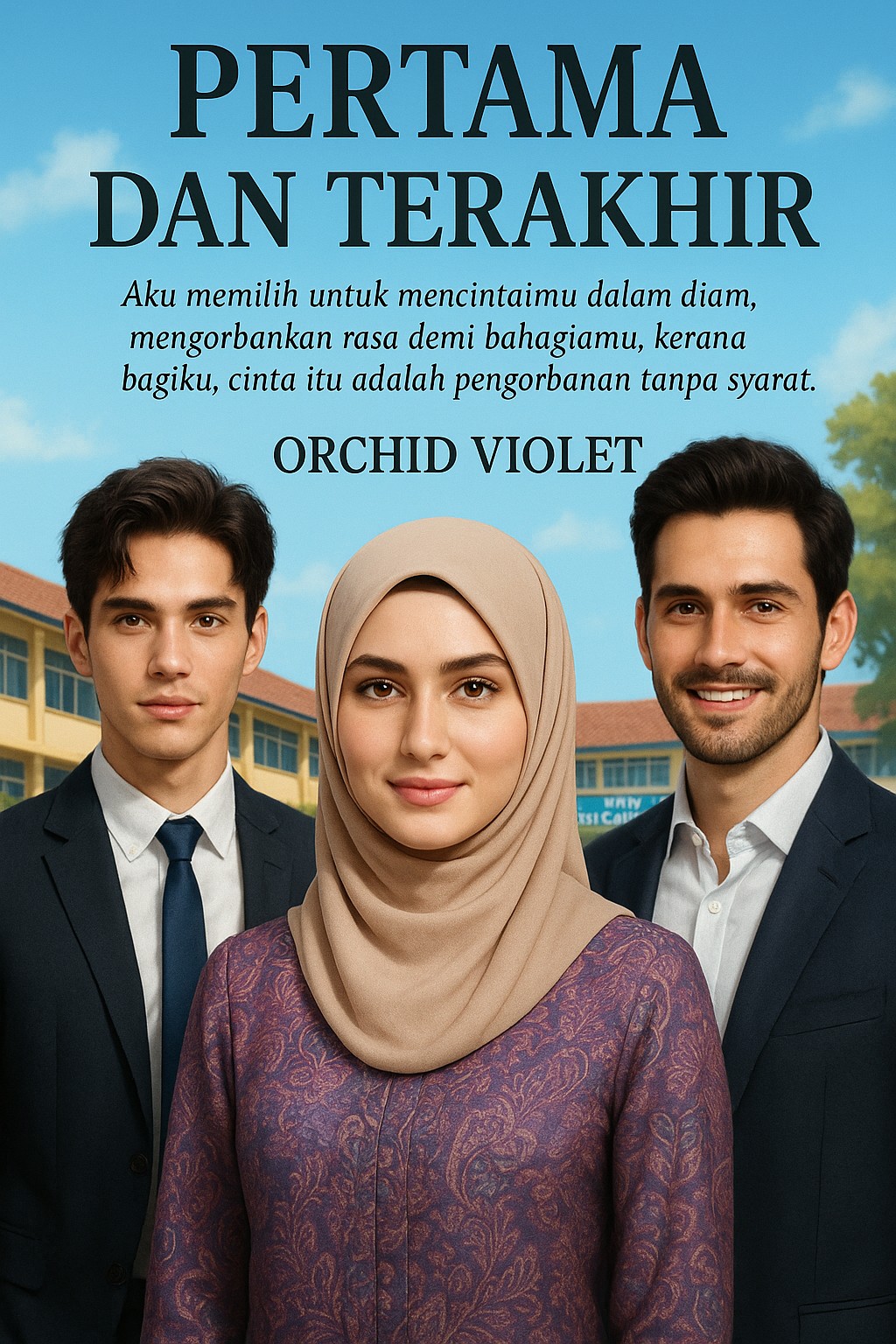
BAB 38 : WARKAH BUATMU
 Series
Series
 59683
59683
LANGIT pagi di luar hospital seakan muram, seperti turut memahami resah hati yang berkampung di aras tiga itu. Ruang luar ICU bukan lagi sekadar laluan sunyi yang dingin dan berbau antiseptik. Ia telah menjadi ruang pertemuan air mata, harapan, dan kenangan yang tidak mampu diulang kembali.
Langkah-langkah kaki yang perlahan tapi pasti kedengaran dari hujung koridor. Seorang wanita pertengahan usia, berbaju kurung polos berwarna krim dengan tudung labuh biru tua, muncul dalam pandangan. Mata yang bening itu, kini kelihatan beriak kekeliruan, seakan-akan hatinya masih belum mahu mempercayai apa yang telah dikhabarkan menerusi telefon subuh tadi.
“Ameena…”
Suara itu tidak nyaring, tetapi cukup untuk membuat tubuh kecil yang duduk bersandar di dinding ICU itu bangkit serta-merta. Mata Ameena membulat, bibirnya sedikit terbuka, dan dalam sekelip detik, dia sudah berlari kecil ke arah wanita itu, seperti seorang anak yang kembali ke dakapan ibunya setelah hilang arah di tengah badai.
Cikgu Zaharah memeluk Ameena erat-erat seperti ingin menarik semua duka keluar dari tubuh bekas pelajarnya itu. Yang mana sudah dianggap seperti adiknya sendiri. Ameena pula tidak dapat menahan getar di dalam dada. Tangisnya pecah juga, tertahan-tahan namun menyayat, jatuh dalam pelukan yang paling dia perlukan saat itu.
“Saya tak sangka… Kak Zaharah, saya tak sangka semua ini akan terjadi pada Abang…” suara Ameena serak di dada wanita itu.
“Ameena… saya pun tak sangka, sayang. Saya tak sangka... Allahu… waktu saya dengar berita tu tadi, jantung saya rasa macam berhenti sekejap. Eman tu… Eman tu macam adik saya juga,” ujar Cikgu Zaharah, suaranya juga pecah di hujung.
Pelukan itu lama. Sunyi di luar ICU tak bermakna sepi di hati juga, tetapi bergema dengan doa-doa dalam hati yang belum terlafaz.
Setelah seketika, Ameena menarik nafas panjang, mengesat air matanya dengan hujung lengan baju, dan memandang ke arah dua kelompok yang berada di tepi kanan dan kiri lorong ICU. Keluarganya dan keluarga mertuanya yang masih duduk menanti, penuh sabar.Dia menggenggam tangan Cikgu Zaharah dan memimpinnya ke arah mereka.
“Mak… Abah… ini Cikgu Zaharah. Dia… guru saya masa sekolah dulu. Lepas tu sempat kerja sekali dalam 2 tahun juga. Saya rapat sangat dengan dia… tapi Kak Za dah bertugas di sekolah lain sekarang.” Ameena cuba mengukir senyum dalam jiwanya yang sedang berperang.
Hajah Sufiah bangkit dengan perlahan, dengan senyuman, dia menatap wajah wanita di hadapannya dengan pandangan seorang ibu yang telah terlalu lama hidup dalam dunia pendidik.
“Saya pernah dengar Ameena sebut nama awak…” Hajah Sufiah memegang tangan Cikgu Zaharah. “Terima kasih sebab datang, cikgu. Kami... kami semua tengah tunggu khabar…”
“Terima kasih juga, Hajah… Eman tu anak yang baik. Saya tak dapat duduk diam tadi bila Amee telefon…” jawab Cikgu Zaharah dengan suara yang lembut namun bergetar.
Cikgu Hasyim hanya mengangguk perlahan, memandang kosong ke lantai namun sempat menekan bahu isterinya. Kartini pula, ibu Ameena, bangkit dan menghulurkan pelukan pada Cikgu Zaharah, lalu duduk di sisi wanita itu. Antara mereka, tidak banyak kata yang perlu diucapkan kerana rasa kehilangan yang sama itu sudah cukup menjadikan mereka sejiwa walau baru bersua.
Dan dalam bulatan keluarga itu, Ameena kembali duduk di sisi dinding, memegang tangan Cikgu Zaharah. Tangisnya sudah reda, tetapi matanya masih berkaca. Masih banyak belum diluahkan. Masih banyak yang tertinggal dalam dada rindu, takut, dan cinta yang tak terucap. Dia sesekali membuang pandang ke arah pintu ICU menantikan khabar daripada Doktor Farah dan Doktor Asrar.
Belum pun sempat suasana mereda dari pelukan hiba itu, kedengaran langkah-langkah laju bergema di hujung koridor. Seorang gadis bertudung biru lembut dengan seragam pengawasnya, dengan mata yang jelas menyimpan riak cemas, muncul tergesa dari arah lif utama.
“Cikgu Ameena!” panggilnya sebaik sahaja wajah itu terakam dalam pandangannya.Ameena mengangkat wajah, dan senyuman kecil hadir di celah kesedihan yang menggunung.
“Aina…” suaranya perlahan, tetapi cukup untuk gadis itu segera merapati dan memeluknya erat.Aina memejam mata di bahu gurunya itu, menahan tangis yang hampir pecah. Hanya dalam pelukan itu, dia dapat merasakan betapa dunia yang disangkanya teguh, kini sedang bergegar di depan matanya.
“Saya terus datang lepas kelas, Cikgu… saya tak tahu nak buat apa, saya tak boleh duduk diam… saya...” Aina terhenti. Suaranya bergetar.
“Terima kasih sebab datang, Aina. Terima kasih sangat…” Ameena membalas pelukan itu, menepuk-nepuk belakang pelajarnya dengan perlahan, seolah mahu menyampaikan ketenangan yang dia sendiri belum miliki.
Cikgu Zaharah memerhati dari sisi, mengesat sudut matanya dengan tisu yang dilipat kemas. Dia tersenyum kecil melihat gadis muda itu, kemudian mengangguk perlahan ke arah Aina. Gadis itu membalas dengan sopan, sebelum duduk di sisi dinding bersama yang lain.
Tak sampai lima minit kemudian, ruang itu sekali lagi dipenuhi langkah-langkah baru. Sekumpulan anak muda dalam pakaian kasual namun wajah-wajah mereka menyimpan satu persamaan. kesayuan yang menular dalam diam.
“Assalamualaikum, Cikgu…”
Suara itu dari Rayyan. Di belakangnya, Sofea, Raisya, Aqilah, Melisa, dan Aliff. Wajah-wajah yang dua tahun lalu pernah memenuhi makmal dan bilik darjah dengan impian, gelak tawa, dan ilmu yang diasuh dengan penuh kasih oleh Cikgu Eman.
Ameena bangkit perlahan, memandang mereka dengan mata yang mulai bergenang kembali.
“Kami... dapat tahu dari group batch. Kami ambil cuti, Cikgu. Tak kira apa jadi... kami nak ada di sini untuk Cikgu Eman.”Rayyan menghampiri dan menyerahkan satu fail biru pada Ameena. Fail itu berisi puluhan pucuk surat. Tulisan tangan, puisi, catatan dari hati yang belum reda dengan rasa terhutang budi.
“Kalau… kalau Cikgu boleh bacakan pada dia nanti…” ujar Sofea dengan suara yang ditahan-tahan.Ameena mengangguk. Air matanya jatuh jua kali ini. Tapi tidak dikesat, hanya dibiarkan mengalir sebagai bukti syukur dan kasih yang tidak terhingga.
“Dia akan suka. Dia… dia sayang kamu semua.”
Raisya menarik nafas panjang. “Cikgu tahu tak, masa hari terakhir sekolah, lepas SPM… dia pernah cakap, ‘Kamu semua yang buat saya percaya, saya bukan sekadar mengajar, tapi mendidik.’”
Mereka semua diam seketika. Melisa tunduk, menggenggam tangannya sendiri. Aqilah memandang dinding ICU yang dingin, seolah membayangkan Cikgu Eman sedang berdiri di sebalik pintu itu dengan senyuman yang selalu mengiringi ayat-ayat motivasinya.
“Dia pernah peluk saya, Cikgu,” Rayyan bersuara, memecah hening. “Lepas saya dapat tawaran ke jurusan undang-undang… dia kata, ‘Jangan lupa awak anak kampung, rayyan. Ilmu bukan untuk bangga, tapi untuk membela.’”
Ameena tunduk menahan tangis. Dalam diam, Cikgu Zaharah menggenggam erat tangannya. Sinar mata mereka bersatu. Dua wanita yang sedang menyaksikan cinta seorang pendidik, tidak dengan kata-kata, tapi dengan bukti kasih yang ditinggalkan.
Hari itu, di luar bilik ICU, bukan sekadar rindu yang bertebaran di udara. Tapi kenangan. Doa. Dan rasa hormat yang tak terganti.
Ameena memeluk fail biru di dadanya.Dalam hati, dia berjanji akan menyampaikan semuanya — setiap aksara, setiap baris cinta dari murid-murid itu kepada suaminya. Sama ada Eman mampu mendengar atau tidak, itu bukan urusan dunia. Yang penting, cinta itu tetap disampaikan.
AWAN Kuala Terengganu petang itu mendung, seolah mengerti duka yang meliputi sebuah keluarga. Di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Sultan Mahmud, langkah kaki manusia bersimpang-siur, namun pandangan Aryan dan Arief hanya tertumpu pada satu wajah iaitu adik bongsu mereka yang baru melangkah keluar dari pintu ketibaan.
"Ameer!" laung Aryan sambil mengangkat tangan, wajahnya sedikit keruh namun cuba dicalitkan senyum.Ameer yang melangkah cepat bersama isterinya, Puteri Qadeeja, terus memeluk Abang Long dan Abang Ngahnya. Pelukan itu erat, penuh makna yang tidak perlu dijelaskan dengan kata.
“Terima kasih sebab datang jemput, Long… Ngah…” Ameer bersuara rendah, matanya sudah berkaca.
“Tak apa, Dik. Kami tahu kau akan balik juga. Kakchik perlukan kita, kau paling utama sebab kau paling rapat dengan dia,” ujar Arief sambil menepuk belakang adiknya.
Puteri Qadeeja berdiri di sisi, wajahnya lembut namun jelas kegusaran menari di sebalik hijab birunya.Mereka segera menuju ke kereta. Sepanjang perjalanan ke hospital, suasana dalam kereta diliputi kesunyian. Bunyi penghawa dingin yang menghembus halus seperti turut berduka.
Ameer memandang ke luar jendela, kelopak matanya merah. “Kak Amee kuat… Tapi aku tahu dalam dia senyum, dia simpan terlalu banyak luka…”
Puteri Qadeeja menggenggam tangan suaminya. “B… dia ada you, Abang Long dan Abang Ngah. Dia tak sendiri.”
Ameer menggeleng perlahan, suara yang keluar penuh emosi, “Tapi Eman… dia satu-satunya lelaki yang betul-betul buat Kak Amee bahagia. Sejak dia bercerai dengan Isa, hidup dia tak tenang. Aku sendiri nampak. Isa… selalu kacau, call malam-malam, tunggu depan rumah...”
Arief menghela nafas berat. “Dan sekarang… dia diuji lagi.”
Ameer memejam mata. “Aku tak sanggup tengok dia kehilangan satu-satunya lelaki yang buat dia rasa dicintai tanpa syarat.”
Puteri Qadeeja mengusap bahu suaminya, cuba menjadi kekuatan dalam retak yang tidak terucap. “Kita ada untuk dia. Dan kita akan sama-sama hadap semua ni.”
Dalam hati Ameer, ada sesuatu yang berkecamuk. Sejak dari Brunei lagi, dia rasa hatinya tidak tenang. Cikgu Eman bukan hanya abang ipar, beliau adalah idola zaman sekolah, guru yang tak pernah letih percaya pada potensi pelajarnya. Dan kini, dia sedang bertarung untuk hidup.
Ameer menoleh pada abangnya. “Berapa lama dia dalam ICU?”
“Sudah dua hari. Ameena tak banyak cakap. Tapi suara dia semalam… menggigil. Kau tahu suara orang yang pegang tali yang hampir putus?”
Ameer menelan air liur, berat. Hatinya terus dihimpit gelisah. Pandangannya kembali dilemparkan ke luar tingkap melihat langit Kuala Terengganu mula menangis bersama mereka.
Deruan enjin yang tenang tidak mampu menyamarkan kekusutan yang mengendurkan wajah-wajah lelaki di dalam kereta itu. Aryan di tempat pemandu sesekali melirik cermin pandang belakang, memerhatikan Ameer yang masih memandang kosong ke luar jendela. Arief di sebelahnya juga terdiam, namun beban di dada makin menyesakkan.
“Adik,” Aryan akhirnya bersuara, nada suaranya tenang namun berlapis. “Sebenarnya… kenapa Isa ceraikan Kakchik dulu?”Soalan itu bagaikan serpihan kaca yang menyentuh hati Ameer. Dia menarik nafas panjang, menyandarkan belakang ke kusyen kerusi sambil menunduk.
Arief yang sedari tadi menahan rasa, menyambung, “Kami tak pernah tahu cerita sebenar. Kakchik tak pernah cerita. Ibu dan Ayah pun tak pernah buka mulut. Kami... kami tak berani nak tanya sebab Ayah... kau tahulah..”
Ameer mengangguk kecil. “Ayah suruh rahsiakan. Ibu kata... dia takut korang bertindak luar kawalan. Ya lah, korang kan Inspektor Polis. Mak takut korang belasah Isa hidup-hidup.”
Aryan dan Arief berpandangan. Ada kelucuan pahit di celah rasa terkejut.
“Dan sebab tu jugalah,” Ameer meneruskan perlahan, “aku yang simpan semua. KakChik... dia dikhianati, Long. Ngah. Dia diceraikan selepas empat belas hari akad.” Suasana menjadi bisu. Bunyi penghawa dingin terasa lebih nyaring dari biasa.
“Tanpa disentuh. Hanya kerana beberapa keping gambar, dan satu gambar ultrasound baby. Ada tangan jahat yang hantar gambar KakChik dipeluk lelaki... dan satu lagi, gambar imbasan kandungan tertulis 'Anak Kita'. Masa honeymoon mereka di Cherating... semuanya sampai ke tangan Isa. Dia tak tanya, tak siasat. Terus dia tampar Kakchik dan terus lafaz talak. Lepas tu tinggalkan KakChik seorang diri kat sana. Nasib Ada Cikgu Eman yang kebetulan ada hari keluarga dekat sana.”
Puteri Qadeeja di belakang, menekup mulutnya. Aryan menumbuk stereng perlahan. Arief menggelengkan kepala, seperti tidak mampu menerima.
“Fitnah apa ni...” Arief menggumam, suaranya geram.
Ameer mengangguk perlahan. “Kami pun tak tahu siapa dalangnya. Tapi… selepas tu, hidup KakChik tak pernah tenang. Isa… muncul balik, ganggu dia. Minta rujuk. Tapi tak ada istilah rujuk. Kakchik janda berhias. Tak disentuh, tak perlu edah. Tapi Isa tetap ganggu, tetap datang dengan harapan.”
Aryan menyisip nafas dalam. “Jadi, Eman...?”
Ameer tersenyum nipis, wajahnya tenang namun matanya berkaca. “Cikgu Eman… dia selalu muncul waktu KakChik dalam kesempitan. Setiap kali Isa buat hal dekat sekolah.. Abang Eman ada. Tapi yang paling ajaib, dia tak tahu pun Kak Amee dah bercerai.”
Arief mengerut dahi. “Tak tahu?”
“Ya. Isa suruh rahsiakan. Tak nak mamanya, Datin Suria, terkejut dan kena serangan jantung. KakChik ikut je. Lagipun, masa tu usia perkahwinan mereka terlalu muda. Kak Amee takutkan Ayah. Dia simpan semua. Luka dia, malu dia... semuanya.”
Sunyi kembali menyelimuti ruang sempit kereta itu. Yang tinggal hanyalah pandangan ke depan yang semakin menghala ke arah hospital. Di dalam hati setiap mereka, berputar wajah seorang wanita yang terlalu banyak menanggung dan seorang lelaki yang kini sedang bertarung dalam diam, selepas menjadi penyelamat yang tidak diduga.
Puteri Qadeeja menggenggam jari Ameer erat-erat. “Dia wanita yang kuat, sayang. Tapi sekarang, dia perlukan kita semua.”
Ameer mengangguk, kali ini lebih yakin. “Dan aku takkan biar dia hadap semua ni sendiri lagi.”
Ameer tunduk seketika. Nafasnya mendesah panjang seperti sedang menahan sesuatu yang lama terkurung di dada. Kemudian dia bersuara, perlahan tapi cukup jelas untuk mengejutkan dua insan di hadapan.
“Korang nak tahu tak… siapa lelaki dalam gambar tu?”Aryan dan Arief serentak menoleh ke belakang.Ameer mengangkat wajah, matanya merah, tapi kali ini ada api kecil yang menyala di balik tenang suaranya.
“Akulah lelaki dalam gambar tu.”Sejenak, masa seakan beku dalam kabin kereta.
“Ya Allah, Dik…” Aryan menelan air liur.Arief bersandar ke kerusi, bagaikan baru ditampar kenyataan.
“Waktu tu... aku tengah cuti sem. Baru balik Malaysia. Kakchik datang ambil aku dekat airport. Masa tu hujan, dan aku peluk dia lama. Lama sangat. Kami dah lama tak jumpa. Aku terlalu rindu... tak sangka langsung ada yang ambil gambar dari jauh. Kami pergi mandi kolam dekat TER. Kami berjalan-jalan tepi pantai Batu Buruk. Kau tahulah KakChik tu cantik, banyak mata duk pandang dia. Itulah dia selalu duk pegang tangan aku ni.”
Puteri Qadeeja meraih tangan suaminya erat, seolah menyalurkan kekuatan agar Ameer tidak rebah di tengah cerita.
Aryan menumbuk stereng, kali ini lebih kuat. “Bodohnya Isa...!”
“Dia tak kenal aku. Waktu akad pun, aku masih di luar negara. Langsung tak pernah bersua muka. Dan dia tak pernah tanya. Tak pernah cuba kenal siapa aku...”
Arief menggeleng perlahan, wajahnya berkerut. “Kakchik tanggung semua tu sendiri...?”
Ameer mengangguk, menelan pahit yang lama bersarang. “Dan Cikgu Eman… dia banyak bagi semangat, dia hormat Kakchik lebih dari Isa yang pernah lafaz janji.”
Kereta kembali tenggelam dalam kesunyian yang panjang. Tapi kali ini, bukan lagi sunyi yang kosong. Ia sarat—dengan marah, sesal, kagum dan kasih yang membuak-buak terhadap seorang wanita tabah bernama Ameena.
Puteri Qadeeja akhirnya bersuara lembut, “Kadang-kadang, Allah izinkan fitnah berlaku… untuk membongkar siapa yang benar-benar ikhlas.”
Ameer mengangguk. “Dan sekarang… aku cuma tak sanggup tengok dia hilang Cikgu Eman. Orang yang satu-satunya tak pernah minta apa-apa, tapi selalu ada bila dia perlukan seseorang.”
Langit Kuala Terengganu terus kelabu, dan rintik yang turun perlahan-lahan membasuh bumi—seolah turut meratapi luka yang tersimpan begitu lama, namun akhirnya terbuka dengan kebenaran.
LANGKAH kaki Cikgu Fahmi dan Isa bergetar perlahan di koridor aras ICU. Di ruang sunyi itu, waktu terasa seperti mengundur. Dinding putih dan lampu kekuningan menambah suram pada suasana yang sudah pun berat dengan penantian.
Ameena yang sedang duduk bersama ibunya, Kartini, segera bangkit saat terlihat kelibat dua insan yang dikenalinya dari jauh. Matanya redup, namun bibirnya menyambut dengan senyuman kecil sekadar menyatakan bahawa dia masih bertahan.
“Assalamualaikum, Cikgu Fahmi..Cikgu Isa,” ucapnya perlahan. Matanya singgah seketika pada wajah Isa, namun tiada getaran apa-apa di sana. Hanya kosong, seperti antara mereka sudah terputus dari sebarang garis masa.
“Waalaikumsalam, Cikgu Ameena,” jawab Cikgu Fahmi tenang. Wajahnya jelas gusar, namun dia menunduk sedikit tanda hormat. Dia tidak menyentuh, tidak mendekat—cukup dengan kata dan raut yang membawa simpati yang jujur.
“Apa khabar Eman?” suara Isa menyusul, serak, namun cuba dikawal.
Ameena menarik nafas panjang sebelum menjawab. “Dia diserang anaphylactic kali kedua. Lebih teruk daripada sebelum ni. Salur pernafasannya sempit… doktor sedang intubate sekarang. Dia perlu bantuan ventilator untuk terus bernafas.”
Wajah Isa berubah tegang. Cikgu Fahmi menelan keluh yang terpendam. “Allahurabbi..” Cikgu Fahmi terduduk menyandar di dinding putih yang telah melihat banyak coreta duka di sudut itu.
Tiba-tiba, keheningan pecah dengan kemunculan dua figura dari sisi kanan koridor,Tuan Zulkifli dan Kartini, baru tiba . Mereka turun ke bawah membeli minuman untuk Ameena dan besan mereka. Langkah mereka terhenti seketika tatkala melihat kelibat Isa. Wajah mereka jelas tergamam.
Isa segera tunduk, lalu melangkah penuh tertib menghampiri kedua-duanya. “Assalamualaikum, Ayah, Ibu.”
“Waalaikumsalam,” jawab Tuan Zulkifli tenang, namun suaranya sedikit berat. Dia tidak menyambut dingin, namun ada garis-garis berjaga pada wajahnya. Tangannya disambut Isa sekadar menjunjung adab.
Kartini menyambut huluran tangan Isa dengan segaris senyuman. “Isa... lama tak dengar berita.”
Isa angguk. “Saya... saya terkejut sangat bila dengar tentang Eman. Saya... cuma nak ziarah.” Tidak mahu disalah anggap.
Tiada kata balas dari Tuan Zulkifli, namun riaknya tidak marah. Hanya sedikit berkira-kira, seperti seorang ayah yang belajar membezakan antara kenangan dan keperluan semasa.Ameena hanya diam di sisi, menyaksikan pertembungan masa silam dan masa kini bersilang di hadapannya.
Cikgu Fahmi memerhati semua itu dengan pandangan yang dalam. Dia tahu, bukan semua luka sembuh dengan waktu. Namun, hari ini bukan tentang silam, hari ini tentang seorang insan bernama Eman Al Hadi yang sedang bertarung untuk hidup.Dan di ruang ini, mereka semua bersatu kerana satu nama.
Dari balik kaunter jururawat, suasana yang tadinya biasa bertukar sedikit riuh dalam diam. Dua orang jururawat muda, Shaza dan Imani, yang baru saja selesai menyusun ubat-ubatan pesakit di ICU, saling berpandangan bila dua orang lelaki segak melewati koridor.
“Eh, Min… kau nampak tak yang sorang tu? Yang pakai kemeja biru tu?” bisik Shaza perlahan sambil menunduk, matanya mencuri pandang ke arah Cikgu Isa yang berjalan di sisi Cikgu Fahmi.
Imani mengangguk kecil, menyiku rakannya dengan senyuman nakal yang ditepis-tepis sopan. “Aku lagi tertarik yang sebelah dia tu. Tall, tanned, and that jawline...”
Shaza menyambung dalam nada lebih perlahan, “Tapi serius, dia senyum pun… ya Allah. Macam pelakon Korea campur British.”
“Dia cikgu jugak ke? Untunglah anak – anak murid diorang ya.. sejuk mata memandang” soal Imani lagi sambil membuka fail pesakit di hadapan mereka, konon mengalihkan perhatian. Tapi ekor matanya masih menjeling ke arah kerusi menunggu ICU.
Shaza cepat-cepat menggigit bibir. “Shh… jangan kuat sangat. Nanti Makcik kat hujung tu dengar.”
Kedua-duanya kembali tunduk pada kerja masing-masing. Namun hati mereka tetap bertanya-tanya.
“Macam mana pesakit tu? Yang ICU tu,” tanya Imani tiba-tiba, kali ini dengan nada prihatin.
“Anaphylactic shock. Serangan kedua. Doktor cakap salur pernafasan dia sempit sangat. Tengah intubate tadi.”
“Ya Allah, kesian...” bisik Imani. “Sampai ramai sangat datang ziarah. Macam VVIP.”
Shaza angguk perlahan. “Aku rasa… dia ni bukan orang biasa. Dia mesti guru yang disayangi. Rapat dengan anak murid. Sebab tu ramai budak-budak IPT pun datang pagi tadi.”
Imani senyum kecil. “Mulia kerja cikgu ni ya. Sampai dalam ICU pun, kasih orang masih mengalir.”
Shaza pandang ke arah Ameena, yang duduk memeluk bahu ibunya. “Dan isterinya… tabah sangat. Kalau aku lah, dah lama meraung.”
“Semoga Allah permudahkan semuanya untuk mereka,” balas Imani perlahan. Kali ini tiada lagi nada nakal. Hanya doa dalam hati, agar di sebalik segala wajah tampan dan kisah yang belum mereka fahami, ada hikmah besar yang sedang ditulis langit.
Suasana ruang menunggu ICU petang itu bagai ditarik sunyi. Jam berdetik, namun waktu seperti tidak berganjak. Hanya desahan perlahan dan helaan nafas yang berat sesekali mengisi ruang, seolah menandakan betapa semua sedang menanti—antara harapan dan ketakutan. Serta bacaan yasin yang kedengaran perlahan dan syahdu.
Tiba-tiba, pintu ICU terbuka. Seorang lelaki tinggi dengan kot makmal putih berjalan keluar dengan langkah tenang. Wajahnya serius, tetapi tidak menggerunkan. Ada cahaya di matanya—cahaya seorang doktor yang tidak mahu memberi harapan palsu, namun tidak juga membiarkan keluarga terus dalam gelap.
"Assalamualaikum," ucapnya perlahan, tapi cukup untuk memecah hening.
Semua serentak berdiri. Kartini memegang lengan suaminya, manakala Hajah Sufiah menggenggam erat tasbih kecil di tangannya. Ameena hanya mampu berdiri kaku, dada turun naik menahan segala kemungkinan.
“Saya Doktor Asrar, pakar bius dan rawatan kritikal. Saya bertanggungjawab dalam kes Encik Eman.”
Tuan Zulkifli angguk perlahan. “Kami keluarga beliau, doktor. Isteri, ibu, ayah… semua di sini.”
Doktor Asrar memandang sekeliling. Matanya jernih, tenang, namun nadanya tetap teguh.
“Pertama sekali, saya mohon kalian bertenang. Encik Eman masih stabil. Itu yang paling utama. Bacaan tekanan darahnya sudah kembali dalam julat yang kami mahu. Alhamdulillah, kami berjaya lakukan intubasi tepat pada waktunya untuk bantu dia bernafas.”
Ameena menunduk, bahu mula terhinggut kecil, lega yang menitis dalam diam. Fahmi di sisi hanya menatap tanpa suara. Isa tunduk, jari-jarinya bersilang kaku.
“Tapi,” Doktor Asrar menyambung perlahan, “beliau masih belum melepasi fasa kritikal. Serangan anafilaksis kedua menyebabkan pembengkakan teruk pada salur pernafasannya. Kami perlu tunggu sekurang-kurangnya 24 ke 48 jam lagi untuk nilai sama ada pembengkakan itu akan surut sepenuhnya.”
“Sampai bila dia kena bernafas dengan mesin tu dan ada komplikasi lain ke lepas tiub pernafasan tu dikeluarkan?” tanya Tuan Zulkifli dengan suara yang tidak menggugat, tapi penuh ketegasan.
Doktor Asrar mengangguk, seakan menghargai pertanyaan itu.
“Saya suka keluarga tahu semua. Selepas extubate, kami akan nilai sama ada Encik Eman boleh bernafas sendiri tanpa bantuan mesin. Ada kemungkinan beliau boleh, tetapi sekiranya salur pernafasannya masih sempit, ada risiko beliau sesak nafas semula. Dalam kes begitu, kami perlu intubate semula, atau guna kaedah alternatif seperti tracheostomy.”
“Ya Allah…” Hajah Sufiah menutup mulut, air matanya tumpah jua.
“Kami juga sedang pantau fungsi jantung dan buah pinggang beliau. Serangan seperti ini boleh beri kesan sekunder. Tapi setakat ini, bacaan makmal masih dalam kawalan. Kami buat yang terbaik,” tambah Doktor Asrar sambil memandang setiap wajah dengan jujur.
“Boleh kami masuk tengok dia, doktor?” tanya Ameena akhirnya, suaranya lirih namun masih bergetar kekuatan.
“Seorang atau dua orang sahaja, untuk waktu yang singkat. Encik Eman sedar secara minimum… tapi kami percaya suara yang dikenal boleh bantu pemulihan.”
Ameena angguk. Kartini merangkul bahunya, dan untuk pertama kalinya, Tuan Zulkifli meletakkan tapak tangannya pada kepala Ameena.
“Masuklah. Baca ayat-ayat suci. Dia dengar,” ujar lelaki tegas itu, kali ini dengan nada yang lebih perlahan daripada biasa.
Doktor Asrar menoleh dan mengangguk kecil sebelum berlalu masuk kembali ke ICU.Langkahnya tenang, meninggalkan keluarga yang kini menggenggam secebis harapan, meskipun bayang ketidaktentuan masih menari di hujung lorong.
Langkah kaki Ameena seolah terbenam di lantai putih yang dingin. Setiap derap membawa doa yang tak pernah putus. Di tangannya tergenggam sebuah fail lusuh berisi helaian-helaian cinta dari masa lalu, bukan cinta sepasang kekasih, tapi cinta anak-anak didik terhadap gurunya.
Pintu ICU terbuka dengan bunyi lembut. Jururawat yang menjaga menunduk hormat, memberi ruang buat isteri yang datang dengan mata yang sudah tidak mampu menampung air mata.
Eman terbaring di sana. Sunyi. Wajahnya masih tampan seperti biasa, cuma sedikit pucat. Tiub pernafasan di mulutnya menjadi penghubung antara hidup dan harapan. Mesin-mesin di sisi berkelip dan berbunyi dalam rentak yang asing, seolah-olah seluruh alam sedang bernafas bagi pihaknya.
Ameena menarik kerusi perlahan ke sisi katil.
“Abang…” suara itu hampir tak kedengaran. “Sayang datang.”
Tangannya menyentuh jari Eman yang terbuka lemah. Sejuk, tapi masih bernadi. Dia membuka satu helaian surat dari fail yang dibawa. Surat pertama.Tulisannya bulat-bulat, kemas seperti pelajar sains tulen yang sentiasa tekun.
“Cikgu Eman, saya dah masuk tahun kedua di UM. Setiap kali saya rasa nak give up, saya teringat cikgu pernah kata — ‘Jangan hina usaha sendiri dengan mengalah terlalu awal’. Cikgu, jangan pergi lagi. Kami belum sempat balas semua jasa cikgu. Kami belum sempat ucap betul-betul… yang cikgu adalah nadi semangat kami waktu itu. Tanpa cikgu, saya tak akan pernah percaya bahawa sastera dan sains boleh berdiri dalam satu jiwa. Terima kasih sebab jadi cikgu yang tak pernah jemu percaya kami boleh. Doakan saya ya, cikgu.” – Sofea.
Ameena senyum sambil menyeka air mata. “Ingat Sofea, Abang? Yang selalu cuba satukan kita. Yang selalu bagi idea untuk Abang tawan hati sayang. Sedangkan dia tak tahu yang kita sudah berkahwin waktu tu. Jari Eman tak bergerak. Tapi air di mata Ameena kian deras.
“Surat ni pula dari Aliff, bekas pelajar yang paling nakal tapi paling sayang Cikgu Eman.”
‘Bro Eman…
Ingat Saya? Aliff. Yang selalu Cikgu sergah sebab pakai kasut tak ikat tali. Yang suka tiru gaya jalan Cikgu masa balik dari perhimpunan. Yang pernah cakap Cikgu macam hero Malaya.
Cikgu, saya menulis ni dengan tangan menggigil. Saya tak reti tulis surat macam Raisya, atau macam Sofea yang berbunga-bunga ayatnya. Tapi saya tahu hati saya ni penuh dengan satu je, rasa hormat.
Dulu saya bukan siapa-siapa. Saya pelajar yang cikgu lain malas nak tengok muka. Tapi cikgu ajar saya macam saya pelajar harapan. Cikgu lawan sistem untuk bagi saya peluang. Cikgu tolong saya hantar borang politeknik. Cikgu pinjamkan duit belanja.
Cikgu… tolong jangan mati. Saya belum sempat cakap terima kasih.
Dan… saya nak tengok senyuman cikgu masa tengok gambar perkahwinan anak saya nanti. Sebab nama anak saya pun saya nak ambil dari nama cikgu.”
Bro Eman. Kalau bukan sebab cikgu, saya dah lama kena buang sekolah. Tapi cikgu layan saya macam anak jantan. Saya belajar jadi orang dari cikgu. Sekarang saya dekat politeknik cikgu, tahun kedua. Cikgu bangga tak?”
Ameena menekup mulut. “Aliff… dia anak nakal yang selalu buat Abang marah. Tapi dia ingat semua kebaikan Abang…Dia panggil abang ‘Bro’. Tapi dia sayang abang macam ayah dia,” bisik Ameena.
Ameena ambil satu lagi. Dari Raisya. Tinta biru, tulisan halus dengan bunga kecil di penjuru.
“Cikgu Eman, masa sekolah dulu, saya selalu doa biarlah cikgu jumpa orang yang betul-betul sayang cikgu. Bila saya tahu cikgu kahwin dengan Cikgu Ameena, saya senyum sorang-sorang. Sebab saya tahu cikgu dah jumpa dia. Ingat tak big Love yang Cikgu bagi untuk saya dulu? Waktu kelas BM. Selepas Cikgu Ameena melintas depan kelas kita. Sekarang impian Cikgu dan impian kami dah jadi kenyataan. Cuma kami minta, bangunlah dan terus kuat. Kami nak tengok puteri dengan putera Cikgu.”
Kali ini, Ameena tidak mampu menahan esaknya. Bahunya bergegar. Surat-surat itu tak mampu menahan air matanya daripada terus bertahan. setiap baris, setiap huruf menjadi alunan zikir yang mengisi ruang ICU itu dengan kasih.
Dia menyandar sedikit, kepalanya menyentuh sisi tilam.
“Sayang tahu Abang dengar. Dengarlah semua ni… Ini semua cinta, Abang. Cinta dari anak-anak kita yang kita ajar bukan dengan buku, tapi dengan hati.” Ameena membuka surat seterusnya. Kali ini dari Melissa.
“Cikgu…
Saya masih simpan gambar cikgu dan cikgu Ameena yang kami tangkap curi-curi masa lawatan sekolah ke Taman Tamadun Islam. Kami semua tahu cikgu dua orang bukan sekadar cikgu, tapi dua jiwa yang sedang saling sembuhkan.
Cikgu,
waktu cikgu berdiri diam lepas habis kelas 5 Sains Tulen dulu, kami semua tahu cikgu hampir menangis. Sebab tahun tu batch kami betul-betul buat cikgu percaya, yang jadi guru itu bukan sekadar kerja.
Cikgu Eman…
kalau surat ni sampai ke tangan cikgu, tolong bangun. Bangun bukan untuk kami. Tapi untuk wanita yang duduk setiap jam di sisi cikgu, baca semua surat kami dengan air mata.
Dia kuat… tapi cikgu tahu, bukan semua orang yang kuat itu tak pernah penat.”
Ameena diam lama. Surat itu diletakkan di dada Eman, sekejap. “Abang… semuanya masih tunggu. Jangan diam terlalu lama.”
Ameena menarik lagi surat seterusnya. Kali ini daripada Aina. Murid yang diberikan kepercayaan untuk jadi wakil debat sekolah.
“Cikgu Ameena, kalau cikgu bacakan surat ni dekat Cikgu Eman, tolong bagitahu saya rindu suara dia marah saya sebab saya tak yakin untuk membidas sewaktu latihan debat. Saya rindu dia panggil saya ‘Yang Berhormat’. Cikgu Eman tak tahu betapa banyak dia dah ubah hidup saya.”
Ameena ketawa kecil dalam tangis. “Dia rindukan Abang…” Tangannya menggenggam jemari Eman yang kaku.
Jemari Ameena terus membuka surat seterusnya. Air matanya masih gugur perlahan. Tersentuh dengan setiap bait kata-kata bekas pelajar suaminya. Terasa berat lidahnya untuk membaca semua surat-surat itu, namun kerana amanah dia terus kuat.
Cikgu Eman...
Saya menulis ini di tengah malam, dengan lampu meja menyala dan hati yang remuk.
Waktu belajar Sejarah dengan cikgu, saya belajar bahawa tokoh yang besar tak semestinya mati dalam perang. Kadang-kadang, mereka gugur dalam diam — dalam ruang ICU — dengan doa anak-anak murid sebagai perisai terakhir.
Cikgu... jika ini takdir, maka biarlah saya jadi saksi bahawa pernah wujud seorang guru... yang mengajar kami mencintai bangsa dengan penuh santun, yang tak pernah memandang kami dengan kecewa walau kami gagal.
Dan dalam senyum cikgu, kami semua belajar bahawa 'merdeka' bukan hanya sejarah... tapi rasa. Rasa bebas untuk jadi diri sendiri. Rasa bangga jadi anak Malaysia. Rasa kuat walau jatuh berkali-kali’
“Abang.. ini surat dari rayyan, abang ingat lagi dengan dia? Abang dengar ya.” Dalam sedu yang masih tersisa. Ameena terus membuka lipatan kemas helaian putih itu.
‘Kata-kata itu roh,’ kata cikgu pada hari pertama saya masuk kelas.
Cikgu tak marah bila saya bercakap loghat utara. Cikgu tak betulkan saya bila saya keliru antara 'di' dan 'ke'. Cikgu cuma pandang saya... dan kata, “Tulis ikut jujur. Biar silap, asalkan hidup.”
Hari ini, saya tulis dengan jujur, cikgu... saya takut kehilangan cikgu. Takut dunia akan kurang satu suara yang pernah percaya saya boleh jadi penulis walau markah BM saya selalu merah.
Kalau cikgu dengar ini... tolong dengar betul-betul. Saya masih bawa buku nota yang cikgu bagi. Yang ada tulisan tangan cikgu — "Rayyan, jangan berhenti menulis."
Saya tak pernah berhenti, cikgu. Jangan juga cikgu berhenti bernafas, ya?’
“Abang kena bangun. Sayang dah baca semua surat. Tapi banyak lagi yang belum sampai. Banyak lagi yang menunggu abang senyum dan angguk macam selalu. Bangunlah, sayang…”
Mesin terus berbunyi seperti biasa, tetapi di hati Ameena, ada getar kecil seolah jari Eman merespon, atau mungkin... harapannya yang terlalu kuat hingga mengubah persepsi.
Namun dalam diam itu, kasih tetap mengalir. Dalam sunyi itu, dia masih percaya lelaki itu akan pulang, dan segala luka akan menjadi kisah yang membina semula sebuah hidup.
Ameena menyentuh setiap helaian surat itu dengan hujung jarinya seperti menyentuh sejarah kasih yang tak pernah berakhir.Air matanya jatuh satu demi satu, namun senyumannya tetap ada. Duka yang dalam, tapi diiringi rasa bangga yang tak terkata.
“Abang... mereka semua rindukan hero mereka. Mereka semua tulis bukan dengan pena, tapi dengan hati. Jangan berhenti bernafas, Abang… surat mereka belum sempat Abang baca sendiri.”
Dan malam itu… walaupun ICU sepi dan lampu-lampu suram, namun ruang di sisi katil Eman terasa terang diterangi cahaya kasih dan doa, dalam bentuk warkah-warkah cinta yang ditulis bukan atas kertas, tapi atas sejarah yang mereka cipta bersama.
Ameena melangkah keluar dari bilik ICU dengan tubuh yang hampir melurut, seolah sebahagian daripada tenaganya tertinggal di sisi katil putih yang menyembunyikan wajah suaminya dari dunia. Nafasnya pendek-pendek, bukan kerana letih fizikal semata, tetapi kerana hatinya seperti telah dicengkam satu kekosongan yang sukar diterjemah.
Di luar, lorong hospital sepi namun tidak sunyi. Cahaya pendarfluor di siling menyimbah pucat pada wajah-wajah yang menunggu dalam debar. Cikgu Zaharah bangkit menyambutnya dengan senyuman yang terpaksa ditahan supaya tidak roboh.
“Ameena…” panggil suara yang penuh kelembutan.
Ameena hanya mengangguk kecil, duduk perlahan di kerusi paling hujung. Matanya tidak merenung sesiapa, hanya menunduk, memandang lantai yang seperti mampu menelan segala pilu.
Isa dan Fahmi berdiri di hujung koridor. Wajah mereka tegang namun penuh hormat. Mereka tidak terus mara. Fahmi menunggu isyarat, Isa menelan kerongkong yang kering. Mereka tahu, wanita itu telah beri segalanya dan kini sedang menahan untuk tidak rebah.
Ameena bersuara, perlahan tetapi tegas.
“Cikgu Isa, Cikgu Fahmi… pergilah tengok Eman dulu. Saya dah lama di dalam… saya tahu, bukan saya seorang yang sayangkan dia.”
Wajah Isa berubah. Terpukul dengan ketulusan yang Ameena beri. Fahmi, yang dari tadi membisu, memandang Ameena dengan mata berkaca. “Cikgu Ameena… awak pasti?”
Dia senyum. Senyum itu bukan milik wanita yang bahagia. Tapi milik seorang isteri yang telah melepaskan dirinya untuk orang yang disayang supaya insan lain yang juga mencintai suaminya, dapat menyampaikan cinta mereka.
“Pergilah. Eman bukan milik saya seorang. Dia milik semua yang pernah disentuh oleh kebaikannya.”
Langkah Isa dan Fahmi perlahan-lahan menuju ke pintu ICU. Di belakang, jururawat yang tadi memandang mereka dengan kagum hanya tunduk, tidak lagi berbual. Mereka mula mengerti — wajah tampan itu sedang melawat wira yang sedang berjuang antara hidup dan mati.
Ameena menekup wajah dengan dua tangan. Dalam diam, air mata itu gugur juga — kerana dia tahu, walaupun Eman sedang tidur, tapi cinta mereka tak pernah lena.
Sunyi. Hanya bunyi mesin ventilator yang berdetik perlahan menjadi latar. Di sisi katil ICU itu, dua sahabat berdiri — Cikgu Fahmi dan Cikgu Isa. Mereka saling berpandangan sejenak sebelum Fahmi duduk di kerusi kecil di sisi kepala Eman, sementara Isa bersandar pada dinding, tangannya masih belum lepas dari poket seluarnya.
“Bro…” Fahmi bersuara perlahan. “Court badminton sunyi sejak kau masuk sini.”
Isa ketawa kecil, hambar. “Siapa lagi nak layan backhand aku yang keras macam smash Lin Dan?”
“Kau silap, bro. Smash kau tu macam bulu ayam. Nasib baik Eman tak masuk hospital sebab terkena shuttlecock,” usik Fahmi, cuba menceriakan suasana walau senyum mereka berbalut duka.
Isa berjalan perlahan ke hujung katil. Matanya jatuh pada tangan Eman yang kaku, dibalut kemas dengan wayar dan tiub. “Bro, Ingat tak, masa hari guru tahun pertama aku kat sekolah tu?”
Fahmi senyum, sambil turut sama cuba mengingat. “Bro Fahmi nyanyi lagu You're Still the One dengan suara sengau tu. Sampai sekarang telinga aku berdosa.”
Fahmi ketawa lebih kuat sedikit, tapi ada kesayuan di hujung suaranya. “Dan kau…” Isa pandang wajah Eman, “…duduk belakang sekali, senyum sambil pegang bunga yang anak murid dia bagi.”
Mereka diam sejenak. Masing-masing larut dalam kenangan.
“Tapi yang paling aku tak boleh lupa, bila kau…” Isa menarik nafas. “Bila kau bagi aku semangat untuk try tackle Ameena.”
Fahmi mengangkat wajah. “Serius?”
“Emanlah orang pertama yang tahu aku suka Ameena. Dia tolong aku, bro. Dia tulis pantun, dia tolong arrange aku bagi hadiah... semua dia buat dengan ikhlas.” Isa ketawa kecil. “Ironinya, dia juga yang jadi suami Ameena sekarang.”
Fahmi tidak membalas. Dia tahu, luka yang Isa simpan itu bukan sekadar kerana wanita, tapi kerana persahabatan yang dikhianati tak sengaja.
“Bila aku dapat tahu korang kahwin, aku rasa macam jatuh dari bangunan. Tapi, kau tahu… aku tak mampu benci kau.” Isa senyum hambar. “Sebab kau lelaki paling baik yang aku kenal.”
Isa tunduk lebih dekat pada telinga Eman. Suaranya menjadi berat.
“Tapi kalau kau tak bangun, bro… aku akan rampas balik Ameena. Aku tak peduli. Kau tak ada, dia perlu seseorang. Aku sanggup.”
Fahmi menoleh pantas. “Bro…!”
Belum sempat dia menyambung kata, tangan Eman tiba-tiba terangkat sedikit, seolah mahu mencengkam sesuatu dan serentak itu, mesin ventilator berbunyi nyaring, ritma yang stabil tadi kini terganggu, seolah ada yang cuba melawan dari dalam.
Fahmi dan Isa serentak berdiri.
“Doktor! Cepat! Mesin dia bunyi!” jerit Isa, wajahnya pucat.
Fahmi menekan loceng kecemasan. “Eman! Bro, jangan buat hal…”
Kakitangan ICU berlari masuk, dan dunia kembali kecoh. Di luar bilik, semua mata mula mencari wajah yang paling mereka harapkan tak berubah. Ya, wajah Eman, yang selama ini menjadi pusat kasih, tawa dan segala kenangan.
Dalam hidup ini Cinta tidak selalu hadir dalam bentuk kata-kata manis atau pelukan mesra. Kadang ia berupa diam yang setia, doa yang tidak terdengar, Dan air mata yang diseka tanpa suara. - Orchid_Violet.
Share this novel
hana1234
2025-04-25 18:02:55
sedihnye baby ni



