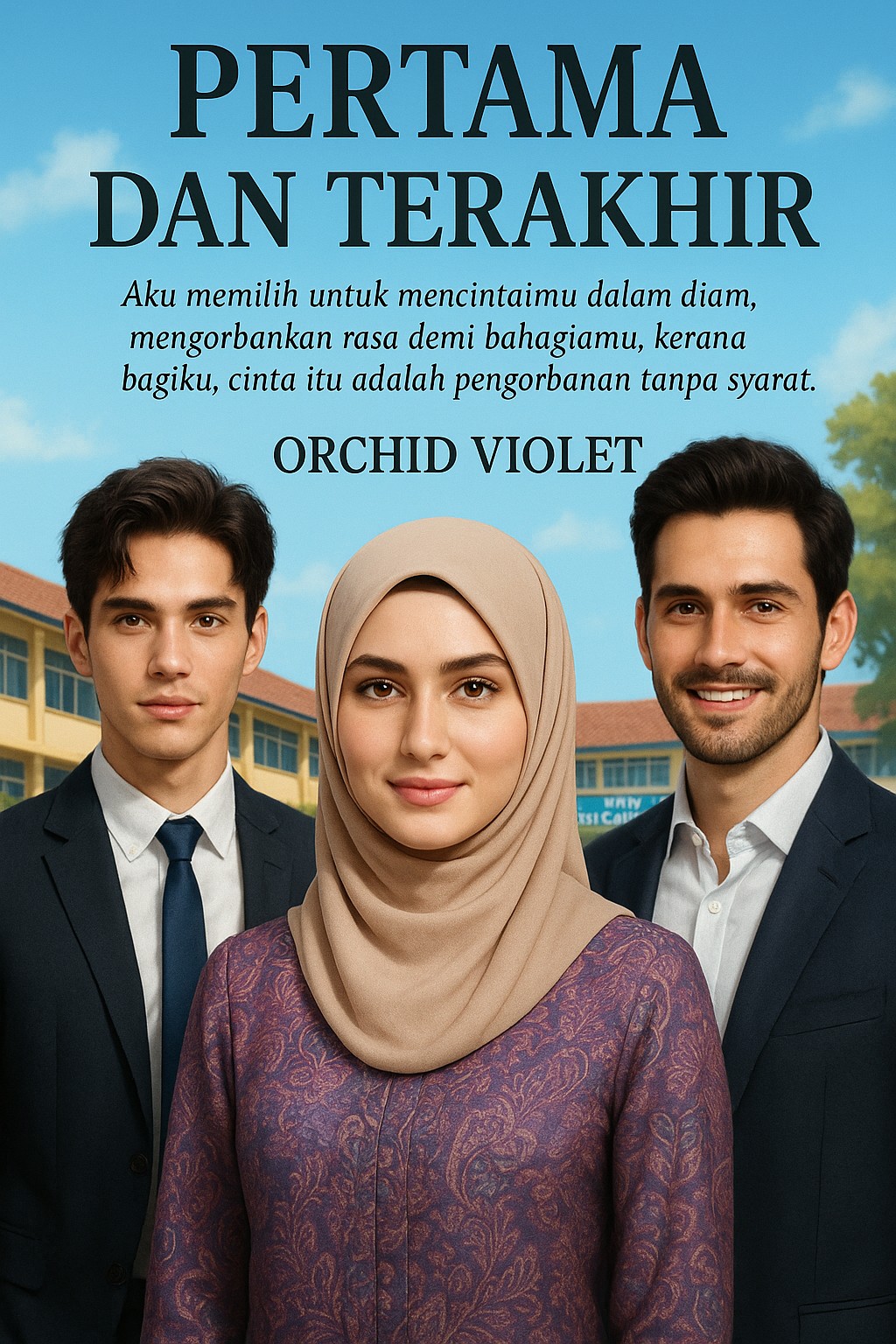
BAB 50 : DIA ISTERIKU
 Series
Series
 59683
59683
MALAM menyelimuti rumah keluarga Eman dengan hening yang menggetar rasa. Lampu dapur bersinar suram.. sesuram hati tua yang ada di situ. Hajah Sufiah duduk di bangku panjang, mengacau perlahan air teh di dalam cawan. Di hadapannya, Cikgu Hasyim sedang membelek surat khabar yang sebenarnya tidak lagi dibacanya.. fikirannya jauh melayang.
“Saya rasa tak sedap hati, bang…” suara Hajah Sufiah pecah dalam kesunyian. “Saya rasa… kita kena bagitahu Along.”
Cikgu Hasyim menurunkan surat khabarnya perlahan. Pandangannya bertaut dengan isterinya. “Awak rasa rupa tu? Saya ni pun fikir rupa tu. Tapi saya risau…”
“KakLong tu... saya takut tertekan. Hari tu pun... nasib baik kandungan dia selamat. Kalau tidak…” Nada Hajah Sufiah makin perlahan, serak dengan kerisauan yang mendalam.
Cikgu Hasyim menghela nafas panjang. “Saya pun tak tahu kenapa Along tiba-tiba cakap nak nikah dengan anak si Saleha tu. Tak bincang. Tak minta pandangan. Tiba-tiba saja.”
“Itulah yang saya risaukan. Along tu keliru. Dia baru nak pulih. Saya takut ada orang guna dia… ambil kesempatan waktu dia tak ingat.”
“Saya rasa salah kita. Kita sepatutnya cakap siapa Ameena pada dia. Anak Si Saleha tu, tak ada kena mengena lansung dengan dia.”
Suami isteri itu terdiam sejenak. Bunyi jam dinding berdetik perlahan. Udara terasa berat.
“Kita pergi sanalah, Sufi…” kata Cikgu Hasyim akhirnya, suaranya berat dengan tekad.
“Esok pagi-pagi kita gerak. Kita kena tahu apa sebenarnya yang berlaku. Dan kalau betul dia nak kahwin dengan Airis… kita kena tanya dia sendiri kenapa.”
Hajah Sufiah mengangguk, matanya berair. “Saya takut, bang. Saya takut kita hilang anak kita sendiri… bukan dari jasad, tapi dari fikiran dia. Dari hati dia.”
“Jangan risau. Kita doa banyak-banyak malam ni. Minta Allah tunjukkan kebenaran. Saya percaya… hati Along tu masih waras. Cuma dia lupa.. sekejap.. Memang doktor tak bagi kita paksa.. tapi kita kena ingatkan dia. Ameena tanggungjawab dia. ”
Dan malam itu, dalam diam dan tangis, dua insan tua itu bangun menunaikan tahajud... memohon pada Tuhan agar anak yang mereka besarkan dengan kasih sayang itu kembali pulih.
RUMAH itu sunyi. Terlalu sunyi hingga dengung kipas di siling pun kedengaran seperti gema di dalam gua.
Eman berjalan perlahan dari ruang tamu ke dapur, kemudian ke bilik tidur, dan kembali semula ke ruang tamu. Langkahnya tidak tentu arah. Mundar-mandir seperti orang yang kehilangan sesuatu…
Tangannya menyentuh permukaan perabot. Sofa berwarna kelabu itu... kenapa terasa seperti pernah ada insan lain yang sering duduk di situ? Di dinding ruang tamu, ada bekas paku tanpa isi. Seolah ada yang pernah digantung, tapi dicabut dengan tergesa.
Dia berhenti di hadapan meja makan. Kerusi di hujung kanan itu... seperti ada bayang seseorang pernah duduk di situ. Ketawa, berbual, menyuap makanan. Tapi siapa?
Dadanya terasa sesak.
"Kenapa aku rasa… rumah ini pernah ada seseorang?"
Aura itu terlalu kuat. Setiap inci rumah ini seperti menyimpan kenangan yang tidak mampu dia capai. Kabur. Samar.
Dengan perlahan, dia menolak daun pintu bilik bacaan.. bilik yang jarang dia masuk sejak pulang semula ke rumah itu. Bau wangian yang bukan miliknya menyerbu masuk ke rongga hidung. Tenang.
Dia duduk. Menarik nafas panjang. Jemarinya menyentuh permukaan meja, lalu perlahan membuka satu-persatu laci. Entah apa yang dicari, dia sendiri tidak tahu.
Laci pertama kosong. Laci kedua hanya pen, klip kertas dan nota kerja sekolah. Laci ketiga, fail-fail lama dan kertas peperiksaan.
Dan akhirnya, dia menarik laci paling bawah. Tangannya terhenti.
Ada sebuah buku nota bersaiz sederhana. Kulitnya sudah sedikit lusuh, berwarna biru tua. Di muka depannya, hanya tertulis satu perkataan dengan tulisan tangan. Tulisan yang tidak asing padanya. Tulisan tangannya sendiri.
‘SAHABATKU’
Dahi Eman berkerut. Perlahan dia membuka helaian pertama. Dan di situlah segalanya mula menggoncang emosinya.
Tulisan-tulisan itu… ya, tulisan tangannya sendiri. Bukan tentang kemas atau serongnya huruf, tapi tentang apa yang terukir dari jiwa ke kertas. Setiap bait, setiap ayat seolah disulam dari hela nafasnya sendiri.
Eman membelek satu persatu halaman yang telah lama tidur dalam diam. Di situ, tertulis cerita tentang hari pertama dia mengenali seseorang. Puisi demi puisi yang dikarang penuh rasa... semuanya berpaksikan pada satu nama.
Ameena Azzahra.
Nama itu muncul berkali-kali, seperti nadi kepada setiap catatan. Seolah-olah tanpa nama itu, tulisannya akan mati... kosong dan tak bermakna.
Dia tersenyum kecil, cuba mengimbas serpihan ingatan yang kabur. Namun senyum itu lebih seperti riak duka. Kenapa aku lupa pada diari ini…?
Dan akhirnya, matanya terhenti pada tarikh tiga tahun lalu. Tepat ketika memorinya lenyap. Di situlah tertulis segalanya tanpa selindung. Catatan yang menjadi saksi kepada apa yang pernah dia rasakan. Apa yang pernah dia korbankan.
___Dia sebenarnya sudah bercerai? Kau memang bodoh, Bro! Aku… akukah yang bersalah? Melepaskan insan yang aku cinta pada lelaki bodoh macam kau! Siapa akan jadi pelindung dia sekarang?__
Eman terduduk, menyandar di kerusi dengan nafas yang semakin berat. Kepalanya berdenyut, jiwanya bergelora.
___Aku sudah terima calon pilihan emak. Tak mungkin aku kecewakan keluarga aku hanya kerana cinta. Ameena… kenapa awak diam? Kenapa awak tak bagitahu saya awak tak bahagia?___
Tangannya menggeletar. Dia cuba lagi. Cuba menarik semula bayang-bayang yang hilang di celah minda. Namun semuanya seperti kabus—tipis dan tak tergapai.
___Ameena menangis kerana aku… Kenapa? Kau ada rasa yang sama? Maafkan aku, Ameena… sudah terlambat. Tiada apa yang boleh diundurkan. Kotak biru tadi… ya, itu tanda sejak bila kau mula hidup dalam hati aku. Maafkan saya, Amee. Saya cintakan awak sejak dulu tapi malam ini sudah terlalu lewat untuk saya mengakuinya. Semuanya akan hanya melukakan awak lebih dalam.__
Eman menggosok belakang lehernya. Matanya berkedip laju, cuba menolak denyutan sakit dari pelipis yang berdenyut-denyut. Hela nafasnya semakin berat, namun dia terus membaca—seolah tidak mahu lepaskan secebis pun dari masa silam yang sedang mengetuk hatinya.
___Ya Allah… ini adalah hadiah paling berharga dalam hidup aku. Terima kasih Mak dan Abah. Terima kasih juga untuk Ayah dan Ibu. Saya akan jaga dia seperti nyawa saya. Dia adalah hadiah yang tak ternilai.__
Matanya mula berkaca. Dan apabila dia membaca ayat terakhir, dadanya seakan mahu pecah menahan rasa.
__Aku tak sangka jodoh yang aku tak kenali itu adalah Ameena Azzahra. Wanita yang mendiami hatiku sejak dulu lagi. Untukmu, Ameena Azzahra… Jangan salahkan saya. Saya pun tak pernah tahu rancangan keluarga kita. Tapi tiada kata yang mampu saya ucap melainkan syukur. Saya bahagia. Kalau saya tahu itu awak… sumpah, saya tak akan lukakan hati awak malam tadi.cinta__
Buku itu terkulai dalam dakapannya. Bibirnya bergetar, dada turun naik menahan segala rasa yang cuba meledak. Dia terasa seperti sedang membaca kisah hidup orang lain... sedang hakikatnya, itulah kisah hidupnya sendiri. Yang terlupa. Yang terpadam.
Namun rasa itu… perlahan-lahan kembali menyala.
Buku itu terlepas dari genggaman Eman. Nafasnya pendek. Matanya membulat. Air mata mula menitis tanpa disedari.
"Jadi... Ameena isteri aku? Ya Allah... Dugaan apa ini?"
Kepalanya ditundukkan. Jemarinya menggenggam rambutnya sendiri. Dada terasa seperti dihentak berkali-kali.
"Anak itu... anak aku. Amee... kenapa awak tak beritahu? Kenapa, sayang?"
Dia menoleh semula ke buku yang terjatuh. Dipungut semula dengan tangan yang sudah basah oleh air mata. Diselak satu-persatu halaman lagi. Mencari. Mencari kalau-kalau ada nama Airis, atau apa-apa kaitan dengannya.
Namun tiada.
Tiada langsung catatan tentang Airis. Tiada kisah tentang gadis itu. Hanya satu nama... Ameena.
Dan saat dia menyelak halaman terakhir buku itu, satu helaian kertas terlipat jatuh perlahan ke pangkuannya.
Eman memandang kosong sebelum tangannya menggigil mencapai helaian itu. Ada sesuatu pada kertas lusuh itu yang membuatkan jantungnya berdegup luar biasa. Nafasnya terhenti seketika. Tangannya bergetar saat membuka lipatan yang seakan menyimpan serpihan jiwanya sendiri.
“Puisi Buatmu Sayang, Isteriku Ameena Azzahra”
Tulisan itu. Tulisan dia.
Ruang sekeliling tiba-tiba jadi sunyi. Hanya degup jantungnya yang bersahut dengan bisikan yang tidak lagi tertahan dalam dada. Perlahan-lahan, dia mula membaca.
_Jika Esok Aku Lupa_
Jika esok aku lupa,
siapa yang selalu temani aku saat sakit,
siapa yang pernah menangis senyap di sisi,
tolong bisikkan perlahan…
itu kau, isteriku.
Kalau aku lupa nama kau,
atau tak kenal wajah yang paling aku cinta,
jangan jauh… duduklah dekat,
sebab hati ini kenal tangan yang selalu aku genggam waktu takut.
Kita pernah simpan impian dalam satu bantal,
pernah ketawa sampai senja,
pernah rancang tua bersama,
dan aku pernah berdoa,kalau hilang semua,
biar rasa ini tetap ada.
Aku tak harap kau jadi kuat,
aku cuma nak kau tahu,
aku tak pernah menyesal memilih kau.
Tak pernah akan.
Kalau nanti aku diam seribu bahasa,
jangan sangka aku tak rindu.
Doa aku tetap sama..
biar pun tak ingat dunia,
aku tetap nak ingat cinta kita.
Sekurang-kurangnya,
dalam rasa
Kertas itu bergetar di tangannya yang menggigil. Pandangannya kabur, bukan kerana samar cahaya tetapi kerana mata yang sudah berkaca. Air matanya jatuh, tidak sempat ditahan.
‘Ameena Azzahra… isteri aku?’
Suara hatinya bergetar, lirih dalam dada yang sedang retak. Fikirannya kacau, emosinya hancur.
Kenapa? Kenapa semua orang diam? Kenapa dia tak pernah beritahu aku? Amee... kenapa kau tak tegur aku, tak peluk aku, tak bisik satu pun kebenaran yang mampu buat aku percaya…?
Dadanya mula terasa sesak. Rasa kehilangan dan kecewa datang menghempas serentak. Dia bukan sekadar kehilangan memori—dia kehilangan hidup yang pernah dia genggam penuh syukur.
Atau... kau sengaja diam sebab kau dah benci aku? Sebab... Airis? Sebab aku pernah sakiti kau sebelum ini?
Dia sudah tidak tahu siapa dirinya dalam hidup Ameena. Suami? Atau lelaki yang patut dipadamkan dari ingatan?
Tangannya menekup wajah yang basah. Bahunya terhenjut perlahan. Dada bergelombang. Esakan yang ditahan bertahun akhirnya pecah malam itu dalam diam, dalam gelita, hanya bertemankan puisi yang membunuh separuh jiwanya.
‘Kalau ini yang semua orang mahukan… aku akur. Kalau ini yang Amee pilih, aku takkan ganggu dia. Aku tak layak… tak layak langsung untuk dia. Aku kotor. Aku jijik. Aku hanya luka yang dia paksa sembuh setiap hari...’
Dia peluk helaian itu ke dada. Seerat dia pernah peluk kenangan, sekuat dia pernah cintakan wanita itu tanpa pernah dia sedar… cinta itu sudah sah jadi halal. Sudah lama.
‘Amee… maafkan saya. Tapi saya janji. Kebenaran yang terbongkar ini akan kekal rahsia… akan mati dengan saya.’
DI SEBALIK koridor sunyi sekolah, Eman berdiri memeluk tubuh sendiri. Nafasnya turun naik. Dada masih belum reda sejak dia menemui diari itu... dan surat yang pernah ditulisnya, tapi tak sempat disampaikan.
Ameena itu isterinya.
Perempuan yang selama ini hadir dalam mimpinya, kini kembali dalam kenyataan. Tapi berselindung di sebalik wajah yang penuh luka, dan senyum yang dipaksa.
Eman menapak perlahan. Seperti jasadnya digerakkan oleh rindu yang tak tertanggung. Di kejauhan, dia nampak tubuh kecil itu berjalan ke taman botanika sekolah. Tempat pertama mereka bertemu. Tempat dia jatuh cinta… tanpa pernah tahu, cinta itu akan menjadi nyata.
Langkah Ameena perlahan. Seperti tidak tahu hendak ke mana, namun hatinya jelas menuju ke satu tempat.. tempat kenangan itu tersimpan.
Eman mengekori. Dari jauh. Dia hanya mampu melihat. Hatinya bergoncang, matanya berair.
“Ameena… awak isteri saya. Tapi kenapa saya tak mampu peluk awak? Kenapa saya biarkan awak menangis sendiri?”
Ameena duduk di bangku kayu usang yang masih teguh berdiri sejak bertahun lalu. Tubuhnya membongkok. Wajahnya disembunyikan di antara lutut dan lengan. Namun dari jarak itu, Eman tahu isterinya sedang menangis. Hatinya remuk.
Dan di saat itu… Eman rebah ke lutut sendiri. Dia bersandar di dinding batu, menekup muka. Cuba menahan segala rasa yang meronta. Air matanya gugur. Mengalir tanpa malu.
“Ya Allah… kenapa aku diuji begini? Kenapa saat aku sedar dia isteriku, aku pula dihukum oleh dosa silamku?”
Dia terbayang wajah Airis. Tubuhnya yang dia sentuh dalam khilaf. Jeritan hatinya yang memaksa dia bertanggungjawab.
“Aku jijik. Jijik dengan diri sendiri. Ameena tak layak untuk semua ni. Dia terlalu suci… terlalu baik. Sedangkan aku… hanya lelaki kotor yang tak mampu menjaga maruah sendiri.”
Tangan Eman menggeletar. Dia meraup wajahnya berkali-kali, seperti mahu membuang semua kekotoran jiwanya. Namun rindu pada Ameena terlalu kuat. Rindu yang membunuh.
Ameena di hadapannya masih tidak sedar. Masih di bangku itu, membiarkan airmata menjadi saksi cinta yang tidak pernah padam.
“Maafkan saya, Amee… Saya cinta awak. Tapi saya tak cukup baik untuk cinta awak semula.”
Dan Eman… hanya mampu menatap dari kejauhan, dengan hati yang terbelah dua, antara tanggungjawab dan cinta.
Sunyi menjadi teman paling setia, saat air mata jatuh tanpa suara. Bukan kerana cinta itu tiada, tapi kerana hati itu tahu.. ada bahagia yang tak ditakdirkan bersama.
Share this novel
Hanadhia12
2025-05-12 17:35:15
kenapa eman ulang balik kesalahn dia melepaskan amee, sakit oulanhati. Amee pon sama adushhh. Airis bagus berani walaupon tipu ...



