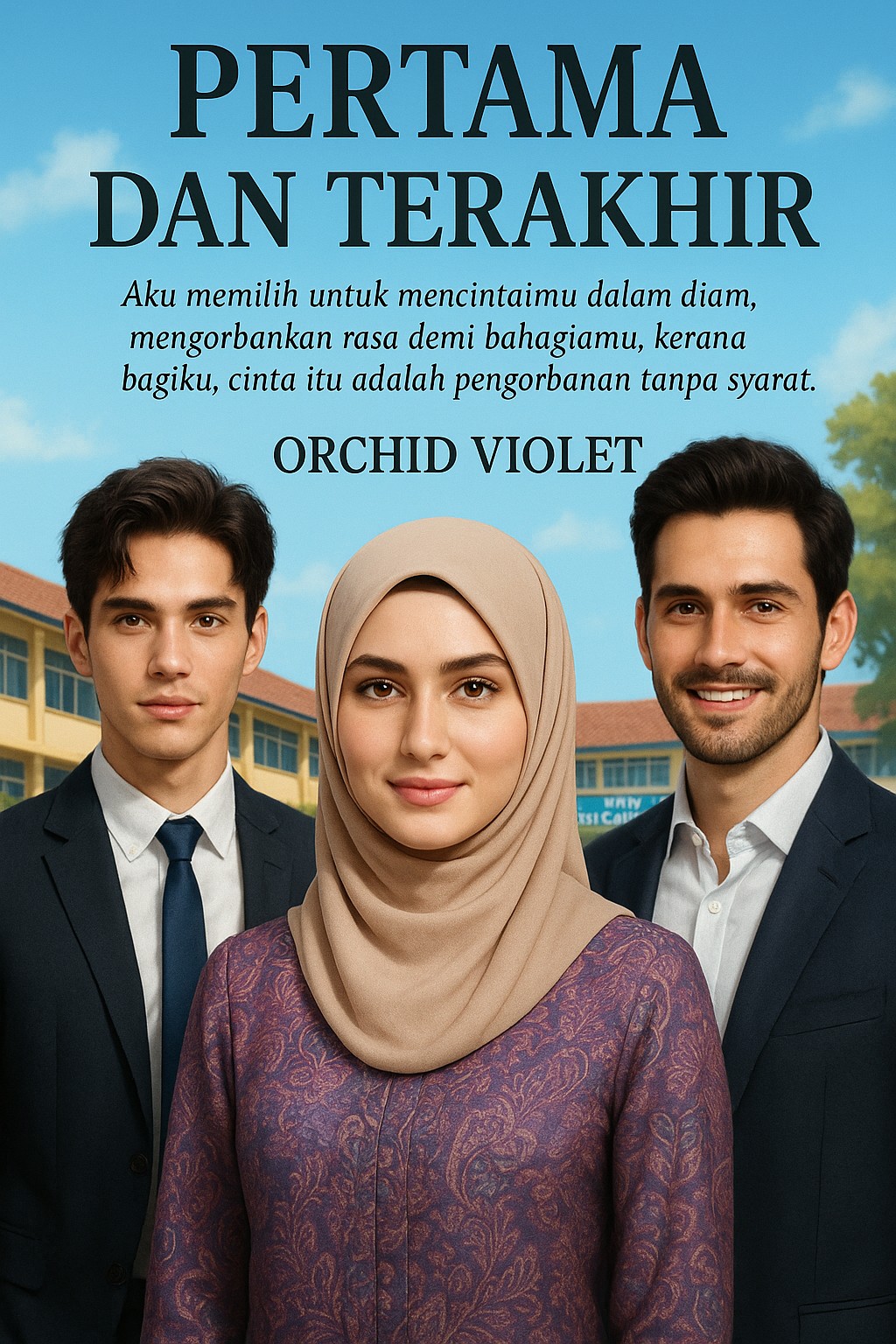
BAB 56 : BAKAL TUNANG?
 Series
Series
 59683
59683
DERUAN enjin memecah sunyi halaman rumah. Hajah Sufiah menjenguk dari balik langsir tingkap kayu. Wajahnya tegang, matanya mengecil memerhati kereta yang baru berhenti. Cermin gelap mengaburkan siapa yang di dalam.
‘Eman.. pulang seorang diri lagi..’ Hati tuanya berdetik, sayu. Bibirnya mengeluh perlahan.
Langkah kaki tangga berderap.
“Mak… Abah mana?”
Suara itu dikenalinya. Eman sudah berdiri di muka pintu, terus merapat dan memeluk tubuhnya yang kecil itu. Ciuman singgah di pipi tuanya. Namun Hajah Sufiah hanya membalas dengan diam. Wajahnya masih kaku. Jauh di sudut hati, amarah seorang ibu belum reda.
“Mak marah Along lagi?” suara Eman sedikit perlahan, mengharap.
“Marah? Buat apa mak nak marah… Kamu tu dah besar panjang, Eman. Dah pandai beza mana betul, mana salah.”
Jawapan itu bukan marah, tapi cukup untuk buat dada Eman terasa perit.
Tiba-tiba… satu suara lembut kedengaran dari belakang.
“Assalamualaikum, mak…”
Hajah Sufiah terpaku. Kakinya terhenti. Perlahan-lahan dia berpaling ke arah suara itu.
Ameena.
Wajah yang dirinduinya saban hari. Wajah yang sering hadir dalam doa tahajudnya. Wajah yang tidak disangka akan kembali menjejak halaman ini bersama anakandanya.
“Ya Allah…” tangan Hajah Sufiah menekup mulut. Air mata yang ditahan-tahan akhirnya tumpah juga. “Anak mak… anak mak…”
Langkahnya laju menyambut Ameena dalam pelukan. Erat. Seolah tidak mahu dilepaskan lagi. Pelukan seorang ibu yang pernah kehilangan, kini dapat semula cahaya harapannya.
“Bertuahlah kamu berdua ni… diam-diam balik. Tak ada sepatah khabar pun. Ibu kamu pun satu.. tak ada pun nak khabar apa-apa dekat mak.”
Ameena senyum dengan genangan air mata. Kepalanya tunduk di dada mertuanya.
Tangan Hajah Sufiah turun ke perut Ameena yang masih kecil tapi cukup untuk dirasai.
“Sihat cucu nenek?”
Eman menyampuk dari sisi, ketawa kecil sambil memeluk bahu isterinya.
“Mak… yang ni menantu mak. Yang ni anak mak ni…”
“Balik dengan isteri Koi la, mak. Nak balik dengan siapa lagi?”
Ameena menunduk. Mukanya berbahang. Malu, tapi hatinya penuh syukur. Ini rumahnya. Ini keluarganya. Dan inilah tempat dia ingin membesarkan zuriat cintanya.
“Mak.. kami bawa tetamu hari ni.. tak apa kan?”
Ameena menggenggam tangan tua itu. Belum sempat Hajah Sufiah bersuara, dua buah kereta sudah menyusul masuk ke halaman. Bunyi enjin dan deruman tayar atas kerikil membelah suasana.
“Haa… tetamu dah sampai…” senyumnya melebar.. Kening Hajah Sufiah seakan bertaut. Cuba mencari tahu, siapa yang bertandang.
Pintu kereta pertama terbuka. Cikgu Fahmi turun bersama isterinya dan tiga orang anak mereka yang sudah besar. Sudah hampir 2 tahun mereka tidak bersua. Yang paling kecil sudah menginjak ke umur tiga tahun.
“Assalamualaikum, Mak Hajah!” panggilan manja dari Cikgu Fahmi yang sudah biasa dengan keluarga itu.
Hajah Sufiah membalas dengan lambai mesra.
“Waalaikumussalam… ya Allah, cucu-cucu mak ni… makin besar, makin comel!”
Intan, Isteri kepada Fahmi bersalaman dan berpelukan mesra dengan Hajah Sufiah.
“Terima kasih mak, tumpang menyibuk lagi musim cuti ni.”
“Eh, sibuk apa… rumah ni memang untuk kamu semua datang. Suka mak ramai-ramai macam ni,” balas Hajah Sufiah penuh ikhlas.
Sebuah lagi kereta berhenti. Kali ini milik Cikgu Isa. Dia turun, membuka pintu penumpang.. keluar Cikgu Lily, tampak sedikit segan tapi tetap tenang.
“Assalamualaikum, Makcik,” sapa Isa, sedikit segan. Tangannya menyinsing lengan kemeja, dan senyumnya masih kelihatan canggung. Cikgu Lily tenang menghulurkan tangannya bersalaman.
“Waalaikumussalam… Mak pernah jumpa awak ni.. nama apa ya?” Hajah Sufiah senyum penuh makna, menyambut keduanya dengan mesra.
“Saya Isa.. Yang ini Lily. Kami sama-sama bertugas dengan Eman dan Cikgu Ameena ni..” Isa masih berdebar-debar. Dia tahu apa yang Hajah Sufiah maksudkan.
“Isa... Kamu anak angkat Kartini kan?” Hajah Sufiah belum puas menyoal siasat. Eman dan Ameena sudah berubah cuak. Tidak sangka Hajah Sufiah akan bertanya banyak.
“Mak... Isa ni kawan Koi.. Bekas suami Amee.” Eman berbisik perlahan di telinga emaknya. Tidak mahu sesiapapun mendengarnya. Demi menjaga hati semua pihak.
Hajah Sufiah tersenyum. Semua cerita sudah ada dalam poketnya. Cuma siapa tuan empunya nama, dia masih belum kenal.
“Maaf mak… singgah kejap. Eman ajak. Dah banyak kali tolak.. segan juga.” Isa ketawa kecil. Sekadar menyedapkan hati sendiri.
“Datanglah… rumah ni bukan rumah orang lain pun. Kalian semua ni dah macam anak-anak mak juga. Tak kisah lah, siapa kamu dulu. Yang penting sekarang dan masa akan datang.”
Hajah Sufiah cuba menyedapkan jiwa-jiwa yang bergelar pendidik itu. Sama dengannya juga suatu waktu dahulu. Banyak cerita dan asam garamnya.
“Dua tiga hari lagi ramailah yang sampai ni…” ujar Hajah Sufiah sambil menjemput tetamu naik ke rumah. “Bolehlah buat kenduri kecil-kecilan. Kita sambut cucu baru mak ni.”
Ketawa kecil bergema di ruang tamu.
BAYU lembut menggoyang reranting, dan dedaunan yang gugur perlahan ke tanah, seperti tahu menyertai tenangnya suasana itu. Bunyi aliran anak sungai membelai telinga, mengalun seperti zikir semula jadi.
Di tebing yang landai, beralaskan tikar kecil dan rimbunan buluh di belakang mereka, Eman duduk di belakang Ameena, menyandarkan dagunya ke bahu isterinya. Tangannya membalut pinggang Ameena erat, seolah-olah mahu menyimpan seluruh kehangatan wanita itu dalam dekapannya.
“Wangi bau Sayang…” bisik Eman di telinga isterinya, suaranya dalam dan lembut.
Ameena tertawa kecil, menunduk sedikit. Pipi merah delima.
“Memang tiap-tiap hari wangi kan..?”
Suara itu manja, mengusik.
Eman ketawa perlahan. “Tapi hari ni macam bau cinta.”
Ameena menjeling ke belakang, “Banyaklah awak punya ayat.”
Eman tidak menjawab. Dia menyelitkan wajah ke celah tengkuk isterinya, mencium perlahan di situ.
Ameena menggeliat. Malu dan tersipu. Berharap tiada yang nampak..
“Abang.... nanti orang nampaklah..”
Eman merebahkan kepalanya ke riba Ameena.
Tangannya memeluk pinggang isterinya dengan kemas, seperti anak kecil yang enggan dilepaskan ibunya. Rambutnya terjuntai ke dahi, dan matanya pejam, menikmati kelembutan tangan Ameena yang mengusap rambutnya perlahan.
"Sayang..." Suara Eman serak, nadanya dalam seperti luahan dari dasar jiwa.
"Sayang tahu tak... tiap kali Abang pandang muka Sayang waktu tidur, Abang takut."
Ameena diam. Jari-jemarinya terus menyisir rambut suaminya, penuh kasih.
"Takut apa?"
Eman membuka mata. Pandangan matanya tepat ke arah perut isterinya yang mula membulat. Tangannya beralih, menyentuh dengan sangat perlahan.
“Takut... semua ni cuma mimpi. Takut satu hari nanti Amee hilang. Atau...Abang hilang lagi. Dan Amee tak tunggu dah.”
Ameena tunduk. Air matanya bertakung. Dia genggam jemari Eman dan membawanya ke dada sendiri.
"Abang pernah hilang... tapi Amee tetap tunggu. Amee tetap cari. Sebab Amee bukan cuma isteri Abang. Amee jiwa Abang."
Eman memandang wajah isterinya.. jari-jarinya menggenggam tangan Ameena yang halus.
“Jauh kan.. kita dah pergi. Tapi Abang bersyukur... sebab Sayang tetap dengan Abang sampai hari ini.. Abang rasa tenang?”
Ameena mengusap rambut suaminya perlahan. Matanya sayu tapi tenang.
“Tenang… sebab awak ada.”
Eman mengangkat tangan Ameena, mengucup jari-jemari itu satu persatu.
“Jari ni... yang jaga Abang masa Abang sakit. Mata ni… yang selalu perhatikan Abang tanpa jemu waktu Abang lupa semua. Hati ni… yang tetap pilih Abang, walaupun Abang bukan lelaki sempurna.”
Ameena tidak mampu berkata apa. Dadanya sesak dengan rasa yang tak mampu dihurai. Tapi wajahnya.. wajah itu penuh cinta.
Lalu Eman bangun perlahan, duduk bertentangan dengan Ameena.
Dia menyentuh pipi isterinya dengan kedua tangan, dan dahi mereka bertemu.
“Kalau dunia ini lenyap, Abang tetap nak jadi lelaki terakhir yang Amee pandang.”
Ameena ketawa kecil sambil tunduk, terlalu malu. Tapi dia tidak menarik diri.
Tangan mereka tetap berpaut, dan anak sungai itu mengalir terus... menjadi saksi dua jiwa yang saling memiliki tanpa ragu.
“Anak ayah… nak tahu tak...” Eman berbicara lagi, kali ini suaranya seolah berbisik penuh kasih ke perut isterinya. “Ayah suka sangat tengok Ibu awak waktu dia sekolah dulu.”
Ameena menjungkit keningnya. Jemari runcingnya masih mengusap lembut rambut Eman. Dia suka. Terasa damai.
“Ayah tak sangka.. pelajar Ayah yang ayah suka sangat tengok dulu.. sekarang dah jadi isteri Ayah. Tak sia-sia Ayah tunggu Ibu. Ayah tolak semua perempuan lain sebab Ayah tunggu Ibu je.”
Ameena tergelak kecil. Ada sendu dalam tawa itu. Hatinya disentuh, namun wajahnya masih menyimpan senyuman. Dia tidak pernah sangka, lelaki yang dulu begitu garang di sekolah, kini begitu lembut, begitu manja… hanya padanya.
“Tapi tu lah.. Ayah sombong.. Masa jumpa Ibu kat kantin.. Ayah tak pandang Ibu pun... Ayah cakap Ibu kerja kantin. Sombong kan Ayah..”
Ameena ketawa perlahan.
“Mana ada Ayah sombong... Ayah malu.. terkejut.. Ayah takut nak pandang Ibu. Takut Ayah tak tentu arah.. Hilanglah macho Ayah.. Ayah kan cikgu disiplin.”
Kali ini tawa Ameena pecah juga. Eman tersenyum puas, lalu kembali merebahkan kepala di riba isterinya. Dia belai perut itu, seolah berbisik lagi dengan zuriatnya.
“Ibu awak tak tahu… jantung Ayah macam mana bila hari-hari kena jumpa Ibu. Jadi mentor Ibu. Kena tanda buku. Kena pantau kelas. Tengok pula muka Ibu yang tak ada perasaan tu… macam nak luruh jantung Ayah. Tapi Ayah kan lelaki… maskulin… kena kawal la semua tu.”
Ameena menggeleng, tak mampu menahan senyum. Tawa mereka berdua menyatu dengan bunyi dedaun yang menari, disaksikan langit senja yang makin kelam. Eman bangun perlahan, lalu tunduk mencium dahi isterinya. Lama. Lama sekali.
“Terima kasih… sebab jadikan mimpi Ayah satu kenyataan.”
Ameena genggam tangan suaminya erat. Suasana sunyi, tapi hati mereka berbicara dalam diam.
ANGIN petang menyapa lembut halaman rumah pusaka itu. Daun mangga melambai perlahan, redup di bawah sinaran cahaya senja yang kian malap. Kanak-kanak ketawa riang, berlari di halaman. Anak-anak Cikgu Fahmi sedang bermain teng-teng, dilayan penuh sabar dan mesra oleh Eman yang sudah tidak kisah berpeluh di bawah cahaya senja.
“Lompat sini… haaa, macam tu… pandai anak Pak Long,” suara Eman disambut gelak tawa kanak-kanak. Ameena hanya tersenyum membayangkan Eman sedang bermain dengan anak-anak mereka.
Di atas pangkin lama, di bawah pokok mangga rendang, Cikgu Lily duduk menyandar perlahan, tudungnya ditiup angin petang. Dia menoleh sedikit ke arah Isa yang duduk di sebelah, kelihatan tenang sambil memerhati suasana.
“Terima kasih, Isa.” Suara Lily perlahan. Tidak mendesak. Tapi cukup jelas untuk sampai ke telinga Isa.
Isa menoleh sedikit. Senyuman muncul di hujung bibirnya. Tapi tidak sepatah pun dibalasnya, hanya pandangan mata yang lembut, seolah-olah menyatakan, ‘aku faham.’
Lily menghela nafas perlahan, lalu membetulkan bingkai cermin matanya yang sedikit senget.
“Aku maksudkan hari tu… masa kau datang… bila Hakimi tu cari aku…” Suaranya perlahan, ada seribu satu rasa yang belum selesai.
Isa tunduk sebentar, seolah-olah menyusun kata, sebelum pandangannya kembali pada Lily.
“I tahu You tak suka drama, Lily. I cuma tak sanggup tengok muka You macam tu. Lelaki tu tak layak buat You rasa kecil. Tak layak dia pijak maruah You”
Lily diam. Tapi matanya berkaca. Angin petang makin sejuk, tapi dadanya terasa hangat dengan kata-kata itu.
Isa bersandar lebih selesa. Tangannya bermain dengan ranting kecil di sisi pangkin.
“I tak tahu kenapa I cakap macam tu hari tu…” dia senyum sedikit, lalu menoleh perlahan, mata bertaut dengan mata Lily. “Tapi hari ni… I masih maksudkan apa yang I katakan.”
Lily menoleh perlahan. “Apa maksud kau?”
Isa senyum. Perlahan, tenang. I tak pandai berkias Lily.
“I kata I bakal tunang You, kan?” Dia ketawa kecil. “Masa tu mungkin alasan. Tapi sekarang… I tak main-main. I memang maksudkannya.”
Lily terpaku. Wajahnya berbahang, tapi senyum kecil di bibirnya tak dapat ditahan. Ya.. hatinya sudah terpaut. Kerana keihklasan.
Di halaman, suara kanak-kanak masih riuh. Eman ketawa sambil mengejar si kecil yang melompat ke kotak terakhir teng-teng.
Dari atas pangkin, dua jiwa yang pernah luka kini saling belajar untuk memaafkan takdir.
Angin petang yang tadi tenang bertukar suram sekelip mata.
Teriakan nyaring mengejutkan semua yang sedang bersantai di halaman. Dari celahan pagar, kelibat seorang wanita menerpa deras.. rambutnya kusut, wajahnya merah padam seperti disambar api amarah. Pisau dapur terhunus di tangan kanan. Nafasnya laju. Matanya liar.
“AMEENA!!!”
Airis.
Ameena tak sempat mengelak. Tubuhnya disambar kasar. Pisau tajam ditekup ke lehernya. Jeritan kecil kedengaran.
“ALLAHUAKBAR!” Intan menjerit atas serambi rumah induk..
“Anak-anak! Sayang.. ambil anak-anak! Sekarang!” laung Cikgu Fahmi. Dengan pantas, dia menarik dua anak kecil ke dalam dakapan dan membawanya kepada Intan.
“Cepat bawa anak-anak naik atas !”
Cikgu Lily menekup mulutnya, wajahnya pucat. Isa berdiri, langkahnya teragak-agak. Tidak percaya apa yang sedang berlaku di depan mata.
“Airis! Airis apa kau buat ni?!” jerit Isa, cuba melangkah ke hadapan.
“Jangan dekat!” jerit Airis.
“Siapa pun jangan dekat!”
Ameena menggigil. Nafasnya tidak teratur. Dia hanya mampu menatap wajah Eman… penuh harap. Penuh ketakutan.
Share this novel



