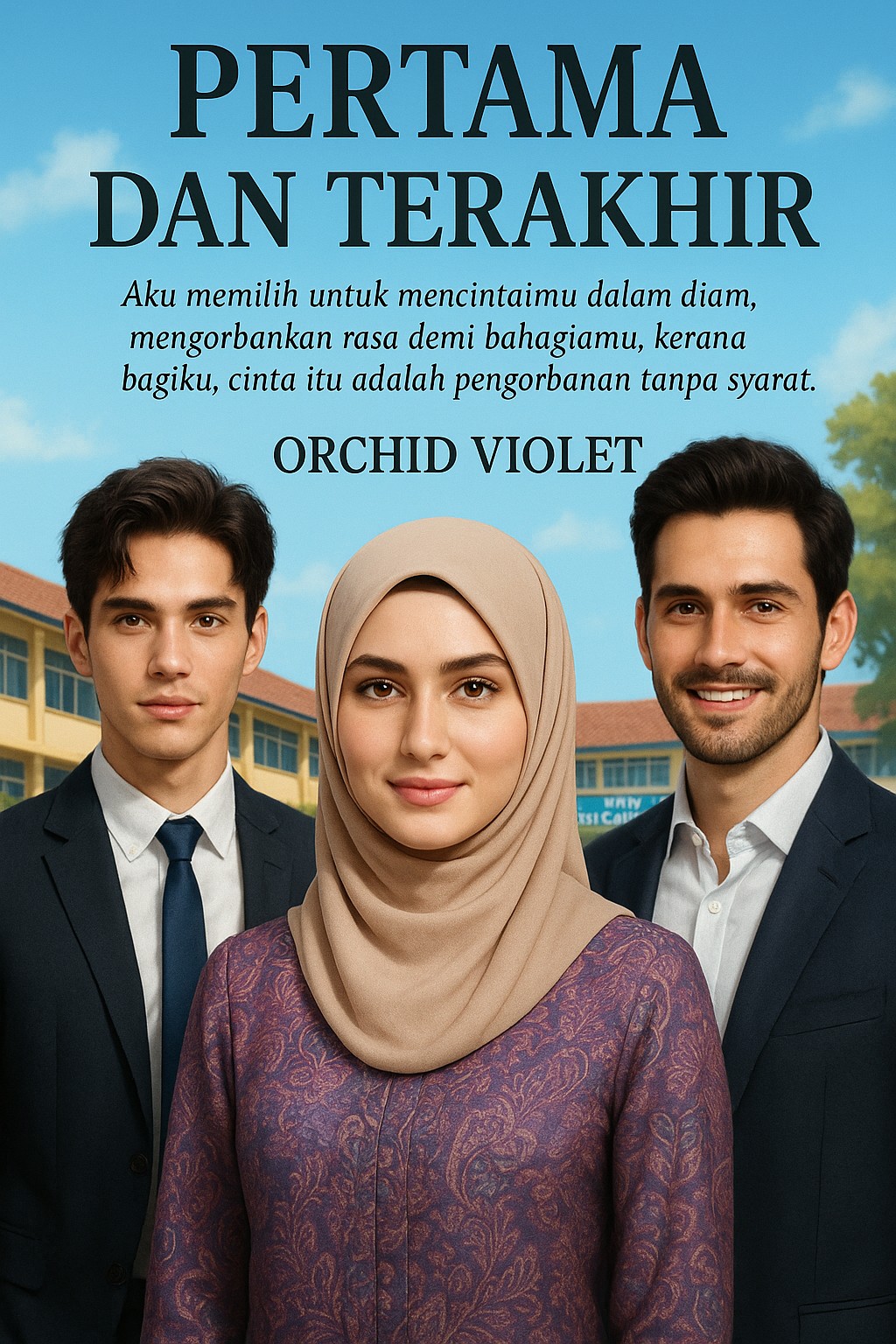
BAB 51 : KAKI PEREMPUAN?
 Series
Series
 59683
59683
RUMAH itu… kosong.
Bukan kerana tiada perabot. Bukan kerana tiada orang. Tetapi kosong pada rasa. Seolah-olah segala cahaya yang pernah menjadikan rumah itu syurga kecil telah lama padam. Hajjah Sufiah melangkah masuk perlahan. Tangannya menggenggam erat tangan suaminya, Cikgu Hasyim. Rumah anak mereka itu nampak kemas, bersih… tetapi tidak hidup.
Dan di tengah ruang tamu, berdiri seorang lelaki.. anak mereka, dengan wajah yang tidak pernah mereka lihat sebelum ini. Wajah yang berlapis seribu kekecewaan. Kekecewaan pada dunia. Pada diri sendiri.
"Eman…" Suara Hajjah Sufiah sayup.
“Mak… Abah…” Eman menyambut langkah mereka. Nada suaranya datar.
“Kenapa datang tak beritahu?”
Hatinya sebenarnya gugur. Bukan kerana marah, tapi kerana dia tahu saat itu juga, semuanya akan terbongkar.
“Kami datang sebab rindukan anak kami. Itu salah ke, Along?” Hajjah Sufiah bersuara perlahan, namun terasa pedih dalam dada.
Eman tunduk.
“Along tak sempat sediakan apa-apa pun. Mak, Abah… dah makan ke?”
Tiada siapa menjawab. Mereka terus melangkah masuk ke ruang utama. Eman mengambil beg pakaian mereka. Langkahnya berat. Seolah-olah beban dunia diletakkan pada bahunya.
Dan akhirnya, Cikgu Hasyim bersuara. Tegas. Lurus. Jujur.
“Along, Abah terus terang. Kami tak tenang sejak awak cakap nak nikah dengan anak Saleha tu.”
Eman tersenyum tawar.
“Bukan itu ke yang Mak dan Abah nak dulu? Kami dah lama bertunang, kan?”
Sejenak sunyi. Hajjah Sufiah tunduk. Matanya sudah berkaca.
“Along… kamu tak pernah bertunang pun dengan Airis…”
Suara itu pecah di hujung ayat. Seolah-olah meruntuhkan segala yang Eman percaya selama ini.
Dia mengangkat muka. “Tak pernah…?”
Nada itu perlahan, tapi ada getar. Ada luka. Ada marah yang cuba dikawal.
“Kami salah… Kami takut nak beritahu kamu. Masa tu kamu baru sedar dari koma, kamu sebut-sebut Airis. Doktor pun tak bagi kami paksa kamu ingat. Kami fikir… biarlah dulu. Tapi bila kamu cakap nak nikah, kami tak boleh biar.”
‘Along pun tak nak sebenarnya, Mak…’ bisik Eman dalam hati. Tapi dia diam. Dia telan.
Cikgu Hasyim menyambung, kali ini suaranya berubah. Ada getar di hujung nada.
“Along… kamu dah ada isteri. Dan isteri kamu sedang mengandung. Itu anak kamu. Tanggungjawab kamu.”
Dan pada saat itu nama itu disebut.
"Ameena."
Eman diam. Matanya berkaca. Tapi dia pura-pura terkejut. Dia mainkan peranan sebaik mungkin.
“Ameena? Isteri Along?”
“Ya… isteri kamu. Isteri sah kamu!” tegas Hajjah Sufiah, nadanya sudah mula tinggi.
“Awak tak ingat tak apa… Tapi takkan hati awak tak rasa? Dia isteri awak, Eman. Dia yang jaga awak… sepanjang awak dekat ICU, sepanjang awak sakit.. dia tak tinggal awak walau sesaat pun. Dia tak pernah tinggal!”
Eman menunduk. Tubuhnya menggigil perlahan.
Kenapa kau tak beritahu aku sendiri, Amee…? Atau kau… dah tak sudi jadi isteri aku lagi?
“Kalau betul dia isteri Along… kenapa dia sendiri tak pernah cakap apa-apa? Tak pernah… pegang tangan Along, tak pernah pandang macam orang yang ada hak…”
Suaranya pecah. Tapi dia masih pura-pura. Dia sedang menyeksa dirinya sendiri dengan kebohongan.
“Along dah sayang Airis…”
Bohong. Dusta. Keji. Tapi itu saja cara nak jauhkan diri dari semua ini. Dari kenyataan yang terlalu menyakitkan.
Dan pada saat itu…
PANG!
Tamparan sulung itu sampai. Tepat di pipi kiri Eman. Dunia sekelilingnya seolah berhenti.
Eman tidak membalas. Tidak mengangkat muka. Tidak berundur. Dia biarkan tamparan itu menjadi penebus segala dosanya.
Hajjah Sufiah terduduk. Menangis. Tangisan ibu yang tidak tahu lagi bagaimana cara menyelamatkan anaknya dari menghancurkan diri sendiri.
“Along… Along anak Mak… Tapi Along buat Mak malu hari ni…” suaranya pecah, lelah, penuh kecewa.
Cikgu Hasyim hanya diam. Tapi dari air mukanya, luka itu sama dalam.
Dan Eman… hanya tunduk. Diam.
‘Maafkan Along… Mak, Abah. Along bukan anak yang baik. Along anak yang tak guna.’
“Bro... awak biar betul. Kawan tak boleh hadam ni. Awak dah tahu Cikgu Ameena isteri awak, tapi awak tetap nak kahwin dengan budak kerani tu?”
Nada Cikgu Fahmi masih terkawal, walau wajahnya jelas menahan amarah. Eman datang padanya hari itu dengan wajah yang sugul, katanya ingin meluahkan rasa. Tapi semua itu... terasa seperti sandiwara. Fahmi tahu—Eman masih keliru. Makin parah.
Dan sekarang, dia hanya mampu menggeleng.
“Dan awak, Bro... kenapa tak pernah bagitahu koi? Yang Ameena tu isteri koi?” Suara Eman sedikit bergetar.
“Koi lagi kecewa dengan awak. Awak kawan koi... tapi awak sama je macam orang lain. Sembunyi, tipu.”
Eman tunduk. Tangannya meraup rambut ke belakang, nafasnya berat.
“Family awak minta kawan tolong. Minta semua cikgu-cikgu dekat sini bantu. Mereka tak nak awak terbeban dengan memori yang awak sendiri tak mampu cari. Paksa pun... kepala awak boleh pecah, Bro.”
Fahmi mengalih pandangan ke tengah padang. Kelihatan pelajar-pelajar perempuan sedang berlatih bola baling. Riuh-rendah suara mereka bagaikan berlatar pada drama tak masuk akal yang sedang berlaku.
“Bro... tak masuk padang lagi ke?”
Satu suara menegur dari belakang.
Cikgu Isa muncul, mengangkat kening. Eman dan Fahmi sama-sama berpaling.
“Isa...” Eman senyum kecil. Wajah bersalah itu tidak mampu disembunyikan. Matanya singgah sebentar pada kesan lebam di bibir Isa.
Isa hanya mengangkat kening, memberikan isyarat mata pada Fahmi yang turut menyambut dengan senyum hambar.
“Kau tanya sendiri la dengan kawan kau ni,” Isa berkata tenang, tapi jelas sinis.
“Aku pun tak tahu setan mana yang rasuk otak dia sekarang.”
“Bro... kenapa?” soal Isa pendek, lalu duduk di sisi mereka. Tiga sahabat. Tiga lelaki yang suatu ketika dulu digilai ramai pelajar perempuan, juga guru-guru bujang. Tapi cinta mereka hanya pada yang satu.
“Maaf, Bro... aku tertumbuk kau hari tu.”
Isa terdiam. Keningnya terangkat. “Kau dah ingat ke?”
Eman angguk perlahan. Isa ketawa, ikhlas. Bahunya digoncang Eman perlahan, lalu ditepuk beberapa kali. Dia lega. Sangat lega.
Namun, kegembiraan itu tidak kekal lama.
“Tak payah seronok sangat, Bro,” suara Fahmi mencelah, hambar. “Dia tak ingat pun. Cuma tahu Ameena tu isteri dia. Tapi hati dia... mungkin dah mati. Sekarang dia gilakan budak kerani tu. Nak nikah pula dengan perempuan tu. Kawan suspicious betul.”
Isa berdiri. Mukanya merah. Nafasnya kasar. Fahmi sudah langgar sempadan.
“Kau gila ke, Bro?! Kau tak nampak ke Ameena tu tengah mengandung?!”
Kata-kata Isa memecah ketenangan.
“Ya... aku gila!” suara Eman meninggi.
“Otak aku ni macam nak pecah! Korang tak tahu... korang semua tak faham!”
“Tahu apa, Bro? Yang kau sanggup buang isteri sendiri sebab percaya cakap perempuan entah dari mana tu?”
Fahmi makin meninggi suara.
“Sampai hati kau buat macam ni.”
Dia menahan marah. Sungguh, dia cuba faham situasi Eman. Tapi ini sudah keterlaluan.
Eman terdiam. Dia tunduk, menatap rumput. Suaranya perlahan, hampir seperti bisikan.
“Bro... Fahmi... aku ni jenis lelaki macam mana? Aku ni kaki perempuan ke?”
Fahmi terhenti melangkah. Soalan itu... buat dia tergamam.
“Soalan kelakar apa ni?” Dia berpaling.
“Kaki perempuan?”
Eman angguk, jujur. Wajahnya tampak lurus, kosong, dan takut.
Isa tergelak kecil.
“Kalau kau kaki perempuan, tak adalah Cikgu Ameena boleh nikah dengan aku dulu... Kau nak mengorat pun kaku.. inikan nak buat ayat manis.. Kau buat lawak ke?”
“Airis... dia cakap...”
Langkah Eman mati. Lidahnya kelu.
“Airis cakap apa?” soal Fahmi, wajah mula berubah.
“Apa lagi yang budak tu goreng?”
Eman telan liur. Berat.
“Dia cakap... kami dah terlanjur. Dia cakap koi yang paksa...”
Sejurus itu, Isa dan Fahmi tergelak serentak. Reaksi spontan. Geli hati. Sakit hati. Bercampur.
“Bro, awak ingat tak dulu Cikgu Lily macam mana? Seksi nak mampus. Pakaian dia.. ya Allah, bukan macam sekarang. Sepuluh kali lebih cantik dari budak kerani tu. Hari-hari datang goda awak,” ujar Fahmi sambil ketawa.
Eman berkerut. Cikgu Lily... ya, dia ingat sedikit. Tapi perangai itu... tidak.
“Dia pernah perangkap kau, Bro. Dekat hotel, ingat? Tapi sikit pun kau tak sentuh dia. Sebab kau ada iman. Nama kau pun... Eman.”
Fahmi menepuk bahu Eman, kuat.
Eman ketap bibir. Perlahan-lahan, dia menoleh.
“Jadi... Airis bohong?”
“Ya, dia bohong!” Isa menyampuk.
“Celah mana kau nak ‘terlanjur’? Kau 24 jam dengan Ameena. Datang gelanggang pun selalu berdua. Bila masa? Cuba kau cakap.”
Fahmi mengangguk. “Kalau nak tahu jadual awak... kawan hafal. Cikgu Ameena tu, dia punya risau pasal awak... lambat sikit je, dia terus mesej kawan. Dia tak mesej awak, sebab banyak kali awak sakitkan hati dia. Tapi kaki perempuan? Tak pernah, Bro.”
Isa menyengih. “Kalau yang ni kaki perempuan... mungkin la,” sambil menunjuk ke diri sendiri.
Fahmi tergelak melihat muka cemberut Isa.
“Tapi serius, Bro... kau jangan percaya mulut orang. Jangan buat keputusan dari mimpi semata.”
Eman tunduk. Tangannya menggenggam kuat.
“Aku takut... Airis kata... dia mengandung anak aku.”
Sunyi.
Fahmi genggam penumbuk. Jika Airis ada di depan, entah apa akan jadi.
Isa pula sudah mengetap rahang.
“Tak apa,” Isa bersuara perlahan.
“Esok ada Hari Dadah. Semua pelajar, kakitangan sekolah akan turun. Kalau dia nak main gila... dia silap orang.”
Dia senyum. Senyum yang tidak menyenangkan.
AMEENA berteleku di sudut taman mini, di bawah pohon rendang yang biasa menjadi tempat dia menenangkan diri. Hujan baru berhenti turun, meninggalkan bau tanah basah dan dedaun yang masih berat dengan titik air. Di pangkuannya, sehelai selendang polos yang Eman pernah beli sewaktu lawatan sekolah ke Melaka. Dia pegang erat, seolah-olah dapat menyalur rindu melalui serat kain itu.
Perutnya mula terasa berat, bukan kerana kandungan semata, tapi kerana beban emosi yang tiada hujung.
Dia tahu. Eman sudah tahu siapa dia. Sudah tahu mereka suami isteri. Sudah tahu anak dalam kandungannya itu darah dagingnya sendiri.
Namun Eman tetap mahu nikah dengan Airis. Itu yang Mak dengan Abah cakap sebelum balik ke Pahang.
Ameena terdiam. Hati seperti dicecah bara. Paru-paru seakan sempit untuk bernafas.
"Ya Allah... kenapa Kau uji aku begini?" bisiknya perlahan.
Angin petang menyentuh pipinya, mengeringkan air mata yang tak sempat dilap.
Hatinya tidak marah.. hanya luka. Luka yang dalamnya tak terukur. Jika dulu dia sabar kerana Eman tak mengenalnya, itu dapat dimaafkan. Tapi kini, setelah Eman tahu, setelah memori sedikit demi sedikit kembali...
Mengapa masih memilih orang lain? Bukan dia? Bukan mereka?
Ameena meraup wajah. Sakit yang menyesak dadanya bukan lagi kerana cinta tapi kerana rasa dikhianati oleh insan yang dulunya sanggup bersujud bersamanya, mengangkat tangan bersama memohon syurga rumah tangga.
"Tak cukupkah cinta aku?"
Langit semakin kelam. Seperti hatinya. Dia tahu tiada siapa akan mengerti. Qadeeja pernah cuba memujuk. Ameer hanya mampu memeluk dan menyuruhnya bersabar. Tapi sabar itu sendiri telah reput dalam dadanya.
Dia terdongak. Wajahnya basah oleh air mata yang entah bila mengalir.
"Kalau Eman sanggup... berpaling walaupun dah tahu semua..." suaranya tersekat,
"...mungkin dia dah tak perlukan aku."
Tangannya meraba perut yang sedikit menonjol. Sudah masuk empat belas minggu kandungannya.
"Tapi ibu ada kamu..." Dia tersenyum hambar.
"Kamu, buah hati ibu."
CIKGU Lily terdiam mendengar berita mengenai Eman melalui Isa. Rasa bersalah bertimpa-timpa datang. Patutlah Cikgu Ameena cuti hari ini. Kesiannya .. Ya Allah. Matanya tiba-tiba menangkap susuk seseorang. Airis.
“ Bahagia kamu sekarang?”
“Oh. Cikgu Lily.” Senyuman tipis menghiasi bibirnya. Sinis.
“Kenapa? Awak sangka orang tak tahu apa yang awak buat?”
Airis menyilang tangan, sedikit mengangkat dagu. “Saya tak faham maksud cikgu.”
Lily senyum pahit. “Awak tak perlu pura-pura. Saya pernah jadi awak dulu, Airis. Saya tahu perasaan minat orang yang tak mungkin jadi milik kita.”
Airis mencebik. “Saya tak pernah rampas sesiapa.”
“Ya?” Lily menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tiada murid di sekitar.
“Kalau betul... awak tak akan reka cerita konon Eman paksa awak. Tak akan tuduh dia, sampai dia rasa dia binatang. Sampai dia nak kahwin awak kerana rasa bersalah, bukan kerana cinta.”
Airis tergelak kecil.
“Cikgu pun percaya cakap orang? Eman sendiri yang datang pada saya. Dia cari saya. Bukan saya yang paksa.”
Lily menggenggam tangan. “Cinta bukan alasan untuk buat dosa. Bukan alasan untuk pisahkan suami isteri. Tambahan pula, isteri dia tu sedang hamil.”
Airis mula goyah. Tangannya menggigil sedikit. Tapi mulutnya masih mahu menang.
“Dia yang cari saya. Dia yang... yang sentuh saya dulu…”
“Fitnah awak tu... akan makan diri sendiri satu hari nanti.” Lily sudah tidak mahu meneruskan.
Sebelum berlalu, dia menoleh semula. “Saya pernah macam awak. Tapi saya belajar tunduk pada takdir. Dan saya harap awak pun sempat belajar sebelum semuanya musnah.”
Share this novel



