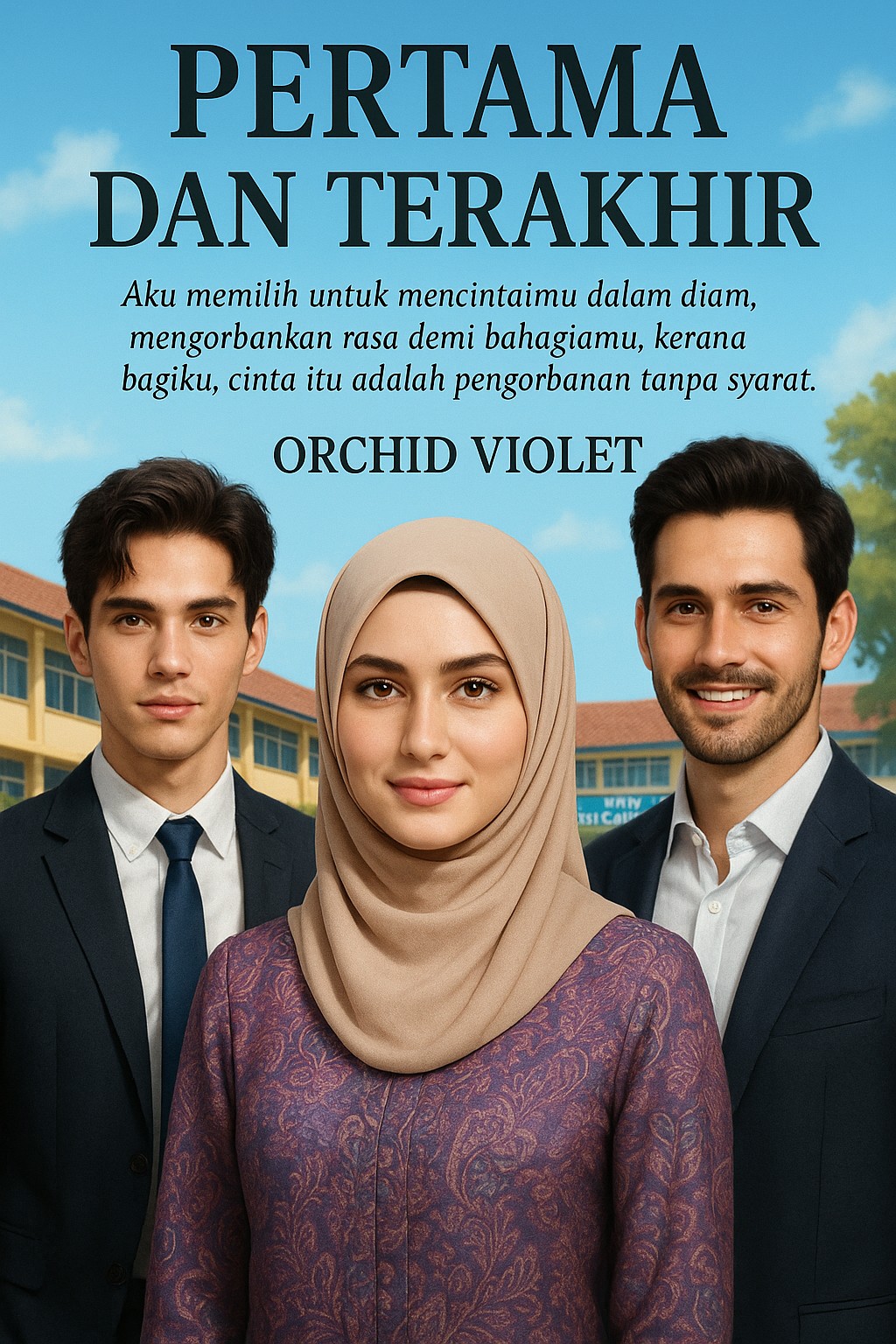
BAB 55 : Cinta Tak Perlu Dekat Untuk Dirasa
 Series
Series
 59683
59683
LANGIT senja mencurahkan cahaya tembaga ke seluruh laman, seolah menyambut kepulangan seorang permaisuri yang lama terasing dari takhtanya.
Ameena berdiri di hadapan rumah itu.. banglo yang pernah menjadi syurganya, namun juga pernah menjadi saksi air mata yang tidak tertanggung.
Rumah yang pernah menjadi tempat dia membayangkan hari tua, kini berdiri bagai mimpi yang disentuh realiti.
Jari-jarinya perlahan-lahan menyentuh daun pintu kayu yang pernah dibelai cinta. Dedaunan yang gugur di laman seolah menyapa semula langkahnya, bertanya dengan bisu, ‘ke mana perginya tuan rumah kami selama ini?’
Ameena diam. Nafasnya sesak.
Air matanya gugur setitis demi setitis, menuruni pipi yang sudah sekian lama lelah menangis dalam diam.
Tangannya refleks memegang perutnya. Masih belum kelihatan… tetapi di situ tumbuh cinta baru. Cinta yang tidak pernah dia duga akan hadir saat segala-galanya hampir musnah.
Tiba-tiba, hangat satu jemari meraih jemarinya.
“Sayang…”
Suara itu. Suara yang dirindui dalam doa malamnya. Suara yang dia sangka tidak akan memanggilnya begitu lagi.
Dia menoleh.
Eman berdiri di belakang, wajahnya lembut, seperti dahulu. Tapi kali ini ada sesuatu yang lain dalam matanya.. penuh penyesalan, penuh pengharapan, dan… penuh cinta.
“Kenapa berhenti dekat sini?” bisik Eman, suaranya hampir seperti doa.
“Rumah ni… bukan rumah kalau awak tak masuk semula.”
Ameena menggeleng perlahan. Suaranya bergetar saat dia cuba menahan tangis.
“Macam mimpi, Abang… Saya takut bila tersedar, semua ni hilang semula.”
Eman menatapnya penuh hiba.
“Kalau ini mimpi, biar kita tidur bersama dalamnya. Kalau ini realiti, izinkan saya buktikan… yang cinta tak pernah lari. Ia hanya sesat sekejap.”
Dia menunduk, mencium tangan isterinya dengan lama.
“Tangan ni pernah pegang hati saya, Amee. Dan bila saya hilang ingatan, jantung saya masih cari tangan ni. Saya tak ingat jalan pulang, tapi saya ingat rasa selamat bila ada awak.”
Ameena menangis tanpa suara.
“Sayang…” Eman menyentuh perut isterinya yang masih rata.
“Bukan hanya kita yang pulang. Anak kita juga menunggu rumahnya. Mari masuk… bukan sebagai tetamu, tapi sebagai pemilik jiwa rumah ini.”
Dengan tangisan pilu bercampur bahagia, Ameena akhirnya melangkah masuk.
Ameena melangkah masuk dengan perlahan. Setiap tapak kaki terasa bagai menjejak masa lalu antara serpihan bahagia dan luka yang belum sembuh.
Dia mengangkat wajah.
Matanya jatuh pada dinding ruang tamu.
Dan di situ… sebaris bingkai-bingkai kenangan yang dulu pernah dia tanggalkan satu per satu, dalam deraian air mata dan hati yang patah.
Gambar perkahwinan mereka, gambar percutian di Langkawi, gambar candid Eman menyuapnya ais krim sambil dia marah-marah manja.. semuanya tergantung semula, pada susunan asal yang tidak berubah walau seinci.
Ameena ternganga kecil. Nafasnya tersekat.
“Ya Allah…”
Dia menghampiri dinding itu, jari-jemarinya menggeletar menyentuh bingkai kaca yang membungkus senyumannya sendiri.
Senyuman yang pernah dia lupa. Senyuman yang pernah dia benci kerana terlalu sakit untuk dikenang.
“Abang gantung balik semua ni?” suaranya parau, antara terkejut dan sayu.
Eman berdiri di belakangnya. Dia tidak menjawab segera.
Sebaliknya, dia melangkah perlahan ke sisi isterinya. Matanya juga menatap gambar-gambar itu.
“Setiap satu Abang cari semula… Abang cuba ingat semula semua susunannya.. walaupun kepala Abang ni hampir nak pecah malam tadi..”
Nadanya tenang, tapi penuh harap. Senyuman nipis tergaris di bibirnya bersama pandangan redupnya.
Lengan sasa itu memeluk kemas isterinya daripada belakang. Seolah tidak mahu melepaskan lagi. Dagunya disangkut pada bahu kemas isterinya.
“Sebab Abang yakin… satu hari nanti Sayang akan pulang. Dan Sayang patut tahu, kenangan kita tak pernah Abang buang.”
Ameena menekup mulutnya. Dadanya bergelora hebat.
“Abang tahu tak, masa saya cabut semua ni dulu… saya rasa macam saya cabut jantung sendiri?”
Eman mengangguk perlahan.
“Sebab tu abang gantung balik. Supaya hati Amee tahu, tempatnya masih di sini.”
Ameena berpaling. Matanya berlinang, basah dengan rasa yang tak mampu diterjemah oleh kata.
Dan dalam diam… dia tahu, rumah ini bukan sekadar tempat tinggal.
Ia adalah tubuh cinta mereka.
Dan dinding-dinding itu, masih setia menyimpan degup yang tidak pernah mati.
“Sayang…” bisik Eman dekat telinganya.
Tiada kertas di tangan, tiada catatan di mana-mana. Hanya suara, dan getar rasa dari hati yang benar-benar ingat. Ingat walau dunia pernah jadi kelam.
Kemudian, dengan nada selembut bayu yang menyentuh telinga Ameena, Eman bersuara…
“Jika esok aku lupa,
siapa yang selalu temani aku saat sakit,
siapa yang pernah menangis senyap di sisi,
tolong bisikkan perlahan…
itu kau, isteriku.
Kalau aku lupa nama kau,
atau tak kenal wajah yang paling aku cinta,
jangan jauh… duduklah dekat,
sebab hati ini kenal tangan yang selalu aku genggam waktu takut.
Kita pernah simpan impian dalam satu bantal,
pernah ketawa sampai senja,
pernah rancang tua bersama,
dan aku pernah berdoa, kalau hilang semua,
biar rasa ini tetap ada.
Aku tak harap kau jadi kuat,
aku cuma nak kau tahu,
aku tak pernah menyesal memilih kau.
Tak pernah akan.
Kalau nanti aku diam seribu bahasa,
jangan sangka aku tak rindu.
Doa aku tetap sama…
biar pun tak ingat dunia,
aku tetap nak ingat cinta kita.
Sekurang-kurangnya,
dalam rasa.”
Ameena tidak mampu berkata apa-apa. Dadanya sesak oleh rasa yang tak terungkap.
Dia hanya mampu menggenggam lengan Eman yang melingkari tubuhnya — seerat mungkin.
Dan di antara hela nafas yang panjang dan mata yang kabur oleh air mata, dia berbisik perlahan…
“Amee tak perlukan apa-apa lagi dalam hidup ini… selain abang.”
Dalam pelukan itu, rumah itu terasa hidup semula. Bukan sekadar bangunan batu. Tapi mahligai tempat doa, luka, rindu dan cinta mereka akan terus bernafas.
Suasana pagi di sekolah berjalan seperti biasa.. derapan kaki pelajar, bunyi loceng masuk kelas, suara cikgu yang memberi arahan dari jauh. Namun di dalam sebuah kereta yang terparkir di sudut sunyi, waktu seakan-akan terhenti.
Ameena tersenyum manja, penuh cinta.
Wajah suaminya yang masih bersandar di pangkuan membuatkan hatinya berbunga.
Dia tahu Eman masih enggan keluar. Masih belum puas menatap, menyentuh, dan merasai kehadirannya yang sebenar.
“Abang..”
Ameena membelai rambut suaminya perlahan, seraya tersenyum dengan nada menggoda.
“Nanti lambat masuk kelas…”
Namun Eman hanya menggeleng manja.
Dia membongkok lebih rapat, wajahnya hampir bersentuhan dengan perut isterinya.
Dengan perlahan, dia melekapkan telinganya di situ, seakan-akan mencari denyut kecil yang sudah pun mencuri sebahagian jiwanya.
“Hari ni, kita pinjamkan Ibu kejap, boleh?” bisiknya lembut kepada si kecil dalam rahim.
“Nanti Ayah janji… lepas loceng terakhir, Ayah curi dia balik.”
Ameena tergelak kecil, namun matanya mula berkaca.Tiap kali Eman menyentuh perut itu, terasa cinta mereka semakin bertunas… bukan hanya sebagai suami isteri, tapi kini sebagai ibu dan ayah.
Eman menoleh, mengangkat wajahnya, dan mendongak memandang isterinya.
"Sayang tahu tak?" katanya, suaranya bergetar lembut,
"Setiap kali abang pandang perut ni… abang tak nampak bayi saja. Abang nampak doa yang Tuhan jawab perlahan-lahan. Abang nampak pengampunan. Abang nampak permulaan baru."
Ameena menggenggam tangan suaminya yang menyentuh perutnya.
Untuk seketika, mereka diam. Berbicara dengan mata.
Mengisi ruang yang lebih indah daripada mana-mana kelas yang bakal menanti mereka hari ini.
Kemudian perlahan, dengan berat hati, Eman menarik nafas panjang dan berkata,
“Okay. Sekarang abang keluar dulu… tapi nanti, lepas waktu rehat… jangan ke mana-mana. Abang nak duduk sini lagi. Dengar suara anak kita cakap balik…”
Ameena tersenyum sambil menggeleng.
“Anak kita belum pandai cakap lagi, tendang-tendang pun belum abang…”
“Tapi dia pandai buat abang rindu…”
Eman mencuit hidung isterinya, sebelum membuka pintu kereta.
WAKTU senggang. Loceng kelas sudah lama berhenti berdengung. Suasana sekolah seperti kembali bernyawa dalam tenang. Pelajar-pelajar lalu-lalang di koridor, suara tawa kecil menyapa angin pagi yang masih dingin.
Eman berdiri di tingkat satu antara blok kelas dan bangunan pentadbiran. Kemeja batik sekolahnya sedikit berkibar ditiup angin. Buku di tangan sekadar alas pandangan kerana matanya, sejak tadi, hanya tertumpu pada satu arah.
Di meja guru di dalam kelas Tiga Amanah, Ameena sedang duduk di kerusi. Wajahnya tunduk, menanda buku sambil sesekali menolak anak rambut yang terkeluar dari celahan tudung. Lengan baju disingsing sedikit, dan bibirnya bergerak-gerak kecil mungkin mengulang ayat dalam buku, atau mungkin hanya berbual dengan hati sendiri.
Eman tersenyum nipis. Ada damai dalam melihat wanita itu.
Bukan lagi dalam baju pengantin, bukan lagi dalam tangisan atau senyum dipaksa. Tapi dalam peranannya yang paling dia kagumi... sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai wanita yang kuat dan tabah. Dan sebagai ibu kepada anak mereka yang sedang membesar diam-diam dalam rahimnya.
“Cinta tak perlu dekat untuk dirasa,” bisik hati Eman.
Dia tidak bergerak. Tidak menyapa. Hanya memerhati. Cukup dari jauh.
Ameena menyedari sesuatu. Hatinya seperti menangkap aura yang cukup dia kenal. Lantas, dia mendongak. Perlahan. Matanya mencari. Dan saat pandangannya bertaut pada Eman, bibirnya menguntum senyum yang terlalu manis.
Senyuman itu tidak lama. Hanya sedetik. Cukup untuk membuat hati Eman rebah lagi.
Dia angkat kening, sedikit nakal. Ameena menggeleng perlahan, malu-malu, tapi ada cahaya bahagia yang tidak mampu disembunyikan di wajahnya.
Langkah kaki menghampiri.
“Tak berubah, ya,” tegur Isa tenang
“Dari dulu… kau memang pandang dia lama-lama.” Kali ini penuh maksud yang mendalam.
Eman tersenyum kecil. “Dulu aku pandang sebab rindu. Sekarang… sebab syukur.”
Fahmi menyusul dari belakang. Menyandarkan diri pada dinding.
“Awak tahu, tak semua orang diberi peluang kedua.”
Eman angguk perlahan.
“Sebab tu koi tak main-main lagi. Bila Tuhan beri peluang… kita tak ulang silap.”
Isa melipat tangan ke dada.
“Kadang, kita sendiri pun tak pasti kita layak ke tak. Tapi kalau dia yang pilih untuk kembali… itu maknanya dia nampak sesuatu yang kita dah lupa dalam diri sendiri.”
“Betul.” Eman menghela nafas...
“Dia tetap di situ. Setia.”
Eman berpaling memandang ke arah Isa. Wajah itu biasa. Tersenyum. Namun dia tahu. Jauh di sudut hati sahabatnya, penuh penyesalan.
“Bro.. aku janji.. Aku akan jaga dia. Dan aku minta maaf..”
Eman menepuk perlahan bahu Isa. Tanda persahabatan mereka tak akan putus.
“Dia bukan untuk aku... Aku seperti merasa.. Menjaga jodoh orang lain...”
Isa ketawa dengan nyanyiannya sendiri.. sekadar menghiburkan hati sendiri. Eman turut ketawa. Rasa bersalah tetap ada.
Fahmi menggelengkan kepala dengan senyuman nipisnya. Dia paling tua di kalangan mereka. Ibarat abang sulung di situ. Pandangannya dihalakan ke arah Ameena.
“Orang macam tu… jangan diuji lagi. Cukup. Sekarang, bahagiakan dia.”
Eman memandang sahabatnya. “Itu misi aku sampai akhir hayat.”
Isa angkat kening. “Berat tu, Cikgu Eman...”
“Tapi kalau bukan kita yang buktikan, siapa lagi?”
Ketiga-tiganya senyap seketika. Dedaunan melambai perlahan. Cuma suara pelajar dan derap kaki di koridor jadi latar.
Ameena berdiri dari bangku. Menyandang beg dan berjalan perlahan ke arah blok akademik. Tak sengaja mata mereka bertemu. Ameena tersenyum malu, tunduk sopan dan terus berlalu.
Fahmi sempat bersuara, mengusik dengan nada matang, “Cantik bila cinta tu halal, kan?”
Eman hanya tersenyum. “Indah. Sebab kita tak perlu sembunyi.”
Isa tersenyum perlahan. “Dan aku doakan kau terus jadi suami yang dia boleh banggakan.”
Eman menepuk bahu Isa. “Doakan aku kuat, itu lebih utama.”
WAJAH Lily menegang. Jantungnya berdegup kencang melihat figura itu berdiri di hadapannya. Dia tidak sangka.. tidak harap pun pertemuan ini terjadi di ruang terbuka sekolah. Bukan dia mahu lari. Tapi dia sudah buat keputusan. Kali ini untuk dirinya sendiri.
“Kau buat apa dekat sini, Doktor Hakimi? Aku dah cakap… Aku silap. Aku tak boleh terima kau lagi.”
Nada suaranya kendur, tapi tegas. Wajahnya cuba dikuasai ketenangan dengan senyuman nipis penuh kepuraan.
Hakimi kelihatan tercengang. Tewas dalam diam. Dia tidak sangka Lily akan menolaknya sekeras itu. Tidak setelah segalanya dia buat untuk perempuan itu.
“Lil… I cuma nak tahu kenapa. Kalau you tak terima I… ada orang lain ke yang sanggup terima you? You tahu, kan… maksud I…”
Kata-kata itu meluncur keluar dengan nada tertekan, hampir tergelincir dari garis hormat. Dan Lily faham benar apa maksudnya.
Dia diam sejenak, sebelum menyambut dengan suara yang lebih dalam, penuh dengan amarah yang ditahan.
“Serendah tu kau pandang aku, Doktor Hakimi? Dan kau rasa kau layak? Siapa kau nak tentukan harga diri aku? Siapa kau nak hukum aku? Tuhan ke?”
Lily menggenggam jari-jemarinya. Menahan degup hati yang laju. Beberapa pelajar kelihatan berjalan di tepi kawasan letak kereta.
“Lily.. ada masalah ke?”
Cikgu Lily menoleh ke belakang apabila namanya diseru. Suara yang dikenalinya. Isa.
Share this novel



