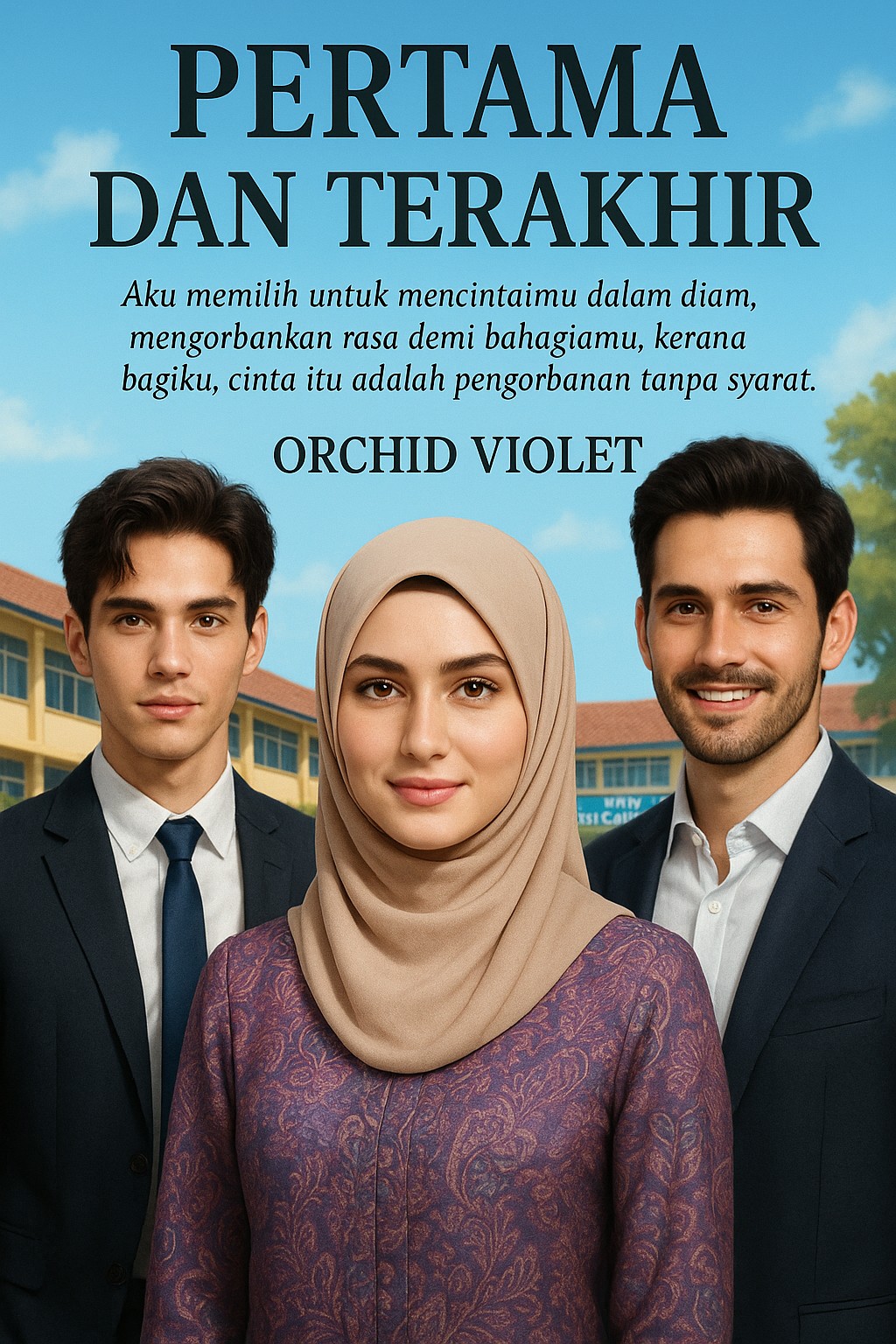
BAB 46 : HATI HITAM FIRASAT KELAM
 Series
Series
 59683
59683
AMEENA hampir rebah, tetapi sempat berpaut pada sisi pintu MPV. Nafasnya tercungap. Matanya terkunci pada sosok Eman yang berdiri kaku, terpaku, dalam kabus keliru yang mengurung jiwanya.
Tuan Zulkifli turun terlebih dahulu. Wajah tenangnya tidak mampu menipu gelodak dalam dada. Kartini menyusul, berteleku di sisi anak perempuan tunggal yang kini bagai direntap dari dunia waras. Hajah Sufiah menyambut mereka dengan senyuman tawar, penuh harap namun berselirat cemas. Di sisinya, Cikgu Hasyim sudah berdiri tenang, bersandar pada tongkat tua yang setia.
“Assalamualaikum, Hajah,” ucap Kartini perlahan.
“Waalaikumsalam. Alhamdulillah sampai juga. Jauh datang ni…” Suara Hajah Sufiah serak ditelan emosi. Matanya tak lepas dari Eman.. anak yang selama ini dipeluk takdir dengan luka.
Eman masih berdiri di sisi pangkin. Matanya merayap dari wajah ke wajah. Seperti sedang menilai potret lama yang warna-warninya telah pudar. Tatkala pandangannya bertemu wajah Tuan Zulkifli, tubuhnya seolah disambar sesuatu.
“Pakcik…?” Suara Eman perlahan, penuh tanda tanya. “Tuan Zulkifli? Ayah… Cikgu Ameena, kan?”
Tuan Zulkifli mengangguk perlahan. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan sejarah luka.
“Ya, Eman. Pakcik. Dah lama tak jumpa.”
Eman mengusap belakang tengkuknya. Wajahnya mengerut, mencuba menyusun serpihan memori yang berselerak.
“Ya Allah… macam mana boleh sampai sini…” Eman bersuara lagi, nadanya tetap sopan, lembut dan beradab walau hatinya sudah seperti benang kusut yang sukar dileraikan. Itulah Eman... bahasanya sentiasa terjaga, bicaranya tak pernah menjulang langit.
Ameena cepat-cepat menukar riak wajahnya, menutup keresahan yang hampir pecah.
“Cikgu Eman?” Dia bersuara ceria, seperti baru terserempak kenalan lama. “Kecilnya dunia… rumah awak rupanya. Saya tak sangka…”
Hajah Sufiah berpaling pantas. “Eh, kamu berdua dah kenal ke?”
Ameena tersenyum, menahan gelora di dada yang hampir tumpah. Dia mengatur nafas sebelum menjawab, cuba mengekalkan nada bersahaja.
“Kenal…” Dia ketawa kecil, seolah-olah terkejut sendiri dengan kebetulan itu. “Kami mengajar di sekolah yang sama. Cikgu Eman ni sebenarnya… bekas guru saya dulu.”
Mata Ameena singgah ke wajah Eman yang masih beku dalam diam.
“Untung saya dapat peluang kerja sekali dengan dia sekarang. Dialah mentor saya juga... banyak yang saya belajar daripada dia.”
Nada suaranya lembut, hampir berbisik.. seolah sedang berbicara dengan kenangan yang belum mati.
Airis yang masih berada di sisi Eman terkejut. Matanya bulat memandang drama tanpa skrip yang sedang terjadi di hadapannya.
‘Apa semua ni? Dah gila ke semua orang kat rumah ni?’
Namun belum sempat dia menyoal, suara tua yang penuh hikmah menyampuk dengan nada tajam.
“Airis...”
Cikgu Hasyim bersuara, perlahan tapi menikam.
“Baliklah dulu… sampaikan pada mak kamu, kami ada tetamu jauh. Yang dah lama kami tunggu…”
Airis terkedu. Kata-kata itu bagai halilintar yang menjentik kewarasannya. Dia memandang Eman, kemudian kepada Ameena… dan dalam diam, dia sedar.. tempatnya mungkin sudah tiada.
Eman masih berdiri. Keliru. Tapi jauh di relung mata itu… ada getar. Ada sesuatu yang tersentuh. Dan mungkin, pintu hati yang selama ini tertutup, mulai retak menanti cahaya menembus masuk.
Langit mula berjingga. Angin petang mengusap perlahan dedaun rambutan yang bergoyang lembut. Di beranda rumah induk, perbualan kecil antara dua wanita berusia itu berlangsung dalam irama tenang namun penuh maksud tersirat.
Eman duduk tidak jauh dari situ, hanya memerhati. Wajahnya tampak tenang, tapi dahi yang berkerut seribu membuktikan fikirannya sedang ligat bekerja.
“Macam mana Mak boleh kenal dengan Pakcik?” tiba-tiba Eman bersuara, matanya masih memandang ke arah Hajah Sufiah.
Soalan itu seperti isyarat awal yang ditunggu-tunggu.
Hajah Sufiah menoleh perlahan, tersenyum tipis. “Mak dengan mak Ameena ni… kawan baik. Sejak zaman maktab perguruan. Kami satu bilik, satu kelas, satu perjuangan.”
Eman mengangguk kecil. Tangannya menggenggam lutut, matanya tajam menatap lantai kayu yang seolah menyimpan sejarah lama.
Ameena pula menyambung, seolah-olah terkejut dengan kenyataan yang baru diketahui. “Eh… Ibu pun cikgu ke?” Dia berpaling pada Kartini yang duduk bersandar dengan tenang. “Ooo… patutlah KakChik pernah nampak muka Aunty… ya, dalam gambar kat rumah kami.”
Dia tersenyum kecil. “Amee tanya dulu… siapa perempuan cantik ni? Tapi Ibu senyum saja, tak jawab. Hari ni baru Amee tahu.”
Kartini tersenyum, namun dalam senyuman itu ada harapan yang disorokkan. Wajahnya tidak memandang Eman secara langsung, tetapi setiap kata-kata mereka adalah untuknya.
“Ibu awak tak nak cerita kot.. macam itulah Ibu awak. Dia minat sangat dengan perguruan ni.. tapi itulah.. takdir tak membawanya ke arah itu.” Hajah Sufiah menggenggam erat tangan besannya. Hari ini semua menjadi pelakon drama tak berbayar demi seorang insan.
Eman mengangkat wajahnya. Matanya merenung Kartini, kemudian ke Ameena… lalu ke Hajah Sufiah. Nafasnya turun naik, perlahan tapi berat. Kelopak matanya seperti mencari dalam ruang gelap kenangan.
Ameena tidak memandang lama. Tapi dari sisi, dia mencuri pandang ke arah suaminya… yang kini kelihatan seperti sedang bertarung dengan kabus tebal dalam mindanya.
‘Ya Allah… ingatlah. Walau sedikit.’
Sesekali, kelopak mata Eman berkedip cepat. Tangannya naik menggosok belakang tengkuk — isyarat biasa apabila dia cuba mengingati sesuatu yang samar. Pergerakan itu membuatkan Kartini menggenggam tangan Hajah Sufiah seketika, tanpa suara.
“Macam pernah jadi…” bisik Eman tiba-tiba. Suaranya seakan tidak ditujukan pada sesiapa. Lebih kepada dirinya sendiri. “Macam pernah… duduk macam ni.”
Hajah Sufiah dan Kartini saling berpandangan, hati mereka mengetap nama Tuhan.
Ameena pula tunduk, menyembunyikan matanya yang sudah mula berkaca.
Kerana pada petang yang sunyi itu satu kisah lama sedang diceritakan semula, bukan untuk mengimbau… tetapi untuk menyembuhkan. Dan pada wajah Eman… untuk pertama kalinya, ada tanda bahawa pintu memori yang tertutup itu, sedang mula bergetar.
Dejavu.
“Cikgu Eman… awak okay ke?”
Suara itu bergetar, bagai embun yang gugur ke tanah panas. Ameena tidak lagi sanggup melihat keadaan lelaki itu begitu. Lelaki yang suatu ketika pernah menjadi seluruh dunianya.
Eman mengangkat wajah, perlahan. Pandangannya mencari wajah yang familiar, namun anehnya terasa asing. Kemudian matanya jatuh pada tangan Ameena—yang sedari tadi bertaut kemas di perutnya.
“Saya okay… pening sikit. Mungkin kesan ubat.”
Nada Eman kedengaran cuba menyembunyikan sesuatu, walaupun semua yang ada di situ tahu… ia bukan sekadar pening.
Cikgu Hasyim menoleh ke arah Hajah Sufiah dan sekadar mengangguk kecil — isyarat bahawa situasi masih terkawal. Tuan Zulkifli di sisi hanya terpaku. Diam. Tidak tahu harus memberi reaksi apa. Antara ingin menenangkan atau menangis.
“Tuan Zulkifli… marilah saya tunjukkan bilik. Jauh datang dari Kuala Terengganu. Rehat-rehat dulu. Mandi pun boleh. Biarlah yang muda ni bersembang. Tak kenal erti penat, kan?”
Kata Cikgu Hasyim dengan nada bersahaja, namun penuh makna. Hajah Sufiah menyambut isyarat itu. Kartini turut bangkit perlahan. Semuanya mengerti… peranan mereka hanya sebagai pelakon sokongan dalam satu skrip besar yang sengaja dilakar untuk memulihkan Eman.
Dan kini… giliran Ameena mengambil pentasnya.
Sunyi seketika.
“Isa tak datang?”
Soalan itu menikam tanpa belas. Ringkas… tetapi menyayat. Ameena terasa seperti dadanya direntap. Tetapi dia tidak boleh rebah.
“Saya dengan Isa… dah tak duduk sekali.”
Jawapannya pendek. Namun cukup untuk menimbulkan riak terkejut di wajah Eman.
“Maksud awak… berpisah? Kenapa? Bukan ke Isa… sayang sangat dekat awak?”
Nada Eman berubah. Wajahnya menegang. Rahangnya mengeras—ada bara yang menyala. ‘Aku lepaskan dia untuk kau, Isa. Tapi ini yang kau buat?’
“Tak sehaluan. Bukan takdir kami.”
Ameena menjawab perlahan, senyum hambar di bibir. Namun di hati, hanya Tuhan tahu pedihnya.
‘Dia tinggalkan saya… tak sepedih awak tinggalkan saya, Eman.’
Eman terdiam. Kata-kata Ameena menyelinap ke dalam jiwanya, mengusik sesuatu yang selama ini terkunci.
“Anak tu… dah berapa bulan?”
Suara Eman kembali lembut. Penuh emosi. Ada keliru. Ada luka. Dan ada rasa yang dia sendiri tak mampu namakan. Tapi dia tahu.. dia peduli.
“Lagi dua minggu, masuk tiga bulan…”
Ameena hampir berbisik. Air matanya bergenang. Dalam suaranya, terselit secebis harapan… seolah dia sedang berkongsi berita gembira dengan Eman. ‘Anak kita.. Abang..’
Eman memejam mata. Penumbuknya tergenggam. Kalau Isa ada di depan saat itu… entah apa yang akan terjadi. Dunia mungkin akan menyaksikan seorang guru menjadi binatang.
“Amee… awak okay ke? Kalau awak nak bercakap… saya ada.”
Dan apabila panggilan itu terbit.. ‘Amee’ air mata Ameena tumpah tanpa kawalan. Bukan kerana sedih. Tapi kerana rindu. Itulah lelaki pertama yang memanggilnya dengan nama itu.. Yang di benci pada zaman remajanya. Dan hari ini… ia kembali.
“Amee… kalau ada orang lain… nak gantikan tempat Isa… awak rasa… awak boleh terima?”
Suara Eman perlahan. Tapi jelas. Tiada lagi keraguan. Dan bila dia bersuara begitu, separuh beban yang menghimpit dadanya seperti hilang. Seperti satu pintu kecil dalam memorinya sudah terbuka… perlahan-lahan… namun pasti.
‘Aku tak mahu terlambat lagi. Peluang kau tiada lagi.. Isa!’
AIRIS termenung sendiri di dalam biliknya. Bebelan emaknya, Saleha dibiarkan berlalu seperti semilir petang. Sejuknya ada namun tetap terasa ngilu ke tulang halus. ‘Ada harapan lagi ke.. Mak.’
Kejadian minggu lepas kembali menerja ke ruang memorinya.
Derapan kasut tumit Airis bergema di lorong bangunan akademik, bersatu dengan suara riuh para pelajar yang baru sahaja tamat sesi pertama hari itu. Dia melangkah laju mengejar bayang yang baru sahaja membelok ke ruang pejabat guru.
“Cikgu Ameena,” panggil Airis, suaranya sengaja dilembutkan, namun senyum sinis di wajahnya tetap terserlah.
Ameena berpaling perlahan. Tenangnya seperti air di tasik pagi, meski di dasar hatinya, ada gelombang kecil yang masih belum surut.
“Ada apa, Airis?”
Airis menegakkan tubuh, menyilangkan tangan ke dada, lalu mendekat dengan gaya separuh mesra.
“Saya cuma nak cakap... tak perlulah kita saling bermasam muka. Saya tahu, tak mudah nak terima kenyataan. Tapi... biasalah, kadang-kadang hidup ni memang macam drama. Siapa sangka, kita bakal bermadu, kan?”
Ameena hanya diam. Sorot matanya jernih memandang wajah wanita muda itu yang penuh yakin dan puas.
“Cikgu janganlah terlalu yakin... atau sombong sangat dengan gelaran isteri tu. Nama saja isteri… tapi kalau suami sendiri tak ingat siapa Cikgu sampai bila-bila, tak ada bezanya dengan orang asing.” Airis tertawa kecil, pedih nadanya.
“Kadang-kadang, yang datang kemudian lebih melekat di hati.”
Ameena menarik nafas, tidak panjang. Senyum nipis menghiasi bibirnya.
“Rezeki dan rasa sayang ni, Airis… bukan kita yang tentukan. Hari ni kita rasa kita tahu segalanya. Tapi esok lusa, Tuhan boleh balikkan semua sekelip mata.”
Airis menjeling, namun belum sempat menyampuk, Ameena menyambung lembut tapi tajam.
“Perempuan yang bijak, dia tak perlu menepuk dada setiap kali rasa yakin datang menjengah. Sebab kalau hati hitam, firasat pun kelam.. cuma bayang yang tak ada rupa.”
Airis terdiam. Tidak faham sepenuhnya maksud peribahasa itu, tapi jelas terasa sentapnya.
Ameena tunduk sedikit, menghulurkan senyuman nipis sekali lagi.
“Jaga maruah, Airis. Bila kita tahu kedudukan kita, kita tak akan tersalah langkah. Tak semua yang rasa manis di awal, akan kekal manis hingga ke hujung. Ingat.. cermin retak tak mencerminkan benar.”
Langkah Ameena meninggalkan lorong itu perlahan dan anggun. Tak berpaling lagi. Airis hanya mampu berdiri di situ, dengan dada yang semakin panas membahang kerana kata-kata yang lembut tapi menikam.
“Hati hitam, firasat kelam.” Airis mengulang perlahan, cuba menghadam makna. Dia tahu dia disindir. Tapi apa maksudnya? Apa yang cuba disampaikan? Mentang-mentanglah aku ni kerani sekolah saja. Kau nak cakap aku bodohlah ya!
Langkah kaki yang keluar dari pintu pejabat menghentikan lamunannya.
“Eh, Airis. Masih kat sini?” suara itu lunak, tapi berbaur sinis seperti sudah lama mengenali permainan hati.
Cikgu Lily, yang baru keluar dengan beberapa buku dalam pelukannya, memandang tepat ke wajah Airis. Senyumannya nipis dan pelik, seolah tahu apa yang sedang berlaku.
Airis menegakkan badan, cepat menyembunyikan wajah yang tadi hampir hilang kawalan.
“Saya… baru berbual dengan Cikgu Ameena.”
“Berbual, ya?” Lily mengangkat kening. “Atau cuba menguji nasib dengan menyelit di celah luka orang lain?”
Airis kaget. “Maksud Cikgu?”
Lily menapak perlahan ke arah koridor yang sama, tapi sebelum melangkah pergi, dia berpaling.
“Ada satu masa dulu... saya pun pernah jadi perempuan yang yakin dia akan dapat Eman.” Nadanya mendatar tapi jelas bergetar dengan kenangan. “Rancangannya dah sempurna. Bertahun juga saya tunggu. Tapi Tuhan tak pernah izinkan.”
Airis tergamam.
“Dan bila saya lihat awak... saya nampak diri saya yang dulu. Yakin sangat dengan ‘perasaan sendiri’, konon cinta akan berpihak bila kita berusaha lebih dari orang lain. Tapi akhirnya…” Lily menjongket bahu, senyum nipis.
“Yang tak diundang pun boleh jadi penghuni tetap hati seseorang, kalau Allah yang tulis begitu.”
Dia kemudian berlalu, meninggalkan Airis terpaku.
‘Patutlah kau sombong sangat dengan aku, ya Cikgu Ameena.. Kau ada plan besar rupanya.. Kau tunggu esok.. kau tengoklah apa aku nak buat.’
Share this novel



