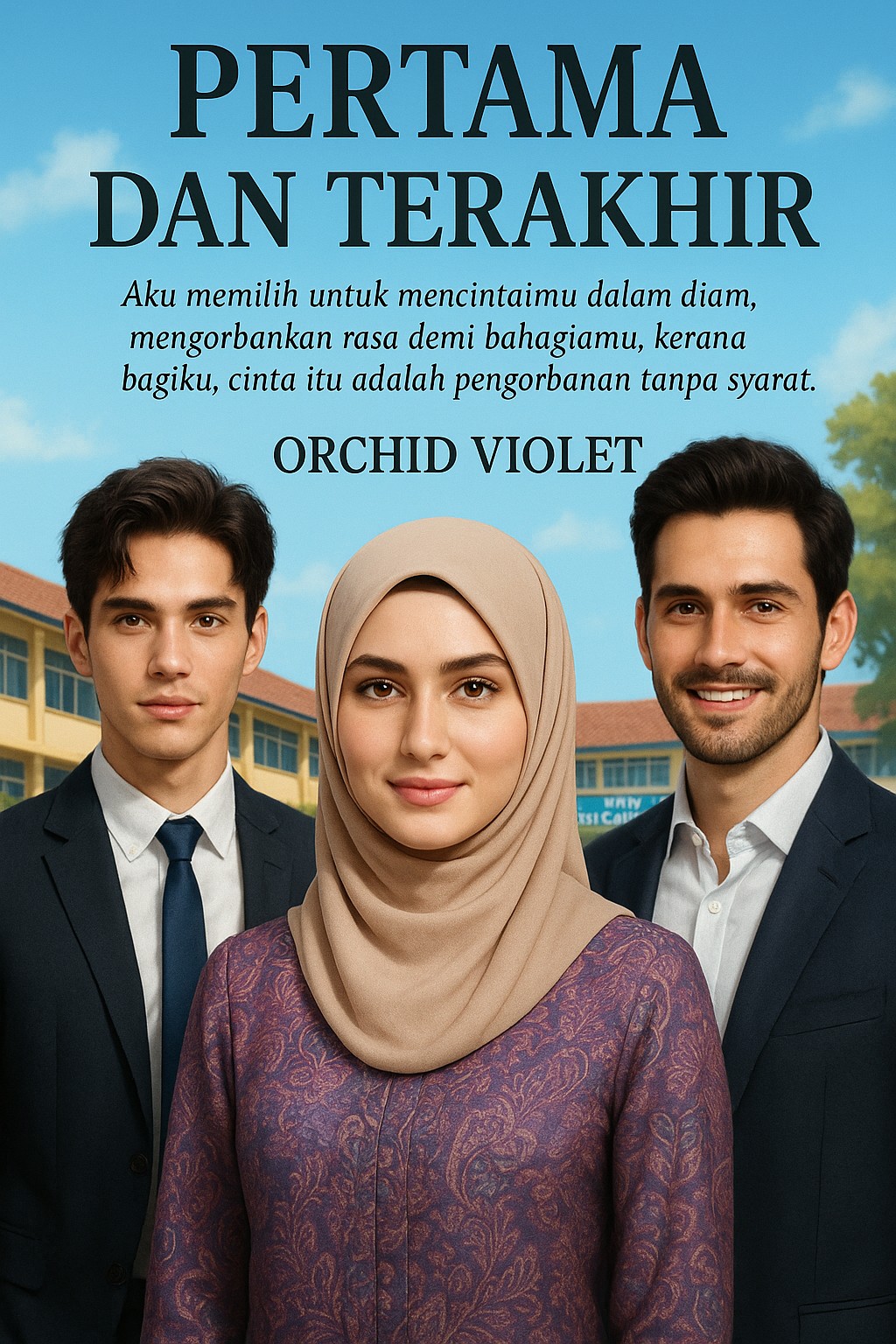
BAB 45 : RINDU YANG MENYESAK
 Series
Series
 59683
59683
Sunyi. Hanya bunyi kicauan burung yang masih setia mengisi ruang di luar jendela.
Eman terduduk semula di birai katil, wajahnya tertunduk dalam-dalam. Darel dan Darren masih di pangkuannya, namun kali ini dia tidak lagi mampu membalas pelukan mereka. Tangannya menggigil, wajahnya pucat. Nafasnya pendek-pendek, seperti sedang menahan gelombang yang cuba pecah dari dadanya.
“Acu… kenapa semua ni jadi pada koi? Mana pergi ingatan koi? Kenapa rasa dalam dada ni seolah-olah... ada seseorang yang koi nak sangat jumpa, tapi koi tak tahu siapa dia…”
Haleeda duduk perlahan di sisi, menarik nafas panjang sebelum bersuara. “Man… dengar Acu cakap baik-baik, ya.”
Eman mengangkat wajah, matanya berkaca. Jiwanya terasa sakit.
“Awak… awak hilang ingatan, Man. Kesan dari ubat sedatif masa awak dalam ICU hari tu. Ubat sedatif yang biasa tak boleh dengan awak sebab awak alergik teruk. Awak kena intubate sebab salur pernafasan awak sempit. Dalam waktu tu, untuk selamatkan nyawa awak, doktor kena guna sedatif lain yang lebih kuat. Mereka pun tak boleh nak jangka benda ni jadi kat awak. Doktor kata awak... hilang sebahagian memori, khususnya tiga tahun kebelakangan ni.”
“Tiga... tahun?” bisik Eman. “Tiga tahun tu... bukan sekejap, Acu.”
“Ya... bukan sekejap. Tapi awak masih awak, Man. Masih Eman yang lembut hati, masih Eman yang hormat orang tua, yang sayang keluarga.” Haleeda menyentuh dadanya perlahan. “Cuma memori awak... seperti pintu yang terkunci. Tak boleh paksa. Tak boleh ketuk dengan paksa.”
Eman menggenggam rambutnya sendiri, cuba menenangkan diri yang mula resah. “Tapi kenapa bila koi nampak wajah-wajah tertentu, hati koi jadi sakit? Bila dengar nama seseorang... koi jadi keliru. Ada sesuatu yang tersimpan... tapi kabur. Kenapa, Acu?”
Haleeda mengelus belakang Eman perlahan. “Itu semua... petanda bahawa awak belum benar-benar hilang. Tapi awak juga belum mampu ingat.”
“Acu… koi rasa gila.”
“Jangan cakap macam tu.” Nada suara Haleeda mula bergetar. “Awak cuma sedang bertarung dengan kekosongan. Awak belum pulih sepenuhnya. Otak awak sedang cuba mencari rentak semula. Jangan paksa diri. Jangan terlalu keras pada diri sendiri.”
Eman memejam mata rapat-rapat. Nafasnya makin dalam. “Kalau koi tak pernah ingat kembali... siapa koi sebenarnya… siapa yang saya pernah bahagiakan atau lukakan…”
Eman berdoa sendiri dalam hati supaya kata-katanya tidak menjadi satu doa. Cinta! Itu sebenarnya yang mahu dia luahkan. Namun tak terluah. Awak tak tahu Acu... Koi sudah hampir gila bila Koi hilang dia! Bila Koi terpaksa lepaskan dia pada Isa... Koi rela dalam terpaksa.
Eman dihantui rasa bersalah pada dirinya sendiri. Peristiwa tahun lepas kerap bermain di mindanya. Senyumnya selama ini palsu. Hipokritnya selama ini membunuhnya dalam diam.
“Kami semua akan tetap ada di sisi kamu, Man,” sampuk Syahrul yang berdiri di tepi pintu. “Kami akan bantu kamu ingat perlahan-lahan. Tapi bukan dengan paksaan. Dengan naluri kamu sendiri. Paksu pun dulu pernah tersesat jalan.. tapi disebabkan naluri, Paksu jumpa jalan pulang...”
Haleeda bungkam.. kata-kata Syahrul menikam relung hatinya yang beku. Keikhlasannya merayap perlahan, mencairkan salju yang lama membungkus rasa, membangkitkan gema yang hampir hilang dalam sunyi jiwa.
Darel dan Darren tiba-tiba mendakap pinggang Eman dengan lebih erat, seolah-olah ingin menampung retak di dada lelaki itu. Salah seorang dari mereka bersuara perlahan, “Abang Long nangis? Jangan nangis...” Tutur mereka masih pelat, belum sempurna, namun dalam ketidaksempurnaan itu terselit harapan kecil dua jiwa suci untuk menjahit luka yang mereka sendiri belum mengerti.
Air mata Eman tumpah juga. Dalam kekeliruan dan kekosongan itu, kasih dari darah dagingnya sendiri menyapa sebentuk cahaya yang sukar dijelaskan.
Haleeda menggenggam tangan Eman erat.
“Kalau pun dunia awak masih kabur, Man... awak masih ada kami. Dan mungkin... nanti, bila Tuhan izinkan, memori awak itu akan datang kembali. Tak perlu dicari. Ia akan datang pada awak semula.”
Ketukan halus di daun pintu memecah sepi yang cuba dikendong perlahan oleh tiga jiwa di dalam bilik itu.
"Assalamualaikum..." suara Hajah Sufiah bergema lembut. Cukup untuk membuat dada Haleeda bergetar, dan Syahrul sedikit menoleh.
“Waalaikumussalam, Kak Lang... masuklah,” sahut Haleeda perlahan.
Pintu ditolak perlahan. Hajah Sufiah muncul dengan wajah yang cuba disamarkan dari segala resah. Namun riak garis pada dahinya jelas mengabarkan sesuatu yang mengganggu hati.
Dia melangkah perlahan menghampiri, duduk di sisi katil bertentangan dengan Haleeda. Wajah Eman ditatap penuh kasih.
“Along…” panggilan itu tenggelam dalam nafasnya yang berat.
Eman cuba senyum, namun senyum itu tidak sampai ke mata. Dia hanya membalas dengan anggukan kecil. Hatinya masih perit. Masih berselerak dengan serpihan memori yang tidak bercantum.
“Kak Lang... ada apa?” Haleeda bersuara apabila melihat kakak iparnya teragak-agak untuk memulakan bicara.
Hajah Sufiah menggenggam tangan Eman yang dingin. “Tadi... Saleha datang lagi.”
Eman mengerutkan dahi, kepalanya sedikit berpaling.
“Mak tak mahu awak runsing, Eman. Tapi… dia datang bawa cerita dan niat yang awak sendiri patut tahu.”
Haleeda dan Syahrul saling berpandangan. Darel dan Darren masih bermain di hujung kaki katil, tidak mengerti apa-apa.
“Dia nak percepatkan majlis awak dengan anak dia. Airis.” Suara Hajah Sufiah hampir berbisik.
Jeda.
Eman kelihatan diam seketika. Wajahnya berubah. Sorotan matanya makin kelam. Nafasnya makin berat.
“Airis…” nama itu seakan terbit dari ruang dadanya, bukan dari bibir.
“Ayah dan Mak pun pernah sebut nama dia pada koi dulu…” bisiknya. “Tapi... kenapa koi rasa hati koi tak senang? Kenapa koi rasa... ada seseorang yang koi sedang khianati?”
Wajah Eman makin gelap, bukan dalam marah, tapi dalam luka yang tidak tahu dari mana puncanya.
“Acu…” katanya memandang Haleeda dengan mata yang basah, “Kalau koi pernah ada seseorang dalam hidup koi... dan koi lupakan dia… bukankah itu zalim namanya?”
Haleeda menyentuh pipi Eman perlahan, menggeleng dengan senyum yang penuh simpati. “Man... kadang-kadang Tuhan tarik ingatan kita supaya kita belajar menghargai dari awal semula. Tak ada yang sia-sia. Cuma sekarang ini... awak perlu tenang. Jangan terburu buat keputusan hanya kerana awak rasa kosong.”
Eman memejam mata rapat-rapat, seakan ingin menggali sesuatu yang tenggelam jauh dalam benaknya.
Hajah Sufiah menyambung, “Kalau awak mahu... awak berhak menolak. Kami tak akan paksa. Jangan pilih sesuatu hanya kerana awak rasa itu satu-satunya jalan. Eman… kalau hati awak bukan untuk dia, jangan kerana hasrat mak kamu korbankan bahagia kamu.”
Kata-kata itu menikam lembut ke dalam dadanya.
“Man.. Awak kena berani. Mungkin Allah nak bagi peluang pada awak sekali lagi untuk buat sesuatu yang awak tak mampu buat dulu. Jujur dengan hati awak sendiri, Man. Zahirkan.. jangan pendam. Jangan menyerah sebelum kalah!”
Masih ada ruang untuk dia membuat pilihan. Masih ada suara-suara yang mahu dia bahagia. Tapi kenapa rasa bersalah ini seperti tak mahu hilang?
“Kalau saya tahu siapa yang pernah saya cinta, saya akan cari dia semula, Mak. Walau siapa pun dia. Saya janji.”
Hajah Sufiah menguntum senyum yang layu, sehalus kelopak doa yang gugur satu-satu dari hatinya. Di balik redup matanya, tersembunyi segunung harapan agar suatu hari nanti, Eman akan kembali mengingati Ameena. Isteri yang pernah menjadi pelengkap hidupnya, kini lenyap dari lipatan ingatan, namun tidak pernah hilang dari takhta takdirnya.
“Ibu… Ayah… tolonglah… dah hampir sebulan Abang kat sana. KakChik nak tengok dia… sekali pun jadilah...”
Suara Ameena pecah dalam sendu.... mengongoi seperti kanak-kanak yang kehilangan dakapan ibu.
Rindunya bukan lagi sekadar pada wajah lelaki itu… tetapi pada segenap ketenangan yang dulu bernaung dalam matanya. Pada damai yang membungkus senyumannya.
“Apa KakChik nak jawab nanti kalau dia tanya, siapa kakak ni? Kenapa datang rumah dia? Apa hubungan Ibu dengan keluarga dia?”
Nada Kartini mula retak. Suaranya sarat risau dan kesal. Raut wajahnya membelah duka yang lama bersarang. Tiada apa lagi yang mampu dipegang untuk menenangkan anak perempuannya itu.
Tubuh Ameena makin susut. Makan hanya bila dipaksa dan itu pun kerana mengingatkan janin yang sedang bertunas di rahimnya. Nyawa kecil itu satu-satunya yang tinggal, yang jadi pengikat dia dengan realiti yang kian jauh.
Kadang, Ameena hilang dua hari. Pulang larut malam, dengan mata bengkak dan jiwa yang makin kelam. Kartini tahu... tak perlu ditanya. Dia pergi ke rumah itu. Rumah yang pernah penuh dengan tawa, doa dan pelukan kasih suami isteri.
Tuan Zulkifli masih diam seperti selalu. Diam yang tidak berisi reda, tapi pasrah. Dan Ameer… satu-satunya yang selalu menyejukkan jiwa Ameena, sudah kembali ke Brunei. Dunia seolah menjauh, meninggalkan Ameena berseorangan dalam gelap yang tak bertepi.
Deringan telefon memecah senyap. Ameena yang masih tersedu memandang skrin, menelan liur. Nama itu tertera — Acu Haleeda. Dadanya bergetar. Kartini dan Tuan Zulkifli saling berpandangan. Bimbang. Resah.
“Assalamualaikum… Acu,”
Suara Ameena serak, cuba menyapu esak dalam bicara. Dia menggenggam hujung tudungnya, seakan mencari tempat berpaut.
“Waalaikumussalam, Ameena. Awak sihat?”
Suara Haleeda lembut, tapi ketara tergesa. Ada sesuatu. Ada hal besar.
Ameena tidak menjawab. Cuma mengangguk perlahan dalam senyum yang tidak sampai ke mata.
“Maaf ganggu… tapi Acu tak boleh diam lagi. Kita kena buat sesuatu. Kita tak boleh tunggu macam ni. Keluarga Airis makin mendesak. Acu takut Eman buat keputusan yang dia sendiri akan sesal.”
Ameena terdiam. Nafasnya tersekat. Tangannya jatuh perlahan ke perutnya yang mulai membuncit. Kandungannya kini sudah sepuluh minggu. Satu rahsia yang belum diketahui Eman… Suami yang langsung tak mengingatinya.
“Kalau kita terus terang pada Eman?” Soalnya perlahan, penuh was-was.
“Tak boleh. Acu rasa itu akan buat dia makin jauh. Dia masih keliru. Dia cuba cari sesuatu dalam dirinya… dan Acu yakin, itu adalah kamu. Kita perlu ulang satu hari yang mungkin telah tertinggal dalam hatinya… tiga tahun lalu. Tiga hari sebelum kamu nikah dengan dengan dia. Masa tu, Eman tak sempat cakap apa yang dia pendam. Dan rasa bersalah itu, Acu percaya… itulah yang menghantui dia sekarang.”
Ameena menutup mulutnya. Air mata meluncur perlahan di pipi. Wajah Eman muncul dalam ingatannya. Wajah yang dulu menahan pilu, namun tetap senyum bila bersua dengannya. Eman, lelaki yang lambat menyusun langkah, tapi hatinya penuh kasih yang tak sempat ditutur.
Kalaulah dulu dia tahu… bahawa lelaki yang ibunya usulkan sebagai jodoh itu adalah Eman, pasti dia tak akan menolak. Tapi waktu itu dia ragu. Ragu pada hatinya sendiri.
“Kamu tak perlu jawab sekarang. Tapi Acu mohon… pertimbangkan.”
Nada Haleeda melembut.
Ameena hanya mampu mengangguk. Hatinya masih berperang. Namun sesuatu dalam dirinya berkata inilah peluang terakhir.
Hajah Sufiah termenung jauh, matanya terpaku pada sosok Eman yang duduk berteleku di atas pangkin, di bawah rendang pohon mangga. Tubuh anaknya itu kaku, seolah menyatu dengan tanah yang sedang dipijaknya. Entah apa yang sedang berlegar dalam benaknya.
Di sudut hatinya, Hajah Sufiah menyulam harapan.. mungkin kehadiran seseorang petang ini akan menjemput sedikit ingatannya. Tidak perlu semuanya… cukuplah walau hanya satu serpihan memori yang pulang.
“Abang Eman… buat apa kat sini sorang-sorang?”
Lamunan Hajah Sufiah terlerai dengan suara manja itu. Lunaknya menggulung keresahan di dada. Berkali-kali dia beristighfar dalam hati.
Baru sahaja dia hendak menuruni anak tangga, lengan tuanya diraih lembut oleh Cikgu Hasyim.
Hanya satu gelengan dari lelaki itu sudah cukup menjadi isyarat.
“Biar Along yang selesaikan. Biar Along sendiri yang cakap, baru dia faham. Mungkin itu juga akan lapangkan dada Along,” ujar Cikgu Hasyim tenang.
Hajah Sufiah angguk perlahan, antara reda dan enggan. Hati seorang ibu, mana mungkin tidak remuk melihat anaknya dijadikan boneka perasaan orang lain. Tapi dia tahu, pertelingkahan hanya akan memburukkan keadaan Eman.
“Airis… buat apa kat sini? Bila balik?”
Nada Eman hambar, sekadar menyambut dengan adab. Matanya sesekali merayap ke hujung jalan, seperti menanti sesuatu yang tidak pasti. Atau mungkin… seseorang.
“Sekolah cuti seminggu. Airis pun ambillah cuti sekali. Abang dah makan? Airis bawa kuih.”
Dia menghulurkan bekas kuih dengan senyuman yang terukir. Tapi Eman hanya menoleh sepintas lalu. Matanya lebih sibuk mencari sesuatu yang lain.
Tiba-tiba, pandangannya tertancap pada sebuah MPV hitam yang perlahan-lahan memasuki laman rumah. Jantungnya berdetak kencang. Ada bayang yang entah mengapa terasa dikenali. Wajahnya berkerut. Seakan-akan sedang menggali sesuatu dari benak yang kusut dan berdebu.
Airis cepat-cepat memaut lengan Eman. Gusar dan cemas, seolah mahu mengalihkan perhatian Eman. Tapi sudah terlambat.
Dari balik pintu kenderaan itu, muncul seorang wanita.
Ameena.
Eman terpaku. Pandangannya kosong… namun di balik kekeliruan itu, ada getar yang tak mampu disembunyikan.
Ameena sudah hampir tumbang. Lututnya lemah menyaksikan pemandangan di depan mata.
Itu Eman. Lelaki yang pernah mengisi seluruh hidupnya. Tapi kini menatapnya bagai seorang asing. Terperangkap antara keliru dan hampa. ‘Sayang datang.. Abang. Kami datang.. Ayah..’
Share this novel



