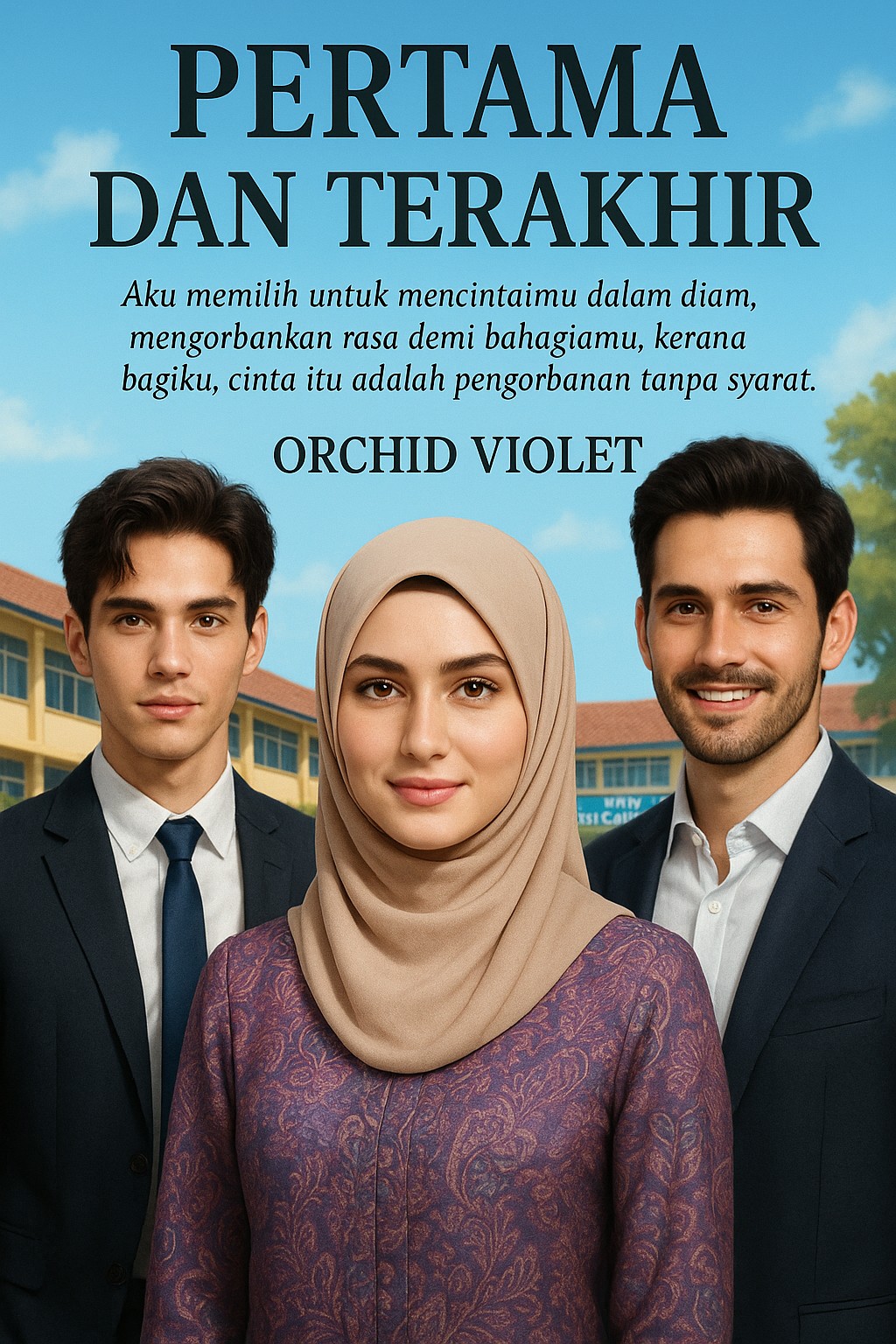
BAB 48 : ANAK ABANG!!
 Series
Series
 59683
59683
EMAN duduk berteleku di meja bacaan.
Cahaya suram dari lampu meja menyimbah wajahnya yang kusut. Kertas-kertas peperiksaan berselerak di hadapannya, namun matanya tidak lagi tertumpu pada angka dan markah. Sebaliknya, matanya berkaca. Ada sesuatu yang mengganggu. Rasa cemas yang tidak tahu dari mana datangnya perlahan-lahan menyesakkan dadanya. Fikirannya berselirat. Banyak soalan yang belum terjawab. Terlalu banyak kenangan yang tidak berjejak.
Namun satu wajah, satu nama, sentiasa muncul menembusi kabus fikirannya. Ameena.
Dan satu peristiwa, meskipun samar, tidak pernah benar-benar pergi.
Bayangan kelmarin menjelma semula.
“Amee… sabar ya…” suara Eman bergetar, dia tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Tangannya terawang-awang, jiwanya berkecamuk.
“Kenapa ni? Cikgu Eman?” Cikgu Reena sudah cemas. Dia bergegas menghampiri apabila melihat Ameena terduduk di tangga, wajahnya pucat, berpeluh dingin, memegang perut yang seolah sedang menanggung azab.
“Ameena terjatuh… Kak Reen… saya rasa dia sakit. Perut dia…” suara Eman tersekat-sekat.
“Ya Allah… kenapa ni, Amee?” suara Cikgu Reena menjerit panik.
Isa muncul tiba-tiba, langkahnya terhenti apabila melihat kekecohan. Dahinya berkerut.
“Cikgu Ameena? Apa jadi? Kak Reen… Ya Allah… darah?” suara Isa serak, wajahnya bertukar pucat sekelip mata.
Eman masih kaku.
Dia tahu dia patut bergerak, patut bertindak. Tapi kenapa dia hanya berdiri? Kenapa kakinya terasa berat, sedangkan hatinya sedang menjerit?
“Bro! Angkat dia, bro! Dia dah tak boleh jalan!” Isa menepuk bahunya, kuat. Darah masih basah di tepi bibirnya, bekas tumbukan Eman tadi.
“Eman! Tunggu apa lagi?! Angkatlah Ameena!” suara Cikgu Reena bergema, tinggi, nyaring. Cemas membuatkan dia lupa tentang keadaan Eman yang masih belum sembuh ingatan. Isa juga sama. Semuanya sudah lupa siapa Eman kepada Ameena atau siapa mereka dahulu kepada satu sama lain.
Eman tergamam.
Kenapa mereka minta aku? Bukan Isa?
Bukankah Isa suaminya? Bukankah dia lebih berhak?
Namun, dalam celaru itu, satu perasaan membuak dari dasar hatinya. Perasaan yang tidak mampu dijelaskan. Perlindungan. Sayang. Takut kehilangan.
Tanpa sedar, Eman merangkul Ameena, mengangkat tubuh yang lemah itu ke dalam pelukannya. Dia tidak peduli lagi. Dia hanya tahu satu.. dia tidak sanggup melihat perempuan itu terus menanggung derita.
Di dalam kereta.
Ameena terkulai di kerusi penumpang, tubuhnya menggigil menahan sakit. Nafasnya pendek. Wajahnya cemas, pucat lesi.
“Abang… tolong… Sayang sakit…”
Suara itu rapuh, bergema ke dalam jantung Eman.
Tangan lemah Ameena meraih lengan Eman, memeluknya seolah-olah nyawanya bergantung pada lelaki itu.
Eman menggigit bibir. Jiwanya kacau. Nafasnya tidak teratur. Kenapa? Kenapa rasa ini seperti tidak asing? Kenapa setiap kali Ameena menyebut ‘Abang’, jiwanya bergoncang?
Dia tahu hukum. Ameena masih dalam edah. Bila-bila masa Isa boleh rujuk. Dan saat itu, mereka akan kembali menjadi suami isteri. Dia siapa? Dia hanya orang luar.
Namun hatinya menolak semua itu. Setiap kali Ameena mengerang kesakitan, dia rasa seperti dialah yang sepatutnya menjaga perempuan ini, bukan orang lain.
‘Amee… kenapa hati aku rasa kau milik aku?’
Dia cuba memandu dengan tenang, tapi tangannya menggigil di stereng. Otaknya bersuara, Jangan buat dosa, Eman. Ini bukan hak kau.
Tapi hatinya membalas, Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan lindungi dia?
Di sebelahnya, Ameena terus teresak perlahan. Matanya memandang Eman dengan penuh pengharapan.
Dan dalam diam, Eman sedar… dia sedang menyayangi seseorang yang bukan miliknya.
Tetapi, kenapa hatinya tetap berkata…
"Dia bahagianku."
SUASANA di kantin masih riuh-rendah. Suara pelajar berselang-seli dengan derap tapak kaki dan bunyi dulang berlanggar. Namun, di sudut paling hujung, di bangku batu yang menghadap padang yang mulai kering kontang, Isa duduk sendirian.. bahunya sedikit jatuh, wajahnya kosong, dan matanya tertancap ke rumput yang tidak dipandang sesiapa.
Terasa dunia bergerak tanpa menunggunya.
Langkah perlahan Cikgu Fahmi menghampiri dari arah bilik guru, membawa dua tin air sejuk di tangan. Dia tahu, sahabatnya itu sedang bertarung dengan sesuatu yang lebih berat dari sekadar rasa bersalah.
“Minum.” Fahmi menghulur salah satu tin. Suaranya pendek, tapi cukup untuk memecahkan dinding kesunyian.
Isa menyambut, senyum tawar di bibir. “Thanks.”
Mereka diam agak lama. Bunyi tawa murid dari jauh seakan gema yang tidak menyentuh mereka.
“Aku tahu kau tengah fikir nak cakap dengan Eman.” Fahmi akhirnya membuka mulut. Nada suaranya tenang, tapi penuh makna.
Isa hanya angkat bahu, menghela nafas yang tertahan.
“Aku rasa aku kena cakap dengan dia. Tak adil kalau aku biar dia terus salah faham,” suaranya perlahan. Matanya tak berani menentang pandangan Fahmi.
Fahmi menggeleng perlahan. “Jangan. Bukan sekarang. Eman belum stabil. Dia masih marah. Masih rasa kau abaikan Ameena.”
Isa telan liur. “Tapi dia kena tahu yang Ameena perlukan dia, bro… Aku nampak sendiri. Semalam aku pergi hospital dengan Cikgu Lily. Kesian sangat tengok dia. Lemah. Diam. Macam tak ada jiwa…”
Fahmi memicit batang hidungnya. Berat. “Aku faham, Isa. Tapi yang Eman nampak sekarang cuma satu… Ameena terlantar. Dan kau—kau berdiri di situ, tak buat apa-apa.”
Isa tunduk. Genggaman pada tin air makin kuat, seolah mahu melepaskan sesuatu yang sudah terlalu lama digenggam dalam hati.
“Kalau aku cakap Ameena tu isteri dia… kau rasa dia boleh terima?”
Fahmi senyum nipis. Mata redupnya seakan tahu sesuatu yang Isa tak tahu.
“Dia boleh terima. Mestilah boleh. Sebab… dia memang sayang Ameena. Dari dulu lagi.”
Isa angkat kepala. Kening ternaik sedikit.
“Dari dulu?” Suaranya hampir berbisik, seakan takut kepada jawapan.
Fahmi angguk. “Ya. Sejak zaman sekolah lagi. Tapi dia pendam. Sebab dia penakut. Sebab dia sayang sangat kat kau... kawan dia sendiri. Dan bila dia tahu Ameena pilih kau, dia kecewa… tapi dia undur. Diam-diam.”
Isa membatu. Jantungnya seakan berhenti berdegup. Tangannya terkulai dengan tin yang kini tidak terasa dinginnya lagi.
“Gila… Jadi selama ni…” Bibirnya bergerak tanpa suara.
“Bukan dia yang rampas.” Fahmi menyambung perlahan. “Kau yang tak sedar.”
Isa ketap bibir. Mata berkaca. Dada bergelora dengan rasa yang baru mula bertunas—bukan sekadar rasa bersalah, tapi rasa kalah.
‘Kenapa, bro?’
‘Kau selalu cakap, the best man wins. Tapi kau… kau mengalah macam tu je?’
Dia telan air liur yang pahit.
“Kalau aku tahu...” Isa akhirnya bersuara. Suaranya tenggelam dalam kekesalan.
Fahmi letak tangan di bahu Isa, tepuk perlahan. “Sekarang kau tahu. Tapi belum masa untuk kau ubah semuanya. Bagi dia ruang. Bagi dia ingat sikit-sikit. Biar dia susun balik serpihan memori yang hilang tu dengan tenang. Jangan bagi kejutan.”
Isa angguk perlahan. Kelopak matanya merah. Nafas turun naik dengan sukar.
“Ya… Dia bahagia bila tahu Ameena isterinya. Tapi dia pun berhak untuk tahu semua… dengan cara yang tak buat dia runtuh semula.”
Fahmi senyum tenang. “Dan kali ni… jangan jadi orang yang rampas. Jadi orang yang redha.”
Suasana kembali sepi. Tapi kali ini bukan sunyi yang menyesakkan—cuma diam yang membina kefahaman.
Fahmi sengaja ubah topik, cuba meringankan suasana.
“Sebut pasal Cikgu Lily… kau ada apa-apa ke dengan dia?”
Isa gelak kecil, gugup. “Eh, ada-ada je kau ni, bro!”
Fahmi sengih. “Kalau ya pun… aku tak terkejut. Dia tu makin lembut. Dah tak macam dulu. Dah nampak muslimah.”
Isa ketawa lagi, tapi kali ini ikhlas. Dalam hatinya, dia tahu.. mungkin hatinya sedang sembuh. Dan kali ini, ia bukan milik Ameena lagi
PANAS mentari tengah hari memancar terik di kawasan letak kereta. Kereta-kereta guru sudah mula bersusun keluar dari sekolah. Suasana di perkarangan sekolah hampir lengang kecuali satu susuk tubuh lelaki yang sedang membuka pintu keretanya perlahan. Tenang dalam kekosongan.
“Abang Eman!”
Satu suara lantang mencantas ketenangan itu. Nafas Eman tertahan seketika.
Airis.
Gadis itu berlari ke arahnya, wajahnya sedikit cemas dan kelihatan seperti menyimpan sesuatu yang besar.
Eman tidak bergerak. Dia hanya berpaling perlahan, menyambut kehadiran itu dengan secebis senyum. Senyuman yang kelat, tak sampai ke mata.
“Airis ada benda nak bagitahu...” Suara Airis lembut tapi mendesak, penuh nada yang memancing simpati.
Eman diam sejenak. Pandangannya tidak benar-benar menangkap wajah Airis. Hanya melihat sekilas, kemudian menunduk kembali ke kunci kereta di tangannya.
“Ya… bagitahulah. Saya nak balik ni.” Suaranya pendek. Datar. Seolah-olah mahu segera menamatkan pertemuan.
Airis menelan air liur. Dia menggenggam hujung lengan bajunya, seakan mencari kekuatan.
“Kita pergi tempat lain boleh? Luar sekolah... kejap saja.” Nadanya rayu. Matanya cuba menangkap mata Eman, berharap dapat menyentuh hati lelaki itu.
Eman mendongak sedikit. Wajahnya berubah.. bukan marah, tapi jelas tidak selesa. Dia geleng perlahan, tetap menjaga nada dan tutur katanya.
“Maaf, Airis. Saya tak biasa berduaan dengan bukan muhrim.”
Jawapan itu tegas, tapi tetap dibungkus dalam santun. Airis terdiam. Tapi dia tak menyerah.
“Hari tu dengan Cikgu Ameena boleh pula...” Suaranya mencabar, sinis berselindung manja. Matanya menikam, cuba mencari jawapan yang menyakinkan.
Eman terhenti seketika. Senyumannya mati. Mata yang tadi mengelak, kini menatap terus ke arah Airis.. dalam dan tajam.
“Dia mengandung, Airis. Saya cuma tolong dia.”
Kata-kata itu dingin, tapi penuh makna. Tegas, tak berbelah bahagi.
Airis terpempan. Riak wajahnya berubah sekelip mata. Bagai ditampar angin panas yang menikam kulit. Mulutnya terbuka, tapi tiada kata terbit.
Eman menarik nafas, membuka pintu kereta. Bahunya tegang. Nafasnya jelas berat. Jiwanya masih dalam kekacauan.. namun satu hal pasti, dia tidak akan beri ruang untuk permainan perasaan yang tidak halal. Seolah-olah ada satu pengalaman itu dalam hidupnya. Cuma dia tidak ingat.
“Kalau tak ada apa-apa... saya balik dulu.” Nada suaranya dingin. Tidak marah, tapi tegas. Garis sempadan jelas dilakar.
Airis menggenggam jari-jemarinya. Matanya berair, tetapi bukan air mata jujur.. ia air mata kecewa kerana tidak berjaya menguasai ruang yang tidak pernah menjadi miliknya.
Eman sudah pun melabuhkan duduk di kerusi pemandu. Tangan kirinya memegang stereng, manakala tangan kanan masih tergantung pada tombol gear. Nafasnya berat, fikirannya berselirat. Namun langkahnya jelas.. dia mahu pergi. Mahu lari dari kekusutan yang tak berpenghujung.
Tapi belum sempat dia menutup pintu kereta sepenuhnya..
“SAYA PUN MENGANDUNG!”
Jeritan itu membelah keheningan suasana.
Terus Eman terpaku.
“ANAK ABANG!!”
Kata-kata itu menghentak jantungnya bagai guruh membelah langit.
Jari-jarinya terhenti di pintu kereta yang separuh tertutup. Perlahan-lahan dia berpaling. Matanya membulat, wajahnya pucat. Nafasnya tersekat.
Airis berdiri di belakang kereta, tubuhnya menggeletar. Wajahnya merah padam, berair mata. Tapi bukan air mata lembut atau pilu. Ia sarat dengan amarah dan dendam.
Eman bangkit dari kerusi perlahan-lahan. Dia berdiri, tapi tidak menghampiri Airis.
"Airis..." Suaranya perlahan, namun tegas. Matanya merenung dalam wajah gadis itu. Wajahnya kini tidak lagi palsu. Tiada senyuman. Hanya getar kecewa dan marah yang ditahan dalam rahang yang menggigil.
"Apa yang kamu cakap tadi...?" suaranya hampir berbisik.
Airis tidak menjawab. Dia menutup wajah dengan tangan, menangis teresak-esak. Tubuhnya mula lemah, lututnya hampir rebah.
Namun mata Eman masih tak berkelip.
Hatinya bergelora. Antara percaya dan tidak. Antara marah dan cemas. Dadanya rasa ditebuk.. terkejut dan keliru bercampur aduk. Tapi dia tahu… dia tidak boleh hilang kawalan.
“Airis…” dia mengulang. Kali ini lebih perlahan. “Jangan main-main dengan benda macam ni.”
Airis masih menangis. Tapi kali ini dia tidak lari. Tidak mengalah. Dia hanya menatap Eman dengan mata basah yang merayu, namun berapi.
“Airis… mengandung anak saya?” tanya Eman lagi, nadanya berat.
Sunyi. Lama.
Dan akhirnya, Airis hanya mengangguk perlahan. Lemah. Tapi cukup untuk menjatuhkan batu besar ke atas kepala Eman.
Tangan Eman menggigil di sisi. Dia tidak tahu sama ada mahu percaya… atau menolak mentah. Tapi satu hal pasti.. ini bukan pengakhiran. Ini baru permulaan kepada satu badai yang lebih besar.
“Saya… saya tak boleh fikir…” Eman bersuara, nadanya tenggelam dalam keliru yang menikam. “Airis… macam mana…”
Kata-katanya terhenti di situ. Nafasnya berat, terputus-putus. Tangan kanannya naik ke belakang tengkuk, mengurut perlahan, cuba menenangkan denyutan yang menggila di kepala. Pandangannya kabur, dada sesak.
Dia tak sanggup lagi.
Tanpa sepatah kata, Eman berpaling. Kakinya longlai melangkah ke arah keretanya. Pintu dibuka, dan dengan sekali hembusan nafas berat, dia masuk lalu menutupnya kuat. Enjin tidak dihidupkan.
Dia hanya duduk, menggenggam stereng rapat-rapat. Wajahnya tersembunyi di balik cermin gelap, tapi gelora jiwanya seolah menembus keluar.
Airis berdiri di situ, memerhati. Senyap. Tenang. Wajahnya kini berubah. Tiada lagi sendu, tiada lagi air mata.
Saat Eman memandu keluar dari kawasan parkir.. Airis tersenyum. Senyuman tipis, dingin. Penuh maksud. Senyuman kemenangan.
Tiada saksi. Hanya dia dan langit yang mula meredup. Angin petang meniup rambutnya lembut, tapi dalam hatinya... badai sedang menari.
"Tak perlu guna takal yang mak bagi," bisiknya perlahan, “Senang saja nak bodohkan dia ni…”
Langkahnya diatur perlahan, meninggalkan kawasan itu dengan hati puas.
“Next step.”
Share this novel

Seri
2025-05-10 19:43:49
Jahatnye budak airis ni...



