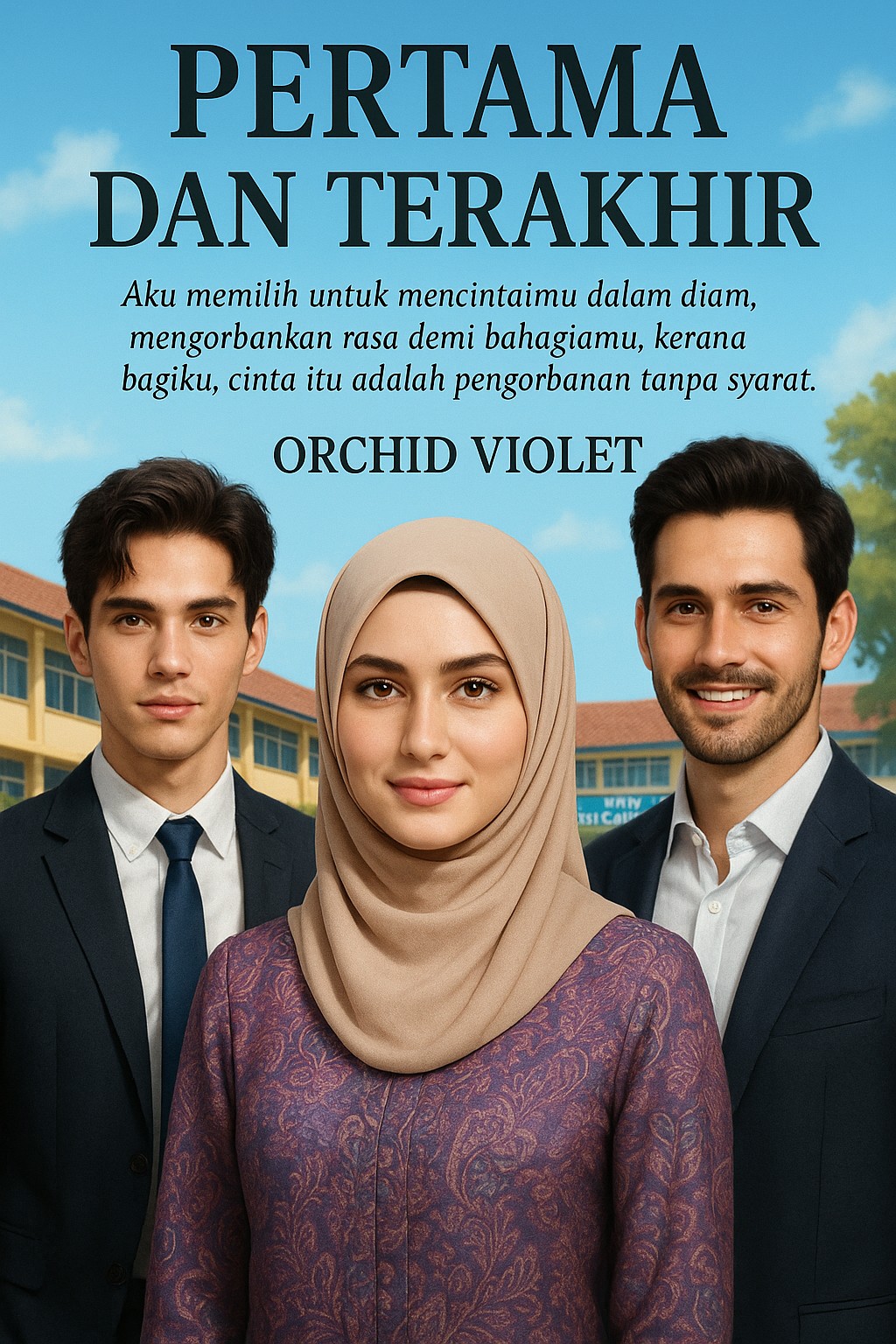
BAB 57 : DEBARAN KELAHIRAN
 Series
Series
 59683
59683
“AIRIS… Airis istighfar… Ya Allah…” Hajah Sufiah tergesa keluar dari dalam rumah, diikuti suaminya Haji Hasyim.
“Airis, lepaskan dia. Ini bukan cara dia, nak…” pujuk Haji Hasyim dengan suara tenang, tangan terangkat perlahan. Mulutnya terkumat kamit membacakan sesuatu.
“Abang Eman…! Abang janji nak kahwin dengan Airis!” tangis Airis. Suaranya retak.
“Tapi kenapa Abang Eman dengan betina ni!” raung Airis, matanya membara. Pisau di tangannya makin erat menghimpit sisi leher Ameena yang sedang menggigil.
“Astaghfirullahalazim, Airis… Ini kerja gila…” Isa cuba mendekat, namun langkahnya terhenti bila Airis menjeling tajam.
“Jangan, Isa! Jangan dekat!” jeritnya.
“Airis… tolong…” suara Eman parau, matanya merah, dadanya turun naik.
“Lepaskan Ameena. Awak boleh marah saya, awak nak maki saya pun boleh… Tapi tolong lepaskan dia. Dia tak bersalah…”
“Airis tunggu Abang Eman…” esak Airis, suaranya bergetar.
“Airis tunggu bertahun-tahun… Airis cari Abang… Tapi kenapa Abang kahwin dengan dia? Dengan betina ni?!” jeritnya sambil menggeletar.
“Padahal Airis yang sayang Abang dari dulu… Airis yang tak pernah tinggalkan Abang…”
“Airis, dengar cakap abang…” Eman angkat tangannya perlahan, hampir mahu rebah dalam panik dan takut. “Lepaskan dia, ya sayang… Abang tak ke mana. Abang ada kat sini.”
“Jangan panggil aku sayang kalau kau tak maksudkannya!” jerit Airis, dan dalam sekelip mata pisau itu dihujam ke sisi perut Ameena.
“AMEENA!!” suara Eman terburai.
Ameena terundur, tubuhnya melentik sedikit — tapi Airis masih memeluknya, pisau itu masih dalam genggaman.
Isa dan Lily menjerit. Hajah Sufiah melutut di laman, menangis teresak. Haji Hasyim terpaksa memegang bahunya agar tidak rebah.
“Ya Allah… Ya Allah…” Cikgu Fahmi muncul semula dari dalam, wajahnya cemas.
Eman terdorong ke hadapan. “YA! YA, KITA KAHWIN! KITA KAHWIN AIRIS! ABANG KAHWIN DENGAN AWAK!” jerit Eman, dadanya terhempas kuat dalam emosi.
Airis kaku. Matanya membulat. Dia menoleh sedikit, wajahnya terpinga-pinga. “Apa… Apa Abang cakap?”
“Kita kahwin, Airis… Abang janji… Tapi lepaskan dia dulu, ya? Kalau Airis bunuh dia… Airis masuk penjara. Macam mana kita nak kahwin kalau awak masuk penjara?” suara Eman merayu. Air matanya tumpah.
Airis terdiam. Tangannya menggeletar. Lama.
Akhirnya pisau itu terlepas jatuh ke tanah. Ameena jatuh mengerekot, tubuhnya dipaut Eman yang segera menyambutnya dalam pelukan. Pisau disisi segera di sepak jauh.
“Sayang! Ameena! Ya Allah… darah… darah…!” Eman menjerit panik, wajahnya mendekap wajah isterinya yang terkulai lemah.
Isa meluru ke arah Airis, menariknya jauh dari tempat kejadian. Mengunci seluruh pergerakan Airis supaya perempuan itu tidak bertindak lenih agresif.
“Ameena… bertahan ya… bertahan untuk abang… untuk anak kita…” suara Eman bergetar, jari-jemarinya menekan luka Ameena sambil tangannya menggigil tak henti.
“Telefon ambulans cepat!!” jerit Cikgu Fahmi ke arah rumah.
Dan petang itu yang sepatutnya damai… bertukar menjadi igauan ngeri — suara tangisan, jeritan, dan bunyi siren dari kejauhan menjadi latar untuk sebuah cinta yang diuji tanpa henti.
Suara siren ambulans masih lagi bergema sayup dari kejauhan. Orang kampung sudah mula berkumpul di luar pagar. Beberapa jiran terdekat berdiri terpinga-pinga, tidak berani menghampiri.
Salleh dan Saleha muncul dengan tergesa-gesa demi mendengarkan kekecohan di rumah jirannya.
“Airis!!!” Salleh mengucap panjang. Mulutnya tidak putus-putus melafaz istighfar. “Apa yang awak dah buat ni, Airis?!”
Airis yang masih lemah di dalam pakuan Isa mendongak perlahan. Matanya kosong. Di tangannya ada kesan darah.
Saleha tergesa melangkah ke depan, tapi langkahnya terhenti saat melihat wajah Ameena yang sudah tidak sedarkan diri, masih dalam pelukan Eman yang menggigil. Suasana hening sesaat. Saleha menekup mulutnya.
“Airis…” suaranya berbisik, tubuhnya tiba-tiba menggeletar.
Namun jeritan meletus tiba-tiba dari tekak Saleha. “Airis! Apa kau dah buat ni?! Aku tak suruh kau buat macam ni!” Suaranya bagaikan orang histeria. Dia terus meluru ke arah anaknya, tapi Isa segera menghalang, takut berlaku sesuatu yang lebih buruk.
Airis memandang ibunya, sayu… gila… kecewa.
“Ini semua salah mak…” katanya perlahan, sebelum suaranya mengeras. “Ini SEMUA SEBAB MAK! Mak yang nak sangat aku kahwin dengan dia tu, kan?!” Jari Airis menunding ke arah Eman yang masih menyeru-nyeru nama Ameena.
Saleha terdiam. Wajahnya sudah pucat, langkahnya bergoyang.
“Dia tak nak aku lah mak… Dia tak pernah nak pun! PUAS HATI MAK SEKARANG?!” suara Airis kini berdentum.
Eman tidak bergerak, hanya memangku tubuh isterinya yang mula dikejarkan paramedik. Tangannya masih berlumur darah, dan dia langsung tak mengangkat wajah.
“Sekarang aku dah boleh kahwin dengan dia…” suara Airis berubah sayu. “Bini dia dah mati, kan…?” Ketawa kecilnya perlahan, namun makin kuat. Ketawa kerasukan, penuh celaka dan derita.
“Pandai tak aku, mak…? Pandai tak…?” Dia menoleh ke arah ibunya, wajahnya penuh luka batin yang tak berbalas.
“Aku… aku dah tak nak pun dia, mak… Tapi mak! Mak yang nak sangat aku kahwin dengan dia! Sebab mak nak sangat jadi ORANG KAYA, kan?!”
Suasana membatu. Semua menahan nafas. Mata Hajah Sufiah sudah merah. Haji Hasyim terduduk, memegang kepala.
“Mak dah kaya hari ni, mak…” Airis mengangkat tangan yang berdarah ke arah langit.
Ketawanya terus meledak, pecah seperti jeritan jiwa yang sudah lama dirantai. Namun wajahnya tetap bergenang air mata. Airis menjerit, menangis, dan ketawa dalam satu masa… jiwanya sudah hancur.
Salleh hanya mampu terduduk di bawah pohon mangga. Matanya melihat ke arah anak perempuan yang tak pernah jentik. Ditatang bagai minyak yang penuh. Memandang pula kepada Saleha.. seorang isteri yang terlalu mementingkan harta hingga akhirnya segalanya musnah.
Bilik Guru petang itu hangat dengan keriuhan mesra. Suara pendingin hawa yang berdengung seolah menyatu dengan deru-deru perbualan ringan antara guru-guru yang baru habis mengajar.
Di satu sudut bilik guru yang agak tenang, Cikgu Ameena sedang mengemaskan barang-barangnya perlahan. Wajahnya berseri, namun kelihatan sedikit penat. Tangannya sesekali mengusap lembut perutnya yang sudah besar. Sudah masuk sembilan bulan. Nafasnya ditarik perlahan, sambil memegang sisi meja untuk berdiri.
Cikgu Lily muncul dengan wajah manis yang tidak mampu menyembunyikan debaran hatinya. Ada sinar yang sukar dijelaskan.
“Amboi…Berseri hari ni, Cikgu Lily…”
Dia menghampiri Ameena sambil mengangkat tangan kanan, menunjukkan cincin emas di jari manisnya.
Ameena yang sudah terbongkok sedikit, tersentak. “Ya Allah…” tangannya cepat-cepat menekup mulut. “Alhamdulillah… Cikgu Isa ke?”
Cikgu Lily hanya mengangguk. Senyumannya bercampur dengan air mata yang bergenang di hujung mata. Hatinya terlalu penuh.
Ameena memegang kedua-dua tangan Lily dan melompat kecil dengan gembira. “Ya Allah... akhirnya...” katanya sambil ketawa kecil.
“Eh! Cikgu Ameena!”
Suara garau Eman yang baru masuk dari arah pintu hampir bergetar. Melihat isterinya melompat walau sedikit, jantungnya hampir luruh.
“Jangan macam tu, bahaya tu, Cikgu,” tegurnya cemas sambil cepat-cepat melangkah ke arah mereka.
Ameena tergelak. “Cikgu Eman! Cikgu Lily dah…” Dia menarik tangan Lily, dan mengangkat tangan Lily tinggi-tinggi ke arah suaminya.
Eman mengangkat kening. Baru sahaja ingin bersuara, tiba-tiba satu deheman kecil datang dari belakang.
Isa.
Dengan gaya tenang, sedikit bersahaja, Cikgu Isa berjalan perlahan menghampiri mereka. Dehemannya yang sengaja itu membuatkan Lily menunduk malu, wajahnya merona merah jambu.
Eman tergelak kecil. Lalu dia menepuk-nepuk bahu sahabatnya.
“Tahniah, bro… akhirnya. Berjaya juga kau,” ucap Eman sambil tersenyum lebar.
Isa hanya senyum nipis. Tapi pandangannya pada Lily berbicara lebih daripada seribu kata.
“Allah dah susun elok, lambat atau cepat… bila sampai waktunya, memang cantik perjalanannya,” balas Isa ringkas.
Ameena berpaut pada lengan suaminya, untuk mengimbangi tubuhnya. Hatinya sejuk melihat dua hati yang akhirnya bersatu. Dalam diam dia tahu, banyak luka yang Cikgu Lily sembunyikan dulu. Sama seperti Airis. Namun dia cepat tersedar. Tidak larut dalam dosa.
Airis pula kini masih di rawat di hospital rawatan mental. Tragis hidup seorang anak yang dikongkong tak siapa yang tahu.
Tiba-tiba Ameena terasa sesuatu di bahagian bawah perutnya. Tangannya menahan sisi meja. Nafasnya tertarik pendek. Wajahnya berkerut. Ada sesuatu.
Seperti gelombang yang naik dari bawah perut ke pusat, menyentap segala saraf yang ada. Ia bukan seperti Braxton Hicks yang biasa. Ini lebih dalam. Lebih menggigit. Bila ia datang, seluruh tubuhnya menegang.
Ameena menggigit bibir. Cuba bertahan.
"Cikgu Ameena... kenapa berpeluh-peluh ni?" tanya Cikgu Lily, yang menyedari perubahan wajahnya. Tangan Ameena disentuhnya. Sejuk.
Ameena berpaling lemah ke arah suaminya. Air mata mula tergenang.
"Abang... Amee rasa macam... macam nak bersalin kot... Sakit… sangat…"
Riak wajah Eman berubah. Panik dan terkejut bertarung di matanya.
"Eh... Sayang, betul ke ni... Baru masuk minggu ke-36 kan? Awal lagi ni… ni sebab lompat-lompat tadi kot.."
Namun tiada jawapan dari Ameena selain keluhan tertahan, nafasnya kian berat, dan tubuhnya mula menggigil. Tangannya menggenggam kuat lengan Eman.
"Cikgu Eman, ini tak boleh tunggu. Kena bawa dia cepat!" suara Lily tegas. Dia sudah mengeluarkan telefon, siap siaga untuk apa-apa panggilan.
Eman pegang wajah isterinya. "Sayang, abang ada… Tarik nafas sama-sama dengan abang, ya? Kita pergi hospital sekarang. Bertahan sikit."
Ameena angguk perlahan. Mulutnya mula beristighfar berulang kali. "Astaghfirullah… Allahumma yassir… Ya Rahman…"
Peluh dingin sudah membasahi tengkuknya. Wajahnya pucat, tetapi matanya masih mencari wajah suaminya — mencari kekuatan.
“Isa! Tolong!” jerit Eman yang sudah mengangkat beg tangan Ameena.
Isa dan Lily serentak bergerak. Lily arahkan pengawal sekolah buka laluan belakang. Isa bantu bawa beg dan minta beberapa guru perempuan lain kosongkan laluan.
Eman merangkul Ameena, membantu dia berjalan sambil menahan kontraksi yang semakin rapat tempohnya. Namun seketika kemudian, Eman terus mencempung tubuh isterinya. Paniknya sudah tidak terkawal.
“Sakit dia lain, bang… Lain macam sangat… Allahu…” suara Ameena parau, terketar-ketar sambil tangannya merangkul kemas leher Eman.
“Kita jumpa anak kita hari ni, sayang… Kuat sikit lagi… Abang dengan Amee… Kita sama-sama, kan?” suara Eman nyaris sebak, tapi dia kuatkan diri. Wajahnya cemas, namun matanya tetap penuh cinta.
Di luar sekolah, kereta Eman meluncur laju menuju hospital. Di dalamnya, doa dan cinta bergaung bersama degup jantung yang semakin tidak menentu.
KARTINI berjalan ulang alik di luar bilik bersalin. Tangannya menggenggam telefon bimbit erat. Hatinya gusar. Anak perempuannya sedang berjuang di dalam bilik itu — antara hidup dan mati melahirkan zuriat yang dinanti.
Bunyi deringan mengejutkan lamunannya. Nama Sufiah terpampang.
“Assalamualaikum… Sufi…”
“Waalaikumussalam… Ameena macam mana, Tini? Masih belum bersalin lagi ke?”
“Belum, Sufi. Masih dalam bilik bersalin. Eman temankan. Doktor kata belum cukup bukaan… saya ni dah tak boleh duduk diam.”
“Allah… kami dah sampai Dungun ni. Dalam sejam insya-Allah sampai hospital. Tini… kuatkan hati ya. Kita sama-sama doa. Ameena tu anak yang tabah. Dia kuat, Tini. Dia kuat.”
Kartini mengangguk perlahan. Matanya masih tertancap ke pintu bilik bersalin yang tertutup rapat.
“Kuat macam mana pun… Setiap kali dia mengerang tadi… macam ada pisau hiris dada saya.”
“Saya faham… tapi percayalah, Allah sedang beri hadiah terindah untuk dia. Dan untuk awak.”
Talian terputus..
Belum sempat Kartini menarik nafas lega, telefon bimbitnya berdering lagi. Kali ini dari anak bongsunya. Ameer.
“Assalamualaikum, Ibu.”
“Waalaikumussalam… Adik. KakChik masih kat dalam. Belum bersalin lagi.”
“Ibu kat hospital sekarang?”
“Haah. Dengan ayah… Ramai ada kat sini. Semua tunggu kat luar.”
Ameer terdiam seketika di hujung talian. Nadanya serius, tapi tetap lembut.
“Ibu… macam mana keadaan KakChik? Doktor kata apa?”
“Doktor kata masih awal. Bukaan baru beberapa cm. Tapi kontraksi dia dah kuat. Ibu tengok dia tadi… menggigil tahan sakit. Ibu tak sanggup, Adik.”
“Ibu… Ibu jangan risau sangat. Dia kuat, Ibu. KakChik tu… dia tak pernah kalah dengan takdir. Ni ujian besar dia. Tapi adik yakin… dia akan lepasi juga.”
Kartini terdiam. Ada air jernih mengalir di pipinya. Kata-kata anak lelakinya itu seperti hembusan tenang yang melegakan dada.
“Ibu tahu dia kuat, Adik. Tapi Ibu tetap rasa nak peluk dia sekarang ni…”
Ameer tersenyum kecil di seberang sana, walau tak nampak.
“Insya-Allah adik sampai tengah malam nanti. Flight adik malam ni. Ibu… kami doakan semuanya selamat. Deeja kirim salam. Kirim salam kami pada Kakak..”
“Ibu sampaikan, sayang…”
“Ibu… Ibu rehat sikit. Jangan lupa jaga diri. Nanti semua perlukan Ibu bila baby tu lahir.”
Kartini tunduk. Matanya memandang langit senja yang makin suram.
“Baik-baik naik flight nanti.”
“Insya-Allah… Doa untuk kami juga ya, Ibu.”
Share this novel



