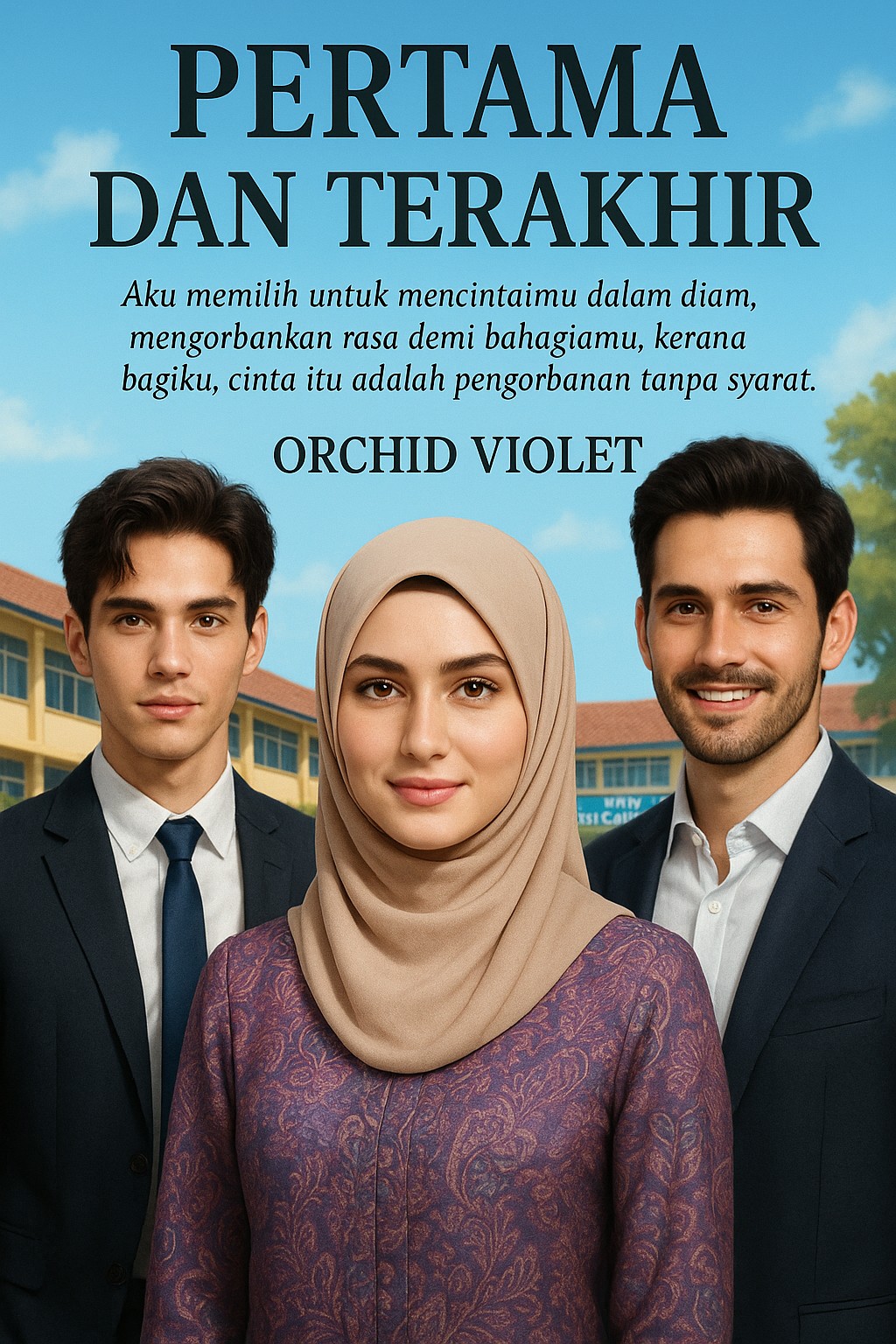
BAB 39 : KE DALAM DAKAPAN MU
 Series
Series
 52946
52946
KERETA mewah hitam metalik itu membelah lebuhraya seperti anak panah yang tidak sabar menepati sasarannya. Di balik tingkap gelap yang menapis cahaya lampu jalan, Haleeda bersandar lemah, memandang keluar ke langit yang berarak kelabu. Kuala Terengganu masih jauh, namun hatinya sudah sampai terlebih dahulu — terikat erat dengan wajah Eman yang terlantar di ICU.
Darren dan Darel, si kembar hampir dua tahun, lena di kerusi belakang dalam buai selamat. Nafas mereka teratur, polos. Tidak mengerti dunia orang dewasa yang sedang dilambung cemas.
"You drive slower sikit boleh tak?" suara Haleeda kedengaran hambar, tidak menoleh pun pada Syahrul yang mengemudi. "The boys tengah tidur."
Syahrul menjeling sekilas, tenang tapi jelas ada keletihan dalam garis wajahnya. "I’m not speeding. You rasa I nak bahayakan anak-anak I ke?"
Haleeda tidak menjawab. Pandangannya kembali kepada pemandangan yang meluncur pergi. Langit, awan, dan jalan raya yang sepi — semuanya seperti mengiringi hatinya yang resah dan sayu.
"Eman is not just my nephew, you know," katanya akhirnya, suara hampir tenggelam dalam deru enjin kereta. "He was my everything when we were kids. My shadow. My best friend. My rival dalam makan coklat."
Syahrul senyap. Dia tahu, saat Haleeda mengimbas kenangan, tidak ada ruang untuk disampuk.
"I remember waktu arwah Tok Bak marah I sebab patahkan bunga orkid dia. I lari menangis. Tapi Eman duduk dengan I bawah rumah, nyanyi lagu Doraemon sampai I ketawa balik. You tahu, dia always had that kind of heart. A gentle one."
"Dia akan okay," balas Syahrul perlahan. "InsyaAllah. Kita kena percaya pada itu."
"I nak percaya," Haleeda menghela nafas panjang. "Tapi I juga tahu macam mana dia tenang cover sakit dia dari semua orang. Dia bukan jenis yang mengadu. Bukan jenis yang mintak simpati. Dia simpan semua sendiri."
Syahrul sekadar mengangguk, tangan menggenggam stereng erat. Di belakang mereka, dua buah lagi kereta mewah milik Paklong dan Pakngah mengekori rapat. Walaupun tiada kata-kata yang dikirim dari belakang, namun kedekatan itu menjadi isyarat bahawa mereka bersama dalam perjalanan yang sama, bukan sekadar ke Terengganu, tetapi ke ruang harapan yang sempit, tempat doa dan kasih bersatu menghidupkan semula nyawa yang dicintai.
Dan Haleeda, dengan luka yang masih belum sembuh bersama Syahrul, menyimpan satu harapan — agar Eman, satu-satunya insan yang pernah menjadi penyambung senyumnya dalam gelita, akan kembali membuka mata, dan dunia mereka tidak akan kehilangan satu cahaya lagi.
Dalam kabin senyap kereta mewah itu, hanya deru angin dan alunan bunyi jalan yang menemani mereka. Dari belakang, Darren dan Darel masih lena, seolah dunia mereka hanya berputar dalam mimpi yang selamat. Haleeda berpaling ke belakang, memerhatikan lena si kembarnya.
“Kalau bukan sebab anak-anak…” Haleeda tiba-tiba bersuara, nada tajam, tanpa memandang ke arah Syahrul. “I takkan ada dalam kereta ni. I takkan duduk sebelah you lagi. Let alone call you husband.”
Syahrul menarik nafas perlahan. “I tahu.”
“I tak pernah berhenti minta maaf. Tapi I tahu, maaf tak cukup. Dan I pun tak expect you lupakan semua tu, Dea…” Suaranya tenang, perlahan, seolah memujuk tanpa kata pujuk.
Haleeda senyum sinis, pandang ke luar jendela. “Don’t call me that. You lost the right.”
Syahrul mengangguk sedikit. “Okay.”
Sepi menyergap lagi. Tapi bukan sepi yang selesa. Ia berat, padat dengan segala yang belum selesai. Namun dari sisi Syahrul, ada satu perasaan yang tetap bersinar , keinginan untuk membetulkan semuanya. Walaupun Haleeda kini hanya ada kerana anak-anak, Syahrul percaya masih ada ruang untuknya kembali membina apa yang telah runtuh.
“You know…” dia bersuara perlahan. “Eman... waktu I cerita semua tentang you pada dia, dia tak pernah salahkan you. Dia cakap, kalau I nak Dea balik, I kena jadi versi I yang dia sayang dulu. Yang tak ego. Yang tak biar bisnes jadi alasan untuk tinggalkan rumah.”
Haleeda tidak menjawab. Tapi wajahnya berubah sedikit. Eman. Nama itu sahaja sudah cukup untuk menggugah perasaannya. Kerana Eman adalah satu-satunya lelaki yang dia percaya tidak akan pernah mengkhianati kasih, sama seperti dia pernah percaya pada Syahrul satu ketika dulu.
“Dia selalu cakap,” sambung Syahrul lagi, “dalam rumah tangga, bukan soal siapa betul, siapa salah. Tapi siapa yang sanggup kalah demi yang satu tu.. cinta.”
Dada Haleeda terasa sempit. Dia benci bagaimana kata-kata Syahrul kadang masih berjaya menyentuh sudut lembut dalam jiwanya. Tapi luka yang dia pikul, masih belum sembuh.
“Jangan guna nama Eman untuk pujuk I,” nadanya dingin. “Dia terlalu baik untuk dijadikan alat.”
Syahrul hanya senyum kelat. “I tak guna nama dia. I cuma sampaikan apa yang dia pernah nasihat I.”
Haleeda pejam mata. Ada air di hujungnya, tapi dia genggam kuat emosi itu. Tak boleh kalah sekarang. Hati dia sudah terlalu lama diguris.
Di luar, langit mula berubah warna. Senja mengintai dari balik awan. Dan di jalan lurus yang panjang itu, mereka terus memandu dalam diam, dalam duka, dalam harapan yang masih bersisa.
Lampu jalan mewarnai malam di pekarangan hospital. Dua buah kereta mewah perlahan-lahan berhenti di ruang parkir yang hampir penuh. Salah satunya milik Syahrul dan Haleeda, manakala dua lagi datang rapat di belakang iaitu kereta keluarga Paklong dan satu lagi milik keluarga Pakngah. Kenderaan mewah itu menyiratkan latar kehidupan mereka yang berada, namun malam ini, tiada satu pun membawa rasa megah—semuanya dalam resah yang serupa.
Syahrul mematikan enjin dan keluar, kemudian membuka pintu belakang untuk mengangkat Darel yang sudah lena. Haleeda pula turun dahulu, kemudian memimpin Darren yang menggenggam boneka kecil di tangan. Wajahnya kelihatan letih, namun masih digagahi dengan ketegasan yang biasa.
Dari kereta Paklong, muncul Raihana, anak sulung Paklong yang baru menginjak usia 22 tahun. Dia segera menghampiri Haleeda.
“Acu, biar Rai pegang Darren ya?” soalnya lembut sambil menghulurkan tangan. Raihana memang suka dengan budak-budak. Begitu juga adik beradiknya yang lain. Namun yang lain tidak dapat turut sama kerana menghadapi peperiksaan penting.
“Thanks, Hana,” jawab Haleeda ringkas, menyerahkan tangan kecil anaknya kepada gadis itu.
Paklong dan Pakngah turut turun, diikuti Makngah dan Anak-anaknya yang lain. Syahrul menghampiri mereka, menyalami Paklong dan Pakngah dengan tenang dan juga anak-anak saudara lelakinya.
“Assalamualaikum, Abang long, Bang ngah.”
“Waalaikumussalam, Syahrul,” balas Paklong, menepuk bahunya ringan. Tiada kata-kata tambahan. Malam itu sudah cukup berat untuk dihias dengan perbualan kosong.
Mereka berjalan perlahan ke arah pintu masuk hospital, hanya ditemani bunyi tapak kasut yang menyentuh jalan berbatu dan rengekan halus Darel dalam pelukan ayahnya. Haleeda tetap mendahului langkah, tidak banyak bersuara.
Di dalam hatinya, hanya satu wajah bermain di benaknya—Eman, teman sepermainan, adik kesayangan yang kini sedang bertarung antara hidup dan mati.
Syahrul mengekori dari belakang, dengan Darel di pangkuan. Pandangannya tidak lepas dari Haleeda. Ada rindu yang tidak disebut, ada penyesalan yang tak pernah cukup ditebus. Tapi malam ini, dia memilih diam kerana semua yang hadir, hanya mahu melihat Eman kembali membuka mata.
SUASANA di ruang menunggu luar ICU yang tadinya suram dan sepi kini bertukar kecoh dalam sekelip mata. Bunyi loceng kecemasan berbunyi dari dalam bilik kaca yang menempatkan Eman sangat nyaring, menusuk, menimbulkan panik dalam dada setiap yang menanti dengan resah sejak tadi.
Fahmi dan Isa bergegas keluar, wajah mereka pucat, nafas tercungap-cungap. Mata Isa merah, seakan hilang pertimbangan.
“Cikgu… Cikgu Eman… dia angkat tangan, tiba-tiba mesin tu berbunyi kuat! Macam ada benda tak kena!” Fahmi tergagap, cuba menerangkan kepada jururawat yang sudah mula masuk dengan pantas bersama pasukan perubatan.
Ameena yang sedang duduk di sisi Cikgu Zaharah tersentak, berdiri dalam keadaan bingung. Tangan halusnya mencari kekuatan pada lutut. Pandangan matanya mencari-cari makna di wajah Fahmi dan Isa yang kini berdiri termangu di pintu kaca. Di sebelahnya, Hajah Sufiah sudah teresak perlahan, menutup mulut dengan telekung yang dipakainya sejak tadi. Tuan Zulkifli pula memeluk bahu isterinya, Kartini yang masih membatu, seakan tidak percaya apa yang sedang berlaku di hadapan mata mereka.
“Ya Allah…” Haji Hashim bangkit perlahan dari tempat duduk, namun gerak langkahnya terhenti separuh jalan. Jiwa tua itu bergetar menahan gundah. Wajahnya berubah kelat, namun tetap digagahkan. Anak lelaki sulungnya… darah dagingnya… kini sedang bertarung dengan sesuatu yang tak pasti.
Jururawat keluar dan menolak pintu ICU ke dalam. Beberapa doktor bergegas menyusul. Pasukan ICU kini bekerja dalam senyap yang tegang. Paparan monitor berkelip ligat di balik tirai.
Ameena menggenggam dadanya. Nafasnya sempit. Dunia seolah berpusing. Namun dia tetap berdiri. Walau hampir rebah, dia tidak akan meninggalkan tempat itu. Tidak selagi Eman masih di dalam.
Ketika itu, pintu utama ruang menunggu ICU ditolak dari luar. Muncul Ameer, lengkap dengan jaket berwarna gelap, diiringi Puteri Qadeeja yang sedang mengendong beg kecil. Di belakang mereka, Aryan dan Arief melangkah laju.
“Apa jadi?” Ameer terus mendapatkan ibunya. Matanya terpaku pada wajah-wajah panik di sekeliling. “Mana Eman?”
“Doktor tengah uruskan… dia...” Ameena tidak sempat menghabiskan kata. Air matanya meleleh tanpa disuruh.
Aryan dan Arief masing-masing memeluk ibu mereka, memberi semangat walau hati sendiri berkocak hebat.
Ameer melangkah ke sisi pintu kaca. Dari celahan tirai ICU, dia lihat tubuh Eman yang tak bergerak dengan wayar berselirat dan mesin berkelip. Beberapa doktor sedang memberi arahan.
“Apa sebenarnya jadi…?” gumam Ameer, lebih kepada dirinya sendiri.
Suasana malam itu pekat. Namun di ruang ini, masa seolah terhenti. Semua yang hadir menanti… menunggu… dengan hati yang seolah tidak berdetak. Dalam ruang ICU itu, nyawa Eman di hujung nafas. Dan di luar, cinta dan doa tidak pernah berhenti mengelilinginya.
Ameer tidak berkata apa-apa sebaik melihat wajah kakaknya. Dia terus melangkah mendekat dan memeluk Ameena erat, seerat pelukan yang menampung seluruh dunia yang sedang runtuh dalam dada wanita itu. Pelukan seorang adik, tapi sejak kecil menjadi sandaran setia yang tidak pernah jemu berdiri di belakangnya.
"KakChik…" bisiknya di telinga kakaknya. "Menangislah… jangan simpan semua tu dalam hati. Aku ada. Bahu ni, sentiasa untuk kau, KakChik. Tak salah kalau menangis. Menangis bukan tanda kau lemah."
Ameena yang tadi kaku, akhirnya melepaskan tangis yang ditahannya sejak dari awal. Tangis yang terpendam, tentang kehilangan, luka lama, dan ketakutan pada kehilangan yang sedang berulang. Dia menangis semahu-mahunya dalam dakapan adik yang paling dia percaya.
Puteri Qadeeja memandang penuh simpati. Dia tahu betapa kuat hubungan mereka, betapa Ameer telah menjadikan kasih pada kakaknya sebagai satu bentuk ibadah sunyi dalam hidupnya.
Ketika tangis Ameena belum juga reda, pintu utama ruang menunggu ICU terbuka. Muncul keluarga Paklong dan Pakngah. Bersama wajah-wajah lain yang sarat kebimbangan, namun tetap tenang dalam gaya yang sederhana tapi terjaga.
Raihana yang turut berjalan di sisi ayah dan ibunya. Dia memandang sekeliling, kemudian pandangannya tertangkap oleh Arief yang sedang berdiri agak jauh, bersandar di dinding, cuba menenangkan diri. Mata mereka bertaut. Tidak lama, tidak berani. Tapi cukup untuk mengingatkan Arief akan perasaan yang telah lama bertapak dalam diam. Raihana sejak kali pertama mereka bertemu di rumah Haji Hasyim dua tahun lalu, sentiasa hadir dalam bayang fikirnya.
Arief cepat mengalihkan pandangan, tapi degupan dadanya tidak dapat disorokkan. Dia belum pernah meluahkan, malah belum tahu apakah waktunya sesuai. Tapi malam ini, melihat Raihana berdiri sebagai sebahagian daripada keluarga yang menyokong, dia tahu, hatinya tak pernah tersalah tempat.
Haji Hashim akhirnya bangun dan menyambut adik-adiknya. Dia memeluk Maklong terlebih dahulu, kemudian Makngah yang menunduk hormat, air mata mengalir di pipinya.
“Alang,” ucap Makngah perlahan, hanya satu patah, namun sarat dengan rindu dan simpati yang tidak terucap.
Hashim mengangguk, matanya bergenang. “Terima kasih datang.”
Kemudian dia memandang Haleeda dan Syahrul yang berdiri di sisi. Haleeda tidak berkata apa-apa, tapi memeluk abangnya erat. Mereka tidak perlu kata-kata. Pelukan itu sudah cukup menyampaikan bahawa hati mereka sama-sama bergetar dalam duka yang satu.
Syahrul turut tunduk hormat dan menyalami Haji Hashim. “Assalamualaikum, Abang Lang.”
“Waalaikumussalam,” jawab Haji Hashim. Dia hanya menyentuh bahu adik iparnya itu ringan. Tiada marah. Tiada dendam. Malam itu bukan tentang kisah lalu, tapi tentang harapan untuk masa depan agar Eman, anak sulungnya, bangkit semula dan menjadi cahaya dalam hidup mereka semua.
Pintu bilik ICU kembali terbuka, dan kali ini muncul seorang lelaki berbaju kot putih, wajahnya tenang namun jelas membawa berita penting. Doktor Asrar, pegawai perubatan kanan yang sejak awal menguruskan kes Eman, melangkah ke hadapan. Di belakangnya, dua jururawat menolak mesin perubatan mudah alih, bergerak pantas namun teratur.
Semua mata segera tertumpu padanya.
"Siapa keluarga terdekat Eman Al Hadi bin Hashim?" soalnya perlahan tetapi tegas.
Haji Hashim bangkit, bersama Hajah Sufiah yang sudah sedia bergantung pada lengan suaminya. Ameena juga melangkah ke hadapan, ditemani Ameer dan Aryan yang memapah tubuh kakak mereka dengan cermat.
“Saya ayah dia,” ujar Haji Hashim perlahan. “Ini isteri saya, anak-anak, dan adik-beradik saya. Itu isterinya dan keluarga besan saya.”
Doktor Asrar mengangguk perlahan, memandang satu persatu wajah yang dipenuhi keresahan. Dia menyusun kata dengan teliti.
“Kami baru sahaja menstabilkan keadaan Encik Eman. Tadi berlaku episod desaturation — paras oksigen dalam darah beliau turun secara mendadak. Beliau berhenti bernafas seketika sebelum kami berjaya bantu semula dengan alat bantuan pernafasan penuh.”
Nafas Hajah Sufiah seakan terhenti. Tubuhnya bergoyang lemah, dan Paklong serta Maklong segera menyambutnya dari sisi, membantu dia duduk kembali. Air mata tidak mampu dibendung lagi. Wajah ibu tua itu pucat, bibirnya bergetar membaca doa yang tidak terlafaz.
Ameena kaku. Dunia seolah terhenti di sekelilingnya. Bunyi, cahaya, dan degupan jantung seakan menjadi satu kesenyapan yang mengerikan. Dia memandang wajah doktor itu tanpa berkedip, hanya menanti dengan harapan tipis... harapan yang berpaut pada setiap nafas Eman yang masih ada.
“Keadaan kini stabil,” sambung Doktor Asrar. “Tapi kami perlu menjalankan imbasan X-ray ke atas paru-parunya. Kami bimbang risiko jangkitan kuman, terutama kepada pesakit yang berada lama dengan ventilator. Kami mahu pastikan tiada fluid build-up atau tanda-tanda pneumonia.”
“Ya Allah…” bisik Ameena akhirnya, suaranya serak, hampir tidak terdengar.
Dia memejam mata seketika, membayangkan senyuman Eman yang selalu menjadi penenangnya. Senyuman yang membuatkan hidupnya terasa masih ada warna, walau dunia sering menghimpit. Senyuman itu yang dia rindukan, lebih daripada apa pun.
“Berapa lama lagi sebelum dia… sedar, doktor?” soal Ameer, suaranya sedikit bergetar.
Doktor Asrar menggeleng perlahan. “Itu kita tak boleh jangka. Kami masih pantau respon otak dan tubuhnya. Namun, selagi ada harapan, kita akan terus berusaha. Doakan dia kuat.”
Anggukan perlahan menggantikan kata-kata. Semua di situ tahu, malam ini akan menjadi satu malam yang panjang. Dan doa adalah satu-satunya yang mereka miliki untuk mengikat Eman kembali ke dunia ini.. dunia yang tak sempurna, tapi penuh dengan orang yang menyayanginya.
Ameena duduk semula, bahunya digenggam erat oleh Ameer. Hatinya masih bergelut, namun satu yang pasti.. dia tidak akan berganjak dari sisi ini. Tidak selagi Eman belum kembali membuka mata dan memberikannya senyuman yang dirindui itu.
Dalam kesenyapan yang panjang itu, hanya deru penghawa dingin dan tangisan tertahan yang menjadi latar. Jam hampir mencecah dua pagi. Di ruang menunggu luar ICU yang kini sepi dan redup cahayanya, Haji Hashim bangkit perlahan. Wajahnya sugul namun tenang, ada sesuatu dalam sorot matanya yang tidak mampu diungkap.
“Ayah nak buat solat hajat,” katanya perlahan, namun cukup untuk menggerakkan semua hati yang hadir. “Kita mohon pada Allah… untuk Eman.”
Mereka mula bangun seorang demi seorang, tanpa kata. Lelaki-lelaki dalam keluarga mengambil tempat. Arief mengatur sejadah-sejadah dari beg sandangnya. Aryan membantu membuka ruang di sudut bilik menunggu, menjauhkan kerusi dan meja kecil ke sisi. Ameer memimpin Haji Hashim ke saf paling hadapan. Arief berdiri di sisi Raihana, membisikkan arahan lembut kepada adik-adik perempuan yang duduk di belakang hijab kain hospital yang ditarik kemas.
Dan malam itu, dalam terang cahaya siling, Haji Hashim mengangkat takbir. Suaranya bergetar, namun tetap utuh sebagai seorang imam. Sujud demi sujud, doa demi doa, mereka serahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Mengetahui. Setiap lafaz terasa lebih berat malam ini, seolah-olah setiap hela nafas mereka turut bertaut pada harapan untuk seorang insan yang sedang bertarung nyawa.
Selesai memberi salam, Haji Hashim menadah tangan tinggi. Suaranya mendayu, tenggelam timbul dalam tangis yang mula pecah dari kalangan keluarga.
“Ya Allah… Tuhan yang Maha Menghidupkan dan Mematikan. Jika masih ada rezeki untuk anakku di dunia ini, Kau pulihkanlah tubuhnya, Kau kembalikanlah semangatnya. Bangkitkan dia dengan senyuman yang kami rindui.”
Suara abah itu kini sudah parau, tenggelam dalam esak kecil yang cuba disorok.
“Tapi jika ini takdirMu, jika ini sampai sini sahaja perjalanan anak kami… Kau ambillah dia dengan cara yang paling mulia. Dalam tenang, dalam damai. Kami redha, Ya Allah… kami cuba redha.”
Ameena sudah terduduk di riba, menekup wajah dengan kedua belah tangan. Bahunya terhinggut-hinggut menahan tangis. Bagaikan belati tajam yang menikam hatinya.. Doa Abah yang terakhir seolah merentap halus seluruh semangat dan harapannya. Ameer di sisinya hanya mampu menggenggam erat tangan kakaknya.
“Ajarkan kami cara melepaskan, Tuhan. Kami ini manusia yang lemah. Tapi kami tahu, Kau tak pernah zalim. Jika suratan hidupnya di sini telah selesai… maka cukupkanlah kami dengan kenangan yang Kau tinggalkan. Dan gantikan kehilangan ini dengan kasih yang lebih luas dari langit dan bumi.”
Air mata Haji Hashim jatuh tidak ditahan lagi.
“Aku hanya seorang abah… yang mahu anaknya kembali. Tapi aku juga hamba-Mu, yang tidak mampu melawan takdir. Jika benar Eman lebih Kau sayang… maka ambillah dia dalam pelukan-Mu yang paling lembut.”
Doa itu menutup solat malam mereka. Tiada siapa yang berkata apa-apa selepas itu. Masing-masing terdiam, ditenggelamkan dalam keheningan yang menikam kalbu. Dan di sebalik dinding kaca ICU, sekujur tubuh masih terbaring kaku — antara hidup dan mati, antara dunia dan akhirat.
...Dan di sebalik dinding kaca ICU, sekujur tubuh masih terbaring kaku — antara hidup dan mati, antara dunia dan akhirat.
Ameena mengesat wajahnya perlahan. Tangisnya sudah surut, tapi hatinya masih terumbang-ambing. Dia bangun, melangkah ke arah cermin kaca. Di situ, dia berdiri kaku, hanya memandang dari jauh.. tubuh lelaki yang pernah menjadi pelindung, sahabat, suami, dan cinta yang tak pernah layu dalam diamnya.
Ameer berdiri di belakang, memeluk bahu kakaknya.
“Kadang-kadang… orang yang paling kuat pun, perlukan waktu untuk menangis,” bisik Ameer. “Dan bila KakChik dah habis menangis… Insya-Allah, kekuatan tu akan datang sendiri.”
Ameena tidak menjawab. Tapi tiba-tiba.. Pergerakan halus. Sangat halus. Dia membetulkan pandangannya.
Jari Eman. Ya, jari Eman..
Jari manis tangan kanannya.. bergerak perlahan. Seolah menyapa. Atau mungkin... hanya reaksi biasa dari tubuh yang tidak sedar. Namun bagi Ameena, itu cukup.
“Abang...” bisiknya dengan suara yang pecah. “Kalau awak masih ada dalam tu… tolong dengar doa kami…”
Dan buat pertama kali malam itu, sebuah senyuman kecil kembali terukir di wajahnya walau sarat luka, ia tetap ada sinar. Harapan.
Ameena masih berdiri di situ, matanya tidak beralih walau sesaat dari tubuh Eman di sebalik tirai ICU yang lutsinar. Bibirnya bergerak perlahan, seakan berbisik, tetapi cukup jelas untuk yang dekat mendengar sebuah luahan yang sekian lama terpenjara di dalam dada.
“Awak tahu tak…” suaranya bergetar, “dalam banyak-banyak hadiah yang saya pernah dapat… cuma satu yang saya ingat sampai hari ni.”
Dia menghela nafas dalam, mengumpul kekuatan untuk meneruskan.
“Satu puisi yang awak tulis..... puisi yang saya sangkakan daripada Isa. Saya masih ingat, awak letak dalam sampul coklat, tulis ‘Jangan buka masa saya tengok’. Dan saya buka sorok-sorok... dan malam tu... malam awak bakal menjadi suami yang awak sendiri tidak tahu siapa pasangan awak.. Saya kembali membacanya semula. Dan.. saya menangis teruk.. Sebab saya tahu, tak ada sesiapa pernah pandang saya macam yang awak tulis dalam bait tu.”
Ameena kemudian memejam mata, seolah mengumpul semangat untuk menyebut kembali bait-bait itu.
“Wahai jiwa yang kupilih menjadi doa,
dalam diam kuikat janji pada langit,
bahawa selagi jantungku belum rehat,
namamu takkan pernah luput dari cinta yang suci…”
Air matanya mengalir semula. Tapi kini bukan dalam tangis kuat. Ia tenang… sayu… seperti sehelai daun yang gugur dalam tenang angin pagi.
“Jika esok aku tiada,
biarlah rindu ini jadi jambatan,
yang menyambung kau dan aku
di dunia yang lebih abadi…”
“Amee masih di sini, Abang. Amee masih rindu. Dan Amee masih sayang…” bisiknya perlahan, suara yang sudah mula terhenti-henti. “Kalau Abang dengar… kalau Abang masih ingat janji kita... pulanglah. Walau hanya untuk sekejap... untuk ucap selamat tinggal dengan mata terbuka…”
Seketika, tubuh Ameena terhuyung.
“Kakchik!!” jerit Ameer, segera menyambut tubuh kakaknya yang melurut jatuh. Puteri Qadeeja turut menerpa, panik.
“Dia pengsan, abang!” jerit Qadeeja sambil menyentuh wajah pucat kakak iparnya.
Beberapa jururawat yang berada tidak jauh segera datang, memeriksa tekanan darah dan denyut nadi Ameena yang tidak stabil akibat keletihan fizikal dan emosi yang melampau.
Dalam dakapan Ameer, wajah Ameena tetap tenang.. seolah akhirnya dia membebaskan semua yang selama ini tertahan. Dan.. dia tersenyum. Seolah telah pergi menemui cintanya.. seakan seorang perindu yang akhirnya lelah menunggu di tepi gerbang mimpi. Bibirnya mengukir senyum halus bukan senyum kemenangan, tapi senyum seorang isteri yang sedang melangkah perlahan ke arah bayang suami di hujung cahaya. Seolah-olah jiwanya sudah bersedia, andai takdir menjemput ke daerah antara nyata dan fana. Di situ, dia berharap akan ada tangan yang menyambut... dan wajah yang dirindui sedang menunggu dengan senyuman yang sama.
Share this novel
User1182
2025-04-27 03:52:52
Jangan laa ending sedihh....

Seri
2025-04-26 01:44:38
Alahai ...



