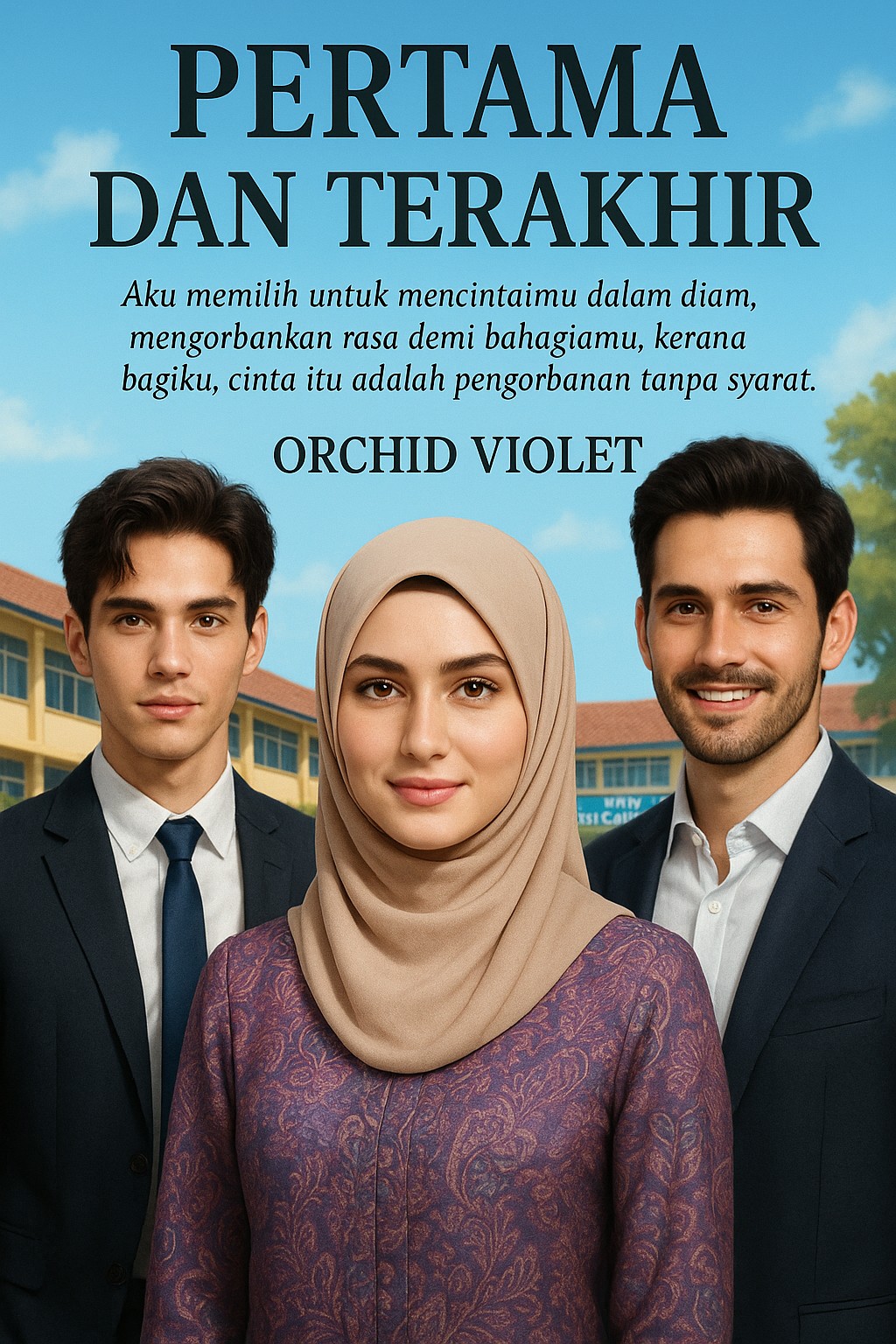
BAB 37 : DI AMBANG KEHILANGAN
 Series
Series
 52946
52946
HATI Ameena berdebar-debar sejak dia keluar dari rumah. Tangan kirinya menggenggam erat bekas bubur yang masih hangat, diletakkan dalam beg kain kecil berzip. Dia memasaknya dengan penuh teliti. Bubur nasi dengan isi ayam yang dikisar halus, sedikit hirisan halia, dan tiada bawang langsung. Dia tahu, Eman sangat cerewet tentang makanan, lebih – lebih lagi sewaktu dia tidak sihat. “Nanti tekak Abang perit,” rungutnya dengan suara manja setiap kali sakit.
Ameena tak menyangka rasa cemasnya menjadi setebal ini. Ketika dia meninggalkan hospital tadi, Eman masih sempat melambai sebelum ditolak masuk ke bilik pembedahan. Wajahnya pucat, tapi masih mencuri senyum, sambil bersuara perlahan, “Sayang balik dulu ya... nanti bawa bubur, macam yang Sayang selalu buat.”
Kata-kata itu terngiang dalam benaknya, menjadi gema yang tidak henti-henti.
Telefon bimbitnya tiba-tiba bergetar. Panggilan dari hospital.
“Puan Ameena?”
“Ya, saya.”
“Saya doktor yang merawat Encik Eman. Suami puan mengalami komplikasi semasa menjalani prosedur. Reaksi alergi terhadap ubat bius. Tekanan darahnya jatuh mendadak. Kami sedang berusaha menstabilkannya. Puan boleh datang segera?”
Ameena terasa lututnya longgar. Nafasnya pendek, jari jemarinya menggigil.
“Ya… ya, saya datang sekarang.”
Sepanjang perjalanan, dia hanya mampu menyebut doa-doa pendek. Harapannya cuma satu, biar Eman terus kuat. Biar dia sempat suap bubur ke mulutnya dan dengar Eman merengek manja, “Sayang suap sikit... macam biasa...”
Sebaik tiba di hospital, dia berlari ke arah ICU. Jururawat segera menjemputnya masuk. Di dalam bilik itu, tubuh Eman terbaring kaku. Wajahnya pucat, mata tertutup, dan mesin di sisi katil berbunyi perlahan, menandakan kehidupan yang sedang digantung harapan.
Ameena melangkah perlahan ke sisi, meletakkan beg bubur di atas meja sisi katil. Tangannya menggenggam jemari suaminya yang dingin.
“Abang... Sayang bawa bubur. Sayang masak macam yang Abang nak. Cuma. Nanti Abang bangun, Sayang suap ya..”
Nafasnya tersekat. Hatinya menjerit, tapi wajahnya masih cuba tenang.
“Abang jangan tinggalkan Sayang... Siapa nak minta suap dengan suara manja tu nanti?”
“Assalamualaikum, puan.”
Ameena menoleh. Seorang doktor lelaki dalam lingkungan awal tiga puluhan menghampirinya. Tag namanya tertulis Dr. Asrar. Wajahnya tenang, tutur katanya sopan, tapi jelas ada beban di sebalik lirikan matanya yang bersungguh.
“Waalaikumsalam.” Suara Ameena hampir tidak kedengaran.
Dr. Asrar menarik kerusi kecil lalu duduk bertentangan dengannya.
“Saya tahu ini bukan berita yang mudah, tapi saya nak puan faham keadaan suami puan sekarang.”
Ameena hanya mengangguk.
“Semasa prosedur, suami puan menunjukkan reaksi alergi yang sangat teruk terhadap ubat bius. Dia mengalami anaphylactic shock iaitu satu tindak balas imun yang ekstrem dan pantas terhadap bahan alergen. Dalam kes ini, mungkin kandungan tertentu dalam ubat bius yang membuatkan sistem badan Encik Eman bereaksi demikian. Buat masa ini pihak kami terpaksa tidurkan dia dahulu untuk memberikan rawatan yang optimum.”
Ameena menelan air liur. Dia cuba kekal tenang.
“Tekanan darahnya menjunam secara tiba-tiba—kami panggil blood pressure crash. Salur pernafasannya juga mula mengecil. Kami terus hentikan prosedur, dan berikan epinephrine untuk buka saluran pernafasan semula. Kemudian kami beri antihistamine dan steroid untuk kurangkan kesan alergi dalam tubuh.”
Dr. Asrar berhenti sejenak, memberi ruang untuk Ameena mencerna kata-katanya.
“Buat masa ini, kami dah berikan semua rawatan yang boleh. Dia sedang dalam pemantauan rapi. Tapi... reaksi tubuh dia terhadap ubat, dan kemampuan dia untuk pulih... itu semua bergantung pada sistem badannya sendiri sekarang. Saya harap puan bersabar dan banyakkan berdoa. InsyaAllah semuanya akan okay.”
Ameena memejam mata seketika. Nafasnya bergetar, tapi dia membuka mata kembali.
“Saya faham, doktor. Terima kasih.”
Dr. Asrar mengangguk perlahan sebelum berlalu dengan langkah berhati-hati.
Di sisi katil ICU, Ameena menggenggam jemari Eman yang diselubungi dingin dengan wayar yang berselirat. Wajah suaminya diam, dan segala suara dunia terasa jauh. Dia tunduk, lalu mencium tangan itu dengan penuh rasa takut kehilangan.
“Abang…” bisiknya. “Sayang kat sini.”
Dan seperti hela nafas perlahan, kenangan lalu menyapa perlahan-lahan, menyusup masuk dari celah-celah sunyi di dadanya.
Ameena masih ingat hari pertama Eman masuk ke kelasnya sebagai guru Bahasa Melayu. Eman waktu itu sudah dua tahun di sekolah itu, terkenal sebagai guru muda yang garang tak kena tempat.
“Kalau tak nak belajar, keluar. Jangan bazir oksigen dalam kelas saya,” katanya tajam pada seorang pelajar lelaki yang tidur di meja belakang.
Semua pelajar takut. Tapi tidak untuk Ameena. Dia benci Eman. Dia masih mentah untuk mentafsirkan semua benda yang dilihatnya apalagi yang tersembunyi dalam hati seseorang seperti Eman.
Tapi di sebalik ketegasan itu, Eman sentiasa ingat nama setiap pelajarnya. Dia tahu siapa yang suka ponteng, siapa yang diam tapi cemerlang, siapa yang suka melukis di belakang buku nota dan Ameena tidak pernah tahu dia diperhatikan. Diam-diam.
Eman cuba mendekatinya bukan dengan kata cinta, tapi dengan teguran yang selalu tepat. Dengan soalan-soalan tambahan selepas kelas. Dengan pandangan yang kadang terburu ditarik kembali.
Dan hari dia jatuh ketika latihan kawad kaki, Eman yang paling cepat sampai. Di depan pelajar lain, dia masih berlagak tegas. Tapi di mata Ameena, dia nampak sesuatu yang selama ini dia tak faham. Dia nampak kerisauan dan ketakutan di wajah itu. Namun umurnya ketika itu tidak mampu untuk faham.
“Lain kali pakai kasut yang elok. Saya tak mahu tengok awak luka lagi, Saya tak ada masa nak jaga benda-benda macam ni. Jangan sebabkan benda ni, cikgu-cikgu disalahkan pula.” katanya selepas membalut lukanya dengan tangan sendiri. Ameena pelik dengan kata-kata itu. Sejak bila dia pakai kasut tak elok? Namun dia malas bertekak dengan Cikgu Eman ketika itu kerana lututnya lebih sakit.
Dia tak pernah berkata lebih dari itu. Tapi sekarang Ameena tahu. Semuanya sudah ada sejak dulu. Dia hanya tak mampu mentafsirnya waktu itu.
Ameena menyentuh dahi Eman dengan tangannya yang lembut. Air mata jatuh satu-satu.
“Abang… Sayang tak pernah sangka Abang sayang Sayang sejak dulu. Tapi sekarang Sayang tahu... Dan Sayang perlukan Abang. Bangun ya…”
Bunyi mesin di sisi katil itu masih konsisten. beep... beep... beep...seakan mengetuk hatinya satu-satu, mengingatkan bahawa masa itu masih ada… tapi mungkin tak lama.
Ameena duduk rapat ke sisi Eman. Hujung jari mereka bersentuhan. Jari yang dulu selalu usap rambutnya bila dia mengadu penat. Tangan yang sama yang dulu selalu menjadi payung setiap kali hujan tiba. Tangan yang sama jugalah yang pernah membela nasibnya disaat dia hampir hilang maruahnya.
“Abang…” suaranya hampir tak bernafas.
Dia tunduk, dahinya menyentuh belakang tangan Eman.
“Kalau Abang dengar Sayang sekarang… Sayang nak minta maaf.”
Tangisnya pecah perlahan, tanpa sedu kuat, hanya getar di dada dan air mata yang tak sempat diseka. Dia tidak tahu kenapa dia sangat lemah bila berhadapan dengan lelaki yang bernama Eman itu.
“Maaf kalau Sayang banyak menyusahkan… kalau Sayang pernah tinggikan suara… kalau kadang-kadang Sayang terlalu pentingkan kerja sekolah… dan lupa Abang perlukan perhatian.”
Dia ketawa kecil, pahit dan kosong.
“Sayang tahu… Sayang banyak buat Abang terasa. Tapi bukan sebab Sayang tak suka. Sayang cuma takut. Takut kalau satu hari nanti… Abang tinggalkan Sayang. Sayang takut luka lama kembali berdarah.”
Dia renung wajah Eman. Pucat, tenang dan diam.
“Sayang garang dengan Abang sebab sayangkan Abang sangat. Sampai Sayang takut kehilangan. Sayang takut tunjuk semua tu… sebab dalam kepala Sayang, cinta tu kena kuat. Tapi sekarang Sayang faham…”
Dia pegang erat tangan itu.
“Sayang tak mahu pisang berbuah dua kali. Dulu Sayang lambat sedar yang Abang jatuh hati dengan Sayang sejak Sayang sekolah lagi. Abang tunjuk dengan cara Abang dengan marah, dengan diam, dengan jelingan yang Sayang benci. Tapi dalam semua tu… ada cinta yang Sayang tak nampak.”
“Sayang tak nak lambat lagi, Abang. Tak nak tunggu Abang hilang baru Sayang sedar. Tolong… buka mata Abang. Sayang masih perlukan suara manja tu. Masih nak dengar Abang minta suap bubur, walau dah sihat nanti.”
Air mata jatuh lagi, kali ini ke dada Eman.
“Sayang minta maaf… dan Sayang minta Abang balik. Balik ke rumah. Balik ke bilik yang kita. Balik ke pagi-pagi yang kita berebut bilik air. Balik ke mahligai kita.”
Dia senyap. Mesin masih berbunyi. Tapi suara Eman tiada.
“Sayang tunggu, ya Abang…”
Dia tunduk, dan letakkan keningnya di dada Eman. Lama. Dalam diam, dia menanti keajaiban..
RUMAH kayu berkonsepkan Bali itu berdiri tenang dalam limpahan cahaya senja. Jambatan-jambatan kayu yang menghubungkan rumah kecil di kiri dan kanan rumah utama seakan melambangkan hubungan keluarga yang tetap erat meski jarak memisah tubuh. Di anjung menghadap taman, Hajah Sufiah duduk diam, sebiji tasbih di tangan, hati tidak seiring dengan ketenangan sekeliling.
“Bang…” Suaranya pecah perlahan.
Cikgu Hasyim memandang dari sudut taman, berhenti menyiram pokok bonsai.
“Hati Saya ni makin berat… bukan saja sebab Eman kat hospital, tapi sebab benda lain jugak.”
Cikgu Hasyim bangkit, berjalan perlahan ke arah anjung, duduk di sebelah isterinya.
“Pasal Airis?” dia meneka.
Hajah Sufiah mengangguk perlahan.
“Saleha tu kita dah lama kenal. Dari dulu lagi saya tahu, dia ada niat lain. Abang tak pelik ke kenapa dia beria-ria nak tumpangkan Airis dekat rumah Eman tu. Siap ugut kita dengan cerita lama Ameena lagi. Allahuakhbar! Kesian sungguh saya dengan menantu saya tu.”
Cikgu Hasyim termenung.
“Dulu pun dia macam tu. Masa Eman baru posting kat sekolah di Terengganu tu, dia dah mula rapat-rapat. Konon nak jodohkan Airis. Tapi dah Eman sendiri tolak si Airis tu, kita nak buat macam mana. Saya rasa ini Agenda yang sama.”
“Sebab tu dia buat cerita.” Nada suara Hajah Sufiah mula berubah, getir. “Masa dia minta izin nak tumpangkan Airis duduk rumah Eman, Saya dah berat hati. Tapi dia cakap kononnya risau anak dara dia duduk jauh sorang-sorang. Katanya, Ameena tak suka. Katanya Ameena tak benarkan Airis tinggal… Sebab itulah dia suruh saya pujuk Eman.”
“Tapi kita tahu, itu bukan perangai Ameena,” sambung Cikgu Hasyim. “Budak tu sopan, lemah lembut, tak pernah tinggi suara.”
Hajah Sufiah mengangguk. “Tu lah… bila Saleha mula buat cerita tak elok, Saya jadi serba salah. Tak nak dia burukkan Ameena pada jiran-jiran. Jadi Saya setuju… sebab tak nak menantu kita difitnah. Tapi dalam hati ni, tetap rasa bersalah pada Ameena.”
“Saleha pandai berlapik, Sufiah. Cakap dia manis, tapi niatnya selalu kita kena baca sendiri.”
“Bang… kita tua-tua ni tak banyak boleh buat. Tapi kita kena doa sungguh-sungguh. Supaya Allah jaga hati anak kita, dan lindung rumahtangga dia. Sebab orang luar belum tentu doakan yang sama…”
Cikgu Hasyim genggam tangan isterinya. “Malam ni kita solat hajat. Kita minta Allah tunjukkan kebenaran. Kalau niat Saleha tak bersih, lambat laun, Allah akan bukakan juga.”
Angin petang menyapa wajah mereka, membawa bersamanya resah yang belum reda. Tapi di hati seorang ibu dan ayah, doa tak pernah putus, walau jarak memisahkan jasad dan anak yang dikasihi.
DI TINGKAT atas rumah itu, Airis bersandar di dinding kaca balkoni bilik tetamu. Dari situ, dia nampak kereta Ameena baru sahaja masuk ke halaman. Wanita itu keluar dengan langkah perlahan, beg makanan berisi bubur masih tergantung di tangan. Wajahnya jelas letih, tapi tetap sempat membalas senyuman jiran sebelah yang memberi salam.
Airis diam. Sudah hampir tiga bulan dia tinggal di situ, dia tidak pernah lihat Ameena meninggi suara dengan Eman. Dia tahu Eman tidak sukakan dia. Namun tidak pernah sekalipun Ameena menegur keras perlakuan suaminya. Kekadang dia nampak ekspresi Eman yang berubah kerana tidak setuju dengan Ameena yang menerima dengan tangan terbuka kehadirannya disitu.
“Kenapa dia tak marah?” bisiknya perlahan, hampir seperti bercakap dengan angin petang yang menerpa masuk.
Sesuatu dalam dirinya terasa berat. Dia bukan tidak sedar akan pandangan mata yang menjelingnya sepi. Bukan juga tidak faham bahasa tubuh Eman yang cuba menjaga sempadan. Tapi bukan itu yang menyakitkan. Yang benar-benar mencucuk, adalah bagaimana Ameena tetap melayan dia dengan baik — walau dia tahu… dia bukan tetamu yang diundang dengan rela.
Airis menghembus nafas. Dia teringat kembali kata-kata ibunya sebelum dia ke sini. “Kau kena ambil peluang ni, Airis. Hidup kau tak boleh bergantung pada simpati orang. Eman tu hak kau, kalau kau tak usaha, kau yang rugi.”
Tapi hari demi hari di rumah ini, dia makin ragu. Bukan pada rancangannya. Tapi pada dirinya sendiri. Mampukah dia menepis bayang seorang wanita yang diam-diam kuat, dan perlahan-lahan menundukkan seluruh rumah ini hanya dengan kebaikan?
Langkah Ameena dihalakan ke dapur. Cahaya petang masuk dari tingkap kecil di atas sinki, membiaskan warna tembaga ke atas seramik putih yang masih lembap dari cucian pagi. Di tangannya, bekas bubur yang tidak disentuh sejak semalam. Eman belum terjaga, tubuhnya masih lelah melawan.
Ameena menyental perlahan, air paip mengalir deras, seakan ingin menghapuskan risau yang bersarang. Tapi hakikatnya, tangannya sahaja yang bergerak. Jiwanya tertinggal di katil hospital, pada jari yang belum genggam semula tangannya sejak semalam.
Langkah dari arah tangga menyapa telinganya.
“Baru balik, Kak Meena?” suara itu datang perlahan, lembut tapi punya nada yang menyelinap.
Ameena berpaling. Airis berdiri di hujung tangga, rambut masih basah, mata bundar memandang dengan senyum separuh. Dia turun tangga dengan langkah ringan, seolah-olah rumah ini miliknya juga.
“Baru sekejap sampai.” Ameena menjawab dengan senyum tipis, kembali menumpu pada kerja di tangan.
Airis berdiri di tepi kabinet, memerhati gerak-geri wanita yang selama ini dia perhati dari jauh dan kadang-kadang, terlalu dekat.
‘Kenapa dia masih tenang begini? Tak letih ke dia jaga Abang Eman di hospital, masak, urus rumah? Kalau aku yang jadi isteri, Eman tak perlu pun susah hati.’ Bisik Airis dalam hati, sambil tangannya bermain dengan hujung baju.
“Saya risau sangat pasal Abang Eman. Dia nampak lemah sangat masa Kak Amee bawa dia ke hospital malam semalam,” ucap Airis, nadanya seperti simpati, tapi matanya mahu menguji.
Ameena berhenti membilas. Perlahan, dia menoleh, mata bertaut dengan pandangan gadis di hadapannya.
“Abang memang kuat. Dia pernah jatuh lebih teruk dari ni… masa dulu. Tapi dia tetap bangun, sebab dia tahu ada orang yang tunggu dia di rumah,” balas Ameena, suaranya lembut tetapi ada sesuatu yang berubah dalam nada itu.
Airis senyum, tapi hatinya terguris.
‘Dia tahu ke maksud aku? Atau dia sengaja? Tapi… dia tetap nampak baik. Macam tak ada niat buruk langsung. Macam aku ni betul-betul adik dia.’ Getus hati Airis, yang mula tidak selesa dengan kekuatan dalam diam wanita di depannya.
“Saya doakan dia cepat sembuh,” balas Airis, hampir tergagap. “Saya tahu kakak jaga dia dengan baik. Tapi kalau ada apa-apa yang KakAmee perlukan… saya ada saja. Anggaplah saya macam adik sendiri, ya?”
Ameena tersenyum lagi. Kali ini, dia mengelap tangan dan memandang tepat ke wajah Airis.
“Terima kasih, Airis. Tapi kadang-kadang, keluarga ni… kita tak boleh sewenangnya anggap. Sebab sayang tu bukan sekadar di mulut, tapi dalam tindakan yang tahu batas.”
Airis tunduk. Dadanya sempit tiba-tiba. Senyuman yang mahu dipamer pun terasa berat.
‘Kenapa dia tak pernah marah? Kenapa dia tak pernah goyah? Macam mana dia boleh tahu aku tak ikhlas? Tapi masih melayan aku baik…’
Ameena berlalu perlahan keluar dari dapur, meninggalkan Airis yang masih terpaku. Hatinya dapat mengesan sesuatu. Langkahnya tenang, tapi hatinya sudah mulai menyusun benteng kerana dalam diam, dia tahu, bukan semua tetamu datang dengan niat bertamu.
Telefon bimbit Ameena berdering tiba-tiba saat dia melangkah keluar dari dapur. Skrin memaparkan nama hospital yang merawat suaminya. Jantungnya bergetar.
“Assalamu’alaikum, puan Ameena?” Suara seorang wanita muda di hujung talian, nadanya tergesa tapi berusaha tenang.
“Wa’alaikumussalam. Ya, saya.”
“Saya Doktor Farah dari ICU. Kami minta puan datang segera. Suami puan menunjukkan tindak balas badan yang agresif terhadap ubat tambahan yang diberikan pagi tadi. Kami sedang cuba stabilkan keadaannya…”
Ameena tak sempat habiskan dengupan di dada. Jari yang menggenggam telefon terasa sejuk. Dia mengucap perlahan.
“Baik, saya datang sekarang,” ucapnya, hampir berbisik. Langkahnya panjang ke arah pintu, tangan meraba kunci kereta yang digantung di dinding. Suasana rumah tiba-tiba terasa sempit.
Airis yang masih di ruang tamu terpandang kelam-kabut Ameena. “Kak Amee? Kenapa?”
Ameena cuba mengukir senyum tapi hanya bibirnya bergerak. “Abang Eman dalam keadaan kritikal. Saya ke hospital sekarang.”Belum sempat Airis berkata apa-apa, Ameena sudah berlalu.
Jalan kelihatan kabur dalam pandangannya yang berair. Jemarinya menggenggam stereng, lidahnya tidak putus berzikir.
“Ya Allah, jangan ambil dia lagi… Bukan sekarang. Belum sempat aku balas semuanya. Belum cukup aku sujud syukur atas cinta yang Kau titipkan...”
“Abang kuat. Abang akan bangun, kan?”
Sebelum sampai ke hospital, dia berhenti sebentar di bahu jalan. Dengan tangan menggigil, dia hubungi Hajah Sufiah terlebih dahulu.
“Assalamu’alaikum, mak…”
Suara Hajah Sufiah yang tenang di hujung sana berubah serta-merta sebaik mendengar nada Ameena.
“Apa jadi, Ameena? Along kenapa?”
Ameena menarik nafas, cuba tidak menangis. “Mak… doktor minta saya datang segera. Keadaan abang tak stabil. Saya dalam perjalanan. Doakan, mak…”
Terdengar suara mak mertua menangis perlahan. Cikgu Hasyim di sebelah kedengaran menyuruh isterinya bersabar.
“Meena, jangan cuai bawa kereta tu. Nanti kami datang, ya?”Ameena mengangguk, walau tidak terlihat.Kemudian, dia menelefon ibunya, Kartini.
“Kak Chik… anak Ibu ni kenapa? Kenapa suara Kakak macam ni?”
“Ibu… Eman kritikal. Kakak takut…”
“Ya Allah!” suara Kartini menjerit kecil.” Ibu datang sekarang. Ayah ada kat masjid, Kakak call ayah ya? Nanti Ibu ambil dia terus kami ke sana.”
Ameena mengangguk lagi. Dia tahu Ibunya sedang menangis dalam diam. Ayahnya, Tuan Zulkifli pula tenang saat dihubungi, tapi suaranya jelas bergetar.
“Ayah doakan dari sini. Jangan lupa baca Yasin bila sampai, KakChik. Kita semua sedang tunggu keajaiban. Tuhan belum habis tulis cerita kamu berdua…”
Ameena melangkah masuk ke hospital dengan debar tak tertahan. Suasana ICU seperti biasa, sunyi tapi penuh tegang. Doktor Farah menantinya di luar bilik kaca.
“Kami sedang cuba stabilkan tekanan darah encik Eman. Beliau kena satu lagi serangan anaphylactic shock. Kami dah berikan adrenaline dan steroid tambahan. Tapi…”
“Tapi?”
“Tubuhnya sangat lemah, puan. Kami perlu lihat dalam dua tiga jam ini sama ada dia stabil atau tidak. Kalau tak kita kena refer ke hospital kerajaan. Dekat sana lebih ramai doktor pakar.”
Ameena mengangguk perlahan. Matanya menatap tubuh suaminya di balik dinding kaca. Kabel berselirat di dada dan tangan. Tapi matanya… masih terpejam.
“Sayang…” bisik Ameena, melekapkan tangannya ke arah dinding kaca, “Bangunlah. Jangan tinggalkan Amee…”
RIUH rendah pelajar di dataran perhimpunan pagi itu seolah tidak mampu menutup hakikat yang bergema dalam diam, kehilangan sementara seorang figura yang selama ini mengisi ruang sekolah bukan hanya dengan ilmu, tetapi juga jiwa.
Di bilik guru, suasananya lain benar. Seperti langit yang suram walau matahari memancar. Kerusi di penjuru, yang biasa diduduki Cikgu Eman, kosong. Fail-failnya masih tersusun rapi, pen hitam masih terbiar terbuka di atas nota mesyuarat terakhir. Seakan menanti tangan yang tak kunjung kembali.
Cikgu Reena menyusun buku latihan di hadapan sambil berbicara perlahan dengan Ustazah Fatimah. “Saya ada telefon Ameena malam tadi. Suaminya masih belum sedar. Doktor kata, keadaannya kritikal.”
Ustazah Fatimah mengangguk, tangannya erat menggenggam tasbih. “Allah sedang uji mereka. Dua jiwa yang sabar... saya sendiri tak mampu bayang.”
Di sudut lain bilik guru, Cikgu Fahmi bersandar pada meja dengan wajah tenang, tetapi matanya jelas menyimpan seribu satu keresahan. “Bro Eman... dia kuat. Tapi bila orang kuat jatuh, kita yang berdiri pun rasa nak rebah,” katanya perlahan kepada Isa yang baru tiba.
Cikgu Isa, dengan kemeja biru gelap dan seutas jam kulit berkilau di pergelangan, melabuhkan duduk dikerusinya. Lesung pipit di pipinya hanya muncul separuh apabila dia tersenyum tawar. “He doesn’t deserve this, bro. He’s always been the best among us.”
Fahmi hanya mengangguk, pandangannya merenung jauh.
Sesaat kemudian, Cikgu Lily melintasi mereka, matanya redup, wajahnya cengkung namun tetap sopan berhias. Isa perasan perubahan itu. Ada sesuatu pada Lily yang sudah lama dia perhati, tapi tidak pernah diberi kata. Hari ini, dia tidak mampu lagi berdiam.
“Lily,” sapa Isa, memanggil perlahan. Lily menoleh, senyum nipis terukir.
“Yes?”
“Mind if I talk to you for a second?”Mereka melangkah ke koridor sunyi di belakang bilik guru. Angin pagi berbisik, seolah mendengar perbualan yang tidak semua berani buka.
“Kau dah berubah banyak,” Isa memulakan, suara dalam dan rendah, dengan irama pelat Inggerisnya yang tersimpan bertahun.
“Sakit mengajar,” jawab Lily, pandangannya jatuh ke hujung tangga. “Bila tubuh tak kuat, kita terpaksa dengar suara hati.”
Isa menyandarkan bahu ke dinding, tangan disilangkan ke dada. “You used to be the loudest one in the room. Now, you're the quietest… but somehow, more real.”
Lily tersenyum tawar. “Dan kau masih penuh teka-teki. Tapi aku tahu… kau juga belum betul-betul pulih dari kehilangan.”Isa tertawa kecil, tetapi tawanya hambar. Matanya kabur sebentar.
“I lost her before I knew what love really means. And now, she’s beside someone who’s fighting death.”
Lily menoleh, matanya bertaut dengan Isa. “Kita cuma pemerhati sekarang, Isa. Tak lebih.”
Isa mengangguk. “Tapi pemerhati pun masih mampu rasa peritnya.”
“Lily.”
“Hmm?”
“I know what it’s like… pretending you're okay when you're not.”
Lily pandang Isa, senyum nipis. “Bila kau dah tahu kau silap, kau cuma mampu berdoa kau tak ulang silap tu. Itu yang aku buat sekarang.”
Isa senyum ikhlas tapi penuh luka. “We’re all broken people, Lil. But some of us… still believe in fixing.”
Langit pagi di Seri Cahaya masih kelabu, seperti turut berkabung. Di blok A tingkat dua, kelas 4 Sains Tulen kelihatan lebih sunyi dari biasa. Meja guru di hadapan kekal kosong, dan papan putih masih tertera nota terakhir yang ditulis Cikgu Eman dua hari sebelum dia jatuh sakit. Hurufnya kemas, tegak berdiri seolah yakin, walau tubuh penulisnya waktu itu sudah pun dalam diam menggigil menahan sakit.
Hari ini, Cikgu Reena menggantikan beliau sementara. Wanita itu berdiri sejenak di pintu kelas, menarik nafas sebelum melangkah masuk. Pandangannya menyapu wajah anak-anak murid yang menyambutnya dengan tunduk dan bisik perlahan. Ada mata yang sembab, ada bibir yang diketap, cuba menahan pecah di dada.
“Assalamu’alaikum,” suaranya lembut.
“Wa’alaikumussalam, cikgu,” jawab mereka serentak, tapi tidak seragam. Ada yang patah di tengah, ada yang nyaris tak terdengar.
Cikgu Reena membuka langkah ke meja guru, meletakkan beg tangan dengan tenang. Sebelum membuka buku atau menyentuh pen marker, dia bersuara perlahan tapi jelas, “Hari ini cikgu tak nak ajar apa-apa. Cikgu cuma nak kita bercakap sedikit tentang… rindu.”
Kepala beberapa pelajar terangkat.
“Siapa di sini yang rindukan Cikgu Eman?” soalnya, tanpa senyum.
Hampir seluruh tangan terangkat dan serentak, suasana berubah. Seorang pelajar lelaki di barisan hadapan, Muiz, menunduk dan menyeka air mata. Seorang pelajar perempuan di sudut kanan, Hana, mengangkat tangan tapi tidak berkata apa-apa hanya menggenggam erat surat yang belum dibuka. Dia tulis untuk Cikgu Eman malam tadi.
“Cikgu Eman pernah beritahu cikgu,” suara Cikgu Reena perlahan, seakan mengusap ruang, “katanya dia tak pernah nak jadi guru hebat, dia cuma nak jadi guru yang anak muridnya masih akan ingat, walau mereka dah tak ingat nama subjek yang dia ajar.”
Pelajar ketawa kecil, penuh sayu.
“Cikgu tahu kamu semua takut. Cikgu pun takut. Tapi mari kita hadiahkan doa yang paling kuat pagi ini, ya? Untuk seorang guru yang tak pernah minta dibalas, cuma minta difahami…”
BILIK guru dipenuhi bunyi kipas berdengung dan sesekali desah kertas yang diselak. Tiada ketawa ringan seperti biasa, tiada senda gurau antara guru. Meja Cikgu Eman dibiarkan kemas, seolah-olah menunggu pemiliknya kembali bila-bila masa.
Cikgu Isa duduk di meja sebelah tingkap. Kemeja kelabu berkolar tinggi tersarung rapi di tubuhnya. Tangan kanannya menyeluk poket seluar, sementara yang kiri menggenggam cawan kopi yang sudah suam. Wajahnya tampak tenang — seperti biasa — tapi matanya… ada sesuatu yang tidak mampu dilitupi kanta bulatnya.
‘Bro, of all people… kenapa kau? Kau lelaki paling lurus, paling setia, paling hidup untuk orang lain. And now… kau terbaring macam tu? Unfair, man. Bloody unfair.’
Lesung pipit di pipinya yang selalunya muncul kala tersenyum, hari ini hanya tinggal bayang. Dia menunduk sedikit, seakan mengelak mata-mata yang mungkin mencuri pandang hatinya yang terbuka.
“Cikgu Isa…”
Suara itu lembut. Cikgu Lily berdiri di hadapannya, sehelai skaf pastel jatuh ke bahu, menutupi sedikit garis wajah yang pucat. Matanya sedikit sembab, tapi masih memancarkan sinar tenang yang sukar ditafsirkan.
Cikgu Isa angkat muka, sedikit mengangguk. “You alright?”
“Sepatutnya aku yang tanya.” Lily tersenyum tipis, duduk di hadapannya. “Kau rapat dengan Eman. Dan… dengan dia juga.”
Isa tarik nafas. Matanya meneliti riak wajah Lily.
“Kau tahu… aku pernah salah anggap tentang kau dulu,” kata Isa, senyum separuh. “But pain changes people, doesn’t it?”
Lily tunduk sejenak, lalu mengangkat pandangan. “Saya tak pernah benci dia. Saya cuma… terlalu mahukan sesuatu yang bukan milik saya.”
“Macam kita semua, huh?” Isa memandang jauh ke luar tingkap. “Some things… tak pernah ditakdirkan untuk kita, no matter how much we try. Tapi somehow, we still end up carrying the guilt.”
Wajah Lily berubah sedikit. Ada kilau yang cuba disembunyikan di hujung matanya.
‘Aku tahu dia tahu. Tentang aku. Tentang semua yang pernah aku cuba sorokkan di sebalik senyuman. Tapi dia tetap bercakap baik. Tak pernah pandang aku sebagai musuh. Kadang-kadang, itu yang lebih menyakitkan…’
“Masa aku dengar berita pasal Eman…” Lily menghela nafas. “Hati aku rasa kosong. Macam hilang satu suara yang selama ni tak pernah pun berbicara dengan aku… tapi sentiasa ada dalam diam.”
Isa angguk perlahan.
“Kau pernah jatuh, Lily. But you got back up. And that means something.”
“Ameena yang ajar aku.” Lily bersuara perlahan, wajahnya sedikit menoleh ke arah meja Ameena yang kosong.
“Ameena…” Isa mengulang nama itu seperti bisikan. Matanya berkaca, tapi tidak pecah.
‘Dia takkan tahu. Betapa aku masih simpan semua puisi yang dia tinggalkan dalam fail kami dulu. Betapa aku… masih ingat bau tudung dia bila angin menerpa di tepi pintu dewan makan. Tapi dia bahagia dengan Eman. Dan aku… sepatutnya belajar reda. Tapi kenapa sakit ni masih ada?’
Lily menunduk. Isa hanya memandangnya lama.
“Kau tahu, Lily… kalau ada satu perkara aku belajar dari mereka berdua…”
“Apa dia?”
“Cinta yang benar… bukan tentang memiliki. Tapi tentang mendoakan orang itu terus hidup dalam bahagia walaupun bukan dengan kita.”
Mereka saling berpandangan. Diam yang panjang tidak terasa canggung, malah seperti doa yang tidak bersuara.
Derap langkah Hajah Sufiah kedengaran lantang dalam sunyi lorong hospital. Kain baju kurungnya sedikit terangkat oleh lajunya hayunan kaki, dan hujung tudungnya menari bersama deruan nafas yang semakin berat. Di sisi, Cikgu Hasyim memegang beg kecil, matanya tidak lepas dari wajah isterinya yang sejak tadi tidak banyak berkata.
Perjalanannya yang jauh dari pahang, tidak lansung membuatkan dia merasa letih. Keletihan badannya telah dikambus dalam oleh rasa bimbang dan risau hatinya.
Saat tiba di luar wad ICU, tubuh Hajah Sufiah terhenti. Nafasnya bagai tersekat oleh pandangan pertama yang menyapa — Kartini, wanita yang sejak dahulu dikenalinya, kini berdiri di sisi dinding kaca, menghadap Eman yang tidak bergerak.
“Tini…” panggilnya perlahan, suaranya bergetar.
Kartini berpaling. Wajahnya tenang, tapi mata sudah sarat dengan genangan yang tak sempat tumpah. Tudung crepe berwarna krim yang dipakainya sedikit terlipat di bahu, seolah-olah dia sudah tidak kisah tentang bentuk lagi — hanya tentang harapan yang masih belum musnah.
“Sofi…”
Mereka saling mendekat. Tidak perlu pelukan, tidak perlu salam — cukup pandangan mata yang menyatu, dan masing-masing tahu, mereka kini berdiri di atas tanah yang sama, tanah doa.
“Saya tak tahu nak kuat macam mana lagi…” suara Hajah Sufiah akhirnya pecah. Dia tunduk, memeluk dirinya sendiri. “Eman tu anak sulung saya, Tini. Saya tengok dia masa dia lahir… dan hari ni saya tengok dia macam ni. Tak bergerak, tak bersuara.”
Kartini mendekat, merangkul bahu wanita itu. Tangannya lembut tapi teguh. “Sofi… anak awak, suami anak saya. Kita sama. Sama-sama jaga doa kita. Sama-sama tahan air mata ni… sebab budak tu kuat. Dia tengah lawan untuk hidup.”
Cikgu Hasyim hanya memandang, matanya merah. Dia bersandar di dinding, membiarkan dua wanita itu berkongsi duka yang hanya seorang ibu boleh faham.
“Ameena tak berhenti zikir. Dari dalam kereta sampai masuk bilik. Dia tak makan, tak tidur. Setiap kali saya pegang dia, dia sejuk. Tapi matanya tetap pandang anak awak, macam semua kepercayaan dia tinggal di situ.” Suara Kartini bergetar, namun tersusun.
Hajah Sufiah mengangguk perlahan. “Saya tak salah pilih menantu, Tini. Dia tak banyak cakap. Tapi hati dia… Tuhan saja tahu berapa dalam cinta dia pada Eman.”
“Cinta mereka ni tak biasa, Sufiah. Saya tahu, saya nampak.” Kartini menarik nafas panjang. “Dan sebab tu kita kena yakin. Tuhan tak bagi mereka jumpa separuh jalan untuk direntap begini.”
Mereka berdiri lama. Di balik dinding kaca, Eman masih terbaring tenang tapi belum selamat. Dan di luar, dua ibu berdiri seperti tiang yang menahan langit. Meski lutut sudah longlai, mereka enggan rebah.
Seketika kemudian, seorang jururawat menghampiri. “Puan berdua ahli keluarga Encik Eman ke? Doktor Farah minta masuk sebentar ke bilik mesyuarat. Ada perkembangan yang perlu dibincangkan. Yang dibelakang sana pun, ya?” jururawat itu tersenyum kepada Cikgu Hasyim dan Tuan Zulkifi yang berdiri tidak jauh di belakang.
Mereka saling berpandangan. Langkah diteruskan. Dan dalam diam, mereka tahu, setiap butir kata yang bakal terucap nanti, bukan sekadar maklumat perubatan. Tapi takdir yang mungkin mengubah hidup mereka selama-lamanya.
Langkah mereka perlahan menyusuri lorong yang sunyi. Bunyi mesin penafasan dan derap kasut jururawat menjadi latar yang menghantui.
“Dulu masa Eman kecil, dia selalu takut gelap,” ujar Hajah Sufiah tiba-tiba, suaranya halus, seperti mengintai kenangan yang sudah bertahun-tahun berlalu. “Kalau blackout, dia akan cari saya. Tak panggil abah dia, tak cari lilin pun. Dia cari tangan saya.”
Kartini tidak bersuara. Hanya senyum kecil yang kelihatan, pahit dan penuh makna.
“Saya masih ingat…” tambah Hajah Sufiah, menoleh. “Masa saya dia tiba-tiba terima menantu pilihan saya, anak awak. Saya takut dia tak cukup matang. Tapi sekarang... saya yang belajar dari mereka.”
“Eman yang ajar Ameena untuk sabar,” balas Kartini perlahan. “Saya ni, Sofi, bukan macam awak. Saya garang. Tegas. Kadang terlajak kata. Tapi bila saya tengok dia layan Ameena, saya terfikir… patutlah anak saya lembut sekarang. Rupanya dia belajar dari suami.”
Mereka sama-sama ketawa kecil, tapi dalam tawa itu ada bayang kehilangan yang sentiasa mencuit bahu.
Hajah Sufiah menyentuh tangan Kartini. Hangat. Kukuh. “Tini, kalau Tuhan ambil dia, saya....”
“Jangan,” potong Kartini, matanya mula berkaca. “Jangan kata macam tu. Tuhan belum izinkan kita menangis untuk kehilangan. Belum.”
Hening sejenak.
Kemudian Hajah Sufiah berkata, hampir berbisik, “Tapi awak tahu, kan? Kalau mereka berdua tak sempat habiskan cerita… tak bermakna cerita kita pun pun terhenti di sini.”
Kartini menarik nafas dalam. Tangannya mengetap jari sendiri. “Sebab itu saya datang, Sofi. Saya datang bukan sebagai ibu yang takut kehilangan anak. Saya datang sebagai seorang wanita yang tahu, cinta itu bukan hanya milik muda. Tapi milik semua yang pernah berharap.”
Dada Hajah Sufiah terasa sesak. Tanpa sedar, air matanya menitis.
“Ada ramai orang doa untuk Eman,” ujar Kartini lagi. “Bukan sebab dia guru. Tapi sebab dia manusia yang tulus. Kita tak boleh kalah sekarang.”
Panggilan dari jururawat memecah sunyi.Mereka melangkah ke bilik mesyuarat, bersama beban yang tak terucap dan harapan yang tak mahu mati.
HARI itu cuaca kelabu. Langit seperti enggan tersenyum, seolah-olah memahami apa yang sedang melingkari sekolah itu. Bangunan dua tingkat yang selama ini riuh dengan tawa dan bunyi tapak kaki murid, hari ini terasa lengang, bukan kerana kekurangan pelajar, tetapi kerana hilangnya seorang guru yang membawa jiwa ke dalam setiap jiwa yang diajarnya.
Di Bilik Guru, suasana suram tapi penuh simpati. Seakan ada yang tidak selesai. Kekosongan tempat duduk Eman begitu ketara. Namanya pada tag meja, buku-buku yang tersusun, malah cawan yang sering diguna untuk membancuh kopi hitam — semuanya masih di situ. Tapi pemiliknya, sedang bertarung di luar jendela dunia ini.
Cikgu Fahmi, seperti biasa, duduk bersandar pada kerusinya. Lesung pipit di pipinya tidak kelihatan seperti selalu — kerana senyum tidak mampu hadir hari ini.
“Bro…” Dia menoleh ke arah Cikgu Isa yang sedang menyandar di dinding luar bilik guru, lengan bersilang, pandangan jauh ke padang sekolah.
Isa tak menyahut. Cermin mata hitam di hujung hidungnya menutupi mata yang sebenarnya sedikit merah. Angin menyelak rambutnya. Dia kelihatan tenang seperti biasa — stylish dengan aura yang tidak dibuat-buat. Tapi wajahnya tidak dapat menipu perasaannya.
“Bro Isa…” panggil Fahmi lagi, kali ini lebih lembut.
Isa akhirnya bersuara, perlahan. British accent-nya masih jelas. “I couldn’t sleep last night, mate. Kept hearing her voice in my head. Ameena…”
Fahmi tunduk. Tak tahu harus menyambut dengan kata apa.
Isa sambung lagi, suaranya hampir berbisik. “You know, I used to think losing her was the worst thing that ever happened to me. But watching her lose him... might be worse.”
Diam panjang menyusul. Kemudian, Cikgu Reena datang menghampiri dengan secawan kopi di tangan. Dia letak di meja Eman. Matanya berkaca, tapi dia tetap tersenyum.
“Cikgu Eman tu bukan jenis yang tinggal luka. Tapi dia tinggalkan bekas. Besar. Dalam,” katanya.
Di hujung meja, Cikgu Yasmin mencuri pandang. Dia dan Ustazah Fatimah berbual perlahan-lahan, sambil melipat kertas latihan pelajar. Tapi mereka tahu, lipatan itu tak mampu menampung rindu yang kian menyesak.
Sementara itu, di ruang koridor, satu pertemuan senyap terjadi. Cikgu Isa terserempak dengan Cikgu Lily, yang sedang berjalan perlahan, memegang fail.
“Lily,” sapa Isa.
Dia berpaling. Wajahnya sedikit cengkung, matanya jelas menahan keletihan. Penyakit yang dialaminya merubah banyak perkara — termasuk suara hatinya yang dulu terlalu lantang memanggil nama Eman.
“Kau pun rasa dia akan pulih?” soal Isa tiba-tiba.
Lily diam seketika, kemudian menjawab, “Aku tak tahu, Isa. Tapi aku harap dia sembuh… bukan untuk aku, bukan juga untuk kau. Tapi untuk seorang isteri yang selama ni tak pernah lari walaupun orang lain mencuba.”
Isa angguk perlahan. Matanya tidak lagi sembunyi.
“Funny, isn’t it?” dia senyum hambar. “We both tried… and we both lost.”
Lily tersenyum, tipis. “Tapi kita belajar.”
Dalam diam, mereka mengangguk — dua hati yang pernah mencuba menceroboh ruang yang bukan milik mereka, kini belajar menerima dan mendoakan dari luar pagar.
Langkah Isa masih berat meskipun koridor sekolah hanya sejengkal panjangnya. Cikgu Lily sudah berlalu ke kelasnya. Suara murid-murid dari kelas bawah bergema samar, namun bunyinya bagai datang dari dunia yang lain. Dunia yang sudah jauh ditinggalkannya — sejak satu jiwa yang dia pernah cinta, kini sedang bertarung dengan takdir.
Dia kembali ke meja guru. Masih kosong di sebelah — meja Eman, masih tersusun seperti biasa. Dan di seberangnya, tempat Fahmi — satu-satunya manusia yang menyaksikan seluruh perjalanan mereka bertiga.
Isa menarik kerusi perlahan, duduk. Tangannya menyandar pada meja, matanya teralih pada lukisan kecil yang pernah mereka coret bersama satu malam hujan — lukisan tiga batang pen merah, terukir nama: Fahmi, Isa, Eman. Seperti tidak ada yang memisahkan mereka waktu itu.
“Eman… kau tahu tak, kau satu-satunya sebab aku boleh hadap hari-hari pertama aku kat sini.”
Hatinya mula bergema, monolog yang sekian lama dipendamkan mula pecah.
“Kau ingat lagi tak, masa kita mula-mula jejak kaki kat Seri Cahaya? Aku dengan seluar slack ketat, kau pulak dengan rambut pacak macho tu… dua-dua confident bukan main. Tapi semua tak jadi kalau tak ada Bro Fahmi.”
“Dia yang ajar kita bezakan pelajar nakal dengan pelajar terluka. Dia yang tunjuk kita cara ajar puisi macam kita lukis langit. Aku ingat lagi ayat dia — ‘kalau anak murid kau tak faham sajak, mungkin dia tak pernah rasa rindu. Tapi kalau kau boleh buat dia rasa, barulah kau cikgu sebenar.’”
Senyuman Isa pahit, tapi muncul juga. Lesung pipitnya tenggelam separuh. Dalam tenang wajahnya, ada ribut yang berpusar.
“Dan kau, Eman. Kau antara manusia paling bersungguh aku pernah jumpa. Tak pernah takut tanya, tak pernah malu belajar. Tapi yang paling aku ingat, kau selalu jadi orang pertama datang bila aku diam. Bila aku mula jauhkan diri sebab… ya, sebab perasaan.”
“Tapi kau tetap melekat. Macam pelita yang tak pernah padam, walau aku sendiri yang cuba tiup.”
Isa memalingkan wajah ke kiri, tempat Fahmi duduk. Lelaki itu masih membisu, tapi seperti tahu Isa sedang bercakap dalam diam. Matanya merenung langit melalui tingkap kecil di hujung bilik guru.
“Bro…” suara Isa akhirnya keluar, perlahan, serak. “Do you remember that one time, masa kita kena ganti kelas 4 Sastera? Kau, aku, dengan Eman… ajar depa pantun lepas hujan?”
Fahmi angkat kening, senyum tipis. “Pantun patah sayap tu?”
Isa ketawa perlahan, kemudian tunduk. Manakan tidak, dia seorang guru Bahasa inggeris tetapi terpaksa mengajar Bahasa melayu ketika itu demi menggantikan guru perempuan yang tiba-tiba cuti bersalin.
‘Tiga lelaki. Satu yang matang, satu yang degil, satu yang jujur. Tapi semua sedang cuba cari makna. Dan bila dia datang.. semua jadi lain.’
‘Aku tak tahu sejak bila aku hilang dia. Tapi aku tahu, aku hilang kau berdua lebih awal.’
‘Bukan sebab kau rampas. Tapi sebab aku terlalu lambat mahu mengaku, bahawa cinta bukan untuk dimiliki — tapi untuk mendoakan.’
Mata Isa berair. Tapi dia cepat-cepat tunduk. Wajahnya kembali tenang, tapi pipinya berat.
Fahmi menyambut senyap itu dengan satu ayat pendek. “Bro, kalau aku boleh patahkan masa, aku takkan ubah apa-apa. Sebab kau tetap Isa yang kita sayang. Cuma nasib kita lain-lain.”
Isa angguk. Tapi suara dalam hatinya tetap bergetar.
‘Kalau aku diberi peluang, aku cuma nak ucap satu hal pada Eman — ‘terima kasih sebab kau pernah duduk di tengah antara kami semua. Dan walaupun kau kini terbaring kaku, sebenarnya… kau tetap yang paling hidup dalam ingatan.’
Isa baru ingin berdiri, saat telefon bimbit Fahmi bergetar senyap di atas meja. Paparan skrin mencatat satu nama yang membuat dahi Fahmi berkerut tiba-tiba — Ameena.
Tanpa sepatah kata, dia terus menjawab panggilan itu.
“Assalamu—”
Kata-katanya terhenti, nafasnya seolah tertarik jauh ke dalam dada.
Isa menoleh. Pandangan Fahmi yang tadi jernih, kini berkaca. Wajah yang tenang berubah jadi kelam, seolah-olah baru disergah oleh sesuatu yang tak terjangka.
“Astaghfirullah… Ameena…” suara Fahmi rendah, serak.Dia berdiri, berbalas kata ringkas dengan suara di hujung talian, tapi butir bicaranya semakin perlahan dan sukar difahami. Matanya tidak lepas dari satu titik kosong di hadapan.
“Okay, awak tunggu. Saya datang. Sekarang juga.”
Dia menamatkan panggilan. Telefon digenggam erat. Isa sudah berdiri di sisinya, matanya menuntut jawapan.
Fahmi hanya memandang Isa. Tiada kata, hanya anggukan perlahan—cukup untuk menyampaikan bahawa sesuatu sedang berlaku.
“Bro…?” Isa cuba menduga.
Fahmi tarik nafas panjang. “Kita kena ke hospital. Sekarang.”
“Hospital?” Isa mendekat, “Eman…?”
Fahmi tidak menjawab. Sebaliknya, dia sudah capai kunci kereta. Langkahnya panjang, tergesa tetapi tenang seperti ombak yang menyembunyikan gelora.
Isa hanya sempat menyambar jaketnya, sebelum mereka keluar berdua dari bilik guru yang kini terasa terlalu senyap, seolah-olah seluruh dinding di situ sedang menyimpan rahsia yang belum terucap.
Share this novel



