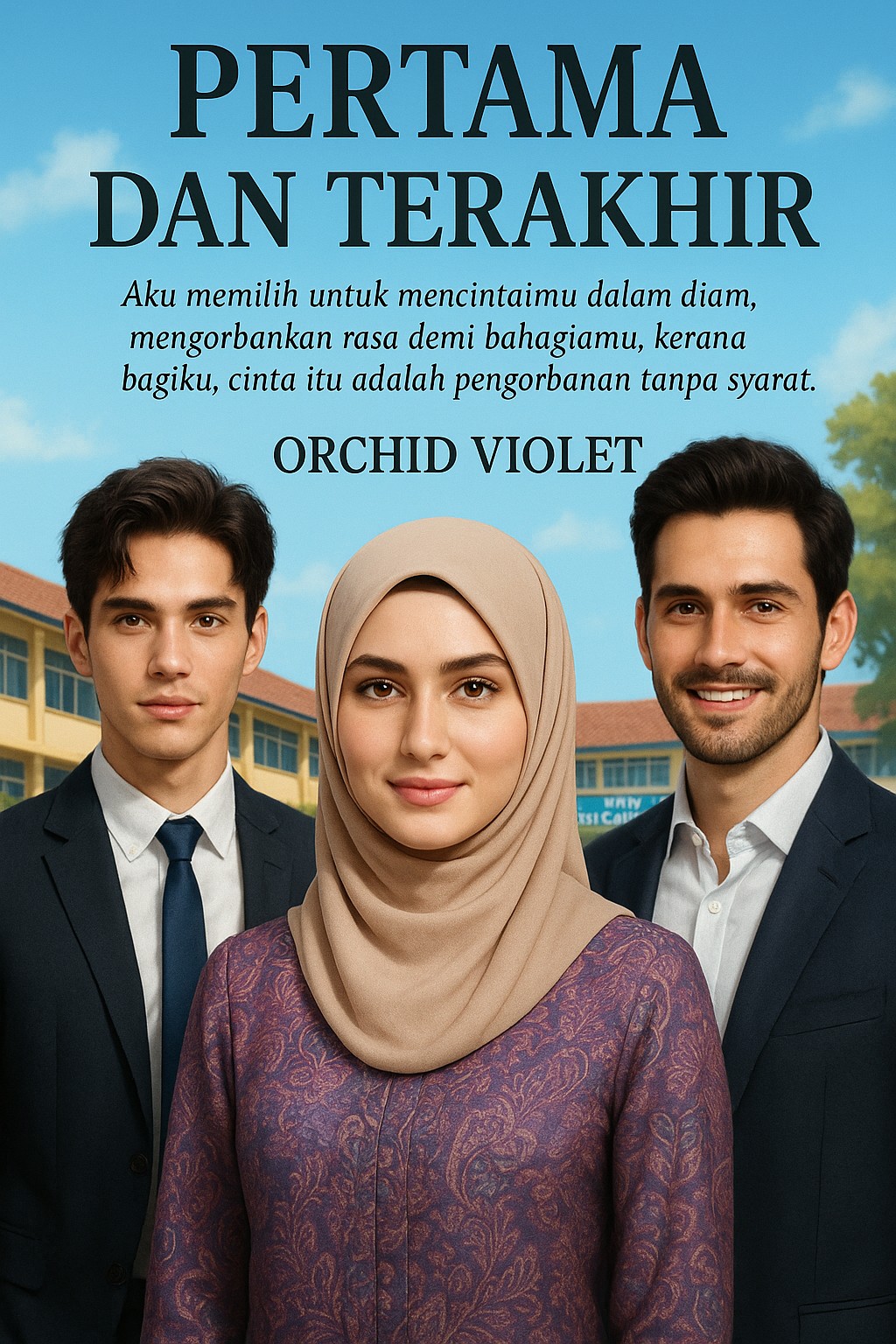
BAB 44 : NIAT
 Series
Series
 59683
59683
MENTARI pagi baru mengintai dari balik bukit-bukit hijau di kaki desa, ketika Saleha sudah berdiri di hadapan rumah pusaka peninggalan Haji Musa. Bekas kuih karipap bertutup kain batik kecil berada kemas dalam dakapannya. Seolah-olah sinar pagi belum cukup hangat untuk mencairkan dingin yang tersembunyi dalam niatnya.
Tanpa sempat menunggu salam bersahut, dia sudah mendaki anak tangga rumah yang berseni ukiran tangan arwah Haji Musa atau lebih dikenali dengan nama Tok Ayah oleh orang kampung itu.
“Kuih karipap panas, Hajah Sufiah. Aku goreng awal-awal tadi. Teringat kat Eman. Niat nak ziarah dia, boleh ke?” suaranya lembut, namun pandangannya tajam... tajam seperti niat yang terbungkus kemas di sebalik senyuman palsu.
Hajah Sufiah cuba berlagak tenang. “Eman masih tidur, Leha. Awal sangat kamu datang ni. Tak ikut Saleh ke kebun ke?”
Pandangan Saleha meleret masuk ke ruang dalam. Matanya memerhati tiap perincian rumah itu seolah mencari sesuatu atau seseorang.
“Airis ada cerita dengan aku semalam…” katanya acuh tak acuh, tapi jelas berniat. Kata-katanya seperti umpan.
Hajah Sufiah menarik nafas panjang, menahan sabar. Tapi sabarnya tipis, seperti kulit bawang yang sekali ditiup angin bisa berterbangan.
Hajah Sufiah mengangkat kening. Nadanya perlahan tapi tegas, “Kalau dah cerita tu berkenaan hal Eman, tak payahlah disambung, Leha. Dada aku ni dah cukup sesak dengan macam-macam hal.”
Saleha menarik nafas panjang, konon bersabar. “Sufiah… anak awak tu… Eman. Dia sebut sendiri Airis tu.. tunang dia. Tak baik kalau kita biar orang terus teka-teka. Tak elok untuk nama anak-anak. Lagipun, mereka dah kerja satu sekolah. Lama-lama orang buat cerita.”
Hajah Sufiah tersenyum nipis. Senyum seorang tua yang tahu benar permainan orang.
“Zaman ni, Leha... cakap orang tak pernah padam. Padam yang ni, menyala yang lain. Kalau kita nak tutup mulut manusia, sampai mati pun tak habis kerja kita. Tapi nak tutup aib yang belum jadi halal, itu kerja kita sebagai ibu.”
Saleha mengangkat kening. Wajahnya masih tenang, tapi mata itu menyimpan api.
“Kalau begitu, apa kata kita halalkan saja hubungan tu? Nikahkan mereka. Mudah semua pihak. Lagipun, Eman tu nampaknya dah lembut hati. Airis pun dah serasi…”
Suara itu terhenti sebaik satu suara lelaki menyapa dari arah ruang dalam.
“Makcik Saleha...”
Langkahnya perlahan, tapi ada wibawa. Eman berdiri di muka pintu rumah induk, berkemeja lusuh dan selendang putih masih tersangkut di bahunya. Wajahnya pucat, namun anak matanya cerah seperti menyimpan badai yang belum reda.
Saleha tergagap kecil. “Eh, Eman... ingatkan masih tidur. Dah nampak segar ya?”
Eman tersenyum, tipis dan berbahasa. Lesung pipitnya singgah seketika. Tapi tiada ikhlas dalam senyum itu. Hanya sisa sopan yang tinggal.
“Makcik sihat? Terima kasih bawa kuih. Pakcik Saleh ke kebun?”
“Ha’ah… makcik datang ni… nak sampaikan hasrat. Kalau boleh, makcik nak bincang majlis kamu dan Airis. Kenal pun dah lama, dah kerja sama, orang pun dah nampak kamu berdua tu serasi. Eloklah kita segerakan.”
Kata-kata itu seperti batu yang jatuh ke dalam kolam hati Eman. Wajahnya tetap tenang, tapi di dadanya, degup jantung seperti dihempap beban tak bernama.
Ameena.
Nama itu datang bersama luka yang belum sembuh. Bayangan wajahnya, senyumannya, suaranya yang lembut bila memanggil “Cikgu Eman…” semua datang menerjah seperti ribut dalam minda yang belum pulih sepenuhnya.
Dialah yang Eman cintai sejak awal. Gadis yang menjentik hati dari balik jelingan. Tapi cinta itu dipendam, ditolak ke hujung jiwa kerana rasa takut, kerana harga diri yang terlalu tinggi untuk mengaku kalah pada rasa sendiri.
Dan saat dia lambat, Isa datang. Sahabat baiknya sendiri. Dan dia menyerah... melepaskan apa yang tak sempat digenggam. Bukan sebab redha. Tapi sebab takut. Dan sebab dia seorang pengecut.
Kini, Airis hadir, menggantikan tempat yang tak pernah kosong. Dan dia terpaksa akur dengan kehendak emaknya.
Eman menggenggam tangan perlahan. Suaranya kedengaran perlahan, tapi cukup untuk menyesakkan ruang tamu itu.
“Makcik… saya minta doakan yang baik-baik. Kadang-kadang, apa yang nampak serasi… belum tentu serasi di dalam hati.”
Saleha terdiam. Hajah Sufiah hanya tunduk, menghela nafas lega. Kata-kata Eman itu, meski perlahan, adalah tanda lelaki itu belum hilang arah.
Eman menoleh, melangkah perlahan masuk ke ruang dalam. Wajahnya kosong. Tapi dalam hatinya, ribut masih bergulung.
“Ameena… kalau masa boleh diulang, aku takkan biar kau jadi milik orang lain.”
ANGIN perlahan dari arah kolam kecil di hujung taman mini itu menyentuh pipi Ameena dengan sejuk yang tidak menghiburkan. Di meja batu yang diteduhi pohon renek, dia duduk berteleku, diam, lesu, memintal hujung selendang dengan jari yang tidak henti menggigil halus.
Tiada kata, hanya hembusan nafas berat yang sesekali pecah dalam sunyi.
Ameer dan Qadeeja berdiri tidak jauh di belakang. Mereka sudah cukup arif dengan kebisuan itu. Sejak Ameena berpindah kembali ke vila keluarga beberapa hari lalu, senyumnya makin jarang. Bila bergurau, bunyinya tawar. Bila bercakap, nadanya kosong.
Ameer dan Qadeeja sudah bulat suara untuk membatalkan penerbangan mereka ke Brunei esok. Keadaan Ameena membuatkan mereka tidak yakin dan tidak berani untuk ambil risiko. Syarikat cawangan kecil Ayahnya di Brunei, diserahkan kepada ayah mertuanya untuk dipantau.
“I think she needs you,” Qadeeja berbisik perlahan kepada suaminya.
Ameer hanya mengangguk.
Qadeeja mengundur perlahan, memberi ruang. Tetapi belum sempat dia memusingkan badan sepenuhnya, tangannya ditarik lembut.
“Jangan jauh…” suara Ameena perlahan, serak. “Duduk sini. Dengan Ameer.”
Qadeeja terpempan seketika. Lalu dia menurut, perlahan duduk di sebelah, dengan Ameer di sisi bertentangan.
Ameena tunduk memandang perutnya yang masih rata, tetapi dalam rahimnya, nyawa kecil sedang tumbuh... enam minggu usianya. Hadir dalam keadaan yang tidak pernah dirancang, tapi tak pernah dia sangkal sebagai anugerah. Jarinya mengusap lembut, seolah berbicara tanpa suara.
“Kakchik ingat… bila Abang Eman sedar, semua cerita sedih kami akan berakhir. Kakchik tunggu… hari tu, tiap-tiap malam dan pagi-pagi yang penuh doa…” suaranya perlahan. “Tapi yang datang bukan lega. Yang datang… sakit yang Kakchik tak pernah sangka.”
Air matanya tumpah perlahan. Tiada sedu, tiada raung. Hanya titisan yang jatuh diam, menyentuh belakang tangannya.
“Aku tak sanggup, Ameer… tengok Airis berkepit dengan dia. Ketawa. Pegang tangan. Macam aku tak pernah ada dalam hidup Abang Eman. Macam aku tak pernah wujud.”
Dia mendongak perlahan, memandang langit melalui celahan daun. “Dia tak ingat aku ni isteri dia. Tapi dalam ingatan dia… Aku masih isteri Isa. Bayangkan… aku kena telan semua tu. Perit!”
Ameer terdiam. Qadeeja tunduk, menahan emosi. Tiada kata yang mampu mengubat luka seperti itu.
“Kakchik rindukan rumah kami. Rindukan gurau senda dia dalam rumah tu. Kakchik menyesal paksa dia terima Airis menumpang rumah kami. Kakchik tahu dia tak happy. Kakchik cuma nak jaga nama baik Mak dengan Abah.”
“Kadang-kadang Kachik rasa nak jerit kuat-kuat. Tapi suara ni pun dah tak mahu keluar. Baby ni saja yang dengar semua.”
Tangan Ameena kembali mengusap perutnya.
“Kamu dengar ya, sayang… Ibu tak kuat, tapi Ibu akan cuba. Demi kamu. Walau Ayah kamu tak ingat Ibu sekarang, Ibu tetap akan sayang dia. Dan Ibu akan sayang kamu… lebih dari nyawa Ibu sendiri.”
Qadeeja akhirnya mencapai tangan Ameena, menggenggamnya erat. “Kakchik… saya tak pernah tahu semua ni. Tapi saya nak ada di sini, kalau kakchik izinkan.”
Ameena hanya mengangguk perlahan. Tanpa kata. Tanpa dendam. Dan itu sudah cukup.
Ameena masih menunduk, mengelus perutnya. Jari-jemarinya melakar bulatan kecil seakan mencari tenang dalam gelora yang tak terungkap.
“Dulu… masa Ibu dan ayah cadangkan jodoh untuk kakak, kakak menolak mentah-mentah. Katanya anak kawan Ibu. Tak kenal pun siapa…” Dia ketawa kecil, hambar. “Kakak kata belum bersedia. Kakak sombong sangat masa tu… rasa macam hidup ni boleh tunggu bila-bila.”
Dia angkat wajah memandang adiknya.
“Kau… tahu tak, kalau aku tahu masa tu yang lelaki yang Ibu maksudkan tu… Eman… aku tak akan tolak. Sungguh, aku tak akan tolak.”
Ameer tertunduk, menahan dada yang sebak melihat wanita yang selama ini tabah, akhirnya mula membuka luka lama.
“Masa minggu orientasi dulu… aku dah ada satu rasa bila pandang dia. Waktu tu dia baik sangat. Ambil berat pasal aku. Tapi aku tak pasti perasaan sendiri. Aku takut… takut kecewa. Jadi aku simpan diam-diam. Aku pendam, aku biar rasa tu berlalu.”
Suara Ameena mengendur perlahan, matanya berkaca.
“Dan bila Isa datang… Dia berubah. Kata – katanya menyakitkan hati aku. Kalau boleh aku nak jadi halimunan. Tak nak tengok lansung muka dia. Tanpa aku tahu dia sebenarnya tengah cemburu. Dan dia sendiri tak reti nak berterus terang. Dua – dua bodoh kan...”
Ameena ketawa perlahan. Pahit. Lama kelamaan bertukar menjadi tangisan halus.. mula pecah perlahan, tetapi dia tetap cuba menahan. Dia masih wanita yang menjaga maruah air mata.
“Sekarang kakchik duduk sini, dalam rumah ni… dengan anak kakchik dalam perut. Dan Abang Eman… Abang Eman hidup lagi tapi tak ingat kakak. Tak ingat semua cerita kita. Yang dia nampak… Airis.”
Perlahan, dia menyandar ke bangku batu. Matanya dipejam rapat. “Kalaulah masa boleh diulang… kakchik sanggup kembali ke hari tu. Hari Ibu tanya, nak tak kahwin dengan anak kawan ibu tu…”
“KakChik… masa memang tak boleh diulang. Tapi kasih yang ikhlas… Allah tahu cara nak pulangkan balik. Jangan putus harap ya? Aku yakin, Abang Eman akan ingat. Cinta kakak tu terlalu dalam untuk hilang begitu saja.”
Qadeeja hanya diam, tapi genggaman di tangan Ameena makin erat. Dalam diam itu, dia tahu hubungan mereka, yang pernah renggang, sudah mula disulam kembali.
Dan di dalam rahim Ameena, ada denyut halus satu kehidupan baru... menjadi saksi kepada cinta, duka, dan harapan yang tidak pernah padam.
BAU tumisan bawang yang samar menyatu dengan aroma kopi yang baru dibancuh. Dapur rumah pusaka itu tenang, hanya kedengaran desiran kipas siling dan dentingan senduk kayu beradu dengan kuali. Haleeda bersandar di tiang kayu, memerhati kakak iparnya menuang air panas ke dalam cawan seramik.
"Saleha datang pagi tadi," ujar Hajah Sufiah tiba-tiba. Nada suaranya tenang, tapi tidak mampu menyembunyikan gelombang yang membuak di dasar.
Haleeda mengerutkan dahi. "Awal pagi macam tu?"
"Datang bawa karipap... dan niat," balas Hajah Sufiah sambil duduk di kerusi rotan. Pandangannya dilempar ke luar tingkap, ke arah rimbun pokok mangga tua yang dulunya tempat anak-anak bermain kejar-kejar.
"Niat apa?" Suara Haleeda berubah sedikit. Hatinya seperti sudah menduga.
"Niat nak jodohkan Eman dengan Airis. Katanya... demi menjaga maruah."
Tertelan liur Haleeda. Tangannya mengepal perlahan. "Ya Allah, Kak Lang... dia ambil kesempatan waktu Eman belum ingat sepenuhnya."
"Ada koi halau dia dengan mata. Tapi bibir koi ni, masih cuba beradab," ujar Hajah Sufiah. “Koi ni... tak sangka manusia boleh berselindung di sebalik karipap.”
Tawa kecil Haleeda pecah, namun hambar. Dia tahu gurauan itu pahitnya tidak terkata. Lalu, dia bingkas bangun.
"Mana Eman?" soalnya lembut.
“Di bilik belakang... bilik yang dia suka tulah. Diam saja sejak sampai hari tu.”
Haleeda mengangguk, menapak perlahan ke luar dapur. Kakinya menyusuri laluan kayu yang menyambung rumah induk ke bilik-bilik kecil di kelilingnya, seperti rumah-rumah inap desa.
Bunyi ketukan ringan dan suara Haleeda memberi salam mengejutkan lamunan Eman.
"Masuklah, Acu."
Suara Eman dari dalam agak perlahan, tapi cukup jelas. Haleeda membuka daun pintu.
"Assalamualaikum, Man..." Haleeda masuk perlahan. Eman bangkit, menyalami dan mencium tangan ibu saudaranya.
“Waalaikumussalam, Acu. Rindu…” Dia tersenyum lemah. “Tapi saya tak tahu... rindu siapa.”
Haleeda ketawa kecil. “Ni jambang apa ni? Dah macam Pakistan jual karpet dekat Pasar Seni.”
Eman turut ketawa namun hambar. Matanya sedikit berkaca
“Acu… Koi rasa kosong sangat. Macam ada sesuatu... yang Koi hilang. Tapi tak tahu apa. Setiap kali koi cuba ingat, kepala Koi sakit.”
“Acu faham, Man... bukan mudah nak hadap semua ni.”
“Acu… Koi penat. Penat sangat. Rasa macam... Koi pernah bahagia. Tapi entah bila. Entah dengan siapa.” Eman tunduk, menggenggam jari sendiri. “Kenapa hati koi rasa kosong sangat, Acu? Macam… separuh jiwa koi hilang.”
Sebelum Haleeda sempat menjawab, pintu diketuk kecil.
“Assalamualaikum,” Syahrul muncul dengan senyum hambar. Darel dan Darren memeluk kaki mereka. “Ni... ada orang rindu Abang Long dia.”
Eman ternganga. Dua pasang mata comel itu merenungnya.
“Abang Long!” jerit kembar serentak, lalu meluru ke arahnya.
Eman terduduk. Matanya tidak berkelip. Tangannya memeluk mereka, tapi jiwanya gementar. “Dah besar... mereka dah besar...”
Dia pandang Haleeda, panik mula menguasai nadanya. “Acu… hari ni tarikh apa?”
Haleeda diam. Syahrul juga terpaku.
“Acu, tolong... Koi minta sangat. Hari ni... tarikh berapa? Tahun berapa?”
“Man…” Haleeda mengambil nafas panjang. “Hari ni... 28 April. Tahun dua ribu dua puluh empat.”
maaf, lepas update app ni, dah tak boleh tulis panjang - panjang. Apa-apa pun instaAllah OV akan update cepat - cepat next chapter.
Share this novel



