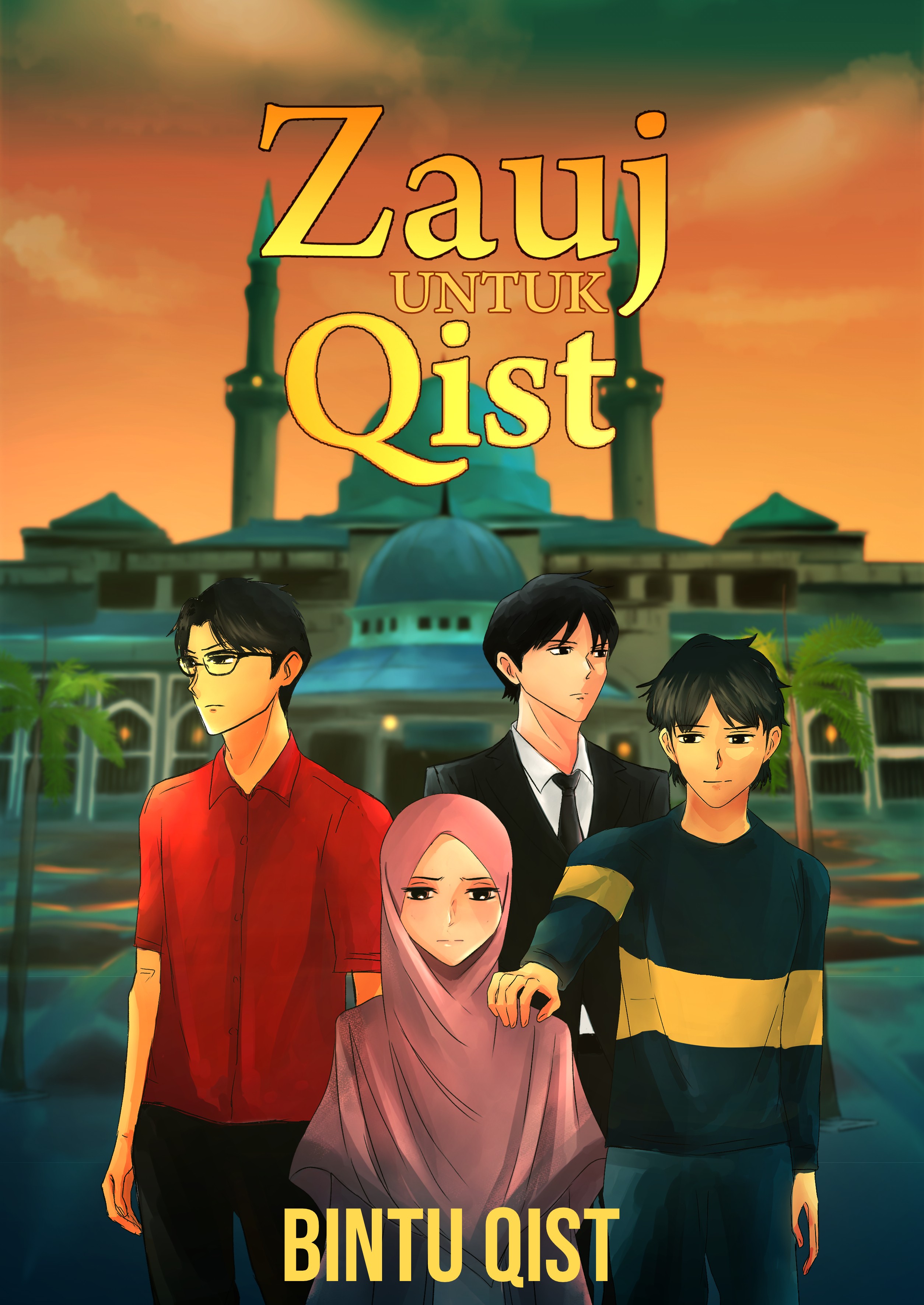
BAB 14
 Completed
Completed
 13719
13719
ABDUL AZIM baru sahaja selesai menikmati sarapan pagi di kafe sekitar Kulliyyah Seni Bina dan Reka Bentuk Alam Sekitar (KAED) itu. Dia melirik waktu yang tertera pada jam tangannya itu. “Allah! Dah nak pukul 10.00 pagi. Aku dah lambat nak pergi kelas ni!” bicaranya sendirian.
Terkocoh-kocoh dia menggalas beg galasnya dan beredar dari kafe tersebut. Atas sifatnya yang kelam-kabut itu, dia tertinggal dompetnya di atas meja makan tersebut.
Kelihatan seorang mahasiswa baru sahaja selesai kuliahnya pada pukul 9.50 pagi tadi, lalu dia bersarapan di kafe KAED itu. Tangan kanannya memegang pinggan berisi nasi lemak berlaukkan ayam goreng berempah manakala tangan kirinya pula memegang segelas teh o limau ais.
Matanya tertangkap pada sebuah meja kosong yang tidak jauh darinya itu. Sebenarnya meja itu tidaklah menarik perhatian pun, namun terdapat barang di atas meja itu. Dia menghampiri meja makan tersebut, lalu dia meletakkan hidangannya di atas meja tersebut. Kelihatan sebuah dompet kulit asli rona hitam jenama Polo. Tangannya mula mencapai dompet berjenama tersebut seraya membelek-beleknya.
“Pergh! Dia pakai jenama ni? Kayanya! Budak kaya mana punya tertinggal dompet ni?”
Dia membuka dompet itu untuk mencari kad pengenalan pemilik dompet tersebut. Mudah bagi dirinya mengesan pemilik dompet itu nanti. Akhirnya, dia menjumpai kad pengenalan tersebut.
“Abdul Azim bin Uthman,” ungkapnya terhadap pemilik kad pengenalan tersebut.
Segera dia menyimpan dompet tersebut di dalam beg galasnya dengan harapan, dia dapat bertemu dengan pemilik dompet itu nanti. Dia bercadang untuk datang semula ke kafe ini pada waktu rehat petang nanti kerana dia pasti pemilik dompet tersebut akan mencari semula di sini nanti.
Dengan lafaz doa makan, dia mula menjamu hidangannya.
USAI sahaja kuliah pada pukul 1.00 petang, perut Abdul Azim mula berkeroncong. Hajatnya, dia ingin merarau di kafe kulliyyahnya (fakulti) sahaja kerana dia perlu menghadapi kelas pada pukul 2.00 petang pula sebentar lagi. Dia membuka zip beg galasnya seraya mencari dompet kesayangannya.
Namun begitu, dompetnya tiada!
Abdul Azim meraba kocek seluarnya pun tiada juga. Dia mula menggelabah, lalu dia bersandar pada dinding dan bertenang seketika. Lantas, dia memaksa mindanya untuk mengingati semula kedudukan terakhir dompetnya itu. Seingatnya, dompetnya masih ada bersamanya waktu sarapan tadi.
Akhirnya, barulah dia teringat bahawa dia telah tertinggal dompet tersebut di kafe. Segera dia mempercepatkan langkahnya untuk ke sana dengan harapan dompet tersebut masih lagi berada di atas meja tersebut. Sesampai sahaja dirinya di kafe tersebut, dia segera menuju ke meja itu semula.
Hampa! Dompet kesayangannya tiada.
Dia bermundar-mandir di sekitar kafe itu. Selain itu, dia juga ada bertanya kepada beberapa orang pekerja di kafe itu tetapi semua jawapan yang diterima olehnya sungguh menghampakan. Hatinya semakin resah gelisah. Surah al-Insyiraah dilafazkan dalam hati bagi mengurangkan rasa resahnya itu. Hampir 20 minit juga dia mencari dompet kesayangannya itu, namun rezeki tidak menyebelahinya.
‘Ya Allah, kenapalah aku cuai sangat ni! Mesti baba sedih sangat kalau baba dapat tahu, dompet yang baba hadiahkan kat aku tu dah hilang. Baba, maafkan Azim. Azim cuai!’ bisik hatinya. Dia benar-benar buntu, namun pada masa yang sama, dia masih berharap jika terdapat insan baik yang terjumpa dan menjaga dompetnya buat seketika ini.
Mindanya menerawang kembali tentang peristiwa dompet itu.
“Azim, nah,” kata Encik Uthman seraya menghulurkan kotak yang diikat dengan reben kepada anaknya itu.
“Eh! Apa ni, baba?” tanya Abdul Azim.
“Bukalah. Mesti Azim suka.”
Abdul Azim membuka ikatan riben tersebut, lalu dia membuka penutup kotak itu. Kelihatan dompet kulit jenama Polo rona hitam edisi terkini tersergam megah di dalamnya. Dia memandang ayahnya itu.
“Wah, dompet ni! Sukanya! Memang salah satu impian Azim nak beli ni tapi kenapa baba hadiahkan pula? Sempena apa?” respons Abdul Azim.
“Kan hari tu Azim dapat CGPA four flat masa keluar keputusan baru-baru ni. Baba hadiahkanlah sebagai pemangkin semangat untuk Azim terus semangat belajar,” terang Encik Uthman.
“Tapi baba… Azim tahu dompet ni mahal harganya. Azim pernah tengok dulu. Hampir RM1000.”
“Tak ada apalah, Azim. Tak luak pun duit baba nak belanja anak kesayangan baba ni.”
Abdul Azim terus mendakap ayahnya itu. “Terima kasih, baba. Insya-Allah Azim akan buat lagi baik untuk semester depan. Baba doakan Azim. Azim nak berjaya macam baba juga.”
“Sama-sama Azim. Insya-Allah, baba sentiasa doakan Azim,” balas Encik Uthman.
Dompet itu merupakan hadiah daripada ayahnya kerana dia berjaya meraih Purata Nilai Gred Kumulatif (CGPA), iaitu 4 rata buat kali pertama pada semester lalu. Namun begitu, sama ada dia mahu atau dia tidak mahu menerima atas apa yang telah berlaku hari ini, dia terpaksa juga menerima hakikat bahawa dompetnya sudah hilang. Berkali-kali dia memujuk hatinya. ‘Ada hikmahnya dompet aku hilang. Redalah ya, Azim.’
Dia merehatkan dirinya pada meja makan yang tersedia di luar kafe itu. Air mineral yang telah dibeli di kafe pada waktu pagi tadi dikeluarkan dari beg galasnya, lalu diteguknya bagi menghilangkan rasa dahaga. Dia tidak mahu memikirkan tentang dompetnya yang hilang buat sementara ini. Seleranya untuk makan pada waktu ini juga sudah mati.
Tiba-tiba, hadirnya seorang mahasiswa dengan menghampirinya seraya memberi salam. “Assalamualaikum brother.”
Abdul Azim mengangkat wajahnya. Dia agak terkejut melihat wajah mahasiswa itu. Wajah lelaki itu kelihatan sangat mirip dengan seseorang yang dia pernah kenali di pusat asasi dahulu, namun dia tidak mengingati gerangannya.
Mahasiswa itu melemparkan senyuman kepadanya. Abdul Azim membalas senyuman lelaki itu, lalu dia menyapanya. “Waalaikummussalam. Ya, kenapa brother?”
“Brother Abdul Azim, kan?” soal lelaki itu.
“Err... Ya. Saya Abdul Azim. Macam mana brother tahu nama saya?”
Tiba-tiba lelaki itu menghulurkan sesuatu kepadanya. “Dompet brother.”
Abdul Azim menyambutnya dengan penuh gembira. “Ya Allah! Alhamdulillah! Terima kasih sangat brother. Kat mana brother jumpa dompet saya? Saya memang tengah cari.”
“Sama-sama. Pagi tadi brother tertinggal dompet brother kat atas meja bahagian dalam kafe ni. Memang saya dah ada kat sini dengan niat nak cari brother tapi saya tak nampak tadi sebab saya ada kat bahagian dalam. Saya tergerak hati nak cari kat luar kafe ni. Kita jumpa juga akhirnya.”
“Terima kasih brother. Terima kasih sangat! Hanya Allah je dapat balas jasa brother. Nama brother?”
“Sama-sama. Amin ya rabb. Semoga Allah juga memulangkan semula kebaikan kepada brother. Nama saya, Suhaib. Suhaibul Umar.”
Huluran salam Suhaibul Umar disambut oleh Abdul Azim sebagai tanda pengenalan.
SEJAK peristiwa dompet itu berlaku sebulan yang lalu, hubungan Abdul Azim dan Suhaibul Umar menjadi sangat akrab sebagai sahabat baik setelah Abdul Azim sangat menyenangi peribadi Suhaibul Umar sebagai seorang senior yang satu major dengan dirinya. Juga, sifat amanah yang terdapat dalam diri Suhaibul Umar.
Malah, rakan-rakan sebilik Abdul Azim, iaitu Amirul Azhar dan Muhammad Syarafuddin yang merupakan bekas rakan sekelasnya sewaktu di pusat asasi dahulu juga sudah sedia maklum akan keakraban mereka berdua itu. Selalu juga Abdul Azim mengunjungi bilik Suhaibul Umar bagi memanjangkan silaturrahim sesama mereka. Begitu juga Suhaibul Umar.
Abdul Azim juga sudah mengenali kawan baiknya itu dan merupakan satu fakulti dengan dirinya, iaitu Kulliyyah Seni Bina dan Reka Bentuk Alam Sekitar (Kulliyyah of Architecture and Environmental Design - KAED) serta merupakan seorang mahasiswa tahun ketiga semester satu di bawah cabang Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dan Seni Reka (Kepujian) atau Bachelor of Applied Arts and Design (Honours). Sama juga seperti Abdul Azim. Suhaibul Umar tidak kekok untuk menghulurkan bantuan jika Abdul Azim meminta dirinya untuk mengajar subjek yang sahabatnya itu kurang faham.
“Azim, boleh tak abang tanya sesuatu?” tanya Suhaibul Umar pada suatu hari.
Waktu itu, mereka berdua sedang melepak di Taman Tasik Titiwangsa bagi merehatkan minda dari menyiapkan replika model-model yang sedang bertimbun.
“Boleh. Tanyalah,” balas Abdul Azim.
“Emm… Azim ada suka sesiapa tak?”
Abdul Azim terkedu. Mimpi apa pula kawan baiknya bertanya soalan sedemikian? “Kenapa tiba-tiba abang tanya?” tanyanya.
“Sebab abang rasa Azim ada suka seseorang.”
Abdul Azim terdiam. Dia juga tidak pasti perasaannya terhadap seseorang yang pernah menyukai dirinya. Dia mula rasa keliru semula. Dulu, dia akui bahawa dia pernah menyukai perempuan tersebut.
Qistur Ruwaidah binti Isyraf Imrani.
Nama yang begitu menggetarkan jiwanya di Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (CFS IIUM) suatu ketika dahulu.
‘Apa khabarlah dia agaknya? Dia masih suka kat aku ke tak ataupun dia dah suka orang lain?’ bisik hati Abdul Azim.
“Azim?” Suhaibul Umar mematikan lamunan Abdul Azim itu.
“Err... Y... Ya,” balas Abdul Azim, gugup.
Suhaibul Umar tersenyum mendengar respons sahabat baiknya. “Betullah tekaan abang. Azim ada suka seseorang ni.”
Abdul Azim menggeleng laju kepalanya. “Jujurnya. Azim tak pernah suka sesiapa pun. Cumanya...”
Dia terdiam seketika.
‘Egokah aku? Apakah sebenarnya perasaan aku terhadap Qist?’ soal hati Abdul Azim.
Perlukah dia berbohong lagi akan perasaannya? Hatinya mula mengakui bahawa dia memang sayang dan rindu akan Qistur Ruwaidah. Sudah hampir setahun lebih mahasiswi itu tidak berhubung lagi dengan dirinya. Biasanya mahasiswi itu akan menghubungi dirinya terlebih dahulu. Mereka berdua telah putus hubungan selepas apa yang telah berlaku.
Abdul Azim menyedari bahawa dialah puncanya perempuan itu tidak lagi menegurnya. Semuanya gara-gara Qistur Ruwaidah meluahkan perasaan kepadanya menerusi peti mesej peribadi Fac miliknya dan dia pula memberikan jawapan yang amat mengecewakan.
“Cumanya apa?” soal Suhaibul Umar seraya memandang sahabat baiknya itu.
“Cumanya, ada seseorang yang pernah minat Azim tapi Azim tak pernah bagi apa-apa harapan kat sister tu,” Abdul Azim terpaksa berbohong.
“Wah, Azim ada peminat rupanya! UIA juga ke? Dia jurusan apa?”
“Haah. Dia UIA juga. Alaa... Tu cerita dulu, abang. Entah-entah, dia dah suka orang lain pula. Dia jurusan BAR kalau tak silap. Rasanya, dia masih kat CFS.”
“BAR? Oh. Abang pun ada adik yang masih belajar kat CFS. Sebaya Azim. Sebelum jurusan BAR, dia jurusan LAWS dulu. Semester ni merupakan semester terakhir dia kat CFS. Insya-Allah.”
Penerangan Suhaibul Umar membuatkan Abdul Azim berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang adik sahabat baiknya itu. Kalau tidak silap, mahasiswi yang pernah suka akan dirinya itu juga asalnya daripada Asasi Undang-Undang (LAWS). Setahunya juga, sekarang mahasiswi itu bersama Asasi Bahasa Arab (BAR) pula. “Siapa nama adik abang tu ya?”
Tiba-tiba telefon bimbit Suhaibul Umar berbunyi. “Eh Azim. Sekejap ya,” katanya seraya mengeluarkan telefon bimbit dari kocek seluarnya.
Abdul Azim mengangguk.
Melihatkan pemanggilnya itu, Suhaibul Umar tersenyum seketika seraya menjawab panggilan itu. “Assalamualaikum adik.”
“Waalaikummussalam. Abang, boleh tak ambil adik pukul 5.00 petang sekejap lagi? Adik tak ada kelas esok. Kelas dibatalkan,” jawab Qistur Ruwaidah, suaranya kedengaran agak ceria.
“Amboi, sukalah tu kelas batal!”
Kedengaran suara Qistur Ruwaidah ketawa di hujung talian. “Mestilah. Pelajar mana yang tak suka kelas dibatalkan. Tak adalah. Adik gurau je. Emm… Abang boleh ambil adik tak? Kalau abang tak lapang, adik balik naik LRT je sekejap lagi.”
“Boleh je. Tak ada masalah. Sekejap lagi abang gerak. Bagi abang masa dalam setengah jam.”
“Okey abang. Terima kasih. Sayang abang. Assalamualaikum.”
“Sama-sama. Sayang adik juga. Waalaikummussalam.”
Talian dimatikan.
Suhaibul Umar amat merindui adiknya itu. Abdul Azim tersenyum melihat senyuman kawan baiknya itu secara tidak langsung. “Rapat juga abang dengan adik abang ya.”
“Hubungan kami memang rapat pun. Dia je satu-satunya keluarga abang yang masih ada.”
Suasana menjadi bisu seketika. Angin sepoi-sepoi bahasa menghiasi Taman Tasik Titiwangsa itu. Wajah Suhaibul Umar kelihatan tenang. Seolah-olah tidak terusik dengan apa yang diperkatakan tadi. Abdul Azim terkedu seketika. Barulah dia mengetahui bahawa sahabat baiknya itu telah kehilangan ahli keluarga tercinta.
Ingin sahaja dia bertanya punca kematian ahli keluarga Suhaibul Umar itu, namun dia mengambil keputusan untuk mendiamkan diri buat masa ini. Tidak sesuai pula untuk dia bertanya pada waktu ini. Bila-bila nanti, dia akan bertanya mengikut masa yang sesuai.
“Azim, boleh tak abang pergi ambil adik abang kat CFS dulu? Sebab dah dekat dari sini. Lepas tu, abang hantar Azim kat UIA balik,” pinta Suhaibul Umar.
“Boleh je abang. Azim tak kisah pun,” balas Abdul Azim.
MELIHATKAN Suhaibul Umar masih belum tiba, Qistur Ruwaidah mengambil keputusan untuk menunggu abangnya di tangga utama Mahallah (Kolej Kediaman) Aisyah (AC). Dia mula menikmati awan biru itu. Tenang rasanya kalbunya itu.
Tiba-tiba jiwanya sedang merindui seseorang. Namun begitu, dia tidak tahu keadaan terkini lelaki itu. Lantas, dia menggelengkan kepalanya.
Lelaki itu...
Abdul Azim bin Uthman.
Setiap kali mendengar nama itu, hati Qistur Ruwaidah menjadi terusik. Dia sendiri tidak tahu mengapa dia perlu berperasaan sedemikian. Walhal, dia sudah sehabis daya untuk melupakan lelaki itu dari kotak memorinya. Dia tidak boleh berharap lagi kepada lelaki yang tidak mempunyai sebarang perasaan terhadapnya dan dia bahagia mempunyai seorang abang yang setia bersama dirinya.
Walaupun mereka berdua saling mengikuti di media sosial tetapi mahasiswa itu jarang memuat naik apa-apa status atau gambar. Itu menyebabkan dia tidak tahu keadaan terkini lelaki itu.
‘Kau sihat ke, Azim? Semoga kau berada dalam keadaan baik kat UIA Gombak sana,’ bisik hati Qistur Ruwaidah biarpun dia tahu itu tidak akan mengubah apa-apa.
Kelihatan kereta Mydi berwarna putih sudah pun tiba. Dia tersenyum melihat kehadiran kereta itu. Namun begitu, dirinya menjadi hairan apabila dia melihat seseorang sedang berada di tempat duduk bersebelahan dengan pemandu itu dari kejauhan.
Siapa pula di sebelah abangnya itu? Apabila kereta itu semakin menghampirinya, Qistur Ruwaidah kaget.
Abdul Azim!
Baru sebentar tadi dia teringat akan lelaki itu. Persoalannya, bagaimanakah Abdul Azim boleh mengenali abangnya itu?
Abdul Azim juga kelihatan kaget. Barulah dia teringat bahawa dia terlupa untuk bertanya kembali nama adik sahabat baiknya di Taman Tasik Titiwangsa tadi. Rupa-rupanya...
‘Qist merupakan adik kepada Abang Suhaib rupanya! Patutlah muka Abang Suhaib ada iras Qist masa mula-mula aku tengok kat kafe KAED dulu,’ bisik hati Abdul Azim, kegirangan. Hatinya berbunga-bunga melihat mahasiswi itu. Bagai ada sebuah sinar harapan baharu untuk dirinya.
Apabila kereta Suhaibul Umar tiba di hadapan tangga utama AC, Qistur Ruwaidah menjadi teragak-agak untuk membuka pintu kereta di bahagian belakang tempat duduk penumpang. Dia sendiri tidak tahu bagaimana hendak berhadapan dengan jejaka itu meskipun Abdul Azim duduk di bahagian hadapan. Akhirnya, dia membuka juga pintu kereta itu.
“Assalamualaikum,” ucap Qistur Ruwaidah seraya menutup pintu kereta. Dia menghulurkan tangannya untuk bersalaman dengan abangnya itu.
“Waalaikummussalam adik,” balas Suhaibul Umar.
Akhirnya, kereta Mydi yang dipandu oleh Suhaibul Umar meninggalkan kawasan CFS IIUM. Suasana dalam kereta menjadi bisu seketika.
“Oh ya adik. Abang lupa nak perkenalkan brother yang duduk sebelah abang ni. Nama dia Abdul Azim, sahabat baik abang. Satu kulliyyah (fakulti) dengan abang.”
“Oh,” respons Qistur Ruwaidah bersahaja.
Walhal, sebenarnya dia berasa amat terkejut. Sejak bila pula Abdul Azim ini menjadi sahabat baik abangnya pula? Misteri sungguh.
Dia perlu bersikap profesional terhadap mahasiswa itu meskipun dia masih ingat lagi jawapan lelaki itu sehingga membekas dalam jiwanya. “Erm... Azim, kau sihat? Lama aku tak dengar khabar kau sejak kau dah habis belajar kat CFS,” tegur Qistur Ruwaidah.
Abdul Azim menoleh ke belakang meskipun dirinya malu untuk menatap wajah perempuan itu. Satu-satunya hati perempuan yang pernah dia lukakan suatu ketika dahulu. Tidak elok pula sekiranya dia memberi respons tanpa memandang mahasiswi itu. “Alhamdulillah. Aku sihat je. Kau pula macam mana? Dah semester berapa?”
“Alhamdulillah. Sihat juga. Ni merupakan semester akhir aku. Kalau tak ada aral melintang, bulan September ni aku masuk main campus. Insya-Allah.”
Mendengar perbualan dua orang mahasiswa dan mahasiswi itu, Suhaibul Umar mencelah perbualan dua orang itu. “Memang adik dan Azim dah pernah kenal ke? Gaya kau orang borak macam dah kenal lama.”
Abdul Azim memandang pula sahabat baiknya itu. “Kita orang ni bekas rakan sekelas BI masa tahun pertama dulu.”
“Oh. Patutlah dah lama kenal pun.”
“Macam mana abang dan Azim boleh kenal? Tak ada pula abang pernah cerita apa-apa,” sampuk Qistur Ruwaidah.
“Abang dan Azim kenal masa semester lepas. Kita orang kenal pun sebab Azim tertinggal dompet dia kat atas meja makan dan abang terjumpa dompet dia. Kan, Azim?” balas Suhaibul Umar seraya memandang sahabat baiknya seketika.
“Betul bang,” balas Abdul Azim bersahaja.
Barulah Qistur Ruwaidah memahami cara pertemuan abangnya dan Abdul Azim itu. ‘Ya Allah, percaturan-Mu sangat tersusun indah. Dunia ni kecil je rupanya.’
Setibanya kereta Suhaibul Umar di Mahallah (Kolej Kediaman) Ali, dia memarkir keretanya di parkir kosong yang disediakan. “Terima kasih abang untuk hari ni. Insya-Allah ada rezeki, kita jumpa lagi. Kalau Azim rajin nanti, Azim datang ziarah mahallah abang,” ucap Abdul Azim seraya menyalam tangan sahabat baiknya itu.
“Sama-sama. Tak ada masalah. Kalau abang rajin nanti, abang ziarah Azim, Sya dan Azhar. Sampaikan salam assalamualaikum abang kat dia orang,” balas Suhaibul Umar.
“Insya-Allah Azim akan sampaikan ucapan salam abang kat dia orang.”
Ketika Abdul Azim membuka pintu kereta, serentak Qistur Ruwaidah juga membuka pintu kereta itu untuk berpindah tempat duduk. Mereka bertentang mata seketika, namun tidak diluahkan apa-apa. Qistur Ruwaidah membiarkan lelaki itu keluar dahulu dari kereta. Perasaan segan membaluti dirinya.
Abdul Azim pula berwajah selamba. Seolah-olah perkara sedemikian merupakan perkara biasa untuknya.
‘Masihkah kau berharap kepada aku, Qist? Qist… Maafkan aku atas luahan lalu. Aku rindukan kau dan aku masih mengharapkan agar aku berada dalam hati kau. Moga kau berikan peluang untuk aku lagi. Maafkan aku, Qistur Ruwaidah. Maafkan aku,’ bisik hati Abdul Azim mengungkap maaf dalam jiwanya.
Sebuah penyesalan tidak berpenghujung bagi seorang Abdul Azim. Terimalah padahnya.
Setelah Abdul Azim melangkah keluar dari perut kereta, Qistur Ruwaidah menggantikan tempat duduk tersebut seraya menutup daun pintu kereta tersebut. Kelihatan Suhaibul Umar menurunkan tingkap kereta seraya melambai tangan ke arah sahabat baiknya manakala adiknya hanya menghadiahkan anggukan hormat kepada jejaka itu. Abdul Azim membalas lambaian sahabat baiknya itu.
Akhirnya, kereta milik Suhaibul Umar mula meninggalkan perkarangan pusat pengajian tersebut.
Abdul Azim memandang kereta sahabat baiknya itu meluncur pergi sehinggalah kereta tersebut hilang dari pandangannya. ‘Qist, masih ada harapan tak untuk aku memiliki kau atau hati kau dah tertutup terus untuk aku?’ soal hatinya sendirian.
Soalan itu sungguh menyakitkan jiwanya.
Sepanjang dalam perjalanan pulang ke rumah, Qistur Ruwaidah hanya membisukan dirinya, namun hatinya masih lagi tidak percaya apabila dia melihat insan itu tadi. Itulah kali pertama dia dapat melihat kembali Abdul Azim setelah jejaka itu menamatkan pengajiannya di Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (CFS IIUM) sejak setahun lebih yang lalu.
“Kenapa tiba-tiba adik diam ni? Biasanya adik banyak mulut sampai abang tak larat nak layan adik,” Suhaibul Umar memecahkan kesunyian.
“Dah adik tak tahu nak cakap apa,” jawab Qistur Ruwaidah, jujur.
“Tak tahu nak cakap apa ke atau seronok tengok Azim tadi?”
Qistur Ruwaidah memandang abangnya. Kelihatan abangnya tersengih. Hakikatnya, dia tidak pernah sekali pun bercerita tentang lelaki yang dia pernah jatuh hati suatu ketika dulu itu kepada abangnya.
“Adik suka Azim ya?” Suhaibul Umar menyerkap jarang.
“Suka Azim? Isy, tak adalah abang! Merepek je,” Qistur Ruwaidah menafikan. Dia tidak mahu abangnya mengesan perasaannya itu. Perasaan masa lalu.
“Yalah tu. Cara adik berhadapan dengan Azim tadi dah menerangkan semua sebenarnya.”
“Dahlah abang. Kita tukar topik. Adik tak selesa okey.”
“Okey, okey. Maafkan abang. Kita lupakan pasal tadi ya?”
Sepi. Kelihatan Qistur Ruwaidah sudah tertidur. Itu menandakan bahawa adiknya sangat mengantuk. Suhaibul Umar hanya menggelengkan kepala melihat adiknya itu. Mudah tertidur sejak dahulu.
SUDAH menjadi kebiasan bagi Abdul Azim untuk menziarahi sahabat baiknya meskipun mereka berdua berbeza mahallah (kolej kediaman). Dia tinggal di Mahallah Ali manakala sahabat baiknya tinggal di Mahallah Bilal tetapi itu tidak menghalang bagi mereka berdua untuk saling menziarahi antara satu sama lain. Begitu utuhnya tautan ukhuwah yang mereka miliki.
Dia memusing tombol pintu bilik Suhaibul Umar seraya melangkah masuk ke dalam bilik sahabat baiknya kerana dia tahu pintu bilik tersebut tidak berkunci pada waktu begini. Tambahan pula, rakan-rakan sebilik sahabat baiknya itu sentiasa ada, namun masing-masing kelihatan sedang melakukan hal sendiri di petak bilik masing-masing.
Semasa Abdul Azim hendak memasuki petak bilik Suhaibul Umar itu, langsir yang tergantung pada petak bilik sahabat baiknya terselak sedikit dan menyebabkan secara tidak sengaja, dia ternampak bekas parut yang begitu banyak pada tubuh sahabat baiknya itu apabila sahabat baiknya hendak menyarung bajunya. Dia tersentak seketika. Jangan kata...
“Abang Suhaib…” Abdul Azim mula menegur sahabat baiknya itu tanpa menilai apa-apa.
Belum sempat Suhaibul Umar hendak menyarung bajunya, perlakuannya itu terus terhenti. Habislah! Abdul Azim sudah ternampak tubuhnya itu. “A... Azim,” tegurnya, gugup.
Tanpa merasa jijik di atas apa yang telah dilihat oleh Abdul Azim, dia menghampiri sahabat baiknya itu dengan memasuki petak bilik Suhaibul Umar. “Ada apa lagi yang Azim tak tahu pasal abang?” soalnya.
Suhaibul Umar terdiam seketika seraya menyarung baju-T berlengan panjang bagi menutupi tubuhnya yang dipenuhi parut itu. Dia tidak pernah mengenakan baju yang berlengan pendek sebagai langkah berjaga-jaga sejak doktor mengatakan bahawa kulitnya tidak boleh tercedera langsung. Jika dia mempunyai baju lengan pendek, dia akan menyarung sarung lengan atau menyarung dua helai baju. Lapisan pertama bajunya berlengan panjang dan barulah dia menyarung baju berlengan pendek.
Sepanjang apa yang telah berlaku terhadap dirinya, iaitu penderaan yang telah dilakukan oleh almarhumah ibu saudaranya suatu ketika dahulu, dia tidak pernah menyarung pakaian di hadapan kawan-kawannya. Dia akan menyalin pakaiannya di dalam bilik air dan dia sendiri tidak mahu kawan-kawannya berasa jijik melihat tubuhnya itu. Selama ini, hanya adiknya sahaja pernah menyaksikan tubuhnya yang penuh parut itu.
Suhaibul Umar melabuhkan punggungnya di atas katil seraya memandang Abdul Azim yang masih kelihatan terkejut dengan apa yang dilihatnya itu. Dia memulakan bicaranya. “Azim, abang minta maaf atas apa yang Azim dah nampak. Bukan abang tak nak beritahu pasal ni. Cuma, abang takut Azim jijik tengok keadaan abang.”
Abdul Azim terus melabuhkan punggungnya di sebelah sahabat baiknya itu tanpa skeptikal. Sungguh, dia rasa amat terkesan dengan apa yang telah dilihatnya itu. “Selama ni, pernah ke Azim menilai apa-apa pasal abang?” tanyanya.
“Abang tahu Azim tak pernah menilai pasal abang. Maafkan abang. Cuma, abang rasa malu kalau orang ternampak tubuh abang ni,” nada Suhaibul Umar berubah menjadi sayu.
“Abang tak perlu minta maaf pun. Bukannya salah abang. Azim faham je abang ada sebab tersendiri. Emm abang… Kita dah kenal agak lama tapi rupanya Azim masih belum kenal abang sepenuhnya lagi dan Azim pun tak pernah nak tanya lanjut pasal abang. Apa yang Azim tahu, keluarga abang dah tak ada dan Qist merupakan adik abang. Tu je Azim tahu tapi tu pun Azim tak tanya lanjut punca kematian ahli keluarga abang masa kita kat Taman Tasik Titiwangsa dulu. Azim tak nak buat abang sedih.”
“Memang betul kita dah kenal agak lama dan abang tak ada masalah kalau Azim nak tanya apa-apa pasal abang. Abang terbuka je nak jawab soalan Azim.”
“Kalau tak keberatan, boleh tak abang cerita kenapa satu badan abang jadi macam tu dan kenapa ahli keluarga abang meninggal dunia?”
Suhaibul Umar mula membuka cerita satu-persatu atas apa yang telah dilalui oleh dirinya dan adiknya dahulu sehingga membuatkan Abdul Azim terasa sebak. Kini, barulah dia mengetahui sejarah silam Suhaibul Umar dan Qistur Ruwaidah pernah menjadi mangsa penderaan ibu saudara mereka berdua suatu ketika dahulu.
Apabila Abdul Azim mengenang kembali perbuatan lalunya menolak perasaan Qistur Ruwaidah dahulu, barulah dia memahami perasaan mahasiswi itu. Kini, barulah juga dia menyedari bahawa perempuan itu pernah mempercayai dirinya jika dia menyambut perasaan Qistur Ruwaidah suatu ketika dahulu.
Usai bercerita, Suhaibul Umar pun menyambung lagi bicaranya. “Macam tulah kisah abang dan Qist. Kita orang tinggal dengan almarhumah Mak Long dalam tempoh sekitar empat tahun tapi kesan jangka panjangnya tetap mengganggu emosi kita orang setiap kali kita orang ingat sampailah sekarang, namun kita orang percaya pada Allah Maha Pengasih. Dia menjaga dan memberikan kekuatan kat kita orang. Kalau kita orang lemah, kemungkinan besar kita orang akan ambil keputusan nak bunuh diri tapi iman kita orang cakap ‘jangan’. Ikut logik ya Azim. Sepatutnya, kita orang boleh mati sebab boleh dikatakan hampir setiap hari kita orang kena dera. Namakan je apa-apa kes penderaan yang Azim pernah dengar, kita orang dah pernah rasa. Kena pukul? Kena rotan? Kena cucuh dengan besi panas? Kena simbah dengan air panas? Kena seterika? Kena kurung? Semua kita orang dah pernah rasa tapi Allah masih panjangkan usia kita orang. Alhamdulillah. Abang fikir satu je kenapa Allah masih panjangkan usia abang? Sebab adik abang.”
“Ya Allah! Azim rasa sakit apabila abang sebut satu-persatu penderaan yang kau orang pernah kena dulu. Kuat sungguh jiwa kau orang. Azim tak tahulah macam mana kalau Azim berada kat tempat kau orang. Berat sungguh dugaan yang kau orang lalui selama ni tapi… Sepanjang Azim kenal abang, Azim tengok abang sangat tenang. Nampak macam tak ada apa-apa masalah.”
“Hanya pada Allah, abang pulangkan kembali kekuatan yang Dia berikan kat abang dan juga adik abang.”
“Alhamdulillah abang. Moga Azim pun dapat mencontohi kekuatan yang abang miliki. Erm abang… Qist pun teruk juga ke kena dera dengan Mak Long dulu?”
“Dulu, Qist kena taklah seteruk abang sebab abang banyak lindungi dia tapi ada juga hari abang gagal nak lindungi dia kalau abang terlalu lemah selepas kena dera atau dia ada buat salah. Sebagai abang, abang tak sanggup tengok adik abang kena dera macam abang. Masa mula-mula dia kena dera dulu, dia baru umur enam tahun. Dia terlalu mentah nak faham semua tu dulu dan tak sepatutnya dia melalui dan menyaksikan apa yang dah jadi tapi Allah bagi dia kefahaman atas apa yang dah jadi. Abang kira dia sangat matang berbanding kawan-kawan sebaya dia masa tu. Jiwa Qist sangat kuat sampailah sekarang.”
“Sepanjang Azim kenal dia, nampak dia sangat aktif, ceria dan mesra orangnya masa kita orang jadi rakan sekelas dulu. Tak sangka dia simpan derita yang sama macam abang.”
“Setiap orang mempunyai kisah tersendiri. Cumanya, setiap orang tu melalui ujian yang berbeza mengikut kemampuan masing-masing. Abang pasti Azim pun ada kisah tersendiri.”
“Kisah Azim biasa je. Alhamdulillah Azim berpeluang rasa kasih sayang daripada bonda baba Azim sampai sekarang. Boleh dikatakan Azim hidup dalam keadaan senang sejak dulu. Apa je Azim minta, mesti bonda baba akan tunaikan dan mereka tak pernah tolak permintaan Azim walaupun sekali. Apabila Azim tahu kisah abang, insaf Azim dibuatnya. Barulah Azim sedar betapa untungnya kehidupan Azim selama ni.”
“Alhamdulillah. Sentiasalah bersyukur di atas nikmat yang Allah bagi kat Azim. Apabila Azim sebut ‘baba’ tadi, abang pun panggil ayah abang sebagai ‘baba’ kalau baba masih hidup. Rindu pula rasanya abang nak panggil nama tu.”
“Sebenarnya, dah lama Azim nak ajak abang datang rumah Azim. Apa kata abang ikut Azim balik Johor petang Khamis nanti? Memang kebetulan Azim nak balik jumpa bonda baba. Bolehlah abang kenal bonda baba.”
“Eh, tak payahlah, Azim! Abang seganlah.”
“Jomlah abang. Bonda baba jadi gembira sangat kalau mereka tahu ada kenalan Azim yang dah tak ada mak ayah datang ziarah mereka sebab mereka akan tolong dari kewangan dan bagi kasih sayang walaupun mereka tahu tak sama dengan kasih sayang ibu bapa kandung. Azim rasa nilah peluang abang nak rasa kasih sayang daripada bonda baba Azim. Satu lagi, bonda baba takkan izinkan mana-mana kenalan Azim panggil mereka sebagai ‘mak cik’ dan ‘pak cik’ sebab buat mereka rasa jurang. Jadi, kawan-kawan Azim pun panggil ‘bonda’ dan ‘baba’.”
“Uniknya bonda baba Azim. Tiba-tiba abang rasa mereka dekat sangat kat hati abang.”
“Kalau abang dah rasa macam tu, jomlah ikut Azim balik Johor. Nanti Azim akan beritahu kehadiran abang kat bonda baba. Mesti mereka gembira.”
Akhirnya, Suhaibul Umar bersetuju untuk mengikuti Abdul Azim pulang ke Johor selepas melihatkan sahabat baiknya itu begitu bersungguh-sungguh mengajak dirinya, di samping dia merasakan keikhlasan ibu bapa sahabat baiknya itu biarpun melalui penceritaan Abdul Azim sahaja.
KERETA GRAB yang dinaiki oleh Abdul Azim dan Suhaibul Umar tiba di vila banglo tiga tingkat milik keluarga Abdul Azim itu. Suhaibul Umar terpaku melihat keluasan dan keindahan kawasan vila tersergam megah itu. Sangat luas dan cantik!
Sebagai seorang pelajar arkitek yang mempelajari seni bangunan, semestinya Suhaibul Umar berasa takjub akan reka bentuk vila tersebut. Jelas menampakkan ciri-ciri rumah tradisional Johor. Di satu sudut lain pula, Suhaibul Umar dapat melihat reka bentuknya seperti rumah Bali di Indonesia. Apa yang mengujakan dirinya, terdapat kolam renang juga!
Memang dia tahu Abdul Azim merupakan orang berada berdasarkan kisah dompet dahulu tetapi dia tidak tahu sejauh ini rupanya kesenangan yang dimiliki oleh sahabat baiknya itu. Jauh beza dengan kehidupannya!
“Selamat datang ke rumah keluarga Azim,” ucap Abdul Azim, rendah diri.
“Seganlah abang nak masuk. Besar sangatlah rumah Azim ni! Eh, silap. Bukan rumah ni tapi vila okey,” kata Suhaibul Umar.
“Laa... Jangan macam tu, abang. Marilah. Nanti kita boleh buat lawatan satu rumah Azim ni.”
Sebelum mereka berdua hendak melangkah masuk ke dalam rumah, kelihatan Abdul Azim menanggalkan cermin matanya, lalu dia mendekatkan kedua-dua anak matanya itu ke arah alat pengimbas retina. Kemudian, muncul pula kata kunci pada skrin tersebut selepas identitinya dikenalpasti. Jari-jemarinya ligat menekan skrin sentuh bagi menaip kata kunci tersebut agar membolehkan pintu utama rumah tersebut dibuka. Kelihatan pintu utama tersebut telah pun dibuka secara automatik.
Sekali lagi, Suhaibul Umar terpaku! Abdul Azim hanya tersengih melihat riak wajah sahabat baiknya itu.
Tiba-tiba Abdul Azim teringat akan dua orang sahabat akrabnya, iaitu Amirul Azhar dan Muhammad Syarafuddin yang pernah mengunjungi rumahnya buat kali pertama suatu ketika dahulu, juga sama terkejut seperti sahabat baiknya. Seribu kesyukuran dipanjatkan pada Yang Maha Esa atas kurniaan ini.
Mereka berdua melangkah masuk ke dalam rumah. Memang Suhaibul Umar sudah kehilangan kata apabila dia baru sahaja melihat beberapa sudut vila tersebut. Belum lagi dia melihat keseluruhan vila itu.
Kelihatan sepi rumah tersebut. Tiada siapa berada di kawasan ruang tamu tersebut.
“Bonda baba ada kat bilik rasanya,” Abdul Azim memecahkan kesunyian rumah tersebut.
“Sunyi je. Azim ada adik-beradik lain tak?” tegur Suhaibul Umar.
“Ada je tapi semua adik-beradik Azim dah kahwin dan ada rumah sendiri. Tinggal Azim seorang je tak kahwin lagi. Rumah ni jadi meriah apabila cuti sekolah atau hari perayaan.”
“Oh. Azim ada berapa orang adik-beradik?”
“Lapan orang. Azim anak bongsu.”
“Subhanallah, ramainya! Sebenarnya, abang ingatkan Azim anak tunggal tahu tapi apabila Azim sebut ‘adik-beradik’, baru abang tahu Azim bukan anak tunggal. Sekali abang dapat tahu pula adik-beradik Azim ada lapan orang, lagilah abang rasa berganda ‘wow’.”
Abdul Azim tersengih apabila mendengar kata-kata sahabat baiknya itu. “Alhamdulillah. Jom pergi bilik Azim. Nanti kita jumpa bonda baba.”
Tiba-tiba kelihatan ibu bapa Abdul Azim muncul di ruang tamu. Segera Abdul Azim menyalam kedua-dua tangan ibu bapanya itu. “Eh, Azim! Bila sampai?” soal Encik Uthman.
“Alhamdulillah. Baru je sampai baba. Ha, baba, bonda. Nilah Abang Suhaib, sahabat baik Azim yang Azim cerita dulu,” Abdul Azim memperkenalkan sahabat baiknya itu.
Suhaibul Umar mengangguk hormat seraya menyalam tangan Encik Uthman. Tidak dapat ditafsirkan kalbunya apabila dia menyalam tangan orang tua itu.
“Bonda baba sihat ke?” Suhaibul Umar berbasa-basi.
“Alhamdulillah kami sihat. Maaflah. Tadi, kami tengah memasak kat dapur. Itu tak dengar Azim dan Suhaib dah sampai,” terang Puan Tengku Aulia.
“Bonda baba masak apa?” tanya Abdul Azim.
“Apa lagi, lauk kegemaran Azimlah. Sambal petai udang, ikan goreng kembung dan sayur campur.”
“Wah, alhamdulillah! Lamanya Azim tak rasa masakan bonda baba. Kalau macam tu, kami naik atas dulu. Nak mandi sekejap. Lepas tu, kami makan sekali dengan bonda baba.”
“Okey Azim. Ha Suhaib, buatlah macam rumah sendiri tahu. Kami gembira dengan kehadiran Suhaib kat teratak kami ni,” kata Encik Uthman.
Suhaibul Umar menguntum senyuman. “Baik baba bonda. Terima kasih juga sebab sudi terima kunjungan Suhaib.”
“Sama-sama Suhaib,” ucap pasangan itu.
Abdul Azim mula membawa sahabat baiknya di bahagian lif. Tangannya mula menekan butang lif tersebut. Sekali lagi, Suhaibul Umar terlopong melihatnya. Lif dalam rumah! Tempat penginapan apa yang dia sedang diami kini?
“Azim, abang rasa abang nak balik Kuala Lumpurlah sekarang,” ucap Suhaibul Umar.
“Eh, abang jangan macam-macam! Abang dah sampai sini pun,” balas Abdul Azim.
“Bukan apa. Tiba-tiba abang rasa abang tak layak nak datang rumah Azim ni. Apatah lagi, nak kenal Azim.”
TING! Kelihatan pintu lif dibuka. Abdul Azim mula menarik tangan Suhaibul Umar untuk berada di dalam lif. Jika dia tidak berbuat demikian, alamatnya memang sahabat baiknya itu tidak akan masuk sampai bila-bila.
“Eh, Azim!” Suhaibul Umar terkesima dengan tindakan sahabat baiknya itu.
Abdul Azim mula menekan butang tingkat dua. Kelihatan pintu lif tersebut ditutup. “Boleh tak abang jangan rasa rendah diri sangat dengan Azim? Bukannya Azim kaya pun. Bonda baba yang kaya. Rezeki Azim je hidup macam ni,” Abdul Azim mula bersuara.
Suhaibul Umar terdiam. Berdasarkan nada sahabat baiknya itu, tahulah dia bahawa Abdul Azim sedang terasa dan tidak selesa.
Akhirnya, lif tersebut tiba di tingkat dua. Terdapat lima buah bilik pada tingkat tersebut. Tingkat tiga pula terdapat empat buah bilik. Setiap adik-beradik Abdul Azim mempunyai bilik mereka sendiri.
Kelihatan Abdul Azim meletakkan ibu jarinya pada alat pengimbas ibu jari di bahagian atas tombol pintu itu. Setelah identitinya dikenalpasti, kedengaran selak pintu itu terbuka. Dia memusingkan tombol pintu itu seraya mengucapkan ‘Dengan nama Allah’.
Suhaibul Umar terpana melihat bilik sahabat baiknya itu. Sungguh luas. Tanggapan Suhaibul Umar, saiz bilik Abdul Azim itu sahaja sudah menyamai saiz ruang tamu di rumahnya. Di satu sudut, dia dapat melihat dinding bilik tersebut dicat dengan rona merah hati. Pada sudut-sudut lain pula, dicat dengan rona krim. Dia tahu sangat warna kegemaran Abdul Azim itu. Tidak sah jika tiada warna merah atau merah hati. Dia dapat melihat juga suis lampu dan penyaman udara dihidupkan dengan sendirinya.
“Abang rehatlah dulu. Azim nak mandi. Nanti Azim sediakan apa-apa yang patut untuk abang,” kata Abdul Azim tanpa memandang sahabat baiknya itu. Dia masih terasa dengan kata-kata sahabat baiknya itu.
“Abang minta maaf, Azim. Abang tak sepatutnya cakap macam tu tadi. Abang tahu Azim tak selesa dan terasa,” ucap Suhaibul Umar, perlahan.
Barulah Abdul Azim mula memandang wajah sahabat baiknya itu. “Azim pun nak minta maaf. Azim pun tak patut buat perangai macam tu. Sepatutnya, Azim kena faham juga situasi abang. Abang tak pernah tengok rumah macam ni. Emm… Abang baringlah dulu. Buat je katil tu macam katil kat rumah abang.”
Pada mulanya Suhaibul Umar teragak-agak, namun akhirnya dia melabuhkan punggungnya di atas katil bersaiz king itu. “Sedap betul tilam ni. Mesti Azim susah nak bangun tidur ni,” selorohnya.
Abdul Azim meledakkan tawanya. “Tak adalah. Alhamdulillah. Senang je Azim nak bangun. Kalau Azim tak bangun nanti, bonda mesti bising.”
Kelihatan Abdul Azim mula mengeluarkan dua helai tuala dari almari itu. Almari biliknya juga disediakan kata kunci bagi membukanya. “Ni tualanya. Kalau abang terlupa bawa apa-apa, beritahu je Azim okey. Azim mandi dulu.”
Dia mula menghilangkan diri ke bilik air. Suhaibul Umar mula berbaring sambil merenung siling. ‘Untungnya jadi Azim,’ bisik hatinya.
USAI menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan menjamah hidangan makan malam, Encik Uthman, Puan Tengku Aulia, Abdul Azim dan Suhaibul Umar berkumpul di ruang tamu. Barulah Suhaibul Umar mengetahui bahawa keluarga Abdul Azim sangat mementingkan solat jemaah. Jika tidak dapat dilaksanakan di masjid, mereka akan menunaikan solat jemaah di rumah.
“Okey tak masakan bonda tadi, Suhaib?” tanya Puan Tengku Aulia.
“Alhamdulillah. Sedap sangat. Terima kasih atas hidangannya, bonda,” ucap Suhaibul Umar.
“Sama-sama. Lega bonda dengar.”
“Azim dah bawa Suhaib jalan-jalan kat rumah kita ni?” tanya Encik Uthman.
“Belum lagi baba. Lagipun, kan hari dah malam. Bukannya nampak semua pun kalau Azim nak tunjuk,” balas Abdul Azim.
“Betul juga. Ha, Suhaib. Bolehlah berenang dengan Azim lepas solat subuh esok. Biasanya Azim akan berenang waktu tu sampai pukul 8.00 pagi,” terang Encik Uthman kepada Suhaibul Umar.
“Insya-Allah,” balas Suhaibul Umar bersahaja. Dia mula rasa tenang bersama ibu bapa sahabat baiknya itu.
JAM 3.00 PAGI.
Kedengaran penggera jam dari telefon pintar Abdul Azim berbunyi menandakan bahawa dia perlu menunaikan qiamullail. Dia segera mematikan bunyi tersebut kerana dia bimbang sahabat baiknya itu terbangun pula. Kelihatan Suhaibul Umar tidur dengan nyenyaknya sehingga dia tidak mendengar bunyi tersebut. Mungkin dia terlalu penat sejak permusafiran mereka berdua dari Kuala Lumpur ke Segamat, Johor pada hari semalam.
“Allah… Sejuk sangat ni. Macam manalah aku nak pergi ambil wuduk ni? Haih… Tak tahanlah aku!” bicara Abdul Azim sendirian.
Dia berkata sesuatu. “30 darjah celsius.”
Melalui bicara kod bagi penyaman udara itu sahaja, serta-merta suhu penyaman udara biliknya itu menjadi kurang sejuk. Abdul Azim tersenyum sendirian. Jika Suhaibul Umar ternampak dia berbuat demikian terhadap penyaman udara biliknya itu, gamaknya sahabat baiknya itu terus pengsan.
Abdul Azim bingkas bangkit dari perbaringannya itu untuk berjumpa Yang Maha Esa. Usai dia membersihkan diri dan mengambil wuduk, dia mula menunaikan solat-solat sunat yang dianjurkan dalam Islam, iaitu solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat istikharah, solat sunat tasbih dan solat sunat witir.
Dia sudah terbiasa melakukan amalan-amalan tersebut sejak dia memijakkan kaki ke Sekolah Menengah Agama Al-Khairiah, Segamat, Johor dahulu sehinggalah kini, dia melanjutkan pengajiannya di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia cawangan Gombak.
Dia tidak menafikan sebagai seorang pelajar Kulliyyah Seni Bina dan Reka Bentuk Alam Sekitar (KAED) yang memerlukan dirinya untuk berjaga malam bagi menyiapkan tugasan, projek dan replika model, sangat mencabar buat dirinya untuk bergelut di antara tugas hakiki dengan amalan ukhrawi pada waktu-waktu begini, namun dia cuba juga seimbangkan di antara kedua-duanya.
Usai memberikan salam terakhir bagi solat sunat witir, dia mula berzikir dalam hati. Dia melirik seketika pada jam dinding. Jam sudah menunjukkan pukul 4.45 pagi. Tiba-tiba jam penggera dari telefon pintar Suhaibul Umar pula berdering. Abdul Azim menoleh ke belakang seketika. Kelihatan sahabat baiknya itu sudah bangun.
“Awalnya Azim bangun. Azim bangun pukul berapa tadi?” tegur Suhaibul Umar.
“Sejak pukul 3.00 pagi lagi. Memang rutin Azim bangun waktu tu,” terang Abdul Azim.
“Subhanallah! Untungnya bakal isteri Azim.”
Abdul Azim hanya menghadiahkan senyuman. “Allah... Abang ni. Ke situ pula. Moga Allah jauhkan Azim daripada salah niat dan sifat riyak. Abang nak bangun qiamullail juga ke?”
“Haah. Biasanya abang bangun waktu ni. Tak sangka Azim bangun lebih awal daripada abang.”
“Setiap orang ada waktunya sendiri. Ha, abang bangkitlah sekarang. Nanti abang terlepas pula waktu berharga ni. Oh ya, abang. Azim nak pergi turun bawah. Nak jumpa bonda baba kat ruang tamu. Biasanya bonda baba dah bangun waktu ni.”
“Okey Azim.”
Melihatkan perbuatan Abdul Azim bangkit dari tempat duduknya itu, Suhaibul Umar bingkas bangun dari perbaringannya. “Azim gerak dulu ya abang. Kalau Azim tak naik bilik sampai nak dekat-dekat azan subuh tu, abang turun je nanti. Kita solat jemaah kat masjid,” kata Abdul Azim.
“Err... Azim. Sekejap. Biasanya, memang Azim solat kat masjid ke?” soal Suhaibul Umar.
“Haah. Alhamdulillah. Dah menjadi satu kewajipan untuk Azim sebab memang baba latih adik-beradik lelaki Azim untuk solat jemaah kat masjid sejak kita orang kecil. Cuma, semalam Azim dan baba tak solat maghrib dan isyak kat masjid sebab Azim tak larat. Yalah, kan Azim dan abang bermusafir semalam. Baba pula demam. Sebenarnya, Azim jadi tak sedap hati kalau tak solat jemaah kat masjid.”
Alangkah takjubnya Suhaibul Umar mendengar akan jawapan sahabat baiknya itu. Nampaknya rutin Abdul Azim itu sangat luar biasa untuknya, namun sahabat baiknya itu sangat merendah diri. Sudahlah dilahirkan dalam golongan kaya-raya, bahkan kaya jiwa pula. Untung sangatlah siapa bakal menjadi isteri Abdul Azim itu nanti.
Kelihatan Abdul Azim mula meninggalkan bilik. Giliran Suhaibul Umar pula bertemu dengan Maha Pencipta.
TING! Kelihatan pintu lif terbuka di tingkat dua. Abdul Azim melangkah masuk ke dalam lif tersebut. Sesampai sahaja dia di tingkat bawah, kelihatan ibu bapanya sedang mengaji Al-Quran bersama-sama di ruang tamu. Sangat romantik! Itulah rutin harian ibu bapanya sejak mereka mula berkahwin sehingga kini. Dia memasang tekad. Dia juga akan melakukan perkara yang sama dengan bakal isterinya nanti jika diizinkan Allah.
“Bonda baba, maaf Azim ganggu bonda baba waktu-waktu ni,” ucap Abdul Azim.
Kedengaran ibu bapanya menamatkan bacaan mereka terlebih dahulu seraya mengucapkan ‘Benarlah kata-kata Allah Yang Maha Agung’. Lantas, Encik Uthman dan Puan Tengku Aulia memberi perhatian kepada anak bongsu mereka itu. “Mari sini, Azim,” panggil Encik Uthman.
Abdul Azim mula menghampiri kedua-dua ibu bapanya itu, lalu dilabuhkan punggungnya di atas sofa menghadap orang tua yang dicintainya itu.
“Azim jarang sangat nak bincang sesuatu dengan kami waktu-waktu macam ni. Biasanya Azim tengah qiamullail waktu ni,” tegur Puan Tengku Aulia.
“Alhamdulillah. Azim dah qiamullail tadi. Emm… Bonda baba, Azim ada perkara nak cerita,” balas Abdul Azim.
“Okey, Azim nak cerita pasal apa?” tanya Encik Uthman.
“Azim tak tahu nak mulakan macam mana,” terang Abdul Azim.
“Azim dah jumpa calon isteri ke?” Puan Tengku Aulia menyerkap jarang.
Abdul Azim tersentak seketika. “Emm… Bukanlah calon isteri lagi buat masa ni. Azim tak terfikir lagi nak kahwin. Memang Azim ada suka seseorang. Cuma, Azim selalu keliru dengan perasaan Azim. Sekejap Azim rasa Azim suka dia, sekejap Azim rasa tak,” balasnya.
“Apa yang membuatkan Azim rasa macam tu?” tanya Encik Uthman.
“Dia pernah luahkan perasaan dia kat Azim tapi Azim tolak perasaan dia. Nak jadi ceritanya, Azim pernah kecewa apabila Azim bertindak macam tu. Waktu tu, Azim suka dia sebenarnya tapi sekarang, entahlah. Azim jadi keliru semula. Azim jadi tak yakin.”
“Siapa perempuan tu?” tanya Puan Tengku Aulia.
“Emm… Adik Abang Suhaib. Nama dia Qist. Qistur Ruwaidah,” jawab Abdul Azim. Dia mula menundukkan wajahnya. Pipinya terasa panas apabila dia menyebut nama mahasiswi itu.
Kelihatan ibu bapanya agak terkejut dengan pilihan hati anak mereka itu. “Adik Suhaib? Jadi, Azim rapat dengan Suhaib sampai jadi kawan baik semata-mata nak dekat dengan Qist atau macam mana?” tanya Encik Uthman.
“Eh, baba jangan salah faham! Masa Azim mula-mula kenal Abang Suhaib dulu, Azim tak tahu pun dia abang Qist. Kebetulan je. Azim baru tahu pun masa Azim teman Abang Suhaib ambil Qist kat CFS. Ni pun Abang Suhaib tak tahu Azim pernah suka adik dia,” terang Abdul Azim.
“Kenapa Azim perlu rasa ragu-ragu lagi? Terang-terang Azim suka Qist,” Puan Tengku Aulia meluahkan pendapatnya berkenaan soal hati anaknya itu.
“Emm… Entahlah bonda. Azim pun tak ada jawapan untuk tu. Bonda baba, andai katalah satu hari nanti Azim terbuka hati nak lamar Qist, bonda baba okey tak?”
“Kalau Azim tanya baba, baba okey je dengan mana-mana calon pilihan Azim, sekali pun Azim tak pilih Qist. Azim lebih tahu kemahuan Azim tapi baba tengok Suhaib tu baik je budaknya. Insya-Allah, baba percaya Qist pun baik. Elok juga Azim cari calon isteri macam Qist tu,” jawab Encik Uthman.
“Kenapa baba cakap macam tu?” tanya Abdul Azim.
“Pada baba, rasanya bonda juga akan bersetuju dengan alasan baba ni. Kami okey sangatlah kalau Azim jumpa calon isteri yang pernah berstatus anak yatim atau anak yatim piatu macam Qist supaya Azim dapat belajar erti rendah diri. Satu lagi, sebagai peringatan buat Azim bahawa kematian tu pasti. Azim kena istikharah untuk ketetapan hati Azim. Soal hati, perasaan dan cinta ni, pulangkan semula pada Allah. Dia Maha Mengetahui,” jawab Encik Uthman sebagai seorang ayah yang sudah lama merasa asam garam dalam bercinta dengan Puan Tengku Aulia.
“Ha, betul. Bonda pun setuju sangatlah dengan jawapan baba tu. Walaupun bonda tak tengok lagi rupa Qist tu tapi insya-Allah bonda akan suka Qist,” sampuk Puan Tengku Aulia.
Abdul Azim mengukir senyuman. Nampaknya, ibu bapanya merestui pilihannya jika dia memilih Qistur Ruwaidah. Cuma, pada sisinya, dia masih belum serius untuk memikirkan ke arah itu. Namun begitu, dia sentiasa menjadikan ibu bapanya sebagai model peranan dalam apa jua yang dilakukan olehnya.
“Terima kasih bonda baba. Bonda baba jangan pula buka cerita ni kat Abang Suhaib. Biar Azim sendiri beritahu nanti,” pesan Abdul Azim.
“Sama-sama Azim. Insya-Allah kami akan zip mulut kami,” kata Puan Tengku Aulia seraya menunjukkan isyarat zip mulut kepada anaknya itu. Encik Uthman turut mengikuti perlakuan isterinya itu.
Abdul Azim ketawa kecil melihat gelagat ibu bapanya itu. Tujuan dia berkongsi rasa hatinya dengan ibu bapanya itu hanyalah sekadar untuk menenangkan hatinya dan mendengar respons mereka berdua. Biarlah dia fokus dengan pengajiannya terlebih dahulu. Itulah azamnya sejak dahulu, iaitu dia mahu membawa pulang kejayaan kepada ibu bapanya.
Seandainya sudah tiba masanya nanti, dia akan memikirkan juga soal jodoh itu. Sama ada dalam tempoh pengajian ini atau selepas dia bergraduasi nanti, dia juga tidak tahu. Hanya Allah Maha Mengetahui perjalanan cinta dan langkahnya.
“Ha Azim, dah nak masuk waktu Subuh. Pergilah kejut Suhaib. Ajak dia solat kat masjid sekali dengan kita,” kata Encik Uthman.
“Dia dah bangun tadi. Tengah qiamullail lagi tu. Rasanya kalau Azim tak ajak pun, memang Abang Suhaib jenis solat kat masjid,” balas Abdul Azim.
“Alhamdulillah. Bagus Azim jumpa orang macam Suhaib. Pastikan Azim selalu temankan Suhaib tu. Beri kata-kata sokongan kat dia.”
“Insya-Allah baba. Memang tulah apa yang Azim buat sepanjang Azim kenal Abang Suhaib.”
Tiba-tiba Suhaibul Umar muncul di ruang tamu seraya menghadiahkan senyuman. “Baba, bonda, Azim,” tegurnya.
“Suhaib dah sedia nak pergi masjid ke?” tanya Encik Uthman.
“Haah dah sedia. Jom semua.”
Lalu, mereka berempat mula bergerak ke masjid yang berhampiran dengan rumah keluarga Abdul Azim itu, iaitu Masjid As-Solihin. Kedengaran azan subuh telah pun berkumandang setibanya mereka di masjid itu.
Menariknya berkenaan Masjid As-Solihin itu, masjid itu direka oleh Encik Uthman sendiri sebagai seorang arkitek. Dia amat meminati hasil seni bina dari Maghribi, Mekah dan Madinah sewaktu dia menunaikan haji dan umrah pada zaman mudanya dahulu. Selain itu, dia berpeluang untuk menziarahi Maghribi sebagai salah satu pakej pelancongan yang dipilih olehnya itu.
Lalu, Encik Uthman mengambil inspirasi dari ketiga-tiga bangunan tersebut dan dipersembahkan dalam bentuk pelan. Akhirnya, wujudlah Masjid As-Solihin tersergam megah sejak 15 tahun lepas itu.
ABDUL AZIM membawa Suhaibul Umar berjalan-jalan bagi menyaksikan setiap sudut di vila banglo keluarganya itu. Taman bunga, kolam renang, kolam ikan dan beberapa buah tempat lagi sangat mengujakan buat Suhaibul Umar. Ternyata sahabat baiknya itu sangat suka dan takjub akan setiap seni bina vila itu.
Di kolam ikan…
“Kalaulah abang berpeluang untuk reka rumah idaman abang dan menjadi realiti, alangkah seronoknya,” luah Suhaibul Umar.
Abdul Azim terdiam. Dalam hatinya, dia seharusnya bersyukur kerana dia dapat merasai semua ini. Bukan semua orang bertuah untuk hidup dalam keadaan mewah begini. Cuma, bagi Abdul Azim, dia tidak suka untuk menggunakan perkataan ‘mewah’ bagi menggambarkan kehidupannya itu kerana dia takut timbulnya rasa riyak.
“Abang nak tahu sesuatu tak pasal kolam ikan ni?” Abdul Azim mula menukar topik. Dia tidak mahu Suhaibul Umar berasa rendah diri apabila melihat kehidupan mewahnya itu.
“Eh, mestilah abang nak tahu! Mesti ada kisah tersendiri, kan,” balas Suhaibul Umar.
“Betul. Kolam ikan ni direka oleh Azim sendiri masa semester akhir Azim kat CFS dulu. Kolam ni baru je siap dalam beberapa bulan lepas. Waktu tu, pensyarah suruh hasilkan replika kolam ikan. Apabila Azim tunjuk hasil replika kolam ikan kat baba, baba suka sangat. Terus baba upah orang untuk bina kolam ikan ni. Satu lagi, kalau Azim marah, sedih dan kecewa, kat sinilah tempat Azim akan lepaskan segala perasaan Azim. Azim rasa tenang sangat. Lagi-lagi, tengok ikan-ikan tu berenang,” cerita Abdul Azim.
“Rupa-rupanya, hati Azim lembut juga ya sebab cara Azim cerita penuh kasih sayang.”
“Bukan hati lembut. Lebih pada hati sensitif Azim rasa.”
“Samalah macam adik abang. Dia pun sangat sensitif orangnya. Manja pun ya juga. Lagipun, dia jelah keluarga abang yang abang nak layan pun. Abang pun bukannya ada sesiapa lagi kecuali dia.”
Abdul Azim tersentak apabila abangnya mula membuka bicara tentang perempuan itu, namun dia cuba memberi reaksi normal. Tiba-tiba dia teringat sesuatu mengenai whatsapp yang pernah dibalas olehnya kepada mahasiswi itu.
See you in Gombak. Selamat jalan untuk perjalanan balik…
Waktu itu, barulah dia menyedari bahawa dia telah memberi harapan kepada Qistur Ruwaidah meskipun sebenarnya, dia tidak berniat pun. Namun begitu, sejujurnya, memang dia pernah mengharapkan agar dia dipertemukan kembali dengan mahasisiwi itu pada satu hari nanti dan dia juga mengharapkan agar Qistur Ruwaidah faham bahawa dia menunggu perempuan itu dalam diam meskipun dirinya keliru akan perasaannya terhadap perempuan itu sehingga kini.
Kini, impiannya itu telah pun tercapai.
Lalu, apakah langkah seterusnya untuk dirinya setelah dia rapat dengan abang Qistur Ruwaidah itu? Ikutkan, peluangnya sangat cerah untuk dia meluahkan hasrat hatinya itu kepada Suhaibul Umar, namun dia tidak bersedia lagi.
Azim oh Azim! Lalu, apakah kau mahukan sebenarnya?
“Abang dah mula rindu adik abang ke?” tanya Abdul Azim.
“Mestilah abang rindu. Abang tak pernah tinggalkan dia jauh-jauh macam ni. Paling jauh pun, abang tinggalkan dia sebab abang sambung belajar kat CFS. Lepas tu, dia pula tinggalkan abang sebab sambung belajar kat CFS. Entahlah dia okey ke tak kat rumah tu,” balas Suhaibul Umar.
“Insya-Allah. Qist okey je tu, abang. Abang jangan risau.”
Suhaibul Umar memandang sahabat baiknya itu. Dia terlupa pula. Qistur Ruwaidah juga sebaya dengan Abdul Azim. Tahun ini, mereka berdua berumur 20 tahun.
Sememangnya Qistur Ruwaidah sudah pandai menjaga dan membawa diri, namun dia tetap risau akan adiknya ditinggalkan keseorangan. Berkali-kali dia memujuk hatinya agar adiknya berada dalam keadaan baik.
Kelihatan Abdul Azim begitu seronok memberikan makanan ikan kepada ikan-ikan tersebut seraya berkata sesuatu. “Semoga kau orang membesar dengan jayanya.”
Suhaibul Umar tersengih melihat telatah Abdul Azim itu. Dia boleh nampak betapa Abdul Azim sangat berjiwa penyayang di sebalik wajah seriusnya itu.
Apakah langkah seterusnya buat Abdul Azim untuk Qistur Ruwaidah atau dia masih dengan egoisnya itu? Nantikan.
Share this novel



