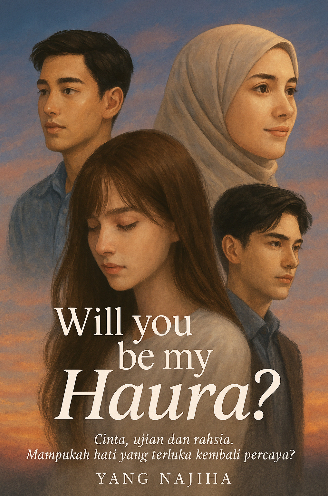
Bab 26
 Series
Series
 298
298
Suasana rumah itu sunyi malam itu. Hanya kedengaran bunyi kipas berpusing perlahan dan siaran TV yang bergema sayup-sayup dari ruang tamu.
Puan Hajar duduk di kerusi sambil melipat kain baju. Di sebelahnya, Fia bersandar malas, mata menonton TV tetapi tangan sibuk bermain dengan telefon.
Dari bilik tidur Atul dan Fia, bunyi bersepah barang kedengaran. Disusuli jeritan kuat.
"MAKKK!!"
Jerit Atul, kuat dan panjang.
Puan Hajar dan Fia yang berada di ruang tamu terperanjat. Lipatan kain baju hampir terjatuh dari riba Puan Hajar.
"Astaghfirullahalazim! Apa pulak budak ni?!"
Fia bangun dulu. "Takpe, biar Fia tengok."
Puan Hajar ikut di belakang, wajah kerut marah. "Buat kerja pun nak jerit-jerit macam apa dah."
Mereka berlari ke tingkat atas. Sampai saja di bilik Atul, terlihat Atul berdiri atas kerusi, menunjuk ke satu sudut.
"Makkkkkk! Tuuuuuuu!"
Puan Hajar berkerut dahi, "Apa benda ko ni?!"
"Mak! Lipasss! Besarrrrr!" Atul jerit sambil hampir menangis.
Fia tahan ketawa. "Ya Allah, Atul! Seekor lipas je kot!"
Puan Hajar mendekat, mata melilau mencari. Betul, ada seekor lipas berlari-lari atas lantai.
"Budak ni... Ya Allah, ya Tuhan ku, Atul! Lipas je pun nak jerit macam kena culik! Berdesup darah mak dibuatnya! Buat malu jiran sebelah rumah dengar kau jerit macam rumah kita kena rompak!"
Fia tergelak kecil. Dia bersilang tangan, memandang Atul dari atas ke bawah.
"Patutlah badan je besar. Hati kecik. Lipas pun nak takut."
Atul mendengus, muka merah. "Eh, aku memang takut lipas, tak boleh buat apa! Dah geli, geli lah!"
Puan Hajar mengeluh panjang, tangan letak di pinggang.
"Fia! Pergi tangkap lipas tu. Buang luar."
Fia cepat geleng kepala, langkah ke belakang. "Eh, tak nak Fia! Fia pun geli, mak. Suruhlah Atul. Dia yang jumpa dulu."
Fia sambung lagi dengan nada menyindir sambil tenung Atul, "Aku ni, pegang pinggan mangkuk boleh la, pegang lipas? Eee... kirim salam!"
Puan Hajar dah separuh hilang sabar. "Ya Allah! Dua-dua sama je! Sikit-sikit takut. Lipas pun nak drama. Dah, tepi, tepi!"
Dia sendiri ambil surat khabar lama, bergegas ke sudut, ketuk lipas itu sekali. Kemudian, dia bawa keluar ke luar rumah.
Sebaik saja masuk, Puan Hajar menyambung bebelannya.
"Anak-anak apa semua ni? Semua nak geli! Kalau kakak korang tu, dia je lah boleh diharap! Lipas ke, cicak ke, semut ke, semua dia boleh sapu sekali jalan! Korang ni... apa nak jadi, ha? Asal nampak benda bergerak sikit, dah melompat macam tengok hantu!"
Dia merungut sambil mengibas kain lap di tangan.
Tapi saat lidahnya menyebut nama Ara, wajah Puan Hajar berubah. Dia terhenti seketika.
"Ha... kakak korang mana?" Dia pandang Fia dan Atul bergilir-gilir.
Fia tunduk. Atul cepat-cepat menjawab, "Akak pergi hospital, mak. Teman abang Hafiyy. Tengok Tok."
Mendengar itu, wajah Puan Hajar bertambah sayu.
"Ya Allah... kesian Tok." Dia mengeluh perlahan, suara mula bergetar sedikit. "Dah lah sakit, anak-anak jauh... si Hafiyy tu lah satu-satunya yang ada dekat situ."
Fia perasan riak maknya yang mula resah. Dia cuba memujuk, "InsyaAllah Tok tu kuat, mak. Tengok la umur macam tu pun tiap hari gigih sapu halaman rumah, bersihkan rumah sendiri. Kita doakan Tok cepat sihat."
Tapi Puan Hajar tetap berwajah gusar. Dia pandang jam dinding. Hampir pukul 10 malam.
"Ee kakak korang ni tak balik-balik lagi, esok dah lah sekolah." katanya separuh berbisik.
Suasana jadi sunyi.
Beberapa minit berlalu.
Tiba-tiba, bunyi pagar dibuka.
Fia dan Atul serentak toleh ke luar tingkap.
"Eh, akak dah balik!" jerit Atul, gembira.
Tak lama kemudian, kedengaran langkah kaki menaiki tangga rumah. Pintu rumah dibuka perlahan.
Ara muncul di ruang tamu, berwajah letih. Dia sempat senyum kecil, baru hendak bersuara.
Tapi Puan Hajar sudah bangkit dari kerusi tanpa berkata apa-apa. Dengan muka masam, dia terus berlalu ke biliknya.
Ara terhenti. Pandangannya mengekori langkah ibu mereka.
Fia dan Atul juga hanya mampu diam, tidak tahu mahu kata apa.
Ara tarik nafas perlahan, pandang adik-adiknya sekejap, kemudian melangkah perlahan ke biliknya tanpa sepatah kata.
***
Matahari tengah hari membakar kulit, namun redup angin dari surau sedikit sebanyak menyejukkan mereka yang baru selesai solat.
Ara dan Wahyun dalam perjalanan ke pagar sekolah seperti biasa — tempat pelajar-pelajar menanti ibu bapa datang ambil.
"Ara, macam mana Tok Hafiyy sekarang?" Wahyun mula bersuara, memecah sunyi.
Ara menoleh sekejap, kemudian pandang semula ke hadapan.
"Masih kat ICU. Hafiyy pun dah dua hari tak datang sekolah."
Wahyun angguk perlahan.
"Patutlah saya nampak awak tak berapa ceria." gumam Wahyun.
Ara senyum nipis. "Saya risau. Kesian Hafiyy. Hafiyy tu memang rapat dengan Tok dia. Dari kecik Tok yang jaga dia."
"Hmm... Moga cepat sembuhlah Tok dia."
Ara hanya membalas dengan senyuman kecil.
Suasana di antara mereka diam sejenak. Sampai sahaja di pagar sekolah, Ara mengambil basikalnya.
"Okey, saya balik dulu. Assalamualaikum."
"Waalaikumussalam," balas Wahyun, mengangkat tangan.
Ara mengayuh basikal meninggalkan kawasan itu, membelah panas siang.
Wahyun memandang belakang Ara seketika. Baru dia teringat sesuatu.
"Aduh... buku!"
Dia tepuk dahinya perlahan. Buku yang dipinjamkan Ara untuk dibaca — masih ada di dalam begnya. Tadi dia rancang nak pulangkan, tapi sekarang Ara dah jauh.
Dia keluarkan buku itu, membelek-belek di tangannya. Penyesalan singgah di wajahnya.
"Dah terlambat nak panggil."
Wahyun hanya menggenggam buku itu, memutuskan untuk pulangkan lain kali.
Tidak jauh dari situ, sepasang mata memerhati dan mendengar.
Ayu, bersandar dengan tangan silang di dada, memperhatikan sejak tadi.
Bibirnya mencebik.
"Huh, bukan main sekarang kau Ara. Ada kawan baru... ada 'bodyguard' baru..." Ayu berkata sendiri, suara penuh sindiran dan perli.
Dia gelak kecil, sinis.
"Dah pandai menggedik dengan budak pandai, kelas depan pulak tu. Macam lah bagus sangat! Lupa dah siapa yang selama ni kawan dia masa semua orang tak layan dia."
Matanya mengecil, penuh rasa tidak puas hati. Tangannya menggenggam kuat tali beg.
Ayu mendengus.
"Takpe lah... Tunggu je, Ara. Kau pun akan rasa macam mana sakitnya nanti."
Dia capai telefon dari poket baju.
Jari-jarinya laju menaip mesej.
Ayu: Jangan lupa plan hujung minggu ni. Aku nak semua perfect.
Tak sampai seminit, mesej balasan masuk.
Shazwan: Ok. Settle.
Ayu tersenyum puas.
Dia simpan telefon ke dalam poket semula. Matanya memandang ke arah jalan di mana Ara sudah pun hilang dari pandangan.
Dalam hati, Ayu sudah mula menghitung hari. Dia tak sabar nak tengok Ara jatuh.
***
Hari Jumaat itu, sebelum loceng pulang bergema, kelas sudah mulai riuh dengan suara pelajar mengemas beg, bersiap untuk pulang.
Di tengah-tengah kekalutan itu, Wahyun kelihatan sedikit gelisah. Tangannya pantas menggeledah ruang dalam beg sandangnya, membelek satu persatu buku teks dan nota, namun wajahnya makin berkerut.
"Eh... mana pergi buku tu?" gumamnya perlahan.
Imran yang sedang memasukkan fail ke dalam beg, sempat menjeling ke arah rakannya itu.
"Kau cari apa, Yun?" tegurnya, kening sedikit terangkat.
Wahyun menghela nafas, masih tidak berhenti mencari.
"Buku." jawabnya sambil terus menyelak ruang kecil di tepi beg.
"Buku apa?" tanya Imran, mendekat sambil menyangkutkan beg ke bahu.
"Buku saiz sederhana. Warna biru lembut. Yang aku baca hari tu... aku letak dalam beg ni." Nada Wahyun kedengaran semakin cemas.
Imran berpaling, meninjau sekitar meja dan kerusi, seolah-olah berharap buku itu terselit entah di mana.
"Tak nampak pun, bro. Mungkin kau salah letak kot?" tebaknya.
Wahyun menggeleng perlahan, jelas ragu.
"Tak mungkin. Aku tak keluarkan buku tu langsung. Aku memang simpan dalam beg."
Imran memicit dagunya, berfikir.
"Kalau tak dalam beg, mungkin tertinggal dekat rumah kot? Kau kan selalu buat jadual belajar tiap malam," kata Imran, cuba menenangkan.
Wahyun terdiam sejenak.
Dia cuba mengingat — adakah mungkin dia tersilap letak semasa menyusun meja belajar malam-malam itu?
"Mungkin juga..." Dia akhirnya mengalah, walaupun wajahnya masih berkerut.
"Sabar lah. Balik nanti kau cari elok-elok," Imran menepuk bahu Wahyun sebelum berlalu keluar dari kelas.
Wahyun masih berdiri di situ, termenung.
Ada sesuatu tentang kehilangan buku itu yang membuatkan hatinya tidak tenang.
Dia menggenggam erat begnya.
'Balik nanti aku mesti cari,' tekadnya dalam hati.
***
Hari itu Sabtu, matahari baru sahaja condong di ufuk, mengirimkan cahaya suram yang menerobos masuk dari tingkap kayu yang sedikit renggang.
Di dalam rumah pusaka itu, suasana terasa berat — seolah-olah setiap sudut menyimpan sebak yang menunggu pecah.
Puan Laila duduk bersimpuh di atas lantai, mengelap bingkai-bingkai gambar lama yang bersalut habuk. Sesekali jemarinya berhenti, sekadar menyentuh permukaan gambar itu seolah-olah ingin memeluk kenangan yang sudah jauh. Di hujung matanya, ada takungan air jernih yang tidak sempat diseka.
Hafiyy yang sedang sibuk mengemas timbunan buku-buku lama di sudut ruang, terhenti.
Dari balik kotak, dia lihat bahu ibunya bergegar perlahan — cuba menahan esakan yang tak tertahan.
Dia bangun tanpa sepatah kata, mendekat, lalu duduk di sisi.
"Mama..." bisiknya perlahan, penuh hati-hati. Tangannya diletakkan di atas bahu ibunya, menepuk perlahan-lahan, seperti mahu memindahkan sebahagian beban itu ke bahunya sendiri.
Puan Laila menggeleng, seakan-akan mahu menafikan kesedihannya, namun tangisan tetap juga tumpah.
"Mak Mama... Mak Mama kuat selama ni. Tak pernah nak susahkan orang. Tapi sekarang..." Dia sapu air mata dengan hujung lengan bajunya. "Sekarang dia terlantar macam tu..."
Hafiyy diam, memandang barang-barang lama itu — semuanya penuh kenangan.
"Mama, Tok kuat. Kita doakan dia, ya?" Hafiyy bersuara perlahan, cuba menenangkan.
Puan Laila hanya angguk kecil, masih sebak.
Sunyi seketika.
Untuk beberapa ketika, hanya suara kipas tua yang berdengung perlahan mengisi ruang itu.
Lama Hafiyy diam sebelum akhirnya dia bersuara lagi, nadanya lebih berat, lebih matang daripada usianya.
"Mama..." Dia tunduk, bermain-main dengan hujung kotak di hadapannya. "Fi... Fi rasa lepas habis SPM nanti, Fi tak nak ikut Mama dengan Papa ke Amerika."
Puan Laila terkejut. "Kenapa?" tanyanya, hampir berbisik.
Hafiyy menghela nafas panjang.
"Fi risaukan Tok. Nanti kalau Fi pergi... siapa yang akan jaga Tok? Fi risau... kalau Fi sambung belajar pun, mesti kena tinggal kat asrama. Siapa nak teman Tok kat sini?"
Wajahnya kelihatan berat, seberat keputusan yang baru dilafazkan.
"Fi rasa... Fi nak duduk je kat Malaysia. Dekat kampung ni pun tak apa. Kalau tak belajar pun, kerja kat kampung ni pun jadilah... Asalkan dekat dengan Tok."
Puan Laila terdiam. Matanya membulat, memandang wajah anak bujangnya itu.
Ada rasa bangga yang menikam dada, bercampur pilu yang tak terucap.
"Fi... Mama faham kamu sayangkan Tok. Tapi... masa depan Fi penting, sayang. Nanti kalau Tok dah sihat, kita pujuk la Tok ikut sekali sampai dia lembut hati."
Suara Puan Laila lembut, seolah-olah memujuk. "Fi masih muda lagi. Takkan nak lepaskan peluang macam tu?"
Hafiyy tersenyum tipis, senyuman yang pahit tapi penuh dengan keikhlasan.
"Ma..." Dia memandang tepat ke dalam mata ibunya. "Banyak kali dah Fi pujuk Tok, dah macam-macam cara dah Fi buat, Tok memang tak nak ikut. Jiwa Tok memang dah dekat sini. Tok pun kata dia nak habiskan sisa umur dia kat sini. Belajar tu... bila-bila masa pun boleh. Tapi Tok..."
Dia terhenti sejenak, menahan rasa sebak yang makin menghimpit dada.
"Tok takkan ada pengganti, Ma."
Sekali lagi, air mata Puan Laila jatuh tanpa dipaksa.
Tanpa berkata apa-apa, dia menarik Hafiyy ke dalam pelukannya — memeluk erat seolah-olah tidak mahu melepaskan.
Hafiyy membalas pelukan itu, diam-diam menitipkan janji dalam hatinya: dia akan terus berada di sini, untuk Tok. Dia tahu, keputusan yang dia buat mungkin susah. Tapi hatinya sudah bulat — dia tak sanggup tinggalkan Tok.
"Anak mama dah besar." bisik Puan Laila, bergetar.
Dan di ruang kecil rumah itu, waktu seakan berhenti, membiarkan dua hati yang rapuh saling menguatkan.
***
Petang itu, Ara duduk bersandar di katil usangnya, asyik menekuni buku motivasi. Angin dari tingkap berayun perlahan, membawa bau tanah basah selepas hujan renyai-renyai sebentar tadi.
Sedang dia tenggelam dalam pembacaan, tiba-tiba telefon di atas meja bergetar. Nada getaran itu memecah keheningan bilik kecil itu. Ara berpaling, mengambil telefon usangnya yang retak sedikit di sudut skrin. Ada satu mesej masuk — dari nombor yang tidak dikenali.
Dahi Ara berkerut.
Perlahan-lahan dia tekan mesej itu.
"Assalamualaikum. Saya nak pulangkan buku awak. Boleh kita jumpa dekat rumah biru terbengkalai dekat hujung lorong kecil yang ada jalan mati tu? Saya tunggu awak."
Ara terdiam. Matanya kembali membaca mesej itu dua tiga kali, cuba mencerna.
Bangunan terbengkalai? Jalan mati?
Kenapa tempat macam tu?
Siapa sebenarnya yang hantar mesej ni?
Namun, ayat "saya nak pulangkan buku awak" itu buat Ara cepat membuat kesimpulan sendiri.
Mesti Wahyun... Sebab hanya Wahyun yang ada buku dia sekarang.
Ara mengeluh perlahan, memandang telefon itu lama. "Tapi... bila masa Wahyun ada nombor aku?" fikirnya hairan.
Seingatnya, dia dan Wahyun tidak pernah bertukar nombor. Mereka cuma bercakap bila terserempak di sekolah atau di surau. "Dia pun tak pernah minta nombor aku. Aku pun tak ada nombor dia."
Kening Ara berkerut lagi. Hatinya mula disapa rasa ragu, tapi kemudian dia menolak rasa itu ke tepi.
Ah, mungkin dia dapat dari pelajar yang lain.
Ara menarik nafas panjang.
Dia malas nak berteka-teki lebih lama. Buku itu penting baginya, jadi dia rasa lebih baik dia pergi saja dan ambil terus.
Bangkit dari katil, dia segera bersiap dan capai telefonnya. Basikal usangnya sudah sedia menunggu di tepi rumah.
Sebelum melangkah keluar, Ara sempat berbisik sendirian, "Kenapa Wahyun pilih tempat macam tu... Macam pelik je. Tapi... mungkin dia ada benda penting nak cakap."
Ara menolak semua perasaan ragu.
Dengan semangat yang bercampur debaran, dia mengayuh perlahan meninggalkan rumah, menuju ke lorong kecil yang disebut dalam mesej itu — ke rumah terbengkalai, tanpa sedar bahaya apa yang sedang menantinya.
Share this novel



