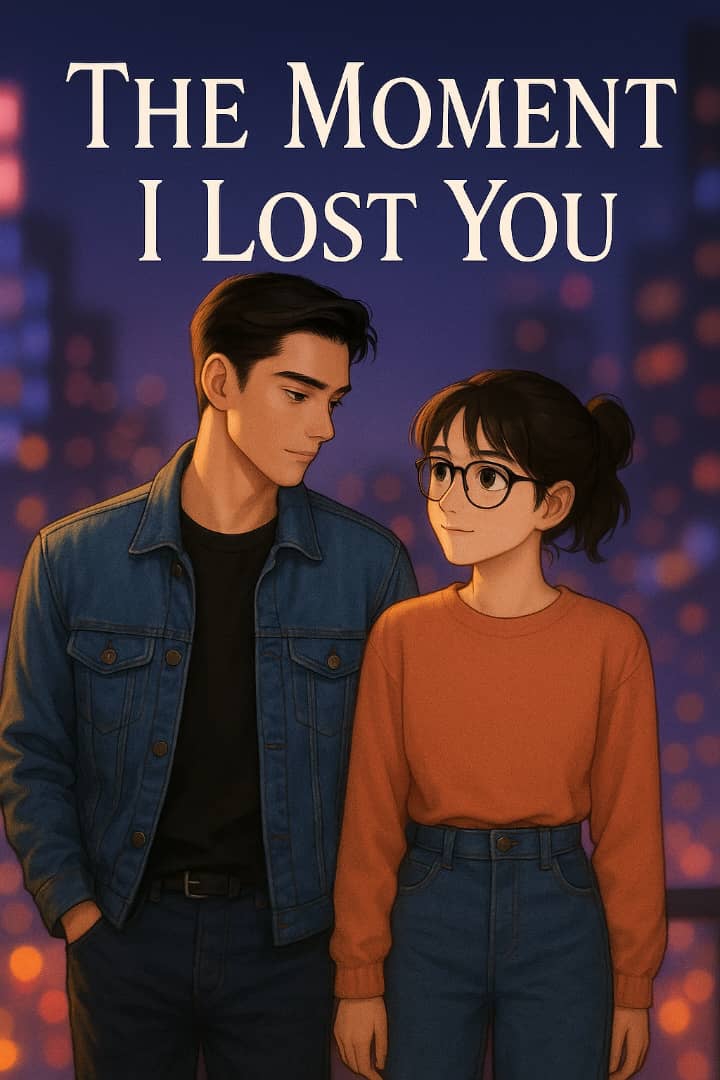
Bab 45: Dalam Sibuk, Masih Ada Kita
 Series
Series
 1488
1488
Langit kampus tampak lebih kelabu daripada biasa, bukan kerana cuaca, tetapi kerana suasana yang perlahan-lahan bertukar. Semester hampir ke penghujungnya. Hari-hari terasa seperti bergerak lebih pantas, dihimpit oleh tarikh akhir tugasan, jadual kelas terakhir dan nota-nota kuliah yang perlu diulang semula.
Di satu sudut perpustakaan, Aurora masih duduk menghadap skrin laptop. Matanya sudah letih, tapi tangannya masih laju menaip isi perbincangan untuk kerja kumpulan. Kertas berselerak di sebelah kiri, air mineral separuh penuh di kanan.
Di luar tingkap, langit sudah mula gelap. Hari berganti malam tanpa dia sedar. Dalam kalendar harian, ada banyak perkara yang perlu dilakukan. Dalam senarai mesej, nama Izhan masih belum dibalas sejak tengah hari tadi.
Sibuk. Sangat sibuk.
Aurora tidak pernah menyangka minggu-minggu terakhir ini akan sebegini padat. Dia bukan sahaja perlu menyiapkan tugasan akhir untuk empat subjek, tetapi juga terlibat dalam pembentangan projek dan latihan debat antara fakulti.
Mesej masuk dari Izhan sekitar jam 3 petang:
“Awak okey hari ni?”
Dan ia hanya sempat dibalas hampir jam 8 malam:
“Baru selesai perbincangan tugas. Maaf lambat balas.”
Di tempat lain, Izhan membaca mesej itu dengan senyuman kecil. Dia tidak kecewa. Tidak marah. Cuma… sunyi.
Dia tahu Aurora tidak mengabaikannya. Tapi kesunyian bukan soal salah siapa. Ia cuma hadir, bila kehadiran seseorang yang kita selalu harapkan… semakin jarang terasa.
Tapi Izhan belajar menerima. Dia tahu dalam hidup, waktu tidak selalu berpihak. Ada masanya pertemuan jadi kerap, dan ada masanya perhatian terpaksa dikorbankan demi tanggungjawab yang lebih besar. Itu bukan kesalahan, itu kehidupan.
Namun, tetap ada rindu. Rindu pada perbualan kecil yang dulu terasa biasa, tapi kini jadi sesuatu yang berharga.
Mesej mereka semakin pendek. Tapi maknanya tidak berkurang.
Aurora: “Tak sempat lunch lagi. Baru free kejap.”
Izhan: “Jangan tinggal makan. Nanti sakit.”
Aurora: “Thanks, awak pun jaga diri.”
Perbualan seperti ini — pendek, mungkin sepintas lalu — tapi bagi mereka berdua, ia adalah penghubung di antara dua dunia yang sedang sibuk berjuang.
Malam Jumaat itu, langit masih mendung. Aurora keluar dari kolej selepas menyelesaikan perbincangan kumpulan. Tubuhnya penat, kepala sedikit berat — tapi perutnya lebih kosong.
Dia berjalan perlahan ke arah kafe kecil di hujung blok kolej, tempat yang jarang dia kunjungi sejak beberapa minggu lalu.
Dan di situ… dia terlihat seseorang.
Izhan.
Duduk di meja luar, dengan satu buku terbuka dan secawan kopi di hadapannya. Rambutnya sedikit kusut, dan wajahnya menunjukkan keletihan yang sama seperti yang Aurora rasa.
Aurora terhenti seketika. Izhan pun menyedari kehadirannya.
Mereka tidak terkejut. Tidak juga teruja secara berlebihan. Tapi mereka senyum — senyuman yang sederhana, namun penuh makna.
Aurora berjalan mendekat.
“Tempat ni sunyi sekarang,” katanya perlahan.
Izhan angguk. “Tapi tenang.”
Aurora duduk di kerusi kosong di hadapannya. Mereka tidak bertanya kenapa masing-masing ada di situ — kerana jawapannya sudah jelas. Mereka letih. Dan mereka perlukan rehat… walau sekejap.
Mereka tidak berbual panjang. Cuma bertukar pandangan tentang kopi yang semakin suam, tentang kertas kerja yang belum selesai, dan tentang betapa malam-malam kampus kini terasa lebih sepi.
Izhan memandang Aurora seketika. Rambutnya sedikit serabut, dan lingkaran bawah matanya makin jelas. Tapi di wajah itu, Izhan nampak kekuatan. Dan dia tahu, Aurora sedang berjuang.
“Awak okay?” soalnya perlahan.
Aurora angguk. “Penat, tapi okay.”
Izhan senyum kecil. “Saya tahu rasa tu.”
Aurora membalas senyum itu. Tidak ada penjelasan panjang, tiada ungkapan besar. Tapi berada di hadapan satu sama lain, walau hanya beberapa minit — sudah cukup untuk memberikan rasa lapang yang tiada pada sepanjang minggu.
Malam itu, selepas pulang ke bilik, Aurora duduk di katil sambil menggenggam telefon. Dia scroll semula mesej-mesej terdahulu antara mereka — dari jenaka kecil di pesta buku, ke mesej motivasi waktu dia demam, hingga ke petikan-petikan pendek yang dia sendiri pernah hantar dalam diam.
Dia rindu. Tapi dia juga takut.
Dan dalam keberanian yang perlahan, dia menaip satu mesej pendek:
“Saya takut masa buat kita jauh, tapi saya tak nak kita hilang.”
Dia tidak berharap balasan segera. Tapi beberapa minit kemudian, mesej masuk dari Izhan:
“Saya tak pergi mana-mana. Saya tunggu — walaupun bukan setiap hari awak ada, saya tahu awak tak lari.”
Aurora memandang skrin itu lama. Senyum yang muncul bukan senyum gembira semata-mata, tapi senyum yang penuh rasa lega.
Dan malam itu, walau masing-masing masih tenggelam dalam kesibukan, mereka tahu satu perkara pasti:
Ada ikatan yang tidak perlukan pertemuan setiap hari, tidak perlu mesej panjang atau panggilan kerap. Cukup dengan kehadiran yang setia — walau diam, walau jauh — tapi tetap ada.
Izhan tidak meminta Aurora memberi lebih masa, dan Aurora tidak memaksa Izhan untuk menunggu tanpa jaminan. Mereka saling faham — bahawa hubungan yang dibina atas sabar dan percaya… akan tetap bertahan, walau diuji oleh waktu.
Share this novel



