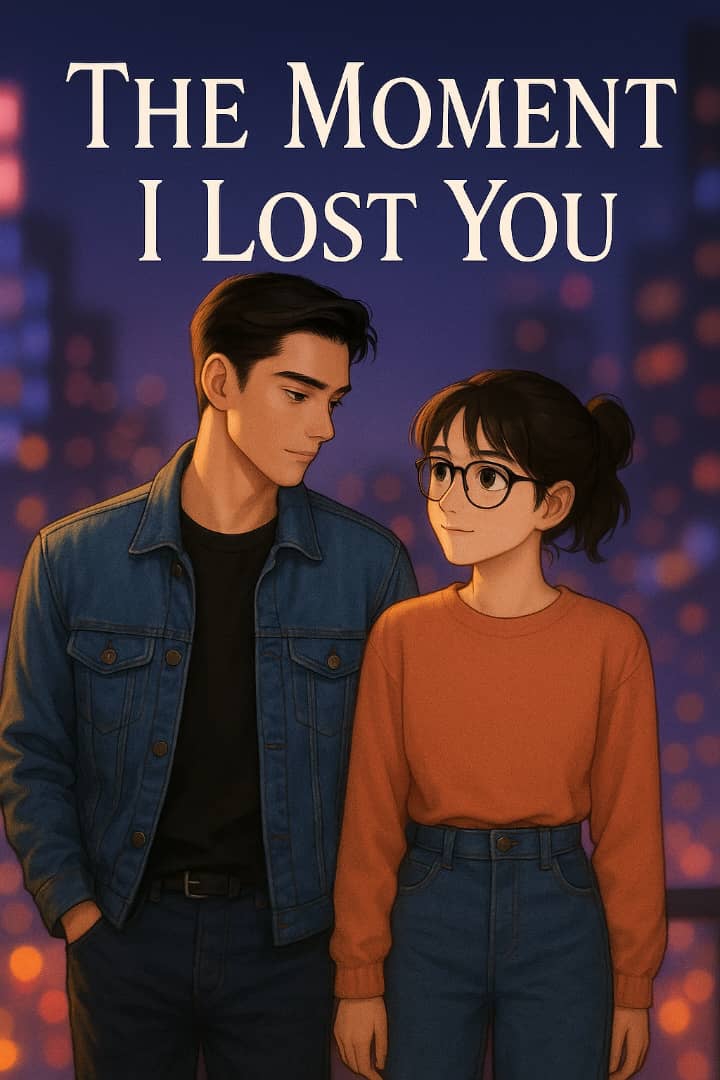
Bab 42: Isyarat Tanpa Kata
 Series
Series
 1488
1488
Aurora termenung di sisi tingkap, cahaya lampu bilik yang suram memantul di cermin. Malam di kolej itu sunyi seperti biasa, hanya sesekali kedengaran bunyi kipas siling yang berputar perlahan. Namun senyuman di wajahnya, walau kecil, terasa sangat berbeza.
Dia teringat semula detik sewaktu di hotel — bagaimana layanan mesra ibu Izhan membuatkan dia rasa sangat dihargai. Kata-kata yang sederhana, tapi menusuk ke dalam hati. “Aunty happy bila tengok kamu dengan Izhan bersama,” ujar wanita itu dengan nada penuh kasih.
Dan dia teringat pula kata-kata Izhan sendiri di lobi hotel, sewaktu tetamu sudah mula pulang dan suasana kembali tenang. “Saya harap… awak rasa dialu-alukan.”
Saya rasa… selesa, bisik Aurora dalam hati.
Entah mengapa, malam itu dia tidur dengan senyuman yang tak sempat dia sembunyikan.
Sejak malam itu juga, Izhan mula berubah sedikit demi sedikit. Bukan berubah menjadi orang lain, tapi dia jadi lebih peka — lebih hadir.
Dia tidak melampaui batas, tidak mendesak. Tetapi dia tahu di mana untuk berada, dan bila untuk muncul.
“Awak okay hari ni?”
“Kalau free petang nanti, jom minum kejap?”
Itu antara mesej-mesej ringkas yang Izhan hantar. Kadang-kadang Aurora membalas terus, kadang-kadang selepas beberapa jam — tetapi dia tetap membalas.
Dalam setiap balasan, tidak ada emoji berlebihan, tiada manja dibuat-buat. Hanya nada yang jujur, yang tenang. Seperti hubungan mereka sekarang — perlahan tapi perlahan-lahan mengisi ruang hati yang kosong.
Suatu malam, di bilik kecil mereka, Sofea perasan sesuatu. Aurora termenung dengan senyuman pelik — bukan senyum main telefon, bukan senyum sebab cerita lawak. Tapi senyuman yang keluar entah dari mana, dan Sofea tahu, itu senyuman yang selalu muncul bila hati seseorang sedang kacau... tapi bahagia.
“Awak ni kenapa senyum sorang-sorang?” soal Sofea sambil menarik bantal dan bersandar ke dinding.
Aurora terdiam sekejap. Tapi mungkin kerana hatinya sudah terlalu penuh, dia tidak mampu menipu lebih lama.
“Saya tak tahu apa sebenarnya saya rasa, Fae…” katanya perlahan.
Sofea tidak menyampuk. Dia tahu Aurora perlukan ruang.
“Tapi bila dekat dia… saya rasa happy. Macam dulu. Macam… ada sesuatu dalam diri saya yang kembali hidup.”
Sofea tersenyum. “Kalau itu rasa selesa, mungkin itu sebenarnya yang awak rindukan selama ni. Suasana tu. Perasaan tu.”
Aurora pandang temannya. “Tapi saya takut kalau saya salah faham. Takut kalau semua ni cuma saya yang rasa.”
“Tapi awak tak rasa dipaksa, kan?”
Aurora menggeleng perlahan.
“Kalau begitu… biar masa tunjukkan.”
Beberapa hari selepas itu, kelas terakhir petang itu tamat lebih awal. Suasana kampus perlahan-lahan mula redup, langit senja sudah mula menguning, dan pelajar-pelajar lain mula bersurai.
Aurora baru sahaja melipat nota bila mesej masuk dari Izhan:
“Kalau awak tak sibuk… jom jalan-jalan sekejap dekat tasik?”
Dia renung skrin itu seketika. Kemudian menaip:
“Okey.”
Langkah mereka sederhana. Mereka berjalan di laluan pejalan kaki mengelilingi tasik universiti yang tenang. Angin petang menyapa lembut, dan daun-daun berguguran dari pokok di tepi tasik memberi suasana yang mendamaikan.
Mereka tidak berbual banyak. Hanya kata-kata ringkas seperti,
“Lega kelas habis awal hari ni.”
“At least boleh tarik nafas sebelum minggu sibuk minggu depan.”
Kemudian mereka duduk di bangku kayu yang menghadap air tasik yang beralun tenang.
Beberapa minit berlalu dalam diam. Tapi ia bukan diam yang menyesakkan. Ia diam yang selesa — yang tidak mendesak kata-kata keluar, kerana kedua-duanya tahu, ada sesuatu yang sedang dibina perlahan-lahan.
Izhan kemudian membuka beg sandangnya dan mengeluarkan sesuatu yang kecil, dibalut dengan plastik lutsinar.
Aurora memandang. Matanya terbuka sedikit apabila dia camkan bentuknya.
Itu… penanda buku. Penanda buku kecil buatan tangan — yang pernah dia hadiahkan kepada Izhan satu masa dahulu, dan kemudian hilang entah ke mana.
“Saya jumpa balik ni masa kemas laci dekat rumah,” kata Izhan perlahan. “Saya simpan. Cuma masa tu… saya tak tahu bila saya nak tunjukkan semula pada awak.”
Aurora memandang penanda buku itu, kemudian pandang Izhan. Dia tidak berkata apa-apa. Tapi cahaya di matanya cukup kuat untuk menyampaikan sesuatu.
Izhan tidak mendesak. Dia tidak perlukan jawapan hari ini. Tetapi bila Aurora tersenyum perlahan, menatap penanda buku itu seperti ia sesuatu yang sangat bermakna — dia tahu, ada harapan yang masih bernyawa.
Senja semakin menebal, langit yang tadi keemasan kini mula bertukar ungu.
Aurora menyimpan penanda buku itu ke dalam begnya tanpa berkata apa-apa, tetapi dengan gerakan yang penuh hati-hati — seolah-olah ia sesuatu yang berharga.
Dan dalam diam, dua hati yang pernah retak kini mula kembali bercantum, bukan dengan kata-kata besar, tapi dengan langkah kecil yang jujur dan perlahan.
Kerana cinta yang tenang tidak perlu dikejar. Ia hanya perlu difahami, diberi ruang, dan dibiarkan mekar mengikut waktunya sendiri.
Share this novel



