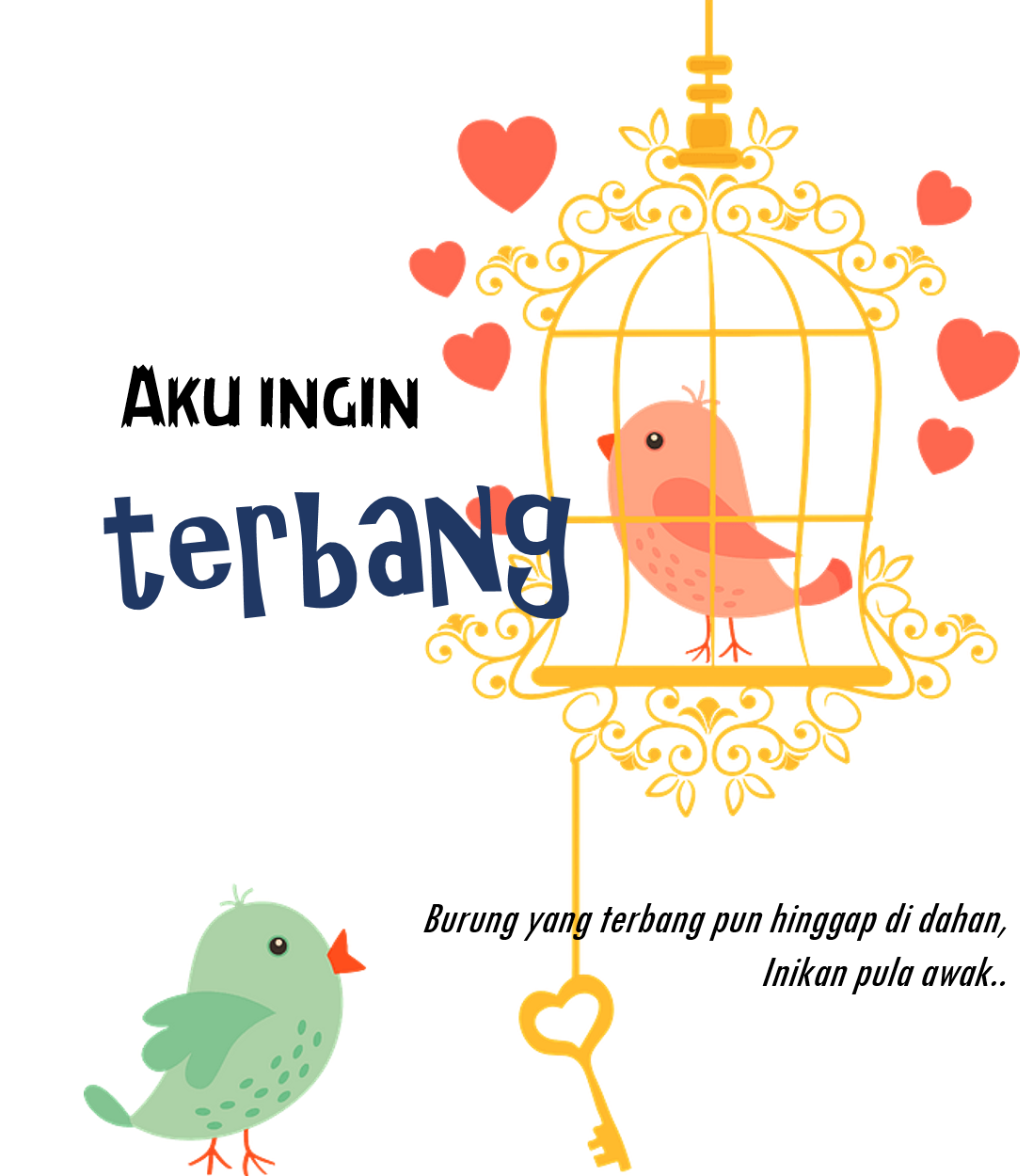
Bab 23
 Series
Series
 2580
2580
Manisa berjalan laju ke depan dan ke belakang. Syahira yang dari tadi menonton televisyen agak terganggu dengan pergerakan Manisa. Terlalu mengganggu kerana wanita itu lalu di hadapannya ketika ini. Dengan mata sekilas, dia menjeling Manisa. Nak cakap, cakap sahaja. Tak perlu buang tenaga, Manisa. Kau ke depan, ke belakang macam poco-poco, ingat boleh tarik perhatian aku ke? Sejujurnya ya, kalau tidak, kenapa sekarang aku fokus pandang muka Manisa yang mencuka dari tadi. Semasam-masam cuka, masam lagi muka Manisa. Kalau diumpamakan macam cecair, muka Manisa ni dah tahap asid, boleh cair besi yang pandang wajah Manisa dek kerana masamnya. Dah tak ada manisnya lagi.
“Cakap je la.” Ujar Syahira sebaik sahaja rancangan kegemarannya bertukar iklan. Menunggu Manisa buka mulut sendiri? Memang tak akan. Nak juga perhatian disuruh buka mulut.
“Aku tak tahu nak mula dari mana.” Mendengar ucapan Manisa, Syahira buat muka tidak mahu melayan. Ini mesti kes kena usik dengan budak pejabat mana lagi. Bukan tak biasa. Terima sahaja Manisa, kau bukan muda lagi.
Syahira bangkit dari tempat duduknya untuk ke dapur mengambil air minuman. Itu niatnya.
“Tuan Saif Haziq dah jumpa Iman.” Sebaik mendengar luahan Manisa, Syahira membatalkan niatnya. Ini berita sangat sensasi.
“Apa dah jadi?” soal Syahira. Riak wajahnya berubah pucat. Benar-benar seperti mayat tak berdarah.
“Dia syak Iman anak dia.” Tangis Manisa yang cuba ditahan sejak petang tadi akhirnya meletus. Syahira yang mendengar jawapan Manisa, menarik kepala Manisa ke dalam dakapannya. Hakikatnya, berita seperti inilah yang paling dia takut hendak dengari. Dia tahu, selama mana mampu Iman disembunyikan. Iman bukan barangan yang boleh disorok.
“Bukan ke selama ni memang itu yang kau nak?” soal Syahira lembut. Dia mengusap lembut rambut Manisa. Tangis Manisa yang begitu syahdu seperti ditahan-tahan menjadikan dia semakin sebak. Hari yang paling ditakuti Manisa sudah tiba. Satu demi satu masalah mula timbul. Entah mengapa, dia sendiri yang merasa gerunnya.
“Tapi aku takut. Kalau lepas ni dia pisahkan aku dengan Iman macam mana?” Syahira ketap bibir. Aku pun takut Manisa. Iman pun dah macam anak saudara aku sendiri. Aku dah anggap dia macam darah daging aku sendiri. Mana mungkin aku sanggup berpisah dengan dia.
“Tak. Kau jangan fikir bukan-bukan. Kau mak dia. Secara sah, mengikut undang-undang. Dia tak boleh ambil Iman macam tu je. Dia bukan macam tu kan? Kau juga yang cakap dia dah berubah.”
Manisa mengangguk. Menyetujui kata-kata Syahira. Ya, aku harap dia dah berubah. Betul-betul berubah.
*****
Manisa mencedokkan nasi goreng ke dalam pinggan Iman buat sarapan pagi. Diletakkan sekeping telur dadar ke dalam pinggan anak itu dan dicarik-carik kepada kepingan kecil bagi memudahkan Iman mengunyah sumber protein itu. Iman yang begitu tekun memenuhi isi perut menarik perhatian Syahira. Dalam diam dia memerhati anak kecil itu. Bagaimana nanti jika Iman pergi dari hidupnya juga? Sanggupkah dia berjauhan?
“Iman, sayang aunty tak?” soalan Syahira menghentikan suapan Iman yang perlahan itu. Seiring dengan anggukan perlahan, dia kembali menyuakan sudu ke mulutnya.
“Hari ni, mommy cuti. Aunty pun cuti. Iman ada nak pergi mana-mana tak?” soal Syahira lagi. Manisa hanya diam tanpa mencelah. Dalam senyumnya, dia sedikit rasa terkilan sekiranya ini adalah waktu-waktu terakhirnya bersama Iman.
Iman, sang pujaan hati Manisa. Demi Iman, dia sanggup bergelar janda. Dia tak peduli pandangan orang. Yang penting baginya, Iman bahagia. Tapi adakah Iman bahagia? Sejak dua menjak ini, Iman kerap bertanyakan ayahnya. Sedangkan aku? Cuba menjauhkan Iman dari ayahnya. Adakah ini yang Iman mahukan? Atau sebenarnya ini cuma alasan bagi dirinya sendiri. Manisa mengelengkan kepalanya.
Tidak, ini semua atas perjanjian yang dia dan Iqwan sendiri bina. Sebelum berkahwin, mereka sudah berjanji untuk hidup bersama hanya selama empat tahun. Walaupun pada hakikatnya, mereka langsung tidak bersama. Hanya suami dan isteri di atas kertas selama empat tahun. Seorang di utara, seorang di selatan. Cukup empat tahun, masing-masing menuntut hak kebebasan mereka sendiri. Jadi, dia tidak salah dalam hal ini. Lagi pula, hanya ini jalan terbaik yang dia rasa pada ketika itu. Berpisah satu-satunya cara agar Iqwan dapat teruskan usaha dia selama ini tanpa sebarang kekangan. Kau tak hipokrit, Manisa. Kau cuma takut kewujudan kau dan Iman dalam kehidupan Iqwan akan merosakkan segala yang Iqwan cuba capai selama ini. Kau tak salah.
“Mommy, Iman nak beli mainan.” Suara Iman sayup-sayup menembusi gegendang telinga Manisa. Entah berapa lama dia melamun. Sebaik sahaja dia sedar, makanan di atas meja semuanya sudah disimpan rapi ke dalam peti ais. Syahira sudah siap mengemas sepanjang dia termenung. Laju benar Syahira bekerja. Tak beri peluang Manisa mahu menjamah walau secebis roti pun.
“Aku dah siap.” Ujar Syahira sebaik sahaja menuruni anak tangga. Dia lengkap dengan beg tangan bertali yang disangkut ke bahunya memandang ke arah Manisa dengan pandangan aneh.
“Nisa, aku naik atas tadi, belum mandi tahu. Kau masih makan. Ini, aku dah turun pun. Kau belum siap makan lagi? Kita jadi keluar ke tidak ni?” Syahira merengek seperti anak kecil. Melihat Syahira yang sudah siap, Iman jadi tak senang duduk. Tangannya masih lekat sepotong sosej yang belum habis dia telan.
“Aku makan sekejap je.” Pujuk Manisa sebelum menelan segala apa yang ada di atas pinggannya seperti orang yang kelaparan. Serupa tidak makan selama sepuluh hari gayanya. Laju bukan main lagi. Kalau orang tidak tahu, pasti tidak percaya dia merupakan seorang ibu tunggal anak satu. Gaya tak seperti orang punya anak. Tak pernah molek.
*****
“Macam mana? Dia okey?” soal Puan Marlia sewaktu dia duduk di meja luar rumah. Petang-petang begini, memang menjadi rutin hariannya keluar rumah untuk menyiram segala bunga-bunga tanamannya. Bunga jugalah tempat paling nyaman yang dia rasakan ketika ini. Sejak dari dia tahu anak sulungnya sudahpun menceraikan Manisa, betapa hatinya tidak berasa begitu tenteram. Dia perasan, Indah semakin berusaha menjaga hatinya sejak dua menjak ini. Takut benar anak keduanya itu sekiranya dia jatuh sakit. Mana sibuk dengan perniagaannya lagi, mengurus anak, kini disambung dengan kes perceraian abangnya. Mana mungkin Indah boleh tenang. Lagi-lagi apabila melihat keadaan ibunya yang semakin hari tidak begitu sihat.
“Siapa?” soal Iqwan. Padahal cukup dia tahu. Siapa lagi mahu mamanya bertanyakan. Menantu perempuan kesayangan dialah. Siapa lagi kalau bukan Manisa.
Puan Marlia berdecit mendengar soalannya dibalas soalan kembali oleh Iqwan. Kalau ikutkan hati, mahu saja dia lepuk guna pinggan. Tapi disabarkan hati. Kalau jadi buruk muka anak aku, ada kena tolak mentah-mentah oleh Manisa.
“Mama, abang nak tanya. Kenapa mesti Manisa?” soal Iqwan secara tiba-tiba. Sejujurnya, dia sedikit aneh apabila mamanya begitu beria mahukan Manisa kembali dalam keluarganya sebagai menantu. Bukan dia tidak suka pada wanita itu, cuma Iqwan sedikit aneh. Puan Marlia begitu mahukan Manisa. Sudah tentu Manisa ada buat sesuatu pada mamanya sebelum ini.
“Kenapa abang pilih dia?” soal Puan Marlia kembali. Iqwan terkelu. Dia tanya kita balik. Sudah semestinya kita tak boleh jawab. Sebab kalau kita beri jawapan jujur, mahu kena sumpah jadi tanggang secara serta merta oleh ibunda Marlia. Iqwan tersengih. Apa kau merepek ni, Iqwan?
“Sebab abang sayangkan Manisa.” Iqwan tak semena-mena tergigit lidah. Haa, itu dia. Menipu. Kan tergigit lidah.
“Haa, tergigit lidah masa minum benda manis. Manisa puji abang tu.” Kembang-kempis hidung Iqwan bila mendengar dia dipuji. Walaupun itu hanya bicara mamanya sendiri, sudah cukup buat dia senang. Memang awalnya, dia kahwin tanpa ada sebarang rasa suka apatah lagi cinta pada Manisa. Tapi entah mengapa, sepanjang dia menyambung pelajarannya, makin hari, makin dia rindu pada Manisa. Bagai ada satu tarikan magnet yang buat dia ingin selalu dekat dengan Manisa.
Semua ini gara-gara seorang rakan kelasnya yang berasal dari Malaysia juga pada ketika itu, mengatakan dia bertemu dengan seorang gadis melayu yang manis wajahnya. Niat Iqwan mahu menemani rakannya itu mengenali gadis itu tidak seindah yang dia sangka. Mana mungkin dia sokong rakannya itu bila tahu gadis yang disebutnya adalah isterinya sendiri. Dari sekadar menemani, dia sendiri jadi cemburu. Melihat Manisa yang mesra melayan pelanggan yang hadir di kafe tempat dia bekerja, makin tidak keruan Iqwan dibuatnya. Senyum Manisa yang manis, buat dia merasa sakit hati apabila senyum itu diukir bukan buat dirinya.
Dek kerana rasa tergugat, sudahnya, hampir setiap hari Iqwan hadirkan diri ke kafe tempat Manisa bekerja. Setiap kali itu jugalah, dia pulang dengan rasa kecewa melihat Manisa yang selalu manis kepada pelanggan yang hadir. Hendak marah? Siapa dia pada Manisa. Hanya sekadar suami di atas kertas. Ketika dia pulang ke Malaysia, dia cuba memujuk Manisa untuk meneruskan perkahwinan mereka. Namun lidahnya sendiri kelu.
“Abang, mama cakap dari tadi. Abang dengar ke tidak?” lembut sahaja bicara Puan Marlia. Melihat Iqwan yang dari tadi melamun, risau juga dibuatnya. Sekejap tersenyum, sekejap berubah serius. Khuatir jika Iqwan terkena penyakit berbahaya. Penyakit angau namanya. Susah dapat ubat kecuali kahwin.
“Apa ma? Abang dengar.” Iqwan menjawab dalam terpinga-pinga. Entah apa yang dia dengar. Dari tadi berangan.
“Mama cakap, lain kali, bawa Manisa datang sini. Mama teringin nak jumpa dia. Riana dan Rania pun sama. Rindu nak bermain dengan mak long mereka. Rindu nak jumpa adik sepupu mereka. Nak harapkan Indah? Balik-balik dia cakap, ‘Indah dah penat mengandung’. Entah berapa kali dia mengandung agaknya? Dia tu senang, mengandung baru sekali, keluar dua terus. Itu pun dah kata taubat. Kalau yang namanya taubat tu, bila anak dah sepuluh.” Bebel Puan Marlia. Sungguh dia kurang berkenan dengan sikap Indah yang seperti ingin mengelak setiap kali ditanya soal anak lagi.
“Jadi kenapa dengan Manisa?”
“Mama ni kan, kadang-kadang pening dengan cara abang berfikir. Hantar belajar sampai Master dah. Tapi prosesnya tu, macam telefon RAM 300mb. Perlahan sangat.” Mendengar kata-kata Puan Marlia membuatkan tawa Iqwan meletus. Mana mama belajar cakap macam ni? Ini mesti Rania tak pun Riana yang ajar.
“Mama nak, abang kahwin semula dengan Manisa. Mama nak cucu ramai. Abang tengok rumah mama ni.” Puan Marlia menuding ke arah rumahnya.
“Besar. Kalau setakat cucu tiga orang, baik mama buat rumah tiga puluh kaki persegi. Kecil. Tujuan mama buat rumah besar, sebab mama harapkan kamu dan adik kamu, lahirkan anak ramai. Seorang sepuluh, dua puluh semua sekali. Meriah dah rumah kita.”
Iqwan tayang muka kelat. Nak cucu ramai, dia pun beranak dua orang je. Dulu pernah juga Iqwan menjawab seperti itu. Sudahnya, melekat lima helai jari di dahinya. Cukup dia ingat jawapan Puan Marlia ketika itu. ‘Bapak kau dah tak ada. Kau nak aku beranak macam mana.’ Setepek tangannya melekat di dahi Iqwan. Boleh tahan bergegar rasanya ketika itu.
“Itu mama jangan tanya abang. Bukan abang yang bersalin.”
“Sebab itu mama suruh bawa Manisa balik. Kita bincang elok-elok. Lagi pun, kamu berdua cerai bukan sebab apa. Rasa tak sehaluan je kan? Bukan ada yang curang. Masih boleh diselamatkan. Ke kamu ada pilihan lain, bang?”
Terkebil-kebil Iqwan mendengar kata-kata Puan Marlia. Dari mana pula datang alasan tu? Manisa yang reka ke? Tak sehaluan? Memang pun. Aku baru nak bergandingan dengan dia, dia dah lari pecut marathon. Mana sempatnya nak kejar. Anti benar dengan aku. Ke dia memang anti lelaki? Manisa tu perempuan tulen kan? Kalau tak tulen, mana datangnya Iman, Iqwan?
“Kalau bincang elok pun, bukan boleh terus beranak ma.”
“Kadang-kadang, abang buat mama terfikir. Mana silap mama dalam besarkan abang. Kenapa kamu ni perlahan sangat dalam bab yang macam ni? Aku nak kau kahwin dulu. Bukan terus terkam anak orang. Tahu itu janda kamu. Tapi dah terputus ikatannya. Itulah, masa buat dulu, tak mahu tanya orang tua. Dah bercerai, lepas tu tak tahu caranya nak berbaik semula. Masa buat, tak fikir panjang. Inilah budak zaman sekarang. Main ikut perasaan je. Suka, kahwin. Tak suka, cerai.” Bebel Puan Marlia lagi. Iqwan menggosok telinganya. Boleh rasa mencair telinganya mendengar bebelan mamanya hari ini. Hari cuti begini, sepatutnya dia menikmati suasana petang yang tenang, sebaliknya dileteri dengan pedih.
“Ini, kamu dekat sini. Tak takut ke Manisa kena kebas?” soalan Puan Marlia membuatkan Iqwan rasa tak senang duduk.
“Kerja dekat sini, jangan risau. Raden ada. Dia boleh uruskan. Mama dah kata dulu. Jaga isteri sebaiknya. Ini kalau Manisa kena kebas, memang melopong ceritanya. Tapi abang degil. Nak orang dengar cakap dia je.”
“Nanti abang pergi sana semula. Mama doakan la.”
“Doa kalau sebakul pun, tak usaha, tak datang juga.” Iqwan memegang dadanya. Pedih sungguh kata-kata mamanya sejak kebelakangan ini. Penangan menantu perempuan dah tak ada ke?
Share this novel



