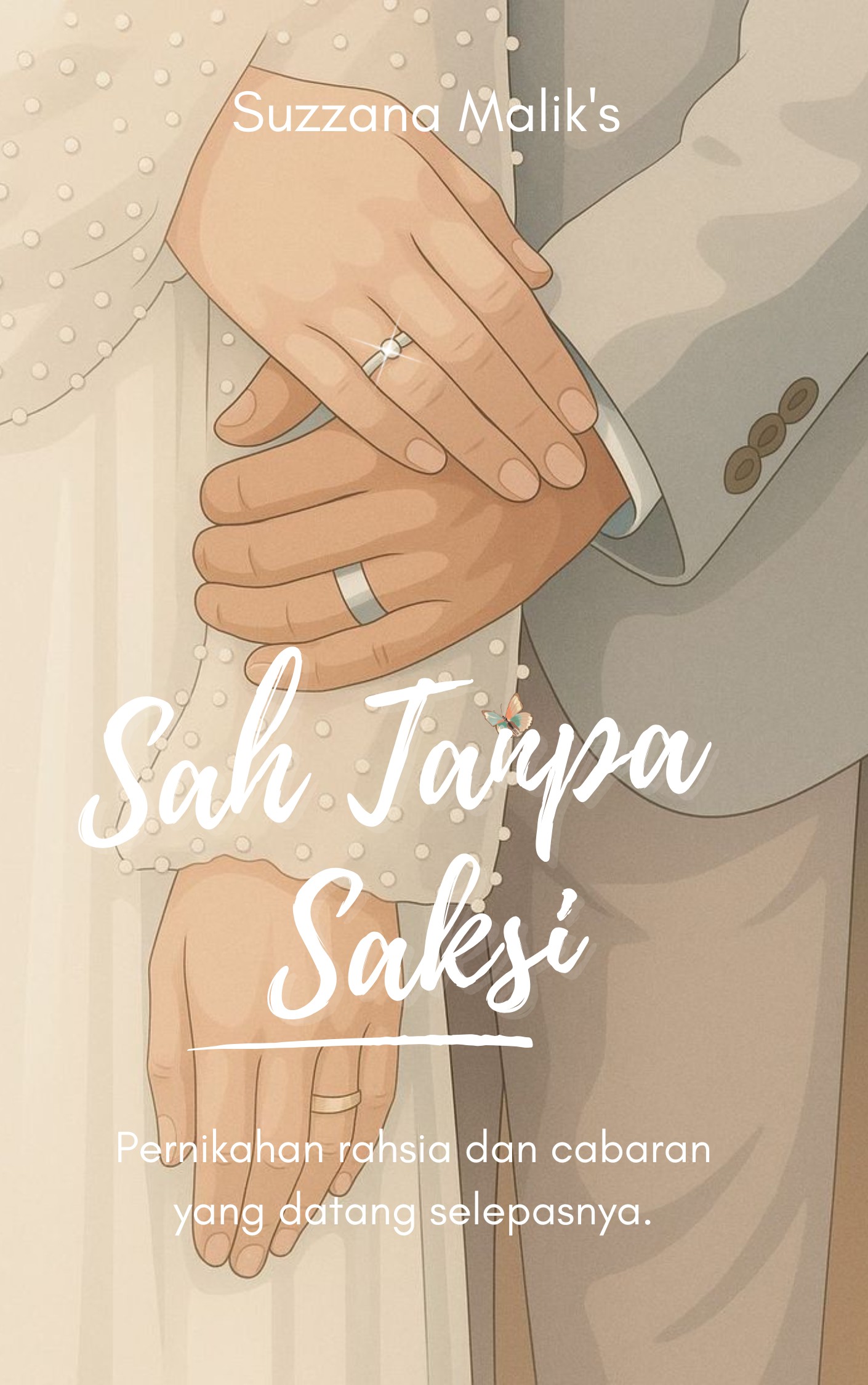
Bab: Bila Disiplin Gagal
 Series
Series
 1624
1624
Hari demi hari, keadaan di Sekolah Menengah Tunas Bakti semakin membingungkan.
Apa yang sebelum ini cuma keluhan kecil kini menjadi isu utama dalam kalangan guru-guru dan staf sekolah. Disiplin pelajar jatuh merudum.
Ketika sesi pagi, suara cikgu-cikgu tidak lagi mendominasi dewan, tetapi sebaliknya dibayangi oleh jeritan dan hilai tawa pelajar yang sudah tidak takut lagi kepada peraturan.
“Cikgu, saya jual burger ni RM3 je, nak tak?”
Itu suara seorang pelajar Tingkatan Dua, berani berdiri di hujung kelas sambil memegang plastik berisi roti burger panas.
Di tepi meja, beberapa lagi pelajar sedang makan nugget dalam bekas polisterin.
Sedangkan waktu itu cikgu Sejarah masih sedang mengajar di hadapan.
“Ya Allah, dah macam pasar malam,” keluh cikgu Salmah bila melintasi koridor.
Ada yang tertawa sinis, ada yang menggeleng, ada yang terus menulis laporan demi laporan. Tapi semua tahu, tindakan sahaja tidak cukup bila pelajar sudah tidak kenal takut.
Lebih menyedihkan, ramai dalam kalangan pelajar mula mengabaikan terus hormat kepada guru. Kata-kata biadab mula dilontar. Ada yang panggil guru dengan nama, malah ada yang berani menegur pakaian cikgu dengan nada menghina.
“Cikgu tu pakai macam mak nenek, patutlah orang tak suka.”
“Cikgu boring lah, cakap tak ada isi.”
Mesyuarat demi mesyuarat dilakukan. Tapi penyelesaiannya? Tiada. Yang ada cuma lebih banyak surat aduan daripada ibu bapa yang kononnya anak-anak mereka 'tertekan' dengan suasana sekolah.
Anehnya, anak-anak itu jugalah yang membawa telefon pintar ke sekolah, bermain TikTok di dalam tandas, dan bergaduh sesama sendiri di belakang makmal.
Cikgu-cikgu disiplin, termasuk cikgu Riduan dan cikgu Malik, sudah mula hilang punca.
“Aku dah denda budak tu, dia datang balik esok dengan vape. Bila aku rampas, dia gelak-gelak. Kata dia ada lima lagi kat rumah.”
“Semalam budak tolak aku dekat tangga. Bila aku tengking, dia buat-buat nangis, cakap aku cabar dia. Lepas tu ibunya datang serang aku dekat pintu pagar.”
Tekanan menebal.
Dalam kalangan guru-guru, nama Tuan Azhar kembali meniti dari mulut ke mulut. Tapi bukan dengan nada marah atau cemuhan seperti tempoh hari. Sebaliknya, nada penuh harapan.
“Tuan Azhar dulu garang, tapi masa dia jaga, sekolah aman.”
“Kita tak boleh biar dia terus duduk diam. Kita perlukan dia.”
Namun apabila mata mereka beralih ke bilik guru kanan, Tuan Azhar hanya kelihatan seperti biasa.
Duduk di meja lamanya, dikelilingi fail-fail tebal dan buku pelajar yang belum disemak. Dia mencatat sesuatu dalam nota kecil, membalik-balik kertas dengan tenang. Air kopi di tepi meja masih berasap, tidak disentuh.
Cikgu-cikgu disiplin mula garu kepala.
“Dia ni takkan tak nampak apa yang berlaku?”
“Atau dia dah putus asa…?”
Sementara itu, Atiha memerhati dari kejauhan. Dari tempat duduknya di hujung meja guru perempuan, dia sesekali menoleh ke arah suaminya. Wajah Azhar tidak pernah berubah.
Tenang, serius, sedikit sinis, seperti selalu. Tapi Atiha tahu di sebalik ketenangan itu, ada badai yang sedang dikumpulkan.
Petang itu, selesai waktu persekolahan, suasana masih hiruk-pikuk di luar. Ada pelajar bermain kejar-kejar di tepi pagar, ada yang bergaduh kecil di kawasan parkir basikal. Dalam bilik guru, semua masih sibuk menulis laporan atau mengeluh dalam nada rendah.
Tiba-tiba, Tuan Azhar berdiri.
Dia mengambil sehelai kertas A4 yang sudah dilipat tiga, memasukkannya ke dalam fail kuning, lalu beredar keluar dari bilik guru.
“Azhar nak ke mana?” tegur cikgu Riduan.
“Jumpa guru besar.”
Jawapan ringkas itu membuat beberapa orang guru bertukar pandangan. Tapi tiada siapa berani tanya lanjut.
Di pejabat guru besar, Puan Rosnah terkejut melihat Tuan Azhar muncul tanpa temu janji. Tapi dia menjemput juga lelaki itu masuk.
“Ya, Tuan Azhar? Ada hal penting?”
Tuan Azhar menyerahkan fail kuning itu.
“Pelan tindakan. Untuk 30 hari pemulihan disiplin. Saya dah siapkan struktur, cadangan pendekatan, borang penglibatan guru, dan model intervensi. Kalau Puan luluskan, saya nak mulakan minggu depan.”
Puan Rosnah terdiam.
Dia membuka fail itu, membaca sepintas lalu. Matanya terbuka sedikit luas. Kertas itu tidak hanya mengandungi jadual atau denda disiplin.
Ia penuh dengan aktiviti psikologi, terapi seni, latihan kepimpinan, dan sesi mentor-mentee. Termasuk modul pendekatan agama, dan pemantauan berjadual oleh guru sukarela.
“Awak... siapkan semua ni?”
Azhar angguk. “Sejak seminggu lalu.”
“Tapi awak nampak tak peduli...”
“Saya lebih suka kelihatan lemah... supaya bila saya bangkit, tiada siapa sangka saya masih simpan taring.”
Puan Rosnah meletakkan fail itu ke meja. “Saya akan bentangkan dalam mesyuarat pengurusan. Tapi saya suka apa yang saya baca.”
Azhar senyum nipis.
“Saya tak minta semua sokong saya, Puan. Saya cuma nak satu peluang.”
Sementara itu, di bilik guru, Atiha menerima satu mesej WhatsApp.
“Sayang, boleh buka peti fail meja abang nanti. Ada sesuatu untuk sayang.”
Atiha segera ke meja suaminya. Dia membuka laci dan menemui satu nota tulisan tangan:
Sayang, dunia mungkin sedang tunggang-langgang, tapi abang dah pilih untuk tak tinggal kapal ni. Abang akan pimpin semula bukan dengan rotan, tapi dengan strategi. Doakan abang.
Atiha menggenggam nota itu sambil tersenyum halus.
Dalam hati dia tahu badai yang melanda sekolah mereka kini akan dilawan. Dan suaminya tidak lagi duduk sebagai penonton. Tapi sebagai nakhoda yang diam-diam sedang memegang kompas.
Sekolah Menengah Tunas Bakti kini terasa lain nadanya. Bukan kerana semuanya sudah sempurna, tetapi kerana ada sesuatu yang sedang bergerak.
Dalam masa kurang dua minggu, kesan daripada pelan tindakan yang disusun rapi oleh Tuan Azhar mula memberi tempias. Pelajar-pelajar yang selama ini bebas menjual makanan dalam kelas mula diajak ke sesi mentor-mentee selepas waktu sekolah.
Mereka yang pernah memaki guru, kini diajak menyertai program Kepimpinan Dalam Diri yang diadakan setiap Khamis. Bahkan kawasan tandas yang menjadi ‘port’ pelajar ponteng kini dipantau dua kali sehari dengan sistem bergilir dalam kalangan guru.
Tiga orang cikgu disiplin yang selama ini seperti hilang punca, kini sudah mula tersenyum kembali.
Cikgu Riduan, yang selalu garang tetapi berhati lembut, kini sibuk mencatat laporan kemajuan tingkah laku pelajar yang dia jaga sendiri dalam sesi kaunseling kecil.
Cikgu Malik, yang dulunya sering mengeluh dalam mesyuarat, kini mula kembali aktif memantau kelas secara rawak, siap dengan kad disiplin mini yang dicetak oleh unit disiplin.
Cikgu Faridah, guru wanita paling lama dalam pasukan disiplin, kembali memegang rotan rotan pendeknya bukan untuk memukul, tetapi lebih sebagai simbol peringatan. Tapi yang penting, aura disiplin sudah kembali berdenyut dalam sekolah itu.
Dan di tengah semua itu, Tuan Azhar hanya berdiri dan memerhati.
Tidak sesekali dia mencelah.
Tidak sesekali dia menuntut penghargaan.
Kerana dia tahu kalau dia melangkah lebih jauh, kalau dia terlalu ke depan, akan ada lagi yang menghentam. Orang luar yang masih menyimpan marah, ibu bapa yang belum tahu cerita sebenar, atau guru-guru yang belum mampu terima perubahan gaya.
Dia memilih untuk berada di belakang. Menjadi nadi yang menolak enjin sistem bergerak. Tapi bukan pemandu utama.
Satu petang selepas tamat sesi kelas pemulihan, beberapa guru masih berada di koridor tingkat atas.
Cahaya senja menembusi celah-celah tingkap, menyinari meja-meja guru yang masih bersepah dengan buku latihan dan fail.
Tuan Azhar berdiri bersandar di tepi tingkap, memegang satu buku rekod disiplin. Dari atas, dia dapat melihat pelajar-pelajar mula meninggalkan sekolah, berjalan perlahan ke pintu pagar utama.
Langkahnya tenang, fikirannya seperti di awang-awangan. Tapi dalam diam, ada beban yang tidak pernah dia lepaskan.
Dan waktu itulah, seseorang menghampiri dari belakang.
“Assalamualaikum, cikgu Azhar…”
Tuan Azhar menoleh sedikit. Seorang guru muda berwajah lembut, mengenakan jubah labuh moden dan tudung lilit sederhana. Ustazah Nur Azalea.
Guru Bahasa Arab yang baru ditempatkan tiga bulan lalu. Tak banyak bercakap, tapi sering kelihatan berhati-hati. Seorang pendengar yang baik, dan yang lebih penting… sering memerhati.
“Waalaikumussalam,” jawab Azhar sopan.
“Cikgu tak balik lagi?” soal Azalea sambil tersenyum kecil, memegang fail hijau di dada.
“Masih ada kerja sikit.”
Azalea angguk, lalu berdiri di sebelah, juga melihat ke luar jendela.
“Saya… sebenarnya dah lama nak ucap terima kasih.”
Tuan Azhar angkat kening. “Terima kasih?”
Azalea senyum. “Sebab cikgu bantu sekolah ni bangkit semula. Ramai cikgu mula nampak harapan. Dan saya… saya sangat kagum dengan cara cikgu bekerja.”
Tuan Azhar tunduk sedikit, menutup bukunya.
“Saya tak buat banyak pun. Yang penting, kita semua ada peranan.”
Azalea memandang wajah lelaki itu seketika. Wajah garang tapi tenang. Serius tapi jelas sekali ada kelembutan tersembunyi. Dan ketika ramai guru perempuan lain cuma datang menyapa dan berlalu, Azalea datang untuk kekal.
“Saya tahu cikgu banyak dipersalahkan dulu. Tapi saya… dari hari pertama saya datang ke sekolah ni, saya nampak siapa cikgu sebenarnya.”
Azhar menoleh perlahan. Ada getaran dalam suara itu. Tapi dia menahan diri.
“Cikgu Azalea… kita semua ada niat baik. Tapi kadang-kadang orang tak nampak apa dalam hati kita. Yang mereka nampak, cuma cara kita bertindak.”
Azalea mengangguk.
Tapi dia tidak berganjak.
“Saya… boleh jadi penyokong cikgu. Kalau cikgu izinkan. Saya sedia bantu.”
Kata-kata itu jelas. Bukan sekadar rakan sekerja yang mahu berkongsi tugas. Ada makna lain. Ada ruang yang cuba diisi.
Tuan Azhar diam. Tidak membalas. Tapi dia juga tidak menolak. Dia cuma menunduk, meletakkan semula bukunya atas meja.
“Terima kasih, cikgu Azalea. Saya hargai sokongan tu. Tapi sekarang saya cuma nak pastikan sekolah ni tak hilang arah.”
Azalea senyum. “Saya faham.”
Tapi sebelum dia melangkah pergi, dia sempat berkata, perlahan tapi cukup jelas untuk didengar.
“Tapi cikgu juga manusia. Cikgu perlukan tempat bersandar, bukan hanya tanggung sendiri semuanya.”
Dan dia berlalu pergi, meninggalkan Tuan Azhar berdiri termenung di tepi tingkap, memandang langit senja yang semakin menggelap.
Di rumah malam itu, Atiha sedang menyusun buku latihan anak-anak muridnya di meja kecil dalam bilik belajar. Wajahnya tenang, tapi fikirannya sesekali terganggu. Dia tahu sejak perubahan berlaku di sekolah, Azhar semakin banyak berdiam.
Makin banyak termenung.
“Abang kenapa ni? Masih fikir tentang di sekolah.” tanyanya bila Azhar masuk ke bilik dan duduk di birai katil.
“Abang masih fikir tentang sekolah, anak-anak murid.. sampai bila kita nak didik mereka dengan ketegasan sayang, abang bukan nak semua ni berlaku.”
Atiha bangkit dan duduk di sisi, mengurut perlahan lengan suaminya.
“Abang penat kan? Sekolah sekarang bukan macam dulu.”
Azhar hanya angguk perlahan. Tapi tak mahu mengeluh.
Dan akhirnya, dia berkata perlahan.
“Ada cikgu muda… nama dia Azalea. Dia mula… rapat dengan abang.”
Atiha tidak terkejut. Tapi dia berhenti mengurut.
“Dia tahu abang dah kahwin?”
Azhar geleng. “Tak. Dan abang tak nak beri harapan pun.”
Atiha senyum pahit. Tapi dia hanya menyandar di bahu suaminya.
“Kalau abang rasa abang bersedia, kita boleh beritahu sekolah… yang kita suami isteri.”
Azhar menarik nafas panjang.
“Mungkin dah tiba masanya.”
Kerana dia tahu… bukan semua sokongan itu ikhlas. Dan bukan semua senyuman itu suci. Kadangkala… hanya kejujuran yang mampu menjadi perisai terkuat sebuah ikatan.
Share this novel



