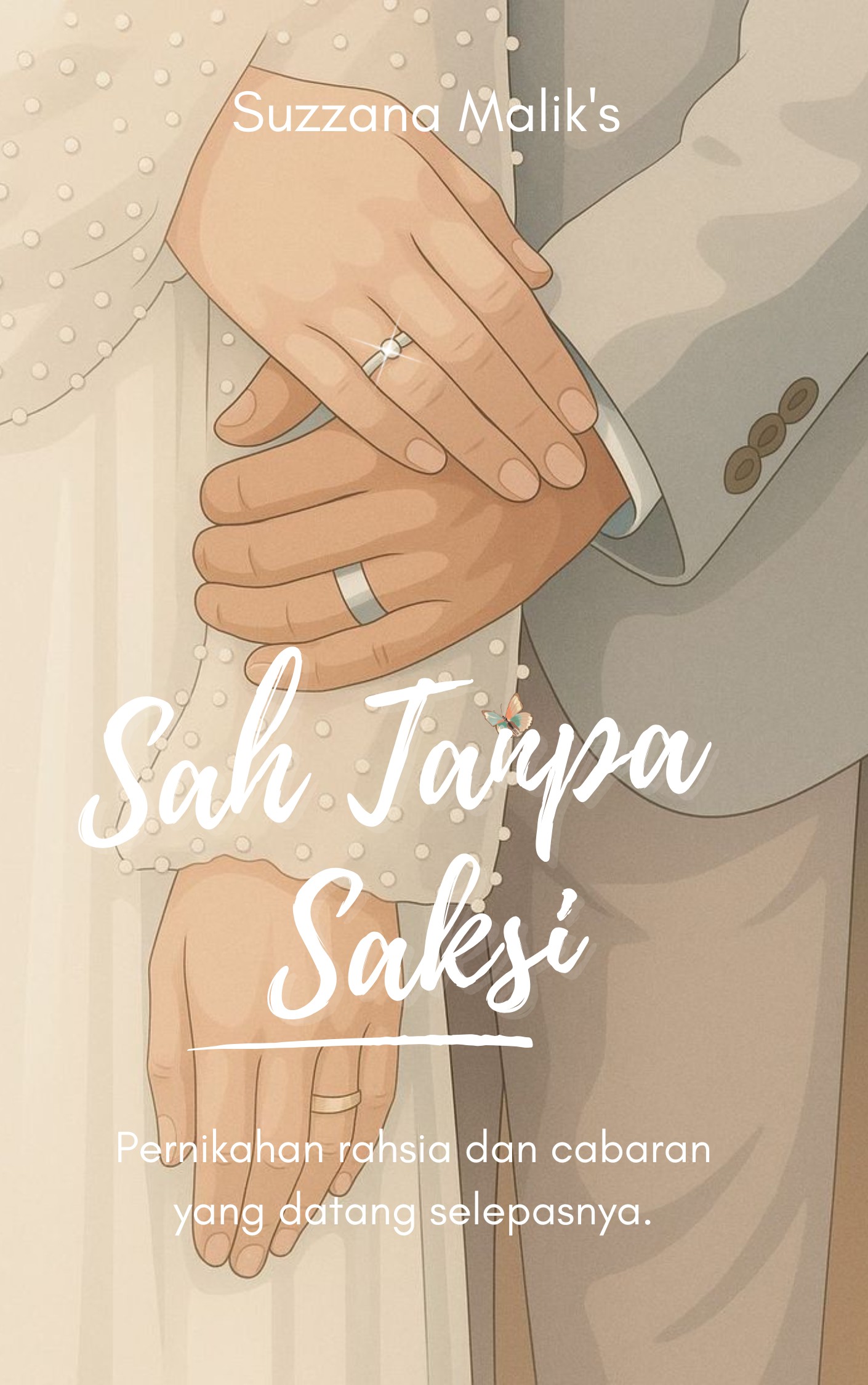
Bab: Rasa Cinta dalam Suapan Pelik
 Series
Series
 1624
1624
Pagi itu, selepas insiden katil patah yang hampir menimbulkan gegaran ‘gempa’ buatan manusia, Tuan Azhar dan Atiha akhirnya berjaya keluar dari hotel kecil yang menyimpan kenangan paling unik dalam hidup mereka. Matahari baru menyinar penuh, namun kedinginan pagi masih belum hilang sepenuhnya.
Di sepanjang jalan utama yang sunyi, deretan warung makanan berdiri dalam barisan, kebanyakannya masih belum dibuka. Namun satu warung kayu kecil di hujung lorong menarik perhatian mereka. Di depannya tergantung papan tanda dengan tulisan besar:
“อาหารฮาลาล”
(Halal Food)
Atiha mengerut dahi sambil membaca papan tanda itu dengan ragu. “Abang… betul ke ni halal?”
Azhar mengangguk. “Ya, tulisan tu maksudnya ‘makanan halal’. Ada logo kecil halal kat penjuru tu.”
Tanpa banyak soal, mereka pun duduk di salah satu meja plastik yang disusun rapi di bawah kanopi usang. Suasana warung itu sederhana, tapi cukup bersih.
Pemiliknya, seorang wanita berhijab separuh usia, menyambut mereka dengan senyum lebar walaupun bahasa Thai pekat menutupi kefasihan dalam Bahasa Inggeris.
Azhar memesan dua mangkuk bubur nasi dan satu set lauk ayam herba serta minuman panas.
Sambil menunggu, Atiha memandang sekeliling. Matanya memerhati orang lalu lalang, suasana luar negara yang asing namun damai. Tapi jauh di sudut hati, dia sudah rindu Malaysia.
Tak lama kemudian, Azhar datang membawa dua dulang. Dia menghidangkan makanan ke atas meja sambil berkata ceria.
“Sarapan istimewa pagi ni. Bukan selalu dapat makan bubur nasi Thai dengan ayam herba, sayang…”
Atiha mengangkat kening. “Ayam herba ke ni? Bau dia macam… bau ubat kampung.”
Azhar tergelak kecil. “Cuba rasa dulu sebelum komen. Kadang-kadang benda pelik tu yang sedap.”
Atiha hanya tersenyum, lalu mengambil sudu dan menyuap sedikit bubur kosong itu. Rasa nasi yang lembut dan hangat menyentuh lidahnya. Tidaklah seperti bubur ayam McD kegemarannya, tapi cukup untuk mengisi perut.
Kemudian matanya jatuh ke lauk ayam yang disajikan bersama. Ayam itu berwarna gelap pekat, hampir kehitaman, disalut kuah likat dengan bau rempah yang asing.
Dia menyenduk sedikit dan mencicip hujungnya dengan hujung lidah.
“Hmm…”
“Sedap?” soal Azhar yang sudah dua kali menyuap bubur.
“Unik…” jawab Atiha, memilih kata diplomatik.
Azhar ketawa. “Sayang tak suka ke?”
“Tak… bukan tak suka, cuma pelik sikit. Sayang biasa makan kari atau ayam masak merah. Ni macam... ayam rebus dalam minyak cap kapak.”
Azhar tergelak besar. “Ish, jangan hina budaya masakan orang. Tu nama dia ayam betik Thai. Abang baca tadi kat menu. Herba dia bagus untuk perut.”
Atiha cuba senyum, lalu menyenduk sedikit lagi ayam herba itu dan makan dengan bubur. Kali ini dia cuba tahan reaksi wajah agar tidak kelihatan seperti sedang bertarung nyawa.
Azhar memerhati. “Sayang okay?”
“Okay…” jawab Atiha cepat, cuba meneguk air kosong untuk menelan rasa aneh yang masih melekat di lidahnya.
Namun, beberapa saat kemudian, perutnya mula berbunyi perlahan. Gelembung angin seperti mula berkumpul dalam perutnya. Atiha meletakkan sudu dan menyandar perlahan.
“Sayang okey ke?” soal Azhar, perasan perubahan pada wajah isterinya yang kini sedikit pucat.
“Sikit… mungkin sebab tak biasa makan herba kuat sangat.” Dia menekup mulut sekejap, terasa loya perlahan-lahan menjalar.
Azhar cepat-cepat hulur air kosong. “Minum ni. Perlahan-lahan.”
Tanpa banyak bicara, Atiha mencapai gelas dan meneguk hampir separuh air dalam sekali minum. Dia pejam mata sekejap, menarik nafas perlahan.
"Sorry abang… sayang cuba makan, tapi perut sayang macam… bercakap bahasa lain sekarang."
Azhar tergelak kecil, sambil mengelap mulutnya. “Tak apa, sayang. At least cuba. Kalau kat Malaysia nanti abang janji bawa pergi makan nasi lemak tiga hari berturut-turut.”
Atiha tertawa kecil. “Janji tau?”
“Janji. Dengan sambal lebih.”
Mereka ketawa perlahan.
Pemilik warung menghampiri dan bertanya jika semuanya okey. Azhar hanya mengangguk sopan dan membayar makanan yang separuh disentuh.
Setelah selesai, mereka berjalan kembali ke kawasan tempat letak kereta. Van pengganti dari syarikat sewa sudah menunggu mereka di seberang jalan. Lelaki Thailand yang memandu mengangkat tangan memberi isyarat.
Sebelum masuk ke dalam van, Azhar sempat memegang tangan Atiha dan memandang wajahnya.
“Sayang rasa okay? Nak cari tandas dulu ke?”
Atiha menggeleng.
“Dah lega sikit. Cuma lepas ni, sayang tolong pilih makanan kita ya. Sayang serah bulat-bulat kat abang sebab percaya, tapi abang percaya sangat kat ‘ayam minyak cap kapak’ tu.”
Azhar tergelak besar, sehingga menunduk menahan perut.
“Baiklah, mulai esok, tugas pemilihan makanan rasmi di bawah kuasa mutlak isteri.”
“Baru adil,” jawab Atiha sambil tersenyum manja.
Dalam van itu, mereka duduk berdua di barisan tengah, tangan tetap bergenggam seperti malam pertama mereka yang baru berlalu.
Walau pagi itu bermula dengan ayam pelik dan perut berontak, tapi cinta mereka tidak berubah. Malah semakin kuat kerana mereka belajar ketawa bersama, menyesuaikan diri dalam perbezaan, dan masih saling menyayangi walaupun di luar zon selesa.
Dan hari itu, dalam perjalanan pulang ke tanah air, mereka tahu perkahwinan bukan sekadar tentang pelamin dan gambar cantik. Tapi tentang menerima semua sisi pasangan, termasuk cita rasa makanan yang ‘luar biasa’.
Langit Malaysia kelihatan lebih bersih dan damai dari bumbung rumah teres dua tingkat itu. Selepas beberapa hari berada di Thailand, akhirnya mereka tiba ke tanah air rumah sebenar bagi dua insan yang kini bergelar suami isteri.
Tuan Azhar mengangkat bagasi dari bonet kereta dan membawa masuk ke ruang tamu. Atiha mengekori di belakang, membawa beberapa beg plastik berisi barang peribadi, cenderahati, dan jajan dari pusat beli-belah di Hatyai.
Rumah itu sederhana tetapi selesa. Dicat dalam rona krim, dengan lantai jubin kemas dan perabot kayu jati yang tersusun rapi. Rumah milik Tuan Azhar ini sering menjadi tempat singgah Atiha sebelum mereka berkahwin, kerana dia pernah mengikuti program bimbingan sekolah di bawah kendalian Azhar yang juga guru disiplin di sebuah sekolah menengah di daerah pinggir bandar.
Namun kali ini berbeza dia masuk sebagai isteri.
Atiha terus menuju ke dapur. Peti sejuk dua pintu dibuka perlahan, matanya mencari sesuatu yang sejuk. Air botol mineral yang terselit di belakang dikeluarkan dan diteguk perlahan-lahan.
“Fuhh…” lega. Walaupun sudah makan dan minum dalam perjalanan pulang tadi, tekaknya masih terasa kering.
Mungkin kerana cuaca Malaysia yang lebih lembap dan panas berbanding udara sejuk Thailand.
“Sayang, abang naik kejap ya!” suara Tuan Azhar kedengaran dari arah tangga.
“Baik, abang,” sahut Atiha sambil meletakkan botol di atas meja.
Perutnya pula tiba-tiba memberi isyarat serius. Gelembung udara dalam ususnya mula berbunyi seperti konsert kecil.
“Oh no…” Dia menoleh kiri kanan, kemudian terus bergegas masuk ke bilik air yang terletak tidak jauh dari dapur.
Langkahnya laju seperti sedang mengejar masa depan. Muka sudah merah menahan segala rasa yang mendesak keluar.
Sementara itu, di tingkat atas, Tuan Azhar sudah masuk ke bilik utama. Dia menolak daun pintu kayu dan meletakkan bagasi di sisi almari pakaian.
Ruang bilik itu tenang, katil bersaiz king tersusun rapi dengan cadar warna kelabu lembut. Langsir tebal tersidai menutupi sinar matahari, dan bau sabun dari cadar bersih mencipta rasa selesa dalam ruang itu.
Azhar menarik nafas panjang, memerhati sekeliling sebelum melangkah ke sisi katil. Tangannya perlahan-lahan menyentuh bingkai kayu katil.
Matanya merenung permukaan kayu yang kukuh itu.
“Harap-harap yang ni tak patah…” bisiknya sambil menggeleng kepala, senyum kecil terbit di hujung bibir.
Tiba-tiba dia tergelak perlahan.
“Macam mana lah boleh patah malam tu… padahal bukan aku ni besar badak pun. Badan sado sikit je,” katanya, separuh berbisik, separuh memperlekeh diri sendiri sambil menepuk dada dengan bangga main-main.
Dia membuka bagasi dan mengeluarkan beberapa pakaian, lalu menyusunnya ke dalam laci almari. Ada juga beberapa bungkusan coklat dan cenderamata kecil yang mereka beli di sana. Satu bungkusan kecil bertulis “For My Wife” diambil perlahan dan diletakkan di atas meja sisi katil.
Dia tersenyum, membayangkan wajah Atiha bila melihatnya nanti.
Di bawah, Atiha akhirnya keluar dari bilik air dengan muka lega tetapi malu sendiri. Dia menyandar sekejap di dinding dapur.
"Takkan baru sehari jadi isteri dah masuk tandas berkali-kali," gumamnya perlahan, mengetap bibir.
Dia membuka pintu peti sejuk sekali lagi, kali ini mencari yogurt atau apa saja yang boleh menenangkan perutnya.
Tiada.
“Hmm… makan roti Gardenia pun jadilah.”
Dia mencapai sebungkus roti dan membawa dua keping ke ruang tamu. Duduk di sofa, dia mengunyah perlahan sambil memandang sekeliling. Rumah itu masih sama tapi semuanya terasa baru.
Setiap sudut kini membawa makna berbeza. Kerusi ini akan jadi tempat dia dan suaminya berbual, ruang makan ini akan jadi tempat dia menyenduk nasi untuk Azhar, dan dapur itu akan jadi tempat dia belajar memasak lauk kegemaran lelaki itu.
Lamunannya terhenti apabila bunyi tapak kaki kedengaran menuruni anak tangga.
Tuan Azhar muncul, mengenakan kemeja lengan pendek berwarna biru laut dan seluar kain santai. Rambutnya sudah disikat rapi, kelihatan segar.
“Sayang okey ke ni...?” soalnya sambil duduk di sisi Atiha.
Atiha menoleh dengan senyum. “Okey… perut pun dah reda sikit. Makanan semalam tu… sangat menguji sistem penghadaman.”
Azhar tergelak. “Abang dah agak dah. Tapi abang hargai sayang cuba juga makan. Walaupun rupa lauk tu macam daging rendang ditinggal lima hari.”
Atiha ketawa. “Nasib baik ada air kosong. Kalau tak, sayang dah longlai atas jalan.”
Azhar menyandarkan tubuh ke sofa. Tangannya meraih tangan isterinya perlahan, menggenggam jemari halus itu erat.
“Sekarang kita dah balik, rutin kita pun bermula. Sayang dah bersedia jadi cik isteri kepada cikgu garang?”
Atiha menjeling manja. “Garang tak apa… janji penyayang. Tapi sayang pun cikgu juga dulu, jadi boleh lawan balik.”
Azhar tergelak besar. “Wah, cabar abang nampaknya.”
“Tapi abang…” sambung Atiha perlahan.
“Hm?” Azhar berpaling, memandang wajah isterinya yang kini berubah serius.
“Sayang takut sikit. Nanti kalau orang tahu kita kahwin senyap-senyap kat Thailand… terutama keluarga…”
Azhar menghela nafas. “Abang tahu. Tapi abang akan uruskan. Kita buat satu-satu. Esok, abang akan bawa sayang jumpa mak abang dulu. Kita cakap elok-elok. Kalau ada yang marah… abang yang tanggung. Sayang jangan risau.”
Atiha mengangguk perlahan.
Wajahnya sedikit redup, tapi senyuman di hujung bibir menandakan dia percaya. Sepenuh hati.
“Abang…” panggilnya perlahan, kemudian menyandarkan kepala ke bahu Azhar.
“Ya?”
“Terima kasih sebab pilih sayang.”
Azhar diam, bibirnya mengukir senyum kecil. Dia mencium dahi isterinya lama.
“Terima kasih sebab sudi jadi isteri abang.”
Dan dalam tenang pagi itu, dengan rumah sederhana dua tingkat yang kini menjadi saksi permulaan hidup baru mereka, dua hati itu berjanji dalam diam—bahawa apa pun yang datang selepas ini, selagi mereka saling percaya, mereka mampu hadapinya bersama.
Share this novel



