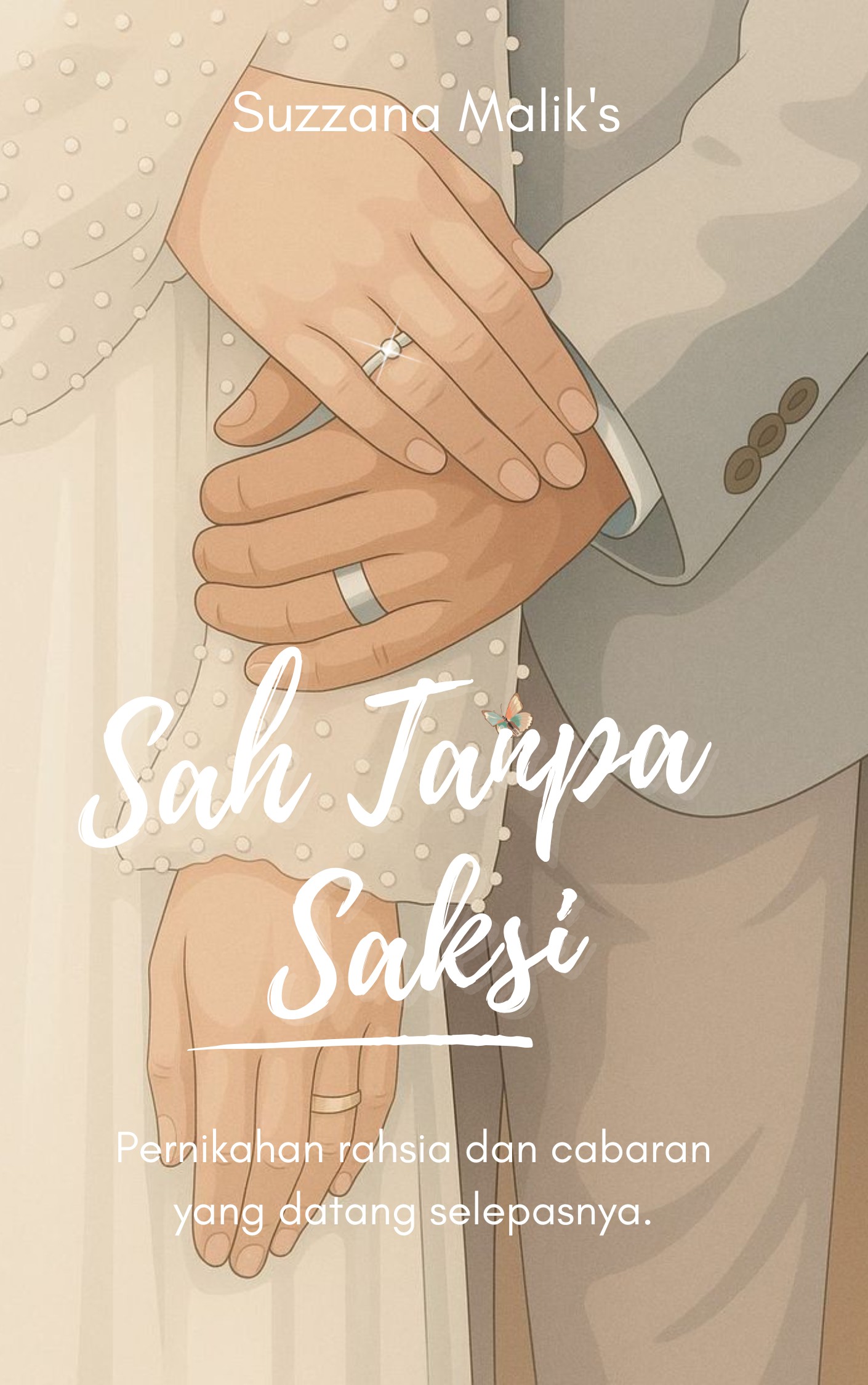
Bab: Isteri Pilihan Siapa
 Series
Series
 1624
1624
Rumah banglo setingkat milik keluarga Tuan Azhar di pinggir bandar Ipoh itu kelihatan tenang dari luar. Namun, dari dalam dindingnya, bergema suara dan desah nafas yang tidak tenteram. Langkah-langkah pertama Atiha menjejak kaki ke ruang tamu terasa berat. Seperti setiap inci lantai itu menyimpan rahsia dan keberatan dari masa lampau.
Mak Jah, ibu kepada Azhar, sedang duduk di sofa utama bersama suaminya, Pak Cik Rahim. Seorang wanita yang agak berusia tapi berwajah tegas, matanya meneliti penampilan Atiha dari kepala ke kaki.
“Assalamualaikum, mak… ayah,” sapa Azhar perlahan, membawa Atiha duduk di sebelahnya.
“Waalaikumussalam,” balas Pak Rahim. Tapi wajahnya serius, tidak seperti kali terakhir Azhar pulang ke sini iaitu sebelum segalanya berubah.
Mak Jah tidak menjawab. Hanya mengeluh perlahan sambil memandang ke arah dapur. Di sana, seorang wanita muda sedang membancuh air tinggi lampai, berjilbab satin ungu, wajahnya halus dan tenang.
Azhar menoleh ke arah wanita itu.
“Azalea?” gumam Atiha dalam hati.
Bukan.
Itu Wanis tunang Azhar yang telah dijodohkan oleh keluarga beberapa bulan lalu.
“Apa mak nak cakap… kami tak marah, Azhar,” kata Mak Jah akhirnya, “Tapi mak kecewa.”
Azhar menggenggam tangan Atiha yang terasa mula bergetar.
“Mak…”
“Mak dengan ayah dah bagi persetujuan. Wanis tu anak kawan ayah. Dah bertunang pun kamu dua tu. Takkan Azhar nak malukan keluarga ni macam kamu dengan Azalea dulu.?”
“Mak… Azhar tak pernah setuju dengan pertunangan tu. Semua tu keputusan mak dan ayah. Azhar dah cakap elok-elok dari awal lagi yang Azhar belum bersedia.”
“Belum bersedia bukan alasan untuk lari kahwin ke Thailand, Azhar,” potong Pak Rahim tegas.
Atiha menundukkan wajahnya, jari-jemarinya menggenggam hujung kain kurungnya sendiri. Dia tidak mampu bersuara. Bukan kerana dia tidak tahu, tetapi kerana dia tahu segalanya. Dan dia bersetuju demi cinta. Demi Azhar.
“Cik… Atiha…” Wanis menghampiri dari arah dapur dengan segelas air suam di tangannya. Dia menyuakan ke arah Atiha.
“Minum sikit.”
“Terima kasih…” Atiha menyambut dengan tangan sedikit terketar.
Azhar bangun dan berdiri tegak di tengah ruang tamu.
“Mak, ayah… Azhar minta maaf. Azhar tahu Azhar salah sebab tak beritahu awal perkara ni. Tapi Azhar serius dengan Atiha. Kami dah bernikah secara sah di i Thailand, betul, tapi semuanya mengikut saluran yang betul. Saksi ada. Dokumen lengkap.”
Mak Jah mendengus. “Sah di atas kertas. Tapi tak sah di mata keluarga.”
“Azhar bukan budak kecil lagi, mak. Azhar boleh pilih sendiri siapa yang Azhar nak hidup sampai akhir hayat.”
“Dan keluarga tak penting? Kami ni siapa?”
“Mak tetap mak. Ayah tetap ayah. Tapi jangan hukum Atiha, dia tak salah dia kahwin dengan Azhar sebab Azhar yang minta. Azhar yang kejar dia, bukan dia.”
Semua mata tertumpu pada Atiha. Dia masih menunduk. Air matanya bergenang tapi belum menitis.
Wanis memandang Azhar. Suaranya tenang. “Saya tahu ini keputusan awak, Azhar. Tapi awak pernah janji untuk beri ruang kepada keluarga buat keputusan. Dan saya pegang janji tu.”
Azhar menghela nafas. “Maaf, Wanis. Saya mungkir.”
Mak Jah berdiri. “Sudah. Kalau Azhar dah pilih jalan sendiri, ikutlah. Tapi jangan harap mak nak raikan perkahwinan ni.”
“Mak..”
“Tak. Mak tak mahu tengok muka menantu yang mak tak pilih. Pergilah. Tapi ingat, keluarga ni takkan terbuka semudah itu lagi.”
Azhar menarik nafas panjang. Dia berpaling pada Atiha. Perlahan, dia menghulur tangan kepada isterinya.
“Jom, sayang. Kita balik.”
Atiha bangun perlahan. Namun sebelum sempat dia melangkah keluar, dia menoleh pada Mak Jah.
“Mak…” suara itu perlahan, nyaris tidak kedengaran.
“Saya tahu saya bukan pilihan mak. Tapi saya cintakan anak mak. Dan saya kahwin dengan dia bukan untuk rampas, tapi untuk lengkapkan.”
Mak Jah tidak menjawab. Wajahnya keras.
Pak Rahim menghela nafas. “Kita tengok sejauh mana kamu bertahan.”
Dalam kereta, sunyi. Hanya bunyi deruan enjin dan jalan yang panjang.
“Sayang tak apa-apa?” Azhar menoleh.
Atiha tersenyum pahit. “Sayang tak kisah kalau tak disambut dengan bunga, tapi bila dilayan macam sampah, itu lain rasa dia.”
Azhar berhenti di tepi jalan, mematikan enjin.
“Sayang… abang tahu abang tarik sayang dalam keadaan yang abang sendiri tak jangka. Tapi abang akan betulkan semua ni. Abang akan buat mak dan ayah terima sayang.”
Atiha hanya mengangguk. Air mata yang ditahan tadi, akhirnya mengalir tanpa suara.
Hari minggu itu bermula dengan ceria. Atiha bangun awal pagi, menyingsing lengan baju, mengikat rambut, dan menyarung apron pemberian Tuan Azhar sewaktu mereka mula berpindah masuk ke rumah teres dua tingkat itu. Di dapur, bunyi sudip berlaga dengan periuk mengisi ruang yang masih dingin.
Dia mahu sediakan yang terbaik hari ini bukan untuk Azhar sahaja, tapi untuk mak dan ayah mertua yang katanya akan datang bertamu.
Sambal udang petai disiapkan dengan penuh kasih. Ikan tenggiri dimasak dengan lemak cili api pekat.
Kari kepala ikan merah dimasak perlahan supaya isinya lembut dan aromanya meresap ke seluruh rumah. Atiha juga sempat menghidang pencuci mulut agar-agar pandan dan serawa durian, kesukaan suaminya.
Di atas meja makan, segalanya disusun rapi. Pinggan dan cawan kaca yang hanya digunakan untuk tetamu penting, kini sudah tersusun.
Ruang tamu disapu bersih, bantal disusun semula. Jam di dinding menunjukkan hampir 11.30 pagi.
Atiha naik ke bilik, mandi dan memilih baju kurung yang lembut warnanya, tidak terlalu menonjol tetapi cukup manis untuk menyambut keluarga suaminya.
Dia menyembur sedikit haruman yang pernah Azhar puji dahulu katanya, bau itu menenangkan.
Jam berdetik laju. Pukul 12 tengah hari, dia sudah berdiri di depan pintu. Matanya menyorot ke arah pagar. Harapan dan debaran memenuhi dada.
Hari ini hari penting hari dia akan cuba diterima sepenuhnya oleh keluarga suaminya.
Akhirnya kereta Azhar masuk ke pekarangan rumah. Atiha tersenyum girang, langkahnya laju meluru ke arah kereta. Tangannya segera membuka pintu penumpang belakang.
Kosong.
Dia beralih ke pintu hadapan. Juga kosong.
Azhar keluar dari tempat pemandu, wajahnya berat.
"Abang… mak ayah ada, kan?" Atiha masih bertanya dengan nada penuh harap, meskipun dia sudah tahu jawapannya dari kekosongan tempat duduk.
Azhar menunduk. "Mereka tak datang, sayang."
Rona ceria di wajah Atiha seperti diragut sekelip mata. Dia hanya mampu mengangguk perlahan. Wajah yang tadi bersinar kini perlahan-lahan diselubungi kelam. Namun, dia tidak mahu membiarkan kekecewaannya terlihat.
Dia memegang tangan Azhar dan menarik suaminya masuk ke dalam rumah. Senyum dipaksa agar tetap manis.
“Abang mesti dah lapar, kan? Pagi tadi abang cuma sarapan roti je.” Dia cepat-cepat ke dapur, menyenduk nasi ke dalam pinggan.
Azhar duduk di kerusi makan, tidak bersuara. Dia tahu isterinya sedang cuba mengawal diri.
“Abang dah makan tadi. Mak… suruh abang makan di rumah,” ujar Azhar perlahan.
Ktak.
Sudip jatuh. Tangan Atiha menggigil. Tapi dia segera membetulkan nada.
“Oh ya? Haha… tak apalah…” senyuman palsu tetap terukir di bibir.
“Sayang… maafkan abang. Abang dah cuba pujuk mereka… tapi mak masih tak bersedia.”
“Eh, tak apa abang. Yang penting abang dah kenyang,” balasnya.
Kemudian dia bangun, mengambil dulang hidangan yang baru sahaja disusun tadi. Dengan tenang, satu persatu lauk dimasukkan ke dalam tong sampah.
Sambal udang petai yang masih berasap… tenggiri masak lemak… kari kepala ikan merah yang dimasak dengan penuh hati… semuanya lenyap dalam perut tong sampah bersama harapan dan cinta yang dia laburkan hari itu.
“Sayang!” Tuan Azhar bangkit, cemas.
“Makanan ni dah lama terhidang, abang. Takut sakit perut.”
“Tapi kita boleh panaskan balik. Abang nak makan…”
“Tak apa… nanti sayang masak lain.” Dia menyapu meja makan yang tidak sempat disentuh sesiapa.
Tangannya laju, seolah-olah mahu menghapuskan jejak-jejak kekecewaan di permukaan meja itu. Perutnya yang berkeroncong dibiarkan. Dia tidak sanggup makan dari makanan yang dibuang kasih.
Azhar mendekat, cuba menyentuh bahu isterinya.
“Sayang, abang tahu sayang sedih. Tapi abang akan betulkan semua ni. Bagi abang masa.”
Atiha menoleh, tersenyum seperti tiada apa yang patah di dalam hatinya.
“Sayang tak sedih pun. Dah biasa macam ni. Lagipun, sayang bukan siapa-siapa… orang yang abang kahwin senyap-senyap.”
Azhar menarik nafas panjang. “Sayang adalah isteri abang. Satu-satunya.”
“Tapi bukan pilihan mak dan ayah abang.”
“Mereka akan terima, lambat atau cepat. Percayalah.”
Atiha hanya mengangguk, tapi pandangannya tetap kosong.
Petang itu, selepas membersihkan dapur, dia duduk di beranda rumah. Matanya memandang langit yang semakin merendah. Di tangan, sehelai kain batik digulung rapi. Langit yang kelabu seperti hatinya yang tidak menemui cahaya hari itu.
Azhar menghampiri perlahan, membawa secawan teh.
“Abang ada buat teh. Sayang belum makan sejak pagi…”
Atiha menyambut cawan itu. Dia meneguk perlahan. “Terima kasih…”
“Kalau mak tak nak datang, abang nak bawa sayang jumpa mak lagi minggu depan. Kali ni kita pergi sama-sama.”
Atiha meletakkan cawan di meja kecil. “Kalau mereka tak buka pintu, abang jangan marah.”
Azhar tersenyum tawar. “Abang akan ketuk sampai terbuka.”
Share this novel



