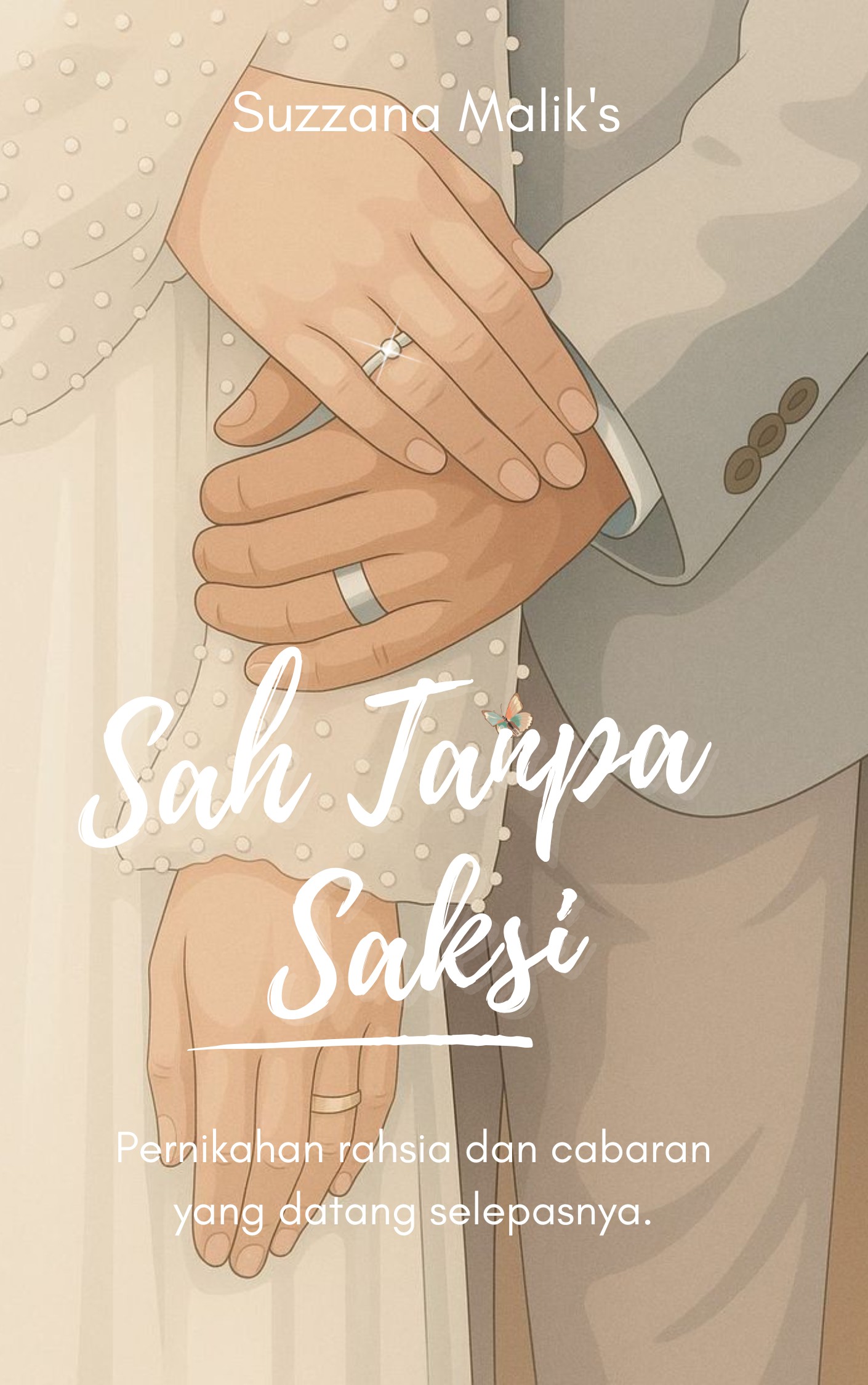
Bab: Rahsia yang Menghimpit
 Series
Series
 1624
1624
Petang itu hujan turun renyai-renyai. Langit muram seperti mengerti hati yang mula diliputi mendung. Angin sejuk menembusi langsir nipis ruang tamu rumah dua tingkat milik Tuan Azhar, membawa bersama resah yang tidak mampu dibendung oleh sepasang suami isteri muda yang baru saja pulang dari kerja.
Di atas sofa, Atiha duduk diam sambil memegang telefon bimbitnya. Wajahnya bersahaja tapi matanya merenung skrin seperti sedang menelan racun perlahan-lahan.
WhatsApp Group: Cikgu-Cikgu Wanita SMK Tunas Bakti
“Saya dah tak tahan tengok gaya Tuan Azhar marah budak tadi. Macam askar tengah marah banduan.”
“Kita ni cikgu, bukan pengadil gusti. Suara tu memang patut dilarang.”
“Anak murid kita bukan semua datang dari keluarga baik-baik. Ada yang trauma. Ada yang tak stabil emosi. Dia marah macam tu, makin teruk jadinya.”
“Saya dah dapat khabar, ibu bapa nak bawa isu ni ke mesyuarat PIBG minggu depan. Siap kata Tuan Azhar tak layak jadi guru disiplin.”
Atiha hanya membaca, tidak menjawab.
Bahu kirinya terasa berat, tetapi bukan kerana beg kerja. Berat yang ini datang dari dalam—hati yang bergolak antara naluri sebagai isteri dan peranan sebagai seorang guru. Dia tahu Tuan Azhar bukan berniat menghukum membabi buta. Tapi dunia di luar tak akan faham lelaki itu sebagaimana dia faham.
Dia tidak menangis.
Tapi diamnya lebih perit daripada tangis.
Bunyi pintu bilik air dibuka mengejutkan Atiha daripada lamunannya. Bunyi langkah kaki lelaki dewasa yang sedang menyarung seluar trek menandakan Tuan Azhar baru selesai mandi.
“Sayang… masak apa? Abang lapar.” Suara garau itu menusuk ke cuping telinganya, lembut tapi jelas.
Wajahnya muncul dari balik pintu bilik, rambutnya masih basah, kemeja-T putih sederhana membaluti tubuh yang sasa. Cukup untuk membuat Atiha ingin hilang dalam pelukan itu seketika sekurang-kurangnya untuk melarikan diri dari beban dunia luar.
Atiha bangkit dan segera memeluk tubuh suaminya dari depan, tanpa sebarang kata.
Tuan Azhar sedikit tersentak.
Bukan kerana pelukan itu asing.
Tapi kerana ada sesuatu dalam pelukan itu. Ia bukan manja. Bukan rayu. Tapi berat. Dan sunyi.
Dia membalas pelukan itu perlahan, membelai belakang tubuh isterinya.
“Sayang okay tak?” soalnya perlahan.
Atiha tidak menjawab. Cuma menyandarkan dagu di dada suaminya dan menghela nafas panjang.
“Sayang masak sambal udang petai… kegemaran abang,” katanya akhirnya, dalam nada yang hampir tak kedengaran.
Azhar senyum perlahan dan angguk.
“Terima kasih sayang… abang turun makan kejap lagi ya.”
Atiha mengangguk juga, lalu melepaskan pelukannya.
Senyuman manis diukir di wajahnya, cukup untuk menutup luka di hati. “Sayang dah makan tadi… masa abang mandi.”
Selesai kata, dia berpaling dan melangkah masuk ke bilik air. Telefon bimbitnya digenggam erat. Tidak dibiar di atas meja, tidak diletak di ruang tamu. Seolah-olah ada yang ingin disorok.
Azhar menoleh, memerhati sehingga bayang isterinya hilang di sebalik pintu bilik air yang ditutup perlahan.
Ada yang tak kena.
Di dapur, Tuan Azhar duduk diam di kerusi. Pinggan nasi di depannya berisi sambal udang petai yang sangat dia gemari udangnya segar, petainya dibelah dua, dan sambalnya merah menyala. Tapi lidahnya seperti hilang rasa. Selera tiada. Setiap suapan hambar.
Dia tahu isterinya sedang menyembunyikan sesuatu.
Mungkin bukan rahsia besar. Tapi cukup untuk membuat hati seorang suami terusik. Dia bukan tak biasa menjadi sasaran kata-kata kasar. Sebagai guru disiplin, dia pernah diludah, pernah diugut oleh pelajar samseng, malah pernah disiasat oleh ibu bapa yang tidak mahu anak mereka ditegur.
Tapi… kali ini berbeza.
Kerana yang mendiamkan diri, adalah isterinya sendiri.
Bukan salah Atiha. Dia tahu. Atiha tersepit. Atiha bukan boleh terus menjawab di dalam grup WhatsApp dan berkata.
“Itu suami saya! Jangan sentuh dia!” kerana tiada siapa pun tahu hubungan mereka sah sebagai suami isteri. Mereka menyimpan rahsia itu atas sebab peribadi dan profesional.
Namun semakin lama mereka berdiam, semakin banyak luka yang mungkin mengalir dalam diam.
Selepas hampir lima belas minit, Atiha keluar dari bilik air. Rambutnya masih basah, kini mengenakan t-shirt longgar dan seluar tidur. Dia tersenyum melihat suaminya yang masih belum habis makan.
“Tak sedap ke, bang?”
Azhar menggeleng. “Sedap. Cuma… abang rasa kurang satu bahan.”
Atiha mengerutkan dahi. “Apa dia?”
Azhar letakkan sudu, memandang isterinya tepat.
“Jawapan dari hati isteri abang.”
Atiha terpaku. Dia tidak menduga soalan itu datang seawal ini. Tapi dia juga tahu, Azhar bukan jenis yang suka memendam lama.
Dia duduk di kerusi bertentangan.
Tunduk.
“Mereka... kecam abang dalam group cikgu,” suaranya perlahan, hampir berbisik.
Azhar hanya diam.
“Mereka kata abang kasar sangat. Tak sesuai jadi cikgu disiplin. Dan… ada yang nak bawa ke mesyuarat dengan guru besar.”
Azhar masih tenang. Tapi dia tidak balas.
Atiha menyambung, “Sayang tak tahu nak buat apa… sayang tak boleh bela abang… sebab… tiada siapa tahu kita suami isteri.”
Azhar mengangguk perlahan. “Abang faham. Dan abang tak salahkan sayang.”
Atiha menggenggam jari sendiri. “Tapi hati sayang berat… sangat berat. Rasa macam gagal jaga abang sebagai isteri.”
Azhar menghulurkan tangan, menggenggam jari isterinya.
“Sayang, tugas abang bukan untuk semua orang suka. Tapi tugas sayang… hanya untuk jadi tempat abang kembali, bila semua orang tak lagi berpihak.”
Atiha mengangkat wajah. Matanya berair, tapi senyum kecil terbentuk juga.
“Abang tak minta sayang bela abang… abang cuma minta sayang genggam tangan abang macam sekarang.”
Dan mereka duduk begitu, diam tapi penuh pengertian. Di luar, hujan semakin deras. Tapi di dalam hati mereka, ada cahaya yang masih menyala walau diuji cemuhan, walau dilanda tohmahan.
Kerana cinta, walau tersembunyi, tetap menjadi pelindung paling kuat dalam diam.
Pagi itu langit cerah, tetapi hati Atiha gelap seperti mendung yang belum jatuh hujannya.
Suasana di bilik mesyuarat besar sekolah itu luar biasa senyap. Tidak seperti mesyuarat biasa yang selalunya bermula dengan bisikan kecil, sapaan sopan dan sedikit ketawa halus. Hari ini, semua duduk diam, bagaikan sedang menunggu hukuman dijatuhkan.
Di tengah bilik itu, meja bulat besar dikelilingi kerusi berwarna biru tua. Guru-guru pelbagai jabatan duduk mengikut pangkat dan peranan masing-masing.
Bahkan cikgu-cikgu prasekolah dan taska pun dipanggil hadir, menunjukkan bahawa isu kali ini bukan kecil. Ia sudah menjadi hal sekolah secara menyeluruh.
Cikgu Atiha Najwa duduk di hujung kanan meja, bahu sedikit rendah, wajah tenang tapi mata... bergetar.
Ada degupan halus di bawah matanya. Otot halus itu tidak dapat dikawal, dan itu petanda paling jelas hati Atiha sedang bersilat hebat.
Di seberangnya, Tuan Azhar, suaminya yang sah, duduk tenang di kerusi. Tangan bersilang di atas meja. Wajahnya seperti biasa serius dan tak tergugat.
Tapi Atiha tahu... diam Azhar bukan tanda dia tak peduli. Ia tanda dia sudah sedia menanggung segala tohmahan, dan mungkin... kehilangan jawatan.
Guru Besar, Puan Rosnah, membuka mesyuarat dengan suara yang berlapik namun tegas.
“Assalamualaikum dan terima kasih semua kerana hadir dalam masa singkat. Saya tahu ini tidak dirancang, tapi saya percaya kita semua ada satu matlamat yang sama memastikan suasana sekolah kekal kondusif dan aman.”
Beberapa guru mengangguk. Yang lain masih diam.
“Pagi tadi saya menerima aduan rasmi bertulis daripada wakil ibu bapa pelajar Tingkatan 2. Beberapa isi utama telah dibangkitkan. Antaranya... kaedah teguran yang dianggap terlalu keras, cara pengendalian disiplin yang menakutkan pelajar, dan ada juga laporan menyatakan ada pelajar yang trauma selepas perhimpunan minggu lepas.”
Suasana menjadi tegang.
Mata Atiha terpejam seketika. Dadanya rasa sakit, seperti ditumbuk dari dalam. Tangan digenggam di bawah meja, cuba menghilangkan getaran. Tapi perasaan bersalah dan takut bercampur aduk.
Namun Azhar masih tenang. Matanya memandang tepat ke arah Guru Besar.
“Cikgu Azhar,” sambung Puan Rosnah.
“Saya tahu cikgu sudah lama berkhidmat dan disiplin adalah bidang utama cikgu. Tapi hari ini, saya perlu beri peluang untuk semua pihak bersuara. Kita mahu adil kepada semua.”
Puan Salmah angkat tangan perlahan.
“Saya tak menafikan niat cikgu Azhar baik. Tapi saya sendiri dengar budak perempuan menangis hari itu. Mereka kata cikgu Azhar garang sangat. Mereka rasa dihina di khalayak.”
“Ya,” celah Cikgu Kamariah.
“Murid kita bukan semua dari latar belakang stabil. Ada yang mudah panik. Kita tak nak mereka ponteng sekolah sebab takut datang.”
Satu demi satu suara muncul. Ada yang membela, ada yang membidas. Azhar hanya duduk tenang, kadang-kadang mencatat sesuatu di dalam fail. Tidak sekalipun dia menyampuk atau membalas. Wajahnya tidak berubah.
Tapi hati Atiha makin parah.
Dia ingin sekali bangun dan bersuara. Tapi lidahnya kelu. Dia tahu, dia tidak boleh terlalu emosional. Kalau dia kelihatan terlalu mempertahankan Azhar, akan timbul persoalan. Status mereka sebagai suami isteri belum diketahui umum.
Dan dalam dunia pendidikan, profesionalisme adalah batas yang tidak boleh dilanggar.
“Baik, sekarang kita beri laluan kepada cikgu Azhar,” kata Guru Besar setelah semua pendapat dikumpulkan.
“Sila beri penjelasan jika perlu.”
Azhar membuka fail di depannya. Dia tidak tergesa. Tidak gugup.
“Terima kasih, Puan Rosnah. Terima kasih semua. Saya tak akan panjangkan.”
Dia berdiri perlahan, menatap semua guru.
“Saya tahu saya bukan guru yang disenangi semua. Saya juga tahu pendekatan saya kasar pada mata sesetengah orang. Tapi percaya atau tidak, saya bukan marah kerana benci. Saya marah sebab saya sayang.”
Azhar menarik nafas perlahan.
“Dalam masa sebulan, kita ada rekod pelajar mencuri, merokok, mencederakan rakan, melawan guru. Saya bukan malaikat. Tapi saya tak boleh tengok sekolah ni jadi tempat hancurnya masa depan anak-anak.”
Beberapa guru tunduk. Yang lain masih menatap tajam.
“Saya tak marah mereka kerana saya nak nampak hebat. Tapi kerana saya tahu—kalau hari ni mereka tak dihentikan, esok mereka akan masuk dalam dunia jenayah sebenar.”
Dia berhenti seketika, menoleh ke arah Atiha. Pandangan mereka bertaut, dan kali ini Atiha tak alih pandang.
“Dan saya tak harap semua faham saya. Tapi saya harap... ada yang sudi bersama saya, membentuk semula anak-anak ini.”
Dia duduk semula.
Bilik mesyuarat diam.
Selepas beberapa detik yang panjang, Guru Besar bersuara.
“Terima kasih cikgu Azhar. Saya akan bawa isu ini ke pihak atasan dan kita akan bincang tindakan susulan secara tertutup. Buat masa sekarang, cikgu teruskan tugas seperti biasa.”
Semua bangun perlahan. Ada yang berbisik sesama sendiri. Ada yang berwajah tidak puas hati. Tapi mesyuarat itu berakhir tanpa sebarang keputusan drastik. Tidak ada pemecatan. Tidak ada penggantungan. Cuma amaran tersirat dan tekanan psikologi.
Di luar bilik mesyuarat, guru-guru mula bersurai. Atiha melangkah perlahan menuju ke ruang belakang sekolah. Dia perlu udara. Perlu ruang untuk bernafas.
Azhar mengejarnya perlahan.
“Sayang...” panggilnya perlahan.
Atiha berhenti. “Abang okay ke? Sayang risaukan abang tadi.”
Azhar angguk. “Abang cuma letih. Tapi... abang gembira sebab sayang tengok abang tadi. Itu cukup.”
Atiha menggenggam tangan Azhar, jauh dari pandangan orang.
“Sayang nak bagitahu dunia. Tentang kita. Tentang semuanya. Tapi sayang tak nak buat masa abang tengah diuji.”
Azhar senyum. “Bila tiba masa, kita umum. Tapi buat masa sekarang, abang cuma nak satu.”
“Apa?”
“Jangan lepaskan tangan abang… walaupun dunia tolak abang, sayang jangan pernah jadi orang pertama yang tinggalkan.”
Atiha senyum, air matanya tumpah akhirnya bukan kerana lemah, tapi kerana hatinya sudah terlalu penuh.
Rahsia yang menghimpit
Share this novel



