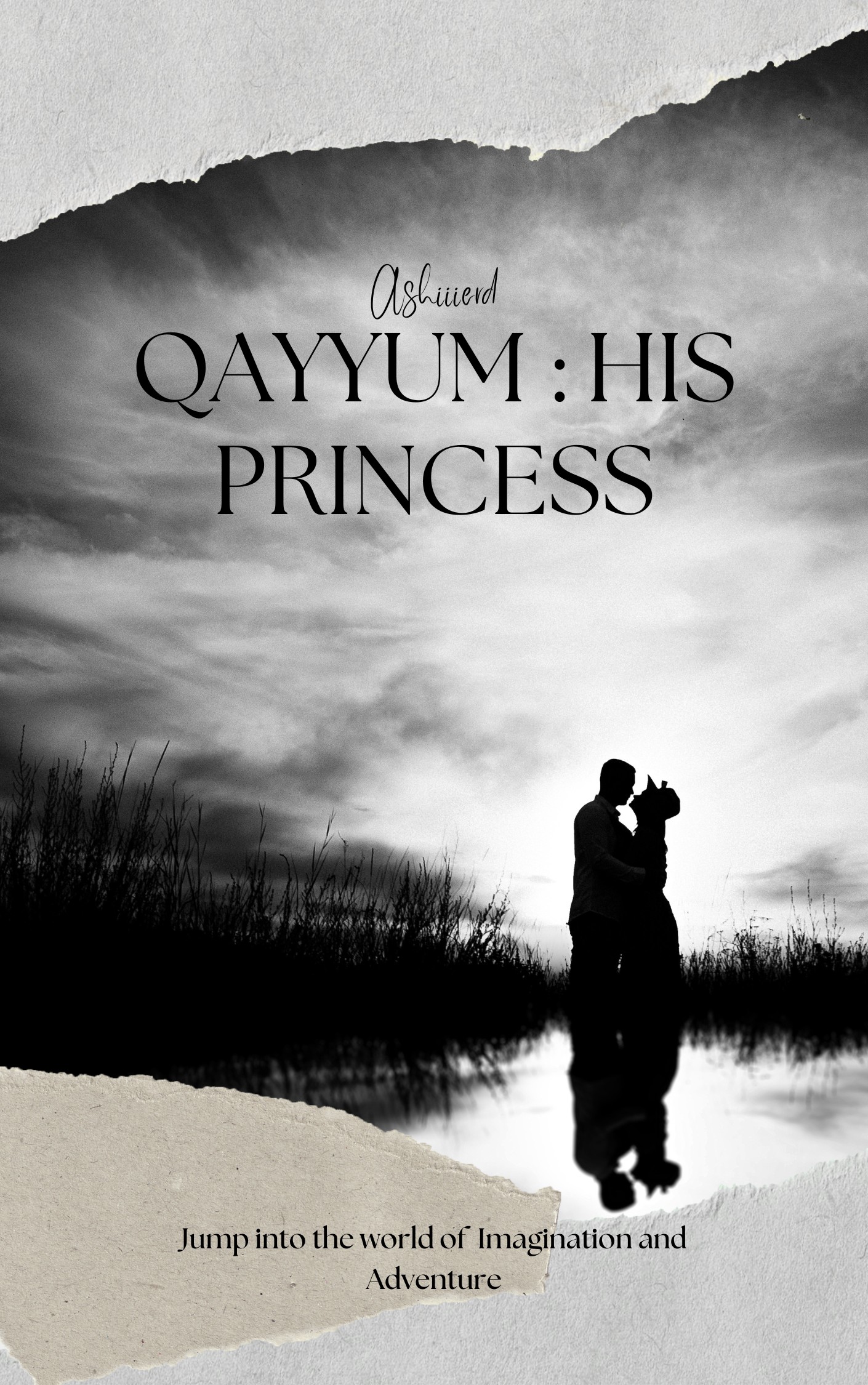
012
 Series
Series
 405
405
Pagi itu, mansion keluarga Idina— rumah yang selama ini sunyi dan bergema dengan keheningan orang-orang yang menyimpan banyak rahsia dalam diam — terasa sedikit hidup.
Bunyi deruman enjin Range Rover milik Abah hilang perlahan di selekoh hujung bukit. Tukang kebun sedang menyiram bunga mawar di tepi laluan masuk. Matahari pagi menyelinap masuk melalui langsir sheer berwarna krim emas, menari-nari di atas marmar lantai ruang tamu dua tingkat. Kristal pada chandelier memantulkan bias cahaya seperti serpihan kaca yang berkilau.
Tapi dalam kepala Idina, tetap berserabut. Emosi masih belum reda. Fikirannya masih terikat pada malam pertengkaran itu — malam Hazwan meninggikan suara pada dirinya buat pertama kali.
Dia belum mesej. Belum telefon. Langsung tiada khabar.
Tapi Idina tahu — diam dia bukan reda. Itu diam yang sedang menilai dirinya seperti Idina ini merupakan kesalahan.
Idina baru nak duduk di atas sofa putih gading bila bunyi intercom dari guard house mengejutkan lamunanku.
> “Miss Idina, Encik Qayyum is here. Dia ada bawa beberapa kotak. Patut ke saya benarkan dia masuk?”
Idina terdiam seketika. Tertanya-tanya — kenapa dia datang pagi-pagi begini?
> “Yes. Let him in. Suruh Kak Yana buka gate depan.”
Tak lama lepas itu, Idina nampak Qayyum dari balik jendela tinggi — berdiri di porch dengan beberapa kotak sederhana besar. Dia pakai kemeja biru muda, seluar khaki, dan rambut dia nampak sedikit berterbangan ditiup angin. Walaupun ringkas, penampilan dia tetap kemas.
Natural. Ikhlas. Tak pura-pura. Tak macam Hazwan.
Idina buka pintu, cuba kawal senyuman yang hampir gugur dari bibir.
"You datang pagi-pagi ni… kenapa?"
Qayyum angkat kotak sikit, lalu senyum. “I tengah kemas stor kat rumah parents I. Tiba-tiba jumpa kotak barang-barang you dari zaman UK dulu. Ada gambar polaroid kita kat Tower Bridge… Ingat lagi?”
Idina tergelak kecil. “You… still simpan semua tu?”
“Sayang nak buang.” Dia angkat bahu. “I selalu ingat — satu hari nanti, kalau you perlukan semangat semula, I akan pulangkan semua ni. Sebab itu semua bukti yang you pernah survive macam-macam.”
Idina terdiam.
Qayyum pandang sekeliling. “And… kalau boleh, I nak jumpa mak ayah you hari ni. Dulu I selalu dengar cerita pasal mereka. Tapi tak pernah berpeluang jumpa.”
Idina angguk perlahan. “Alright. Masuklah… I’ll call them.”
---
Ibu turun dari tangga, anggun seperti selalu. Dia pakai baju kurung moden rona pastel, rambut bersanggul kemas, dan wajah dia bersinar tenang.
"Salam, Qayyum,"
“Waalaikumussalam, Puan Sri.” Qayyum tunduk sopan.
Tak lama lepas tu, Abah muncul dari bilik bacaan. Masih dengan baju batik halus dan iPad di tangan. Dia jarang benar nak melibatkan diri kalau bukan hal bisnes atau keluarga. Tapi pagi ni, dia sendiri duduk.
“Doktor, ya?” soal Abah, suaranya serius tapi tak menolak.
Qayyum angguk. “Cardiologist, Tan Sri. Baru habis fellowship beberapa bulan lepas. Sekarang bertugas di hospital Ampang dan satu private wing kat Bukit Damansara.”
Idina perasan anggukan kecil dari Abah — isyarat dia menghormati.
Bila Abah diam tapi teruskan dengar, itu tandanya dia sedang menilai dengan tenang — dan dia suka apa yang dia dengar.
---
Kami semua duduk di ruang tamu utama. Qayyum buka salah satu kotak perlahan-lahan.
Dalamnya ada buku nota lama Idina yang penuh conteng waktu kuliah, hoodie lusuh berwarna kelabu yang pernah dipakai hampir setiap minggu waktu musim sejuk, dan satu folder kecil.
Qayyum hulurkan folder tu kepada Idina.
Bila Idina buka, ada beberapa gambar polaroid — Idina dan Qayyum di Tower Bridge, di kedai buku kecil dekat Notting Hill, dan satu surat — surat yang dirinya sendiri pernah tulis ketika waktu tahun akhir, tapi tak pernah dibaca semula.
Tangan Idina menggigil sedikit waktu pegang surat tu.
"Macam mana you boleh simpan semua ni…?"
“I janji dengan diri I,” suara dia perlahan, “Kalau satu hari nanti you hilang ingatan, atau hilang rasa percaya pada diri sendiri, I akan kembalikan semua benda yang buat you rasa hidup semula.”
Ibu terdiam.
Idina tengok wajah ibu — dan untuk pertama kali dalam hidup Idina, mata ibunya bergenang air. Cepat-cepat dia tunduk dan lap sudut mata dengan hujung selendang.
---
Selepas makan tengah hari — yang dimasak oleh chef rumah dan dihidang oleh pembantu — Idina bawa Qayyum ke taman belakang.
Taman yang Idina panggil tempat paling selamat dalam dunia.
Kolam kecil berbatu di tepi gazebo, diselubungi pohon lavender, orkid, dan bunga hydrangea biru lembut. Bau tanah basah dan bunga segar menyambut mereka.
Idina dan Qayyum duduk bersebelahan atas bangku batu berhias besi tempa.
“You tahu tak,” Idina mula berkata perlahan, “I dah lama sangat tak rasa… macam ni.”
“Macam mana?”
“Macam diri I sendiri.” Idina pandang jauh. “Macam tak perlu pura-pura jadi orang lain. Tak perlu jaga skrip bila bercakap.”
Qayyum diam seketika, sebelum dia pandang Idina betul-betul. “Dina, you tak perlu jadi siapa-siapa bila dengan I. Tak perlu betulkan rambut. Tak perlu tapis perkataan. Just… be.”
Idina tunduk. Air mata hampir tumpah.
“I takut…” suara Idina tenggelam dalam angin. “Kalau I lepaskan Hazwan… I hilang semuanya.”
Dia senyum kecil. Tapi bukan senyum simpati.
Senyum penuh makna.
“If the thing you’re holding is poison, why still swallow it?”
Ayat dia menikam — lembut tapi cukup kuat.
---
Sebelum Qayyum balik, Idina temankan dia ke porch.
Idina tumbuk perlahan bahu Qayyum.
“Thank you sebab datang hari ni. I really needed this.”
“I’ll always show up, Dina. No matter how broken you feel. Sebab bagi I, you worth it.”
---
Malam itu, bilik Idina sunyi. Lampu meja menyala samar. Idina duduk di meja study dan buka diari yang sudah berhabuk. Penulisan terakhir dia dalam tu — bertarikh dua tahun lepas.
Tangannya mula bergerak. Pen itu tumpah semula dakwatnya.
> “Hari ini, aku belajar — bukan semua lelaki datang untuk memiliki. Ada yang datang hanya untuk tengok kita sembuh.”
Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam masa yang sangat lama… Idina menangis.
Bukan kerana Hazwan.
Tapi kerana Idina mula rasa… yang dia layak untuk bahagia.
---
See you in Chapter 13.
Share this novel



