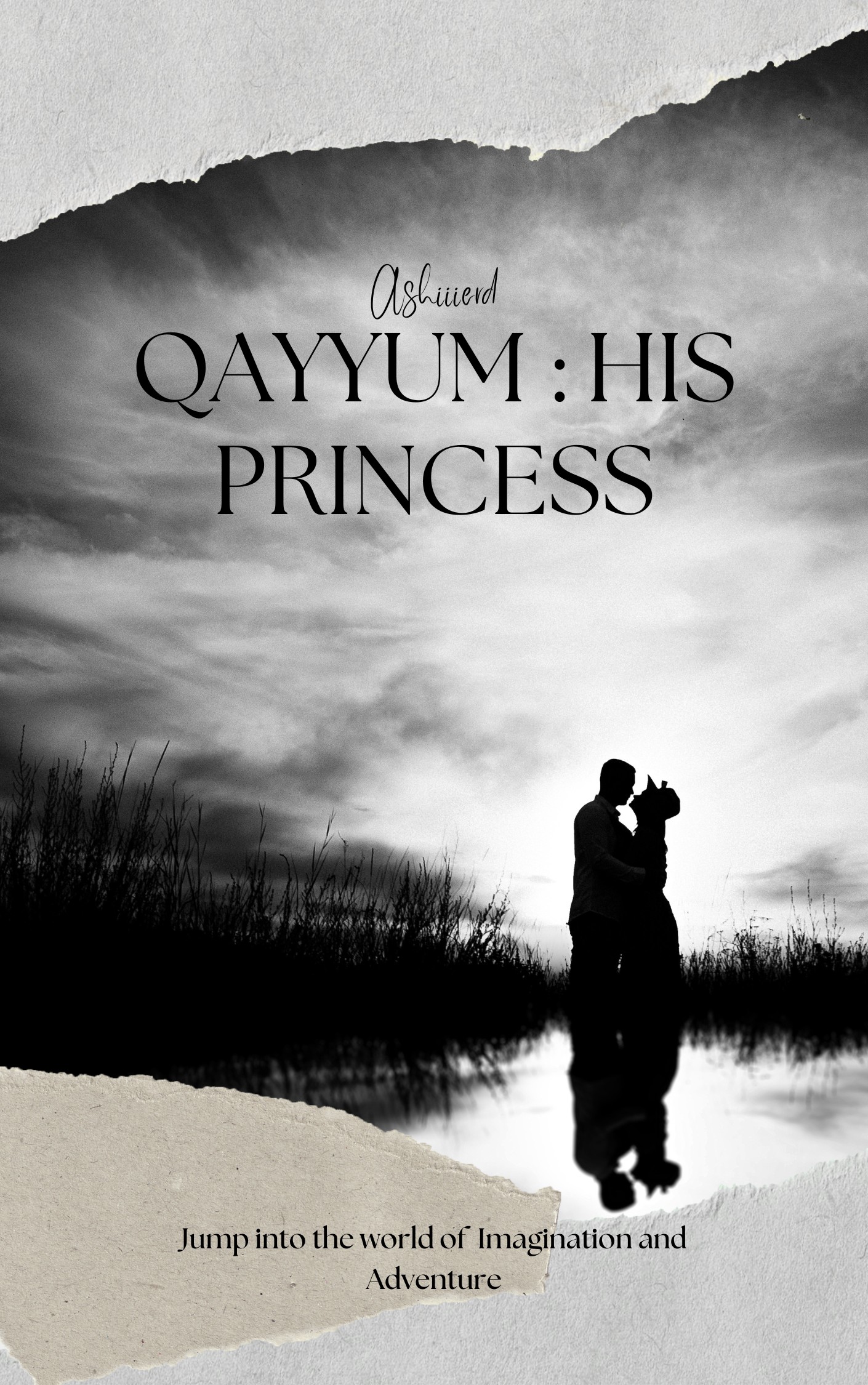
009
 Series
Series
 405
405
Pagi Sabtu yang sepatutnya sibuk dengan fitting baju nikah, jadi kosong.
Langit mendung. Hujan turun halus.
Dan dalam butik pengantin mewah di tengah Bangsar, Idina duduk diam — tubuh disandarkan ke kerusi empuk berlapis baldu, dikelilingi kain putih satin, renda Perancis, dan lace halus yang disusun penuh elegan.
Tapi kosong.
Hazwan tak datang.
Lagi. Ini bukan kali pertama tetapi rasanya sakit setiap kali.
"Maaf, Miss... fitting ni kita kena tangguh lagi ke?" soal tukang jahit, Puan Lela, dengan suara lembut — terlalu biasa dengan pengantin yang berubah fikiran di saat akhir, tapi belum biasa dengan pandangan mata yang seperti milik Idina; mata yang kelihatan patah.
Idina senyum nipis, suara tersekat di halkum.
"Ya... minta maaf. Tunang saya ada hal. Last minute."
Dia tak ingin menjelaskan lebih.
Dia dah penat beri alasan — pada orang lain dan juga pada dirinya sendiri.
Waktu Idina keluar dari butik, hujan makin lebat. Dia tidak membawa payung. Langkahnya perlahan, kasut bertumit rendah basah disirami titis hujan. Dia tidak berlari ke arah kereta. Tidak menutup kepala dengan tangan. Sekadar membiarkan hujan terus menimpa dirinya, menutup kesedihan di hati.
Biarlah basah. Biarlah sejuk. Sekurangnya, itu lebih jujur dari senyum dia selama ini.
---
Petangnya, di rumah, Idina baring di atas sofa sambil merenung siling.
Dia tak menangis. Tapi perasaannya seperti berlubang. Seperti lubang kecil yang makin lama makin besar — dan tiada siapa yang dapat menampalnya semula.
Kemudian telefonnya berbunyi.
Qayyum.
Nama itu kini terasa seperti tempat perlindungan yang perlahan-lahan jadi biasa. Tapi Qayyum tak pernah mendesak. Dia muncul… hanya bila Idina terdiam, tidak tahu arah tuju.
"Assalamualaikum, Princess. Dah makan?" Suaranya tenang, seperti biasa.
"Waalaikumsalam. Belum lagi. Tengah fikir nak order apa."
"I see. Kalau I hantar makanan, can you promise me, you makan?"
"You nak deliver food personally ke, Doctor Qayyum?"
Dia tergelak kecil. Ada nafas yang dia tarik perlahan di hujung tawa. Letih. Tapi tetap nak buat dia senyum.
"Kalau I cakap ya, you halau I tak?"
"Maybe. Tapi depends on the food."
"Okay ngam. Nasi briyani, teh tarik kurang manis. I’ll be there in 30."
---
Setengah Jam Kemudian
Pintu diketuk.
Idina buka, dan dia nampak Qayyum berdiri di luar — baju t-shirt putih ringkas, seluar slack hitam. Rambutnya sedikit kusut. Mata bawahnya ada bayang hitam. Tapi bila pandang dia, ada sinar yang buat Idina rasa dilihat.
"Princess." Suaranya penuh ikhlas.
"Qayyum."
Dia hulurkan bungkusan plastik berisi nasi briyani dan satu cup teh tarik panas. Dan dia tidak masuk selagi tidak dijemput.
Tangan Idina mempersilakan.
---
Mereka makan di meja kawasan luar rumah.
Qayyum duduk di atas rumput sambil menyandar ke kerusi, dan Idina melipat kaki di sebelahnya. Lampu kuning malap, aroma makanan memenuhi ruang.
Tak banyak cakap. Tapi tiada kekok.
Tidak seperti Hazwan, yang sentiasa semak telefon, buka laptop, jawab call client walaupun waktu makan malam bersama.
Qayyum tak bawa telefon ke ruang tamu, menghormati makanan dan dirinya.
Dia hanya ada di situ — hadir sepenuhnya.
---
Selesai makan, Idina kumpulkan bekas makanan dan membawanya ke dapur. Qayyum mengekori, membantu basuh tangan dan lap meja.
Di situ, di antara sunyi dan bunyi air paip, Qayyum bersuara perlahan:
"I tahu you kuat, Dina. Tapi I juga tahu... kadang orang kuat pun penat."
Idina diam. Jari-jari dia berhenti menyusun pinggan.
Bahu dia jatuh sedikit. Perlahan.
Mata dia tak angkat.
---
Sebelum pulang, Qayyum berdiri dekat pintu. Dia perhatikan kotak-kotak hadiah kahwin yang tersusun masih berbalut, tak dibuka.
Dia tanya perlahan, hampir berbisik:
"You deserve someone yang… actually shows up."
Idina telan liur. Kata-kata itu lebih tajam dari dia jangka.
Tapi dia tak marah.
Cuma tunduk. Diam.
---
Malam Itu
Selepas Qayyum pergi, Idina mandi, dan bersandar di katil sambil menggosok losyen ke lengan. Dia bukak telefon.
Satu mesej baru.
> “Kalau satu hari nanti you penat tunggu… you don’t have to wait alone.”
Idina baca mesej itu berkali-kali.
Tidak ada emoji. Tidak ada pengakuan. Tapi entah kenapa, itu lebih menyentuh daripada "I love you" yang Hazwan pernah ucap.
Dan untuk kali pertama, Idina tak terus padamkan.
Dia simpan.
Mesej itu kekal di situ — seperti seseorang yang tak pernah benar-benar pergi.
---
Di Tempat Lain
Hazwan sedang duduk di sebuah restoran mewah bersama Ayu dan beberapa kenalan bisnes ayahnya. Ketawa mereka kuat, mesra, dan jelas tidak tergesa.
Telefonnya bergetar.
Nama di skrin: Idina.
Dia pandang — tapi tak jawab.
Letak semula telefon di tepi, dan terus menyambung gelak.
See you in Chapter 10.
Share this novel



