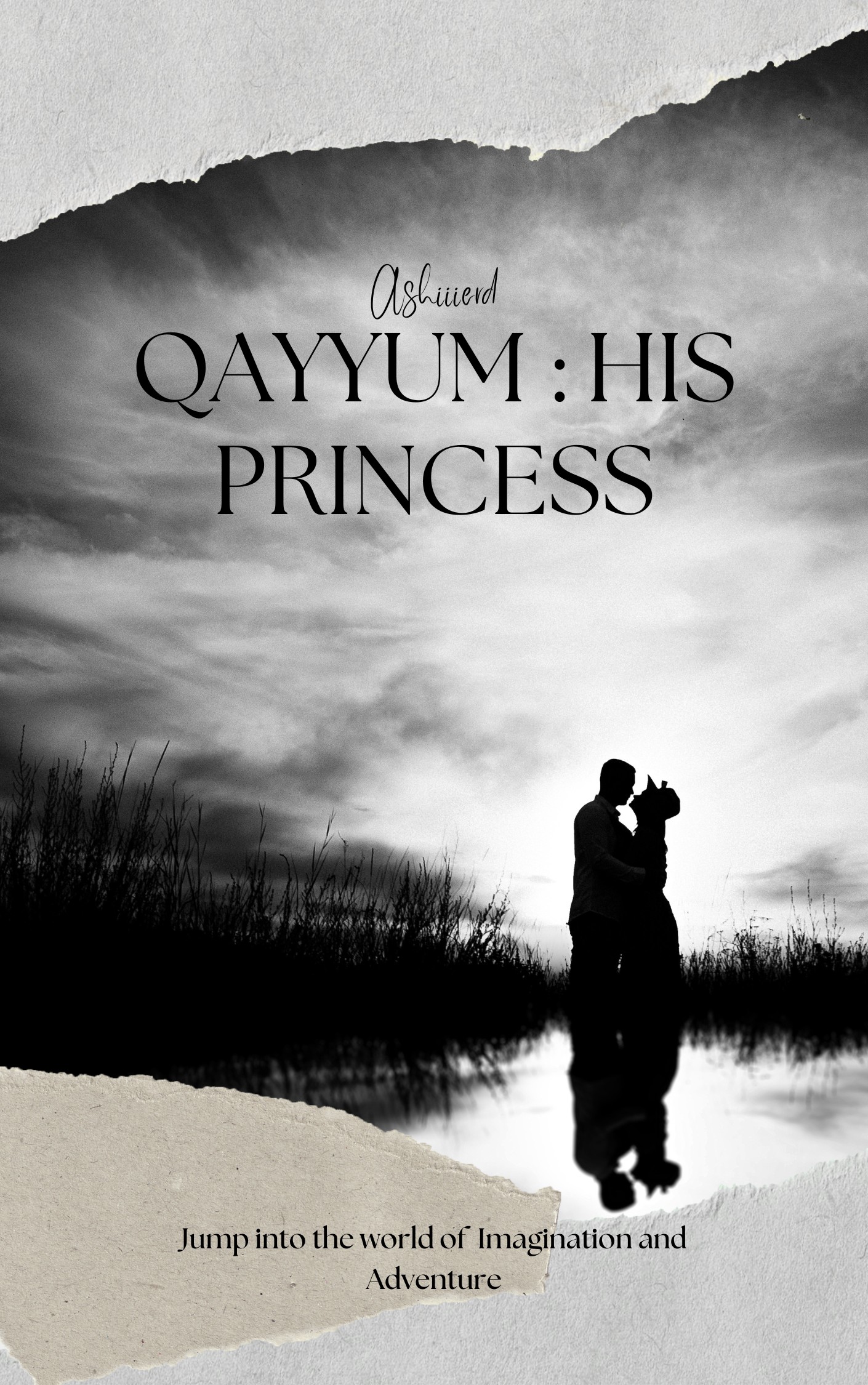
005
 Series
Series
 405
405
Suasana pejabat seperti biasa. Bunyi mesin pencetak, bunyi ketukan papan kekunci, dan deringan telefon bersahut-sahutan di ruang pejabat di tingkat enam. Tapi bagi Idina, semua itu hanya seperti gema jauh dalam gua sunyi. Jiwanya tenggelam di tempat lain — tempat di mana suara Hazwan pagi tadi masih terngiang dalam kepalanya.
“Sorry sayang, I kena outstation. Fitting baju nikah nanti kita reschedule.”
Itu saja. Satu baris teks.
Tiada emoji senyum. Tiada nota suara manja. Tiada penjelasan lebih dari itu.
Dan yang paling mencucuk hati — tiada 'I miss you'. Tiada 'Are you okay?’.
Dia tatap mesej itu lama-lama, seperti mahu mesej itu berubah nada. Tapi tak berubah.
Dia letakkan telefon perlahan atas meja, dan terus menekup muka. Tidak percaya.
Lagi satu janji yang dibatalkan.
---
Petang itu, langit KL mula gelap — bukan kerana malam, tapi kerana awan tebal yang membawa hujan lewat hari. Lounge hotel tempat Idina selalu singgah selepas mesyuarat hampir kosong. Hanya ada dua pelancong berbual perlahan di sudut kiri dan bunyi instrumental lembut dari pembesar suara siling.
Idina duduk di sofa biru kelabu yang menghadap jendela tinggi, fail atas riba — tapi tak dibuka.
Tangannya diam. Matanya kosong.
Dia cuba fokus. Tapi hati dia terlalu bising.
Flashback:
Tiga bulan lepas, Hazwan pujuk dia tempah gaun nikah awal. Katanya, dia tak sabar tengok Idina pakai baju pengantin. Dia kata, dia tak sabar nak cium dahi Idina, peluk erat dari belakang bila mereka dah bernikah nanti.
Sekarang?
Dia hilang dari panggilan. Dia jawab mesej macam urusan kerja. Seperti semakin hilang dari hidup Idina.
---
“Princess?”
Suara itu bukan Hazwan.
Suara dari belakang itu, lembut dan menenangkan. Jantung Idina berdetak sedikit kencang. Dia berpaling perlahan.
Qayyum.
Dengan kemeja biru tua dan coat labuh, rambutnya sedikit kusut dek angin petang. Tapi senyumannya masih sama — sederhana, tidak memaksa.
Dia memegang botol kecil.
“I buatkan you favourite tea. Still pahit macam dulu,” katanya, menuangkan air itu ke dalam cawan di hadapan Idina.
Idina cuba senyum. Tapi senyuman itu tidak sampai ke matanya, dan Qayyum nampak itu.
Dia duduk perlahan di kerusi bertentangan. Tidak terlalu dekat. Tapi cukup untuk rasa kehadirannya.
“You okay?”
Idina hela nafas. “I penat sikit. Kerja banyak. Banyak projek baru masuk.”
Qayyum tunduk sedikit, matanya jujur. “Kalau penat kerja, mata you takkan sembap macam orang tahan nangis.”
Idina terpaku.
Ayat itu, lembut tapi penuh kebenaran.
Dia tunduk, bahunya sedikit turun. Air mata mula mengalir, tanpa suara, tanpa esak. Dia cuba lap cepat-cepat, tapi jari-jemarinya menggeletar.
“I okay,” katanya perlahan. Bohong.
Qayyum tak menyentuh dia. Tak hulur tangan. Tapi dia bangun, duduk perlahan di kerusi sebelah, hanya dua jengkal jaraknya.
Dia diam seketika sebelum berkata perlahan, “I tahu I tak patut tanya lebih… tapi you boleh cerita kalau nak. I janji I tak judge.”
Idina diam. Perlahan-lahan, dia angkat kepala. Mata mereka bertemu.
“I tak nak orang tahu, simpati dekat I. I cuma… penat. Penat kena rasa kuat. Penat rasa macam semua orang tengok macam I kena perfect. Macam... kalau I mengeluh or simply complain pun, I jadi perempuan demand.”
Qayyum hanya mendengar.
“You tahu tak,” katanya perlahan, “Dina yang I kenal dulu, dia simpan semua dalam. Dia belajar macam tak pernah penat. Dia tolong semua orang. Tapi bila I nampak dia menangis sorang-sorang kat tangga belakang dewan waktu study week — I tahu dia penat sebenarnya.”
Idina ketawa kecil, tapi suara itu tersekat. “You nampak ke masa tu?”
Qayyum senyum tipis. “I nampak. Tapi I tak tahu nak buat apa. I takut kacau. I rasa I tak cukup penting dalam hidup you untuk tanya.”
Sunyi seketika.
“Tapi sekarang… boleh I jadi orang yang you boleh bersandar sikit bila penat?”
---
Lewat malam, Idina masuk ke biliknya. Cahaya lampu tidur malap, dan gaun putih ivory tergantung di pintu almari. Gaun yang sepatutnya dipakai petang tadi untuk sesi fitting.
Masih dalam plastik. Masih ada tag.
Dia duduk perlahan di hujung katil. Tangannya menyentuh renda gaun itu. Dingin. Kaku.
Dia capai telefon.
Tiada mesej baru dari Hazwan. Tiada missed call.
Seolah-olah fitting baju nikah itu cuma satu item dalam jadualnya — bukan detik penting dua jiwa yang mahu bersatu.
Dan bila Idina baring, matanya terbuka luas. Tak mampu pejam. Dalam senyap malam, air mata mengalir satu-satu ke bantal. Dia tak menangis kuat. Tak ada suara.
Cuma diam.
Air mata dalam diam.
Dia teringat kata-kata Qayyum tadi.
"I ingat, I tak nak kacau hidup you. Tapi I tak sanggup tengok you pendam semua sendiri."
Dan entah kenapa… suara itu lebih buat dia rasa dihargai berbanding sepuluh mesej Hazwan.
---
Keesokan paginya, matahari masuk perlahan melalui langsir tipis bilik tidur. Idina masih di katil, duduk bersandar dengan telefon di tangan.
Satu mesej masuk.
Qayyum:
> "Kalau you tak okay, tak apa. But, I tetap ada dekat sini kalau you perlukan I. I’m just a call away, Princess."
Mata Idina panas semula. Tapi kali ini… air mata itu bukan kerana sedih semata.
Dia taip perlahan.
Idina:
> "Thanks, Qayyum. Your words really heal me. You nampak I, even when I cuba untuk sembunyikan semua."
Dan untuk kali pertama dalam tempoh yang lama…
Dia rasa dilihat.
Share this novel



