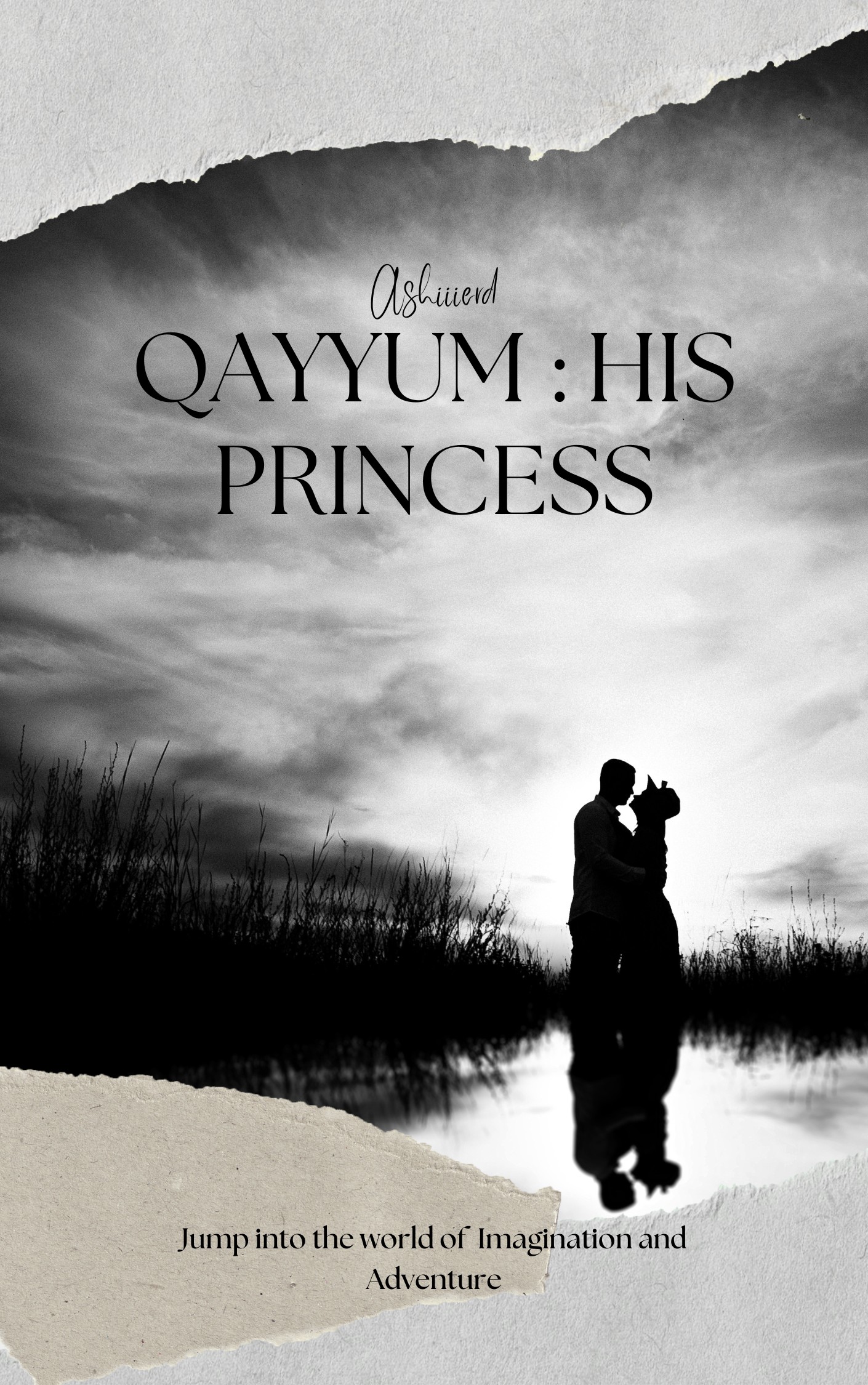
006
 Series
Series
 405
405
Kafe kecil di sudut Bangsar itu terasa seperti satu mesin masa.
Dengan aroma kopi arabika yang pekat, kerusi kayu berbunyi perlahan bila diduduki, dan lagu jazz lama yang mengalun perlahan dari pembesar suara di siling — semuanya terasa seperti membawa Idina kembali ke satu tempat yang pernah jadi rumah kedua di United Kingdom.
Tempat di mana dia dan Qayyum dulu menghabiskan berjam-jam belajar, berdebat tentang ilmu perubatan dan masa depan, sambil ketawa kecil di bawah cahaya jingga senja musim sejuk London.
Tempat yang pernah buat hatinya rasa tenang, buat seketika.
Idina memilih meja paling hujung, betul-betul di bawah jendela kaca yang memperlihatkan deretan pokok kecil dan titis hujan renyai-renyai di luar. Tangan kirinya menyentuh permukaan meja — sejuk, bersih, tapi terasa seperti penuh dengan kenangan.
---
"You pun suka tempat ni?"
Suara Qayyum lembut, tapi cukup untuk mengusik perasaan yang cuba Idina simpan jauh.
Dia mengangguk sedikit. "Macam mana I nak boleh lupa tempat yang paling dekat rasa dia dengan The Brixton Café?"
Qayyum senyum, senyuman yang tak berubah sejak dulu. Tenang. Tak memaksa. Tak terburu.
"You tahu tak," katanya sambil tarik kerusi dan duduk di hadapan Idina, "Sejak I balik Malaysia, I selalu datang sini waktu kerja habis lambat. Bila I rindu masa dulu. Tak sangka ada cafè yang hampir sama dengan cafè time kita study dulu."
Idina senyum nipis. "You pun rindu kenangan yang sama?"
"Of course," jawabnya, pandang Idina lama. "Susah nak lupakan seseorang yang selalu bawa bekal nasi goreng untuk I, masa I asyik tak cukup duit sebab kerja part time dekat farmasi."
Idina tergelak kecil, dan tawa itu datang dari tempat yang dia ingat dah lama mati.
---
Qayyum pesan latte untuk dirinya dan green tea untuk Idina. Sama seperti dulu.
Tapi kali ini, tak ada meja dipenuhi buku teks. Tak ada highlighter warna-warni. Tak ada bunyi salji ketuk tingkap. Cuma dua manusia yang pernah saling memahami — kini cuba bercakap semula, selepas bertahun menjarakkan diri.
"So..." Qayyum mulakan, perlahan. "Macam mana hidup you sekarang, Dina? Maksud I... yang betul-betul. Bukan yang I nampak dalam tv, dengar dalam radio.."
Idina diam lama sebelum menjawab. Pandangannya jatuh ke permukaan cawan di hadapan, wapnya masih menari lembut ke udara.
"I taktahu nak kata. To be honest, I penat, Qayyum," suaranya akhirnya keluar. "Penat sangat. Tapi I tak boleh berhenti. Kalau I berhenti, semua orang akan kecewa. Staff hotel, keluarga, nama mama papa..."
"Dan Hazwan?" soalnya, nada hati-hati.
Idina telan liur. Perlahan. Satu nama yang sepatutnya bawa tenang — kini hanya tajam dan penuh luka.
Idina mengeluh perlahan. "Dia dah bukan macam dulu. Hazwan dah banyak jauhkan diri. Tapi I masih cuba... I tried to make things work for both of us. But..."
"I believe that everything akan sama macam dulu. Maybe I just tipu diri yang semuanya okay. Sebab I dah terlalu banyak invest dalam hubungan ni. Masa. Kepercayaan. Harapan."
Qayyum tak potong. Dia hanya dengar. Tangannya tenang atas meja, tak cuba menyentuh, tapi matanya tak pernah lepas dari wajah Idina.
"You tahu tak," ujar Idina lagi, suara makin perlahan. "Kadang-kadang I rasa... kalau I hilang, tak ada siapa pun perasan."
Qayyum tersentak.
Kerana dalam kata-kata itu, Qayyum nampak segalanya.
Segala yang Idina pendam. Segala yang dia sorok di balik senyum manis dan pakaian korporat. Segala luka yang tak berdarah.
"I wish I boleh peluk you sekarang... I really want to." Qayyum berbisik. "Tapi I tahu I tak boleh. Tapi kalau ada apa-apa I boleh buat — untuk you, I akan buat."
---
Lewat malam, Idina pulang ke kondominium mewah yang terasa lebih seperti hotel kosong dari rumah.
Dia buka pintu bilik, lampu sisi menyala. Cahaya kekuningan menyinari ruang yang kemas, terlalu kemas — seolah-olah tak pernah dihuni.
Di atas meja sisi, sebuah kotak baldu biru tua masih terletak di tempat yang sama sejak sebulan lalu.
Perlahan, Idina buka penutupnya.
Cincin tunang.
Masih berkilau. Masih indah. Tapi terlalu asing.
Dia ambil perlahan, genggam di antara jari. Cincin itu dingin — bukan kerana suhu, tapi kerana sudah lama tak disentuh dengan kasih.
Mata Idina tertancap pada fail perancangan perkahwinan di hujung meja. Dia tarik fail itu. Kertasnya sudah renyuk, dan catatan merah bertindih di sana sini:
“Reschedule.” “Pending approval.” “Hazwan not available.” “To be confirmed.”
Tiada satu pun yang pasti.
Tiada satu pun yang selesai.
Seperti hidupnya.
Dan malam itu, di tengah bunyi hujan dan sepi yang mencengkam, Idina hanya duduk diam — cincin di tangan, helaian kertas di riba, dan hati yang terus berdarah dalam senyap.
---
Pagi esoknya, telefon bimbitnya berbunyi.
Satu mesej masuk. Dari nombor yang sejak kebelakangan ini, dia paling harapkan tapi juga paling takut untuk baca.
Qayyum.
> “Kalau you tak okay, tak apa. Tapi I tetap di sini kalau you perlukan. I’m just a call away, Princess.”
Idina pandang skrin itu lama.
Dan akhirnya, dia taip:
> “Terima kasih. You selalu nampak I, even when I cuba nak lari dari semua.”
---
Untuk pertama kali dalam beberapa minggu, Idina rasa... sedikit kurang berat di dada.
Walaupun hanya sekelumit.
Walaupun cuma satu mesej.
---
See you in Chapter 7.
Share this novel



