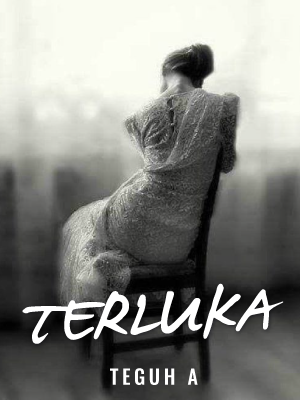
BAB 4
 Completed
Completed
 8187
8187
LANGIT yang kelam aku renung lama. Sekelam masa depanku. Sekelam kisah hati ini. Aku seka airmata ini dengan kasar. Semakin ku seka, semakin lebat pula. Tanpa tempat berlindung, tanpa pendapatan, tanpa teman, aku bagaikan tercampak jauh ke tengah lautan. Membiarkan diri terumbang ambing sendiri tanpa ada yang sudi membantu.
“Iqlima,” seru Saif. Bila aku kalih, dia sedang menghulurkan sebotol air mineral buatku.
“Betul tak nak makan ni?” tanya dia. Aku menggeleng bila teringatkan yang dia belum mendapat gaji dan andai ada pun, berapalah sangat untuk kerjanya sebagai pembantu stor di pasaraya Parkson itu.
“Kenapa awak cakap macam tu tadi, Iqlima?” tanya dia tenang selepas melabuhkan duduk di sisiku. Agak menjarak.
Aku tidak terus menjawab, sebaliknya aku lemparkan sekali lagi pandanganku ke dada langit malam yang semakin merangkak tua.
“Awak tahu tak, awak dah susahkan diri sendiri?”
“Dan saya juga menyusahkan awak, Saif,” sambungku pantas. Tubir mataku bergenang lagi. Dia ketawa nipis. Air mineral itu diteguknya lagi.
“Saya dah biasa susah, Iqlima. Saya ni anak yatim. Lari dari rumah anak yatim, dah lama hidup sendiri. Macam-macam kerja saya dah buat. Macam-macam benda dah saya lalu. Kena maki tu toksah cakap lah. Tapi, awak lain. Awak puteri pada keluarga yang kaya. Awak tak takut ke hidup kat luar sorang-sorang?”
Aku telan liur yang terasa kelat. Perit tekak ini hendak meluahkan kata. Biarpun aku teguk air ini, perit itu semakin menyengat.
“Saya tak ada pilihan, kan?” soalku semula pada dia.
“Saya memang tak pernah ada pilihan dalam hidup ni, Saif. Mungkin orang lihat saya adalah seorang puteri dalam rumah banglo tu, tapi kehidupan saya bagaikan satu urusniaga saja pada mata keluarga. Bila saya disuruh menerima Muiz, saya ikhlaskan hati menyintai dia. Bila hubungan atas dasar perniagaan ini putus, saya terus dibuang keluarga. Hari ini, saat ni, saya tak ada apa-apa. Saya tak ada tempat tinggal, saya tak ada teman, saya tak duit. Seperti kata awak, saya hanya ada Allah tempat saya berlindung. Tempat saya bergantung harap,” ujarku sebak.
Saif diam saja. Mata itu sedari tadi merenung wajahku. Seperti biasa juga, wajah tanpa riak. Aku ketap bibir membalas renungannya. Sesaknya dada ini memikirkan keluarga sendiri telah membuang aku jauh dari mereka.
“Mungkin awak rasa awak susah sebab awak anak yatim, dicaci, dimaki demi sesuap nasi. Tapi saya, diatur dalam segala hal demi sebuah kehidupan, Saif. Sukar, kan menjadi seorang perempuan. Hidup sendirian di luar yang memang sudah jelas bahayanya yang menanti. Tapi, saya yakin dengan Allah. Dia akan melindungi saya. Akan sentiasa ada bersama saya,” sambungku kembali dan kali ini, bahuku kembali terhenjut-henjut.
“Saya pasti awak ada pendidikan, Iqlima. Awak boleh mulakan hidup baru. Buktikan yang awak boleh hidup tanpa mereka. Marah ibu bapa ni sekejap je, Iqlima. Dah reda nanti, mesti mereka cari awak semula. Yakinlah!” pujuk dia bersungguh-sungguh.
Kepala ini aku geleng beberapa kali. “Awak tak kenal ayah dan abang saya, Saif. Setiap kata-kata itu mesti dikota. Setiap kata-kata itu adalah bisnes buat mereka. Termasuk saya menjadi cagarannya. Bila ayah kata dia bekukan semua akaun saya, ternyata benar, kan?”
Aku terkedu di mesin ATM tadi bila ternyata akaun kepunyaanku sudah dibekukan. Sudahlah kala ini, wang di dalam poket jeans hanya ada beberapa puluh ringgit saja.
“Awak ada kelulusan. Try la pergi interview kat mana-mana,” cadang dia lagi dan aku pantas menggeleng.
“Bila dia kata akan senarai hitamkan nama saya, pun sama juga. Kecuali saya kerja di tempat-tempat biasa je. Waktu ni saya tak boleh memilih. Apa saja kerja, saya sanggup buat asal saya dapat teruskan hidup,” jawabku kembali.
Saif renung wajahku lagi. Kali ini, kau nampak bunga senyum pada hujung bening matanya.
“Nak kerja ni, kena ada modal, Iqlima. Maksud saya, modal ni, dari segi pakaian buat masa ni sebab awak dah la sehelai sepinggang. Esok nak pakai apa? Sekarang ni nak tinggal dekat mana?” Dia beriak risau. Aku hela nafas panjang dan memaksa diriku mengukir senyuman menerima ketentuan hidupku kali ini.
“Terima kasih, Saif. Sudi risaukan saya.” Aku berdehem beberapa kali. Sebolehnya aku akan pastikan bibir ini tersenyum saja nanti biarpun hati aku akan terus menangis.
“Awak pergilah. Saya rasa dah tiba masanya saya pandu arah hidup saya sendiri. Bila fikir balik, inilah yang saya nanti selama ni. Bebas menjadi boneka keluarga sendiri. Bebas dari dibentuk oleh mereka sesuka hati. Saya janji dengan diri sendiri, rentak hidup ini akan beralun indah. Tak mungkin ada gema yang sumbang. Kita berpisah di sini jelah. Maafkan saya sekali lagi sebab saya awak terpaksa tanggung semua ni. Bila awak tanya kenapa saya hadang tubuh saya dari biarkan awak kena pukul tadi, dan sanggup mengaku yang awak suami saya hanya kerana satu jawapan je Saif. Saya rasa sakit sangat bila melihat awak sakit. Saya tak tahu kenapa, tapi itulah seikhlasnya yang hati saya rasa,” ucapku pada dia.
Saif terkedu. Mulutnya sedikit melopong. Aku renung dia lama kali ini. Melihat penampilannya dari hujung rambut hingga hujung kaki. Rambut yang agak panjang mencecah kolar baju, wajah yang agak selekeh dengan misai dan janggut tipis, jeans lusuh yang sedikit koyak di lutut dengan kasut yang juga agak lusuh. Segala yang membaluti tubuhnya lusuh namun aku yakin, hatinya segar, tidak pernah lusuh melihatkan kesungguhannya mempertahankan aku daripada fitnah Muiz.
“Terima kasih sekali lagi, Saif. Hanya terima kasih yang mampu saya ucapkan. Sebab saya tak ada apa nak beri pada awak. Tak ada wang nak bayar.” Aku bangkit dan menyapu belakang seluar. Tudung yang ditiup angin, aku betulkan sedikit.
“Awak nak ke mana, Iqlima?” tanya dia turut bangkit.
“Takdir saya akan bawa langkah saya ke arah yang sepatutnya saya melangkah,” jawabku berjeda. Saif senyum sinis.
“Jangan terlalu berserah pada takdir Iqlima. Takdir meminta kita berusaha. Bukan berserah semata-mata. Jangan sampai awak jadi habuan, diratah lelaki-lelaki jahat kat luar sana,” ucapnya dengan nada mengugut. Aku telan liur. Kecut. Serta merta mata ini melilau ke sekeliling.
“Lagipun, awak masih ada banyak harta pada awak. Jadi, untuk itu, biarlah saya minta sikit. Saya minta sikit kepercayaan daripada awak untuk lindungi awak sementara waktu ni.” Dia angkat kedua belah keningnya meminta persetujuan daripadaku.
Aku teragak-agak pada mulanya dan seperti yang pernah aku katakan, aku berasa di satu lorong saja. Tiada simpang yang mampu aku pilih. Hanya Saif di depanku. Hanya Saif yang menjadi papan tanda untukku. Hanya dia yang menjaga perjalanan ini hingga akhirnya, aku mengangguk jua dan dia tersenyum lebar. Hati ini terasa diragut melihatkan senyuman manis itu. Pertama kali melihat dia begitu, ada rasa gundah yang hadir dalam diri ini.
Share this novel



