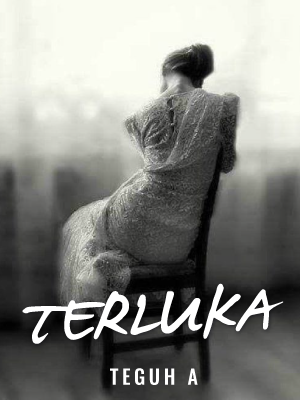
BAB 3
 Completed
Completed
 8187
8187
JAM sudah menghampiri 9.30 malam. Aku masih lagi merayau-rayau sendirian di dalam Parkson. Banyak kedai yang sudah mahu tutup. Suasana Parkson juga sudah bertukar sepi. Hanya beberapa orang pekerja saja yang sedang berkemas-kemas dan pengunjungnya pula hanya aku seorang.
Lenguh kaki ini terus menapak tanpa hala dan tujuan, aku labuhkan duduk di sebuah bangku. Merenung ke arah beberpa orang pekerja yang sedang bergelak ketawa. Namun aku, tidak pernah bekerja, dimandikan kemewahan semata-mata. Mengenali Muiz juga kerana urusan perniagaan antara ayah serta Abang Iqbal dengan keluarga Muiz tapi aku benar-benar ikhlas cuba menyintai dia. Hari ini, andai aku dihalau keluar daripada rumah itu, ke mana hendak aku bawa langkah kaki ini? Terasa bagaikan patah sayapku hendak terbang tinggi lagi.
Tanpa sedar, airmata aku merintik tanpa paksa. Bermula dengan titisan tanpa suara hingga menjadi esakan yang kasar dan akhirnya bersendu.
“Tak elok perempuan kat luar malam-malam macam ni,” tegur satu suara sambil tangan itu menghulurkan sehelai sapu tangan.
Bila aku angkat wajah, tubuhku juga terangkat sama. Mata yang berair ini buntang melihatkan wajah yang jelas di mataku. Saif! Dia pandang aku tanpa riak. Tanpa senyum, tidak juga terbias dengan riak marah.
“Kan saya dah suruh awak balik tadi. Kenapa awak merayau kat luar lagi sampai malam ni?” tanya dia keras. Aku ketap bibir. Tidak tahu apakah jawapan yang harus aku katakan. Rasanya lidah ini sudah terpasung pada lelangit. Kelu seribu bahasa.
“Saya… saya…,” Aku tidak mampu bersuara. Kala ini, terngiang-ngiang suara Abang Iqbal dan ayah di telingaku. Silih berganti memarahi dan menghalau aku daripada rumah.
“Saya apa?’ Dia jungkit kening dan aku pantas menggeleng dengan airmata yang kembali berjuraian.
“Awak nak cakap awak kena halau dari rumah, macam tu?” tanya dia. Kali ini aku diam bila telahan dia ternyata benar biarpun semua itu adalah syarat daripada keluargaku bila aku tidak mahu memujuk Muiz.
Dia mengeluh lalu duduk di atas bangku. Sapu tangan yang dia hulurkan tadi, dia genggam erat. Aku hanya tertunduk lemah. Tunduk menjadi seseorang yang tewas. Tunduk menitiskan airmata.
“Kenapa awak kena halau?” tanya dia tenang.
“Tunang saya dah tinggalkan saya,” jawabku teragak-agak.
“Oh, siang tadi tu, tunanglah? Bukan pakwe?” Dia sengih sumbing.
“Kalau kata tunang awak tinggalkan awak, kenapa pulak awak yang kena halau? Patutnya keluarga awak tak halau awak sebab bukan salah awak. Melainkan ternyata awak yang curang.”
Aku angkat wajah dan terus merenung wajahnya. Rautnya tenang saja. Setenang waktu dia menyelamatkan air mukaku siang tadi.
“Dia lebih dulu cakap nak putus sebab saya ada lelaki lain,” jawabku.
Dia angkat kening. “Siapa? Awak memang ada lelaki lain ke?”
Entah mengapa, dengan lelaki ini, aku berasakan diri ini tertarik dengan sendirinya. Namun kemudiannya, tertolak pula. Wajahnya langsung tiada berperasaan. Simpati atau sedih. Cinta jauh sekali. Tiada langsung kemesraan pada wajahnya.
“Dia cakap saya ada hubungan dengan awak.” Jujur saja aku menjawab dan kali ini, jawapanku mengundang tawa dia. Tawa halus saja. Atau lebih tepat lagi, tawa yang cukup sinis.
“Nama awak Eiy, kan?”
Aku angguk mengiyakan soalan itu. “Iqlima,” jawabku menyatakan nama penuhku.
“Iqlima… Iqlima…,” ulang dia beberapa kali. Aku lihat dia meramas rambutnya bagaikan kepala itu berat tertimpa masalah sedangkan akulah sebenarnya yang ditimpa masalah kerana kemunculannya tadi.
“Iqlima bermaksud puteri Nabi Adam yang cantik dan memang sesuai dengan awak sebab awak puteri yang cantik pada mak ayah awak, cuma saya pelik. Kenapa semua wanita cantik mesti bodoh?”
Aku terkedu dengan soalannya. Dengan kata lain, dia mahu katakan aku sebenarnya bodoh.
“Apa maksud awak?” tanyaku dengan nafas yang tidak menentu.
“Itulah maksud saya. Kebanyakan wanita cantik yang saya jumpa semuanya bodoh. Tak sesuai langsung punyai kecantikan pada wajah. Satu lagi, terlalu lemah. Suka mengalirkan airmata,” ujar dia tenang. Jemarinya tersulam sesama sendiri.
Aku renung mata itu tajam. Langsung tidak berkedip memberi amaran dalam diam yang aku tidaklah sebodoh yang disangka. Aku punyai pendidikan biarpun tidak berkerjaya.
“Saya tak sebodoh yang awak sangka, encik!” tekan aku keras dengan airmata yang masih membasahi pipi.
Dia ketawa nipis. “Tak bodoh ke sampai sanggup melutut di kaki lelaki? Tak bodoh ke sampai sanggup merayau tak tentu hala bila keluarga halau? Tak bodoh ke sebab suka menangis tak tentu pasal sedangkan awak ada Allah tempat untuk awak mengadu?”
Terhenyak aku sendiri dengan soalan demi soalan yang terbit daripada celah bibir kemerahan itu. Dia sengih lagi di hujung bibir dan terus bangkit. Sapu tangan itu sekali lagi disuakan ke depanku. Bila aku tidak menyambut, dia tarik tanganku dan diletakkan sapu tangan itu di telapak tanganku.
“Jangan jadi bodoh, Iqlima. Ambil sapu tangan ni. Lap muka tu bersih-bersih. Tunggu sini kejap. Saya puch card, lepas tu saya hantar awak balik. Saya tolong awak terangkan yang benar pada keluarga awak pasal hal siang tadi sebab awak kata kerana saya awak kat sini, kan?’ Dia jungkit kening.
Aku tidak menjawab. Tidak tahu lagi apa yang harus aku katakan. Perlukah aku mempercayai dia yang baru aku kenali sesaat cuma? Rasa curiga itu ada tapi aku bagaikan berada di jalan mati. Tiada persimpangan lagi yang harus aku pilih. Hanya satu-satunya yang tinggal, iaitu Saif.
Hampir 15 minit aku menanti Saif datang semula, dia akhirnya muncul dengan wajah yang penat. Tapi, rautnya tenang. Sukar hendak ku tebak rasa yang ada di dalam hati lelakinya itu.
“Rumah kat mana?” tanya dia.
“Jalan Haji Ahmad.”
Dia angkat kening. “Saya ada motor je. Tapi, tak elok nak tumpangkan awak malam-malam buta ni. Siang-siang pun tak elok. Tak manis. Kita naik bas je. Nak naik teksi, saya tak dapat gaji lagi. Tapi, tak tahulah kot-kot awak banyak duit nak naik teksi, saya tak kisah,” jujur saya dia berkata-kata.
“Kita naik teksi je,” ujarku lalu dia angguk dan terus melangkah.
Jenuh aku menyaingi langkahnya. Rasanya, selangkah dia, dua langkah aku terpaksa mengejar. Dia menonong saja tanpa menghiraukan aku yang sesekali terpaksa berlari anak mengejar langkahnya.
Di dalam teksi, Saif hanya diam sendiri. Langsung tidak dikerlingnya aku di sisinya. Bila tiba tepat di depan rumah mak dan ayah, aku jadi terpaku di dalam teksi itu. Punggung ini bagaikan melekap sedangkan Saif terlebih dahulu turun dan terus saja membuka pintu di sebelahku.
“Ni ke rumah awak?” tanya dia dan aku mengangguk.
“Awak cantik, kaya, apa lagi yang awak nak sesalkan kalau kata kehilangan jantan perangai macam tu, hah Iqlima?” tanya dia kasar. Sentiasa dihiasi bunga sindiran itu.
Aku membayar tambang teksi dan keluar juga bila Saif mendesak. Kini, aku tegak berdiri di depan pagar rumah bersama lelaki yang mungkin akan dihempuk oleh Abang Iqbal. Mereka memang begitu. Tidak boleh dibuat main apatah lagi segala perkara yang berkaitan untung dan rugi ini termasuk memperdagangkan anak atau adik sendiri.
“Assalamulaikum….,” laung Saif kuat. Sekali salam saja, aku nampak wajah Abang Iqbal terjengul di pintu. Pagar otomatik ini terbuka luas.
Dia keluar dengan wajah kelat dengan bercekak pinggang. Diikuti pula dengan ayah dan mak.
“Hah, Eiy? Mana Muiz? Aku telefon Muiz dia kata kau tak datang jumpa dia pun?” tanya Abang Iqbal kasar. Aku terus membawa tubuhku bersembunyi di belakang Saif. Dia yang mengerti hanya menjeling sekilas ke arahku.
“Aku memang dah agak yang kau tak akan minta maaf pada Muiz tapi kau memang akan bawa balik jantan lain. Aku memang dah agak Eiy!” marah dia semakin kuat. Airmata aku menitis lagi. Takut menerima tamparannya lagi.
“Kenapa Eiy tak pergi minta maaf dengan Muiz?” tanya ayah pula. Langsung tidak bertanya, baikkah aku, dari manakah aku ini? Sudah makankah?
“Pak cik, bang… Saya Saif…”
Belum sempat Saif menghabiskan kata-katanya, dia sudah tersungkur ke bumi. Rebah di kakiku bila Abang Iqbal menumbuk wajahnya. Peliknya, dia hanya tersenyum dan mengesat bibirnya yang sedikit berdarah tanpa merungut atau hendak membalas sedikit pun.
Bila aku hendak membantu dia bangkit, dia menghalang. “Kita bukan muhrim untuk awak pegang saya, Iqlima. Sepatutnya awak pergi pada abang awak, darah daging sendiri,” tegurnya berbisik.
Tanganku terhenti. Lalu aku hanya mampu memandang dia bangkit dengan kudrat sendiri.
“Dengar dulu penjelasan saya, bang… pak cik…,” rayu Saif bersungguh-sungguh.
“Saya datang ni nak hantar Iqlima balik je. Dia merayau sorang-sorang dekat bandar waktu-waktu macam ni, tak elok untuk anak gadis macam dia, bang… pak cik,” ujar Saif.
Aku lihat wajah ayah dan Abang Iqbal merah. Hanya mak yang diam terkaku di belakang mereka tanpa ada tanda hendak membela aku kerana aku tahu, mak juga tidak sudi menerima aku kembali jika tidak bersama Muiz.
“Tunang anak pak cik ni, lelaki tu yang curang sebenarnya. Dia tak salah.” Saif jeling ke arahku yang kembali menitiskan airmata.
“Kau jangan nak tuduh Muiz kalau kau tak kenal dia,” jerkah Abang Iqbal kasar. Saif mengeluh.
“Kita tak akan kenal seseorang hamba itu kecuali hanya Penciptanya sahaja, bang. Tak elok abang buat adik sendiri macam ni. Benarkanlah dia masuk, bang,” pujuk Saif lagi.
“Eh, budak. Kau jangan nak tutup kesalahan kau dengan dia, kau cakap Muiz pulak buat hal. Kalau betul dia buat hal, kenapa dia datang mengadu yang kau dengan Iqlima ni….” Abang Iqbal tuding jarinya terus padaku.
“…. ada hubungan sulit kat belakang dia?” Meninggi saja suara Abang Iqbal. Matanya berapi-api memandang kami silih berganti.
“Jangan cepat memfitnah, bang. Abang tak kenal saya dan saya yakin, abang juga tak kenal siapa Muiz tu. Ini adik abang, abang lebih kenali dia daripada saya.” Saif tolak aku mendekat kepada Abang Iqbal.
Tubuh ini terus membatu berdiri di sebelah Saif tanpa mampu aku melangkah bila ditolak. Kali ini, rasanya diri ini hanyalah barangan yang sedang dijual beli oleh mereka. Ditolak ke sana sini tanpa ada yang mengerti perasaanku.
“Aku dah agak, kau memang hasut Iqlima ni tinggalkan Muiz. Kau memang suka dia sebab nak tumpang harta kami, kan?” tuduh Abang Iqbal lagi dan kali ini, penumbuknya sekali lagi mahu menyapa kasar wajah Saif bila aku lebih cepat membawa tubuhku berada di depan tubuh sasa lelaki yang tidak aku kenali ini.
Aku tidak rela dia disakiti lagi sedangkan niatnya terlalu luhur. Hendak membantu. Namun, kenapa darah daging sendiri tidak mempercayaiku?
“Jangan pukul dia lagi, bang. Sakit dia sakit lagi Eiy. Jangan pukul suami Eiy, abang,” tangisku dengan mata yang penuh merayu agar abangku ini tidak terus berkasar.
Tanpa sedar, terpacul perkataan suami itu dari bibirku. Aku tahu, hanya dengan cara ini, Abang Iqbal dan ayah akan melepaskan Saif pergi dan sudah pastinya aku jua.
Aku rasa tangan Saif menolak bahuku ketepi, tapi aku tidak mahu berlalu. Aku mahu dia bawa aku pergi bersamanya bila aku bagaikan tidak berharga langsung pada keluarga sendiri.
“Jangan pukul suami Eiy,” ulang aku lagi dan kali ini lebih keras biarpun di dalam esak tangis yang semakin menggila.
Aku palingkan wajah merenung anak mata Saif. Aku tahu mata itu jelas terkejut. Dia tidak terkata apa. Kelu saja.
“Aku dah agak dah. Tengok ni mak, ayah apa budak sial ni buat pada kita?” Berdentum suara Abang Iqbal kali ini.
Mak memandang kami tidak berkelip. Riaknya langsung tidak berperasaan. Ayah mendekat pada kami dan bila aku renung matanya, pipi aku sekali lagi menjadi sasaran dan pantas Saif menyambut bila aku hampir tersungkur ke simen.
“Mulai hari ini, kau bukan lagi anak aku, Iqlima. Iqbal, kamu bekukan semua kad kredit dia, bekukan semua elaun dan akaun dia sekarang jugak. Ayah nak kau senarai hitamkan nama dia supaya dia tak boleh nak mohon apa-apa jawatan dekat mana-mana syarikat selagi ayah hidup!” tekan ayah keras. Dia terus berlalu dengan mata yang merah.
Aku yang mendengarkan hampir saja terkulai sekali lagi. “Jangan buat Eiy macam ni, ayah. Mak, tolong Eiy mak. Eiy tak salah…” rayu aku pada mak.
“Pergilah, nak ikut suami kamu. Mak juga punyai suami untuk mak patuh pada dia dan mak harap, Eiy juga patuh pada Saif.” Mak menitiskan airmata. Dia membuka seutas rantai dan seutas gelang dari pergelangan tangannya lalu diletakkan di atas telapak tanganku.
“Ini je mak mampu beri untuk Eiy,” ucap mak. Dia memandang pula ke arah Saif yang sedari tadi diam membisu.
“Saif jaga amanah mak ni baik-baik, nak. Jangan persiakan dia macam mana kami layan dia tak ubah macam barang selama ni,” akui mak jujur. Airmatanya terus menitis dan bila aku paut tubuhnya, mak mencium dahiku lama dan dia terus berlalu tanpa menoleh lagi.
Serentak itu, pagar otomatik tertutup rapat menghalau langkah aku dan Saif. Aku tersedu-sedu. Tubuh ini menggigil bila terbukti kini, aku benar-benar dihalau pergi. Sehelai sepinggang. Tanpa membawa apa-apa kerana ayah telah mengharamkan segalanya.
Share this novel



