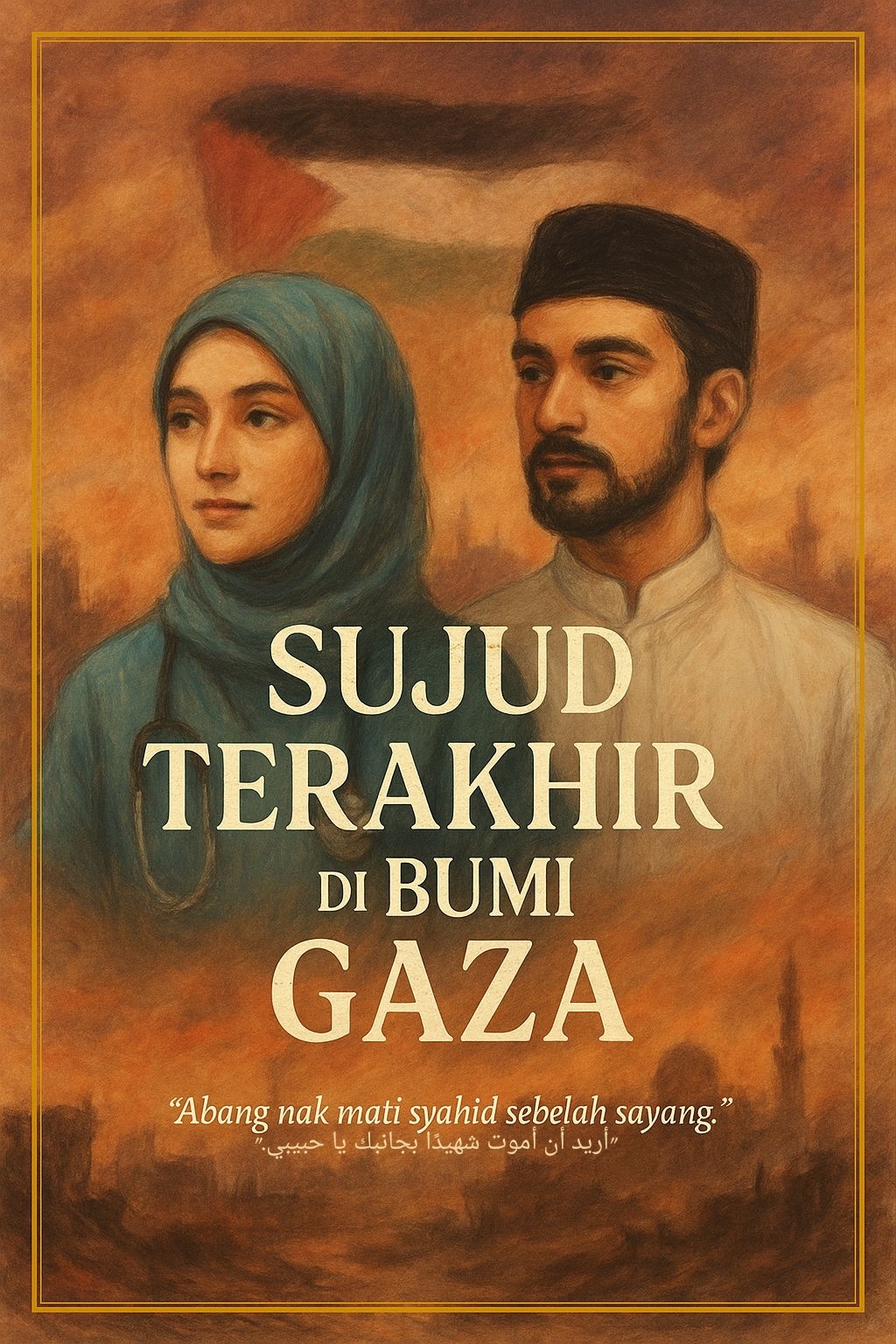
BAB 8 – Nama Yang Ditakuti
 Series
Series
 57
57
Langit pagi kelabu. Kabus masih menggantung rendah ketika Atma dan Damar menuruni bukit menuju ke sebuah kampung terpencil bernama Pematang Lera — terletak di celah lembah yang dikelilingi hutan rimba dan sawah padi lama.
Mereka berjalan dalam diam, hanya ditemani bunyi cengkerik dan gema tapak kaki atas tanah lembap.
Tapi dalam kepala Atma, tiada senyap.
Masih kedengaran suara — suara yang lembut, tapi menusuk:
“Kau tak pernah tahu aku simpan perasaan itu, kan, Atma?”
“Aku cuma dayang istana. Tapi aku tetap berdoa, agar kau pulang dari setiap misi dengan nyawa kau yang masih ada…”
Suara Purnama.
---
Atma menoleh ke sisi.
Sekilas, dia melihat sosok bayang perempuan berbaju ungu berjalan perlahan di antara pokok rimbun. Rambut panjang. Tubuh yang halus. Langkah yang tenang.
Tapi bila dia menoleh semula — tiada sesiapa.
Dia pejam mata. Nafasnya berat.
“Aku tahu kau marah, Purnama. Tapi yang paling aku kesalkan… bukan hanya kerana membunuh kau — tapi kerana tak pernah membalas cinta yang kau simpan diam-diam.”
Damar memerhati dari sisi. Dia tahu sesuatu sedang membebani sahabat mudanya itu, tapi tidak bertanya. Tidak perlu. Cukup dia berjalan bersama.
---
Pematang Lera
Desa itu tampak mati walau masih ada nyawa. Rumah-rumah sunyi, pintu tertutup. Tiada kanak-kanak berlari, tiada bunyi lesung ditumbuk. Hanya mata-mata curiga mengintai dari celah tingkap.
Mereka disambut oleh seorang lelaki tua bertongkat, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Sidin, ketua kampung.
“Kami tidak menerima musafir sekarang. Bukan kerana benci… tapi kerana takut.”
“Takut apa?” soal Atma.
Lelaki tua itu menghela nafas. “Ada pembunuh berkeliaran. Sudah tiga orang mati. Mereka mati dengan dada terbelah — dan setiap kali… ada kertas diletak di sisi mayat.”
Pak Sidin menarik keluar kertas yang sudah kekuningan.
Di atasnya, hanya tertulis:
“Atma Datang Menuntut.”
---
Atma terasa darahnya sejuk. Damar berpaling kepadanya, mata tajam. Atma angkat tangan.
“Bukan aku.”
Pak Sidin memandang Atma lama. “Kau… Atma?”
“Ya. Tapi aku bukan pembunuh itu. Aku datang untuk menebus, bukan menakutkan.”
Pak Sidin tidak menjawab. Dia hanya berjalan semula ke arah rumah, meninggalkan mereka berdua di halaman yang sunyi.
---
Malam itu, Atma duduk sendirian di pangkin kayu. Damar sudah di dalam rumah usang yang disediakan. Angin malam meniup rambutnya perlahan. Di seberang sawah, bayang pepohon menari mengikut cahaya bulan.
Atma tunduk. Suara Purnama datang semula.
“Kalau aku masih hidup, Atma… aku akan ajar kau erti hidup yang lembut. Bukan hidup dalam darah.”
“Tapi sekarang… kau hanya ada sepi. Dan sepi itu… adalah aku.”
Air mata Atma tumpah perlahan.
Bukan kerana takut.
Tapi kerana dia rindukan peluang yang dia musnahkan sendiri.
“Maafkan aku, Purnama. Andai rohmu masih memerhati… aku akan terus berjalan. Biar pun seluruh dunia panggil aku pembunuh… aku hanya mahu satu perkara: penebusan.”
---
Tiba-tiba, Damar keluar dari rumah. Dia hulur sehelai kain.
Atma ambil, dan mengelap wajah.
Kemudian Damar menulis di tanah dengan hujung lembing:
“Musuh gunakan nama kau. Kita cari dia. Dan kita tamatkan fitnah itu.”
Atma angguk.
Matanya kini tidak lagi hanya duka.
Ada api kecil — bukan dendam, tetapi tekad.
“Kita tamatkan ini, Abang.”
Share this novel



