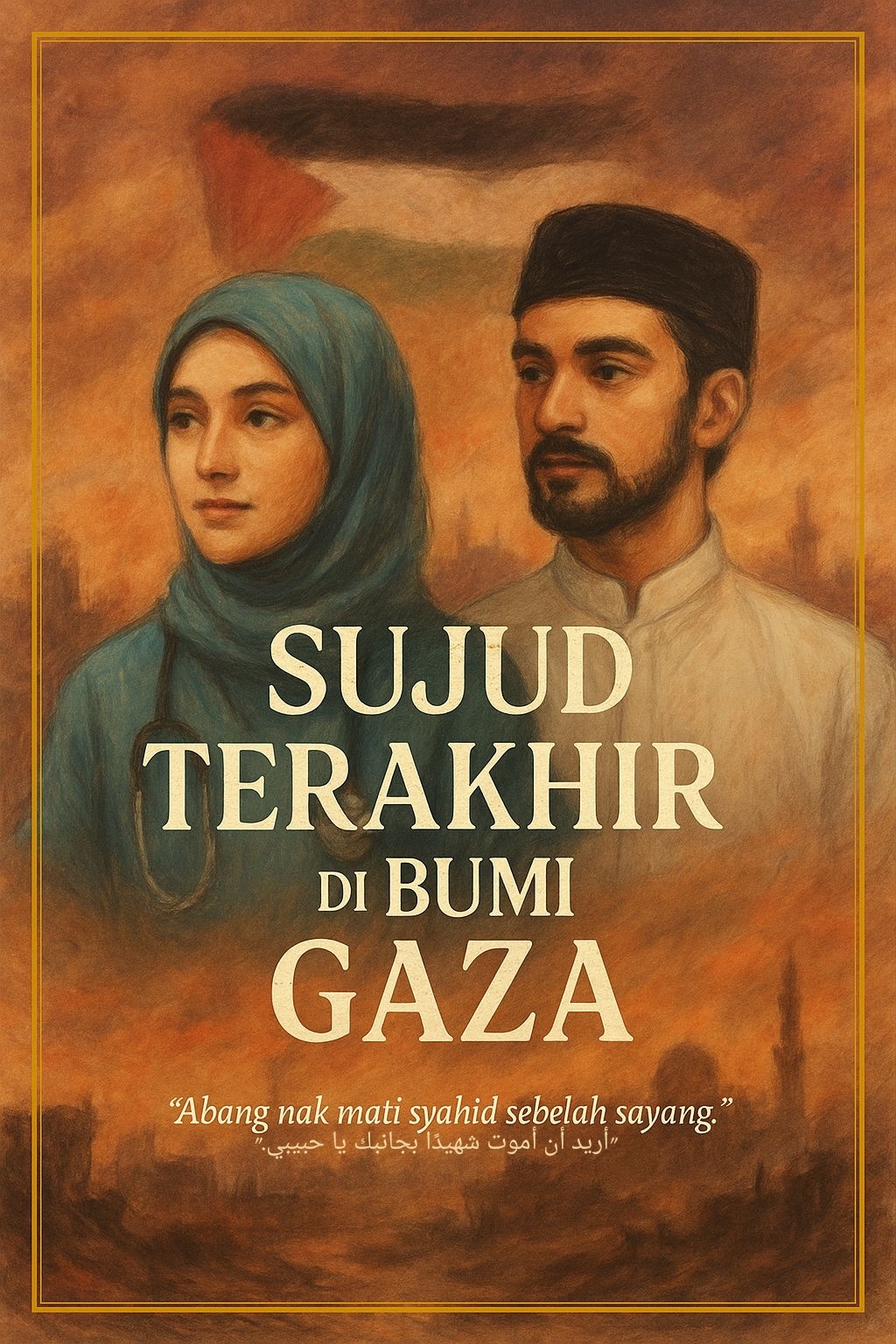
BAB 4 – Desa yang Pernah Berdarah
 Series
Series
 57
57
Matahari pagi menyinar lembut di balik rimbunan hutan.
Atma dan Damar melangkah keluar dari pondok kecil, menuju ke jalan tanah merah yang hampir dilupakan manusia. Damar menyandang lembing pendeknya di belakang, terikat silang dengan tali kulit. Atma pula membawa sehelai kain sarung dan sebilah pisau kecil — bukan untuk membunuh, tapi untuk bertahan hidup.
Hari itu, mereka menempuh perjalanan menuju ke sebuah desa di pinggir Bukit Lemping. Di sanalah Atma menerima upah pertamanya sebagai pembunuh, bertahun-tahun lalu — dan di situlah dosanya bermula.
---
Desa Lereh.
Sebuah perkampungan kecil yang dulunya makmur dengan ladang padi dan air bukit yang bersih. Tetapi kini, seperti tanah yang menyimpan dendam, desa itu suram dan senyap.
Mereka tiba menjelang tengah hari. Seorang budak lelaki memandang dari kejauhan sambil menyorok di sebalik tangga rumah papan. Di kejauhan, asap dapur naik perlahan dari beberapa rumah.
Atma berdiri lama, memandang sekeliling.
Dia ingat rumah itu — yang kini tinggal tunggul — pernah dihuni oleh seorang lelaki yang gigih membela tanah adatnya daripada rampasan pembesar korup. Nama lelaki itu: Pak Mentang.
Dan Atma, dalam satu malam, telah menyelinap masuk dan menamatkan riwayat lelaki itu atas arahan orang istana.
Atma mengetap bibir. Damar memandangnya dari sisi — seolah tahu, ini bukan lawatan biasa.
---
Mereka bertanya arah dan akhirnya tiba di sebuah rumah tua, hampir reput. Di halaman, seorang wanita tua sedang mengasingkan beras dengan nyiru. Di tepi tangga, seorang budak lelaki — sekitar usia sepuluh tahun — sedang mengikat rakit mainan dari daun kelapa.
“Salam sejahtera, Makcik,” Atma menunduk, perlahan.
Wanita itu angkat muka. Wajahnya penuh garis usia dan kedukaan. Matanya tajam menilai.
“Kamu orang luar?”
Atma mengangguk.
“Saya… pernah kenal arwah Pak Mentang. Saya mahu… beri sedikit bantuan. Kalau dibenarkan.”
Wanita itu tidak menjawab. Dia terus mengasingkan beras. Tapi budak lelaki tadi mencuri pandang pada Atma dengan mata yang bersinar — mata anak kecil yang tidak kenal dosa orang dewasa.
Atma keluarkan uncang kecil berisi wang perak. Dia letakkan di atas anak tangga. Tangannya menggigil sedikit.
“Untuk budak itu. Sekadar bantuan orang musafir.”
---
Ketika mereka berpusing mahu beredar, suara wanita tua itu bersuara perlahan:
“Kalau kau benar-benar kenal Pak Mentang… maka kau tahu, dia mati dibunuh dari belakang. Pada malam yang hujan.”
Atma terhenti. Damar menoleh sedikit.
“Orang yang bunuh dia… tak pernah ditangkap. Tapi aku tahu, satu hari nanti, dia akan datang juga. Dan Tuhan akan hantar bayang-bayang untuk ikut dia sampai akhir.”
Suara wanita itu tidak keras, tidak marah — tetapi cukup dalam, seperti doa yang ditelan bertahun-tahun.
Atma tidak berani menoleh.
“Aku tahu, Makcik.”
“Dan aku sudah lama dengar bayang itu mengikuti aku.”
Dia tidak kata lagi.
---
Di luar desa, mereka duduk di bawah pohon sena besar.
Damar meletakkan lembing di pangkuannya. Dia memandang Atma lama, kemudian mengangkat arang dan menulis pada tanah:
“Kenapa kau tak mengaku?”
Atma menghela nafas.
“Kerana dia belum bersedia untuk maafkan. Dan aku belum layak untuk diampunkan. Hari ini, cukup kalau aku boleh bantu mereka hidup sedikit lebih baik.”
Damar memandangnya lama, kemudian mengangguk perlahan.
Mereka tidak bercakap selepas itu.
Tapi ketika matahari mula tenggelam di ufuk bukit, dan suara azan kecil bergema dari surau lama di hujung desa, Atma tahu: walau sedikit… mungkin dia telah mengubah sesuatu.
Dan walaupun Makcik itu tidak memaafkan… anak lelaki kecil itu telah memandangnya bukan sebagai pembunuh, tapi sebagai manusia.
Itu sudah cukup untuk hari ini.
Share this novel



