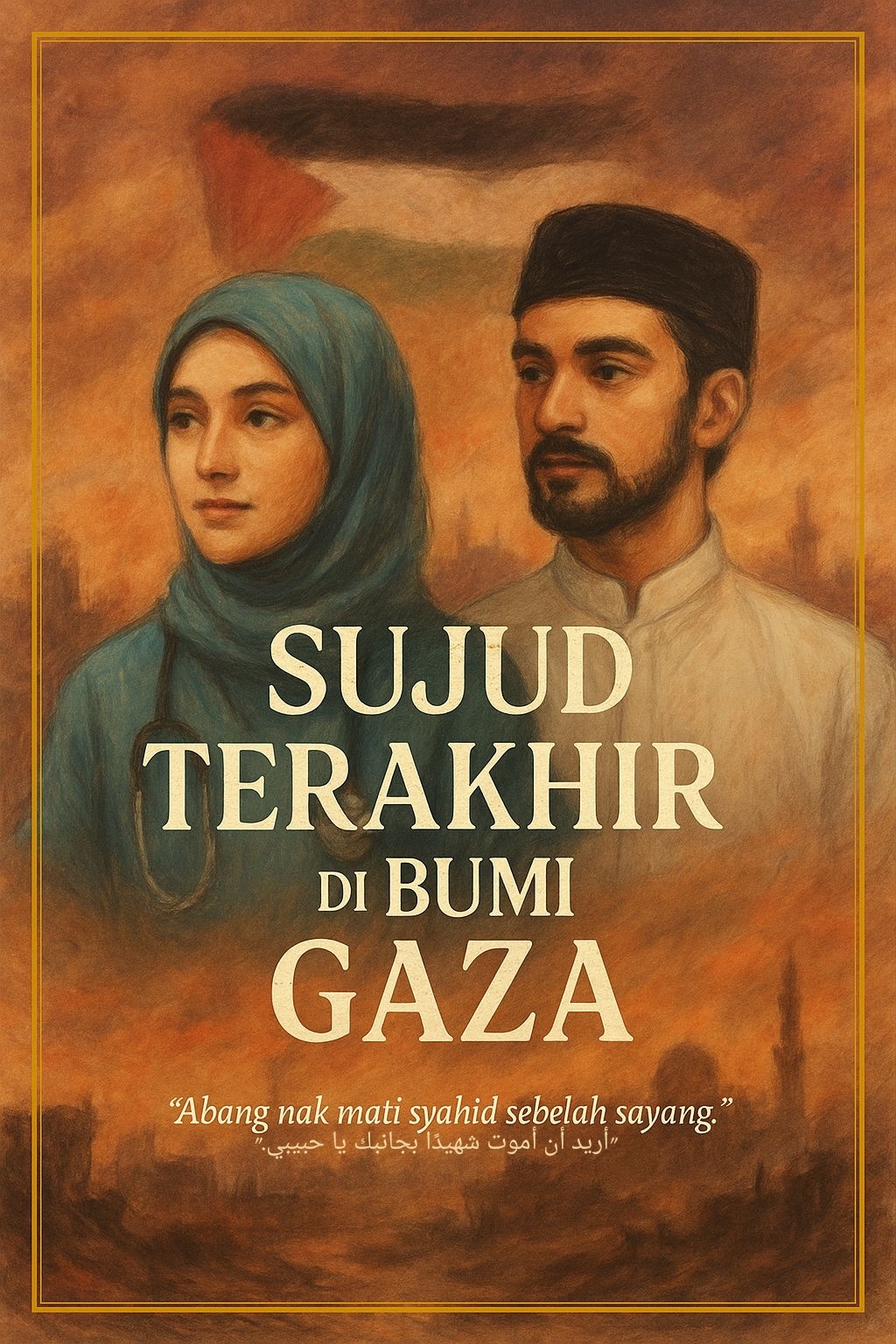
BAB 5 – Azmara, Kekasih yang Memburu
 Series
Series
 57
57
Pasar Pekan Sendang mula sesak sejak awal pagi.
Jeritan peniaga, bunyi ayam dan kambing, serta bau rempah dan peluh bercampur dalam udara yang hangat. Atma dan Damar berjalan perlahan di antara lautan manusia, menyamar sebagai dua pengembara biasa.
Atma bertopi pandan rendah, Damar menyorok lembingnya dalam sarung kayu rotan di belakang. Mereka tidak menonjol, tetapi sentiasa waspada.
> Tiga hari sudah berlalu sejak mereka meninggalkan Desa Lereh. Dan walaupun tubuh terus bergerak ke hadapan, jiwa Atma masih sesekali tertinggal di belakang.
---
Mereka berhenti di sebuah gerai kuih. Atma menghulurkan dua keping wang perak.
“Untuk kau juga, Abang,” katanya sambil menyuakan kuih kelapa pada Damar. Damar mengangkat kening, lalu tersenyum sedikit — isyarat ringkas bahawa dia terhibur.
Tapi keselesaan itu tidak lama.
Ketika Atma memandang ke seberang pasar, pandangannya bertembung dengan sepasang mata yang dia tidak jangka akan temui lagi.
Azmara.
---
Dia berdiri tegak di hadapan gerai senjata lama, menyelusuri anak panah dengan jarinya seperti pelayan biasa. Tudung nipis hitam melilit rambutnya, namun matanya — mata yang sama yang pernah memandang Atma dalam pelukan malam berdosa bertahun dahulu — kini memancarkan ancaman yang tenang.
Dia melihat Atma.
Dia senyum.
Dan dia menghilang ke celah keramaian pasar.
Atma segera bergerak. Damar ikut tanpa tanya. Mereka menyusuri lorong-lorong sempit antara gerai, lalu masuk ke lorong belakang bangunan kedai. Bayang Azmara muncul di hujung jalan, berjalan perlahan — seolah-olah menggoda mereka untuk mengekori.
---
Mereka sampai ke halaman kosong belakang gudang kayu. Di situ, Azmara sudah berdiri di tengah ruang.
Tangannya memegang dua kerambit melengkung, bersinar di bawah cahaya pagi. Rambutnya kini terurai separuh, melayang perlahan ditiup angin. Wajahnya masih cantik — tapi bukan lagi wajah kekasih. Itu wajah pembunuh.
“Atma.”
Suaranya halus, tapi tajam.
“Masih hidup, ya? Aku sangka kau sudah hanyut bersama dosa-dosa kau ke dasar sungai.”
Atma melangkah ke hadapan.
“Azmara.”
“Aku tak mahu berlawan. Aku tak mahu bunuh sesiapa lagi.”
Azmara ketawa kecil. Matanya sinis.
“Itu kata-kata orang yang sudah kalah dengan diri sendiri. Aku tak datang untuk berbual tentang keinsafan kau.”
Dia menghunus kerambit dan menggayakan posisi silat rendah, lutut dibengkokkan dan tangan kanan terkedepan.
“Aku datang sebab ada harga atas kepala kau. Dan juga sebab aku mahu lihat… apakah yang pernah aku cinta dulu masih tahu cara berlawan.”
---
Damar maju ke hadapan, tapi Atma mengangkat tangan.
“Abang… biar aku.”
Damar menatapnya lama, kemudian mengundur — tapi masih bersedia dengan lembing jika perlu.
---
Pertarungan bermula dalam sekelip mata.
Azmara menyerang dengan putaran rendah, kerambit menyasar rusuk Atma. Atma mengelak dengan kilas badan, lalu cuba menangkis serangan kedua. Dia tidak lagi punya senjata, tapi langkahnya masih hidup — langkah silat tua peninggalan ibunya.
> Mereka bukan sekadar berlawan. Mereka menari — di antara luka lama dan perasaan yang tak sempat mekar.
Azmara menikam ke arah dada, tapi Atma menepis dan menangkap lengannya. Dalam jarak dekat itu, mata mereka bertemu.
“Aku tak mahu lawan kau, Mara,” bisik Atma.
Azmara menggigit bibir. Tangan kirinya menyambar ke leher, tapi Atma menahan. Dia tolak Azmara perlahan ke belakang dan melepaskan tangannya.
**“Pergi,” kata Atma. “Aku bukan orang yang sama.”
Azmara berdiri semula. Nafasnya deras, dada naik turun. Tapi matanya kini keliru. Sebahagian dirinya mahu terus menyerang. Tapi sebahagian lain… masih kenal Atma.
Dia menyarung kembali kerambitnya.
“Kau bukan orang yang sama?”
“Aku harap begitu. Tapi jangan lupa… orang seperti kita, Atma… tidak pernah layak untuk jadi baru.”
Dengan itu, dia melangkah pergi — meninggalkan Atma dan Damar dalam keheningan halaman belakang pasar.
---
Share this novel



