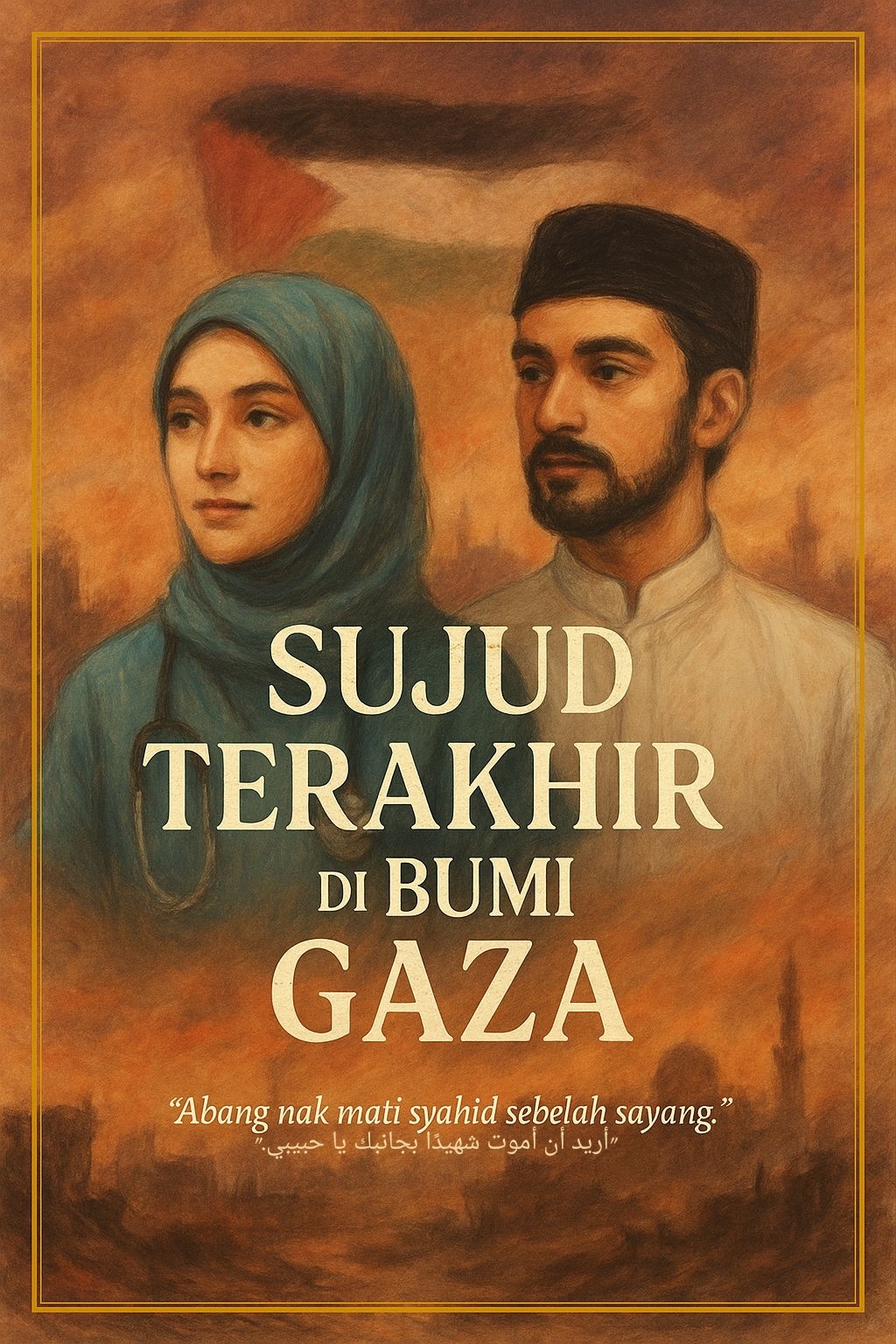
BAB 1 – Dosa Dalam Bayang
 Series
Series
 57
57
Angin malam membawa bau darah.
Langkah-langkah Atma perlahan menuruni anak tangga batu yang basah. Hujan baru reda. Di belakangnya, tubuh kaku seorang wanita masih terbujur di atas lantai berlumuran merah. Pakaian indah berwarna ungu lembut kini digenggam lumpur dan luka. Matanya terbuka, memandang langit yang tidak lagi membalas pandangan.
Atma tidak menoleh lagi.
Tangannya menggenggam kuat sarung keris. Nafasnya masih berat — bukan kerana perlawanan, tetapi kerana jantungnya sendiri.
“Kenapa aku?”
“Mengapa bukan orang lain?”
Soalan itu bergema dalam fikirannya seperti bisikan halus yang mengakar dalam tulang. Dia diberi nama mangsa seperti biasa. Lokasi, masa, bayaran. Tapi tidak diberitahu siapa.
Dan kini, dia tahu.
Dayang Purnama. Gadis istana. Wajahnya pernah singgah dalam lenanya, namun tidak pernah dia undang untuk mati dalam tangannya.
Tiga tahun dahulu, dalam satu majlis tertutup istana, Purnama pernah menghampirinya sewaktu dia sedang mengawal perkarangan luar. Dia menyapa. Senyumannya halus, lembut, dan benar.
“Kau seperti seseorang yang memikul dosa terlalu besar untuk usia semuda ini,” katanya.
Atma hanya diam ketika itu. Tapi kata-kata itu masih terikat dalam benaknya hingga malam ini.
Dia turun ke halaman belakang istana, menyeberangi lorong-lorong batu tanpa suara. Di kejauhan, suara anjing penjaga sudah mula menyalak.
Dia tidak peduli.
Malam ini, dia bukan sekadar pembunuh. Dia pembunuh yang tahu namanya sendiri sudah tidak ada erti.
"Aku Atma Nirmala," bisiknya kepada angin. "Dan aku telah membunuh orang terakhir yang pernah menyentuh hatiku."
---
Dia tiba di tebing sungai di luar kota menjelang fajar. Awan masih menggantungkan sisa gelap, seolah-olah langit sendiri belum sudi menyaksikan apa yang akan berlaku.
Atma duduk di atas batu besar, menghela nafas panjang. Tangannya menggenggam Keris Tundung Nyawa — senjata yang diwarisi daripada ibunya, seorang pendekar wanita yang mati kerana mempertahankan kebenaran.
Keris itu telah menjadi tangan kanannya dalam pembunuhan, dalam diam, dalam bayang.
Tapi malam ini, ia jadi saksi kepada kejatuhan terakhir jiwanya.
Tanpa sebarang kata, dia berdiri, dan menghumban keris itu ke dalam sungai.
“Pergilah,” katanya perlahan. “Jadi saksi kepada dosaku, bukan senjataku.”
Air sungai tenang. Tiada pusaran. Tiada bunyi. Seolah-olah keris itu pun enggan mengganggu keseimbangan dunia.
Dia melutut di situ. Merenung air. Suara Purnama datang semula.
“Dosa boleh dimaafkan, Atma. Tapi hanya jika kau sendiri berhenti berdarah dalam hati.”
Atma menutup matanya.
Dan buat kali pertama dalam hidupnya — dia menangis.
Share this novel



