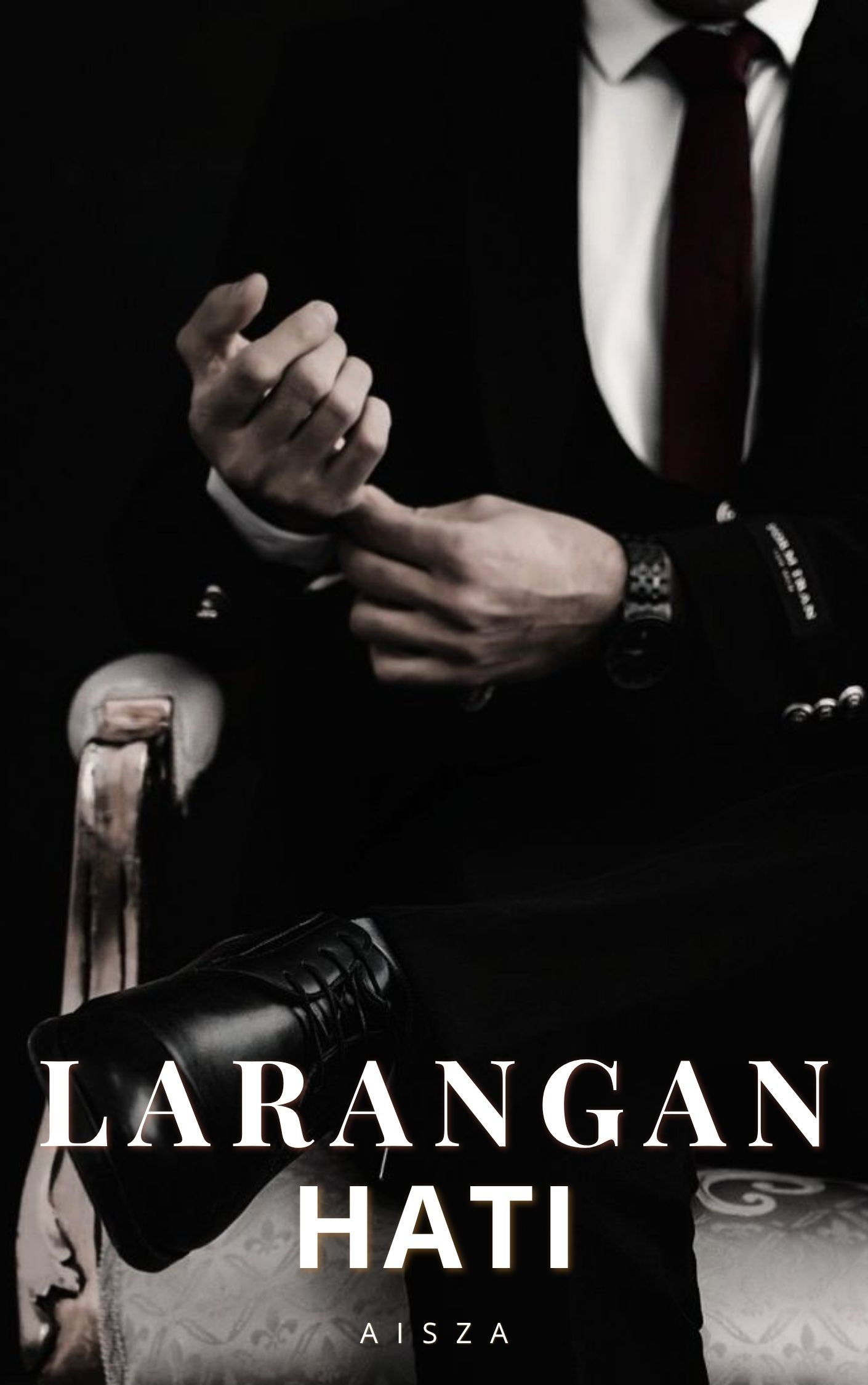
Bab 2: Pensyarah Baharu yang Misteri
 Series
Series
 224
224
“Dia pandang kau lagi tadi masa dekat kafeteria. Aku nampak! Tak payah nak nafi,” bisik Farah penuh semangat sambil menyudu nasi goreng ke dalam mulut.
Amira mengeluh. “Farah, tolonglah. Aku tak nak jadi bahan gosip. Aku cuma jawab soalan dalam kelas. Benda biasa, kan?”
“Biasa untuk pelajar lain, tapi luar biasa untuk Amira Zulaikha,” balas Farah sambil tersengih. “Kau kan selalu low-profile. Bila tiba-tiba dapat perhatian, mestilah orang perasan.”
Amira mengalihkan pandangan ke luar tingkap kafeteria. Matanya tertumpu pada halaman fakulti di mana beberapa pelajar sedang bersantai. Namun fikirannya jauh mengembara, teringat pada pandangan mata Dr. Rayyan. Pandangan yang dalam, seolah-olah menyimpan sesuatu yang tidak terucap.
Sejak pertemuan pertama itu, dia mula merasakan kehadiran lelaki itu terlalu dekat, terlalu nyata. Entah kenapa, Amira tidak mampu mengabaikan getaran aneh yang muncul setiap kali mendengar namanya disebut.
Di pejabat fakulti, Dr. Rayyan menyemak tugasan pelajar dari kelas lain. Pandangannya fokus, tetapi sesekali matanya berhenti pada satu fail — senarai pelajar dalam kelas Teori Komunikasi Massa. Namanya satu demi satu diperhatikan, sehingga matanya singgah pada satu nama.
Amira Zulaikha binti Rahmat.
Dia meneliti kad matrik yang dilekatkan bersama fail pelajar itu. Wajah dalam foto pelajar itu terlalu berbeza dengan wajah nyata yang dilihatnya di dalam dewan kuliah. Dalam gambar, Amira kelihatan seperti pelajar biasa — tenang, berdisiplin, dan sopan. Tapi dalam realiti, ada satu aura dalam dirinya yang tidak boleh dijelaskan dengan kata-kata.
“Dr. Rayyan?”
Suara itu mengejutkan lamunannya. Pintu bilik pensyarah diketuk dan muncul Prof. Marina, Dekan Fakulti Komunikasi. Wanita lewat 50-an itu terkenal dengan prinsipnya yang ketat dan pendiriannya yang konservatif.
“Ya, Prof. Marina. Sila masuk.”
Prof. Marina melangkah masuk dengan senyuman formal. “Saya cuma nak bertanya, bagaimana minggu pertama awak di sini? Segalanya berjalan lancar?”
Dr. Rayyan mengangguk. “Setakat ini, semuanya baik. Pelajar saya juga nampak bersemangat. Saya cuba kenal pasti potensi mereka lebih awal.”
Prof. Marina tersenyum sedikit. “Itu bagus. Tapi saya ingin ingatkan sesuatu, Dr. Rayyan. Di universiti ini, kita amat menitikberatkan etika. Hubungan antara pensyarah dan pelajar, walaupun hanya profesional, harus dijaga batasnya.”
Dr. Rayyan menelan liur. “Sudah tentu, Prof. Saya faham.”
“Bagus. Saya tahu awak muda, dan pelajar kita pun ada yang agak… agresif,” tambahnya dengan sinis.
Dr. Rayyan hanya mengangguk, walaupun di dalam hatinya terasa sedikit terganggu. Dia tahu peringatan itu bukan sekadar prosedur biasa — mungkin sudah ada yang memerhatikan.
Beberapa hari berlalu. Kelas Teori Komunikasi Massa menjadi antara kelas paling popular semester ini. Ramai pelajar dari jurusan lain pun mula mencari alasan untuk menyertai kelas itu walaupun tiada dalam kurikulum mereka.
Dalam suasana yang semakin meriah itu, Amira cuba mengekalkan fokusnya. Dia menyibukkan diri dengan tugasan, membaca jurnal dan menyiapkan projek akhir bersama kumpulannya yang terdiri daripada Farah, Haris, dan Syafiq.
Namun begitu, perhatian Dr. Rayyan terhadap dirinya makin sukar untuk diabaikan.
Setiap kali dia bercakap dalam kelas, Dr. Rayyan akan memandangnya sedikit lebih lama daripada pelajar lain. Setiap kali kelas tamat, beliau akan memberikan komen peribadi tentang kerja yang dilakukannya — sesuatu yang tidak pula dilakukan terhadap pelajar lain.
Dan setiap kali pandangan mereka bertembung secara tidak sengaja, ada sesuatu yang terbit dalam dada Amira. Sesuatu yang hangat. Sesuatu yang… berbahaya.
“Farah, aku rasa… Dr. Rayyan layan aku lain macam,” luah Amira suatu petang ketika mereka sedang duduk di gazebo taman kampus.
Farah yang sedang menatal telefon bimbit mengangkat kening. “Kau baru sedar? Aku dah lama perasan. Tapi kenapa kau cakap macam tu? Ada apa-apa yang dia buat?”
Amira menceritakan beberapa insiden kecil — seperti komen tambahan dalam emel, pujian yang agak peribadi dalam kelas, dan cara dia memberi perhatian lebih dari sepatutnya.
Farah mendengar dengan penuh serius.
“Mira, kau tahu kan hubungan macam tu… tak sesuai. Maksud aku, dia pensyarah. Kau pelajar. Kalau orang tahu, habis reputasi kau.”
“Aku tahu. Tapi aku tak buat apa-apa pun. Aku cuma rasa… tak selesa. Tapi dalam masa yang sama, aku pun tak nafikan ada sesuatu dalam cara dia pandang aku…”
Farah memegang tangan Amira. “Jaga diri kau. Jangan terbawa perasaan. Kalau betul dia ada hati pada kau, dia patut tahu batas.”
Amira mengangguk perlahan. Tapi dalam hatinya, badai perasaan sudah pun mula berkocak.
Suatu hari, selepas kelas selesai dan pelajar sudah beredar, Dr. Rayyan menahan Amira sebelum dia keluar.
“Amira, boleh saya cakap sekejap?”
Amira berasa gementar tetapi tetap mengangguk. Dia berdiri di hadapan meja pensyarah sambil menggenggam bukunya.
“Saya cuma nak ucapkan tahniah. Kertas kerja awak minggu lepas sangat mengagumkan. Saya jarang tengok pelajar tahun akhir yang boleh buat analisis sebaik itu.”
Amira tersipu. “Terima kasih, Dr. Saya cuba buat sebaik mungkin.”
Dr. Rayyan memandangnya dengan pandangan yang sukar ditafsirkan.
“Amira… saya tahu ini mungkin kedengaran pelik, tapi saya harap awak tahu yang saya bukan cuba beri layanan istimewa. Saya cuma… hargai pelajar yang punya potensi.”
Amira mengangguk, walaupun hatinya semakin keliru.
“Saya faham, Dr.”
“Dan satu lagi… kalau awak perlukan bantuan dalam projek akhir nanti, saya sudi bantu. Di luar waktu kelas pun tak mengapa,” tambahnya.
Ayat itu membuatkan Amira terdiam. Dia tidak tahu bagaimana harus membalas. Tapi sebelum sempat dia memberi respon, Haris muncul di pintu dewan kuliah.
“Mira, jom. Kita ada perbincangan kumpulan.”
Dr. Rayyan kembali tersenyum sopan. “Baiklah. Jumpa lagi dalam kelas.”
Beberapa hari kemudian, desas-desus mula tersebar. Ada pelajar yang menyuarakan rasa tidak puas hati kerana merasakan Amira mendapat layanan khas daripada pensyarah baru.
“Yalah, tengoklah. Asyik-asyik Amira je yang dapat pujian. Dalam kelas pun asyik dia je yang diajak bercakap,” kata Liyana, pelajar senior yang memang tidak senang dengan Amira sejak awal.
Syafiq yang turut mendengar hanya menjawab, “Tapi Amira memang pelajar cemerlang pun. Mungkin Dr. Rayyan cuma kagum dengan kebolehan dia.”
“Ah, jangan nak bela sangat. Aku dengar-dengar, mereka selalu berjumpa kat luar waktu kelas,” tambah Liyana dengan nada sinis.
Amira mula merasakan tekanan. Bukan sahaja dia terpaksa menanggung kekeliruan dalam dirinya, kini dia juga menjadi bahan bualan dalam kalangan pelajar lain.
Dia berbual dengan Farah malam itu di bilik asrama.
“Aku takut, Farah. Aku rasa aku dah jadi sasaran. Aku tak minta semua ni berlaku…”
Farah memeluk bahu Amira. “Kau cuma perlu berhati-hati. Elakkan jumpa dia seorang diri. Kalau perlu, minta dia beri panduan melalui emel je. Kau kena lindungi diri kau sendiri.”
Amira mengangguk perlahan. Tapi dia tahu, hatinya sudah mula terusik dengan perhatian yang diberi oleh lelaki itu. Dan bila hati sudah mula berbicara, logik seringkali hilang suara.
Pada malam yang sama, di pejabat fakulti yang kini sepi, Dr. Rayyan termenung di hadapan skrin komputernya. Emel Amira masih terbuka. Dia meneliti kata-kata pelajar itu — ringkas, berhemah, dan sopan.
Namun dia tahu, di sebalik kata-kata itu ada sesuatu yang menyentuh jiwanya. Sesuatu yang membuatkan dia lupa pada peraturan, lupa pada batas.
Dia tahu dia tidak sepatutnya membenarkan perasaan itu tumbuh. Tapi perasaan bukan seperti fail yang boleh dikawal dengan klik tetikus.
Dia berbisik sendirian, “Amira… kenapa awak muncul dalam hidup saya sekarang?”
Share this novel



